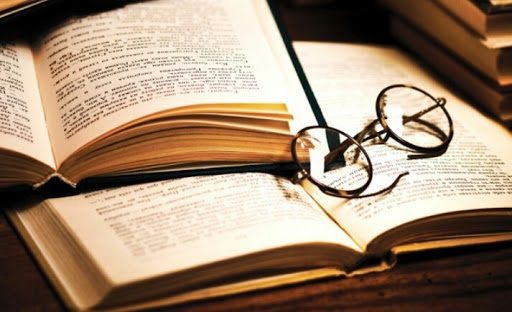Sastra, Simbolisme Agama, dan Narasi Dakwah Mutakhir
Mircea Eliade, seorang sejarawan merangkap filsuf yang memberi kontribusi masyhur berupa Teori Eternal Return bagi pembelajaran religius, suatu kali menautkan kelindan agama dan simbol.
Baginya, simbol merupakan cara khusus untuk mengenal hal-hal religius. Pernyataannya merujuk pada sebuah pemahaman fungsional ihwal simbol, sesuatu yang unik yang dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai yang sakral dan realitas kosmologis.
Dalam konteks agama, terminologi simbolnya Eliade itu dapat mewujud bahasa sebagai instrumen fundamental dalam ikhtiar memahami agama. Di sinilah ikhtiar pemahaman itu mulai dibentuk. Terbukanya ruang interpretasi terhadap ajaran agama, terbuka pula sawala religius yang dialektis. Dialog dan dakwah agama merupakan dua entitas tak terpisahkan dari kegiatan sawala religius itu.
Melalui dua kegiatan sawala religius inilah bahasa menempati posisi yang signifikan. Ia menjadi unsur fundamental dalam sebuah dakwah misalnya, sebagai medium menyampaikan ajaran agama. Penggunaan bahasa yang baik dapat membantu seseorang lebih mudah untuk memahami agamanya secara komprehensif.
Medium Sastra, Representasi Simbolis Memahami Agama
Merujuk pada aspek kebahasaan, Don Cupitt, seorang filsuf Inggris yang sarjana teologi Kristen menulis, “When Language is policied Too Tiggly, Religion slowly die” (Jika bahasa diatur terlalu ketat, agama akan mati secara perlahan). Hal ini menandakan bahwa ajaran agama sepatutnya disampaikan dengan menggunakan bahasa yang fleksibel dan longgar.
Ajaran agama akan menjadi lebih indah dan hidup dalam lubuk sanubari pemeluknya jika ekspresi dakwah dapat menyatu dengan aspek kebahasaan berkelindan cita rasa sastrawi. Sebab, bahasa sastra mengandung estetika keadaban yang paling subtil (halus). Di dalamnya, pertautan antara ajaran agama dan nilai seni saling membuhul satu sama lain.
Realitas pertautan agama dan nilai seni itu pada tataran lebih lanjut berakhir pada suatu konklusi integratif, bahwa agama secara simbolik dapat direpresentasikan melalui karya sastra. Nuansa religiusitas, moral, dan kisah lain di balik lakon kehidupan agama dan manusia menjadi objek yang banyak dibidik dan diulik sastrawan maupun penyair mutakhir.
Hal tersebut selaras ketika Faruk dalam artikelnya Memasuki Dunia Imajiner: Soal Sastra Mutakhir dan Kritiknya (1997) menyatakan bahwa perkembangan karya sastra Indonesia terus-menerus merepresentasikan hasrat-hasrat manusia akan sebuah dunia lain. Dunia yang dibayangkan sebagai sebuah situasi dan kondisi surgawi, yang memungkinkan orang memperoleh kesenangan dan kebahagiaan sejati.
Memikirkan kembali aspek religiusitas dalam setiap karya merupakan kulminasi dari ikhtiar panjang sastrawan memantik kesadaran umat manusia pada kesadaran spiritual. Ikhtiar mulia itu seolah meneguhkan posisi sastrawan sejajar dengan Nabi.
Bahkan, Adonis tak segan menyejajarkan ‘jalan kepenyairan’ dengan ‘jalan kenabian’. Baginya, azwaq al-adabi (cita rasa sastra) sanggup menggapai tangga tertinggi dan dapat menangkap pesan profetik laiknya Nabi.
Simbolisme Agama dalam Puisi Gus Mus
Pada puisi Gus Mus bertajuk “Agama” misalnya, betapa simbolisme agama teraktualisasi lewat metafora-metafora religius nan reflektif. /Agama adalah kereta kencana // yang disediakan Tuhan // untuk kendaraan kalian // berangkat menuju hadirat-Nya // Jangan terpukau keindahannya saja // Apalagi sampai dengan saudara-saudara sendiri bertikai // berebut tempat paling depan // Kereta Kencana cukup luas untuk semua hamba yang rindu Tuhan // Berangkatlah ! // Sejak lama ia menunggu kalian .
Simbolisme agama dalam tilikan Gus Mus semacam kendaraan yang menghubungkan makhluk dengan Tuhannya. Ia (agama) dalam terminologi Weber, kendati eskatologis, tetap dibutuhkan sebagai pemandu umat manusia menuju yang transenden (Tuhan).
Metafora Kereta Kencana pada bait pertama terlihat jelas betapa simbolisme agama secara fungsional menjadi pelopor keterhubungan substantif dengan Tuhan.
Sublimasi pemahaman Gus Mus terhadap agama yang disimbolkan Kereta Kencana yang demikian, seolah mengonfirmasi kembali definisi sistem simbol, sebagai segala sesuatu yang membawa, menyimpan, serta menyampaikan ide dan makna.
Di dalamnya tersimpan makna-makna yang dapat membangun suasana hati. Bahasa, dengan demikian, bukan sekadar medium penyampai kehadiran yang diandaikan (Agama yang disimbolkan Kereta Kencana). Bahasa, bagi Heidegger, adalah medium penyingkapan bukan penyampaian.
Di titik inilah medium puisi perlahan tumbuh menjadi upaya alternatif menyingkap entitas makna agama di ruang publik. Lewat puisi, penalaran publik terhadap agama membuka ruang pemahaman yang kontekstual-eksklusif.
Tentu tanpa berpretensi mengagungkan bahasa dalam menyampaikan ajaran agama, namun bahasa sastra dapat dengan mudah menyimbolkan segala keagungan agama lewat penalaran intuitif.
Ada penundukan ego di sana. Sastra yang merupakan manifestasi penalaran intuitif itu memberi kita kesempatan untuk sejenak merenung dan memahami realitas agama secara kontekstual-eksklusif. Tidak buru-buru memahami agama.
Sebaliknya, keberadaan agama diterima , dikaji, dan dimaknai melalui permenungan filosofis-kontemplatif. Karena itulah, medium sastra sedari titimangsa islamisasi merupakan formulasi lawas yang banyak digunakan para pelopor Islam guna mendedah pemahaman masyarakat terhadap Islam.
Muatan Agama dalam Sastra
Muatan agama dalam seni sastra di titimangsa Islamisasi Nusantara maujud dalam bait-bait syair, suluk, gurindam, pantun, prosa, dan prosa lirik. Bersastra sembari berdakwah merupakan kulminasi dari ikhtiar panjang menuntun masyarakat memahami agama dengan baik. Mereka memanfaatkan sastra sebagai media melancarkan penyampaian pelbagai detail narasi keilmuan mulai dari sejarah, hukum, serta tasawuf.
Di Jawa, Sunan Bonang menjadi representasi pelopor Islam berkemajuan yang menggunakan sastra berbentuk tembang untuk menyebarkan dakwahnya, terutama tasawuf. Ahmad Tohari dalam Sastra Pesantren, Sastra Dakwah menyebut “Suluk Wuragul” yang ditulisnya itu memuat kelindan pemikiran teologis paham Jabariah dan Qadariyah.
Suluk yang diciptakan dengan memadukan antara konsepsi sastra dan ajaran Islam terbukti akomodatif dalam menyampaikan dakwah di tengah realitas sosio-kultural masyarakat pribumi kala itu.
Formulasi Sastra dalam Kegiatan Dakwah
Kini, spirit kesusastraan penting untuk diformulasikan kembali di inti dakwah kekinian, setidaknya dapat mereduksi narasi dakwah yang penuh justifikasi hitam-putih itu. Dengan kata lain, sastra dapat menyelamatkan manusia dari bahasa yang buruk. Sebab, bad language (bahasa yang buruk) dalam tilikan Locke (1992: 14) merupakan salah satu indikator kerusakan suatu bangsa.
Ada semacam pergumulan etis ketika kita berikhtiar mengintegrasikan ajaran agama dengan sastra yang merupakan produk seni. Kontroversi dan perdebatan yang merujuk pada paradigma seni sastra dalam perspektif Islam selama beberapa titimangsa terakhir, mesti segera ditampik. Mengingat kelindan spiritualitas Islam dan seni telah maujud dalam sebuah teks suci bernama Al-Qur’an.
Dengan demikian, mengeja setiap detail taraf berbahasa kita dalam menyampaikan sesuatu yang esensial (ajaran agama) merupakan perilaku mulia. Kita seolah mengasah nurani menuju taraf imani yang paripurna. Untuk mengasah nurani, manusia tak cukup hanya memiliki tata nilai logika (benar salah), dan etika (baik-buruk), tetapi juga membutuhkan estetika (indah-jelek). Salah satu tolok ukur kecerdasan etika yaitu melek sastra.
Akhirnya, kita merindukan orang semacam Gus Mus, D. Zawawi Imron, dan Emha Ainun Nadjib yang begitu getol merepresentasikan ajaran agama sembari bersastra dan berdakwah. Kecenderungan menyampaikan pesan-pesan agama melalui sastra yang disampaikannya terbukti menyejukkan dan membawa iklim perdamaian bagi etos keberagamaan kita hari ini. Begitu.
Editor: Rozy