Sebagaimana orang Islam pada umumnya, aku diajarkan membaca Al-Qur’an sejak usia dini. Bahkan di dalam keluargaku ada sebuah tradisi bahwa seorang anak harus bisa membaca Al-Qur’an sebelum dia masuk sekolah. Ibuku adalah yang mula-mula mengenalkanku pada Al-Qur’an, hingga kini aku belajar tafsir Al-Qur’an secara khusus.
Dengan penuh kesabaran, ibuku mengajariku mengeja kata demi kata (Al-Qur’an) dengan buku panduan bernama ‘Buku Iqra’. Butuh waktu beberapa bulan bagiku untuk menamatkan ‘Buku Iqra’ yang terdiri dari enam jilid itu. Setelah menamatkan ‘Buku Iqra’ aku mulai bisa membaca Al-Qur’an, tentunya masih dalam bimbingan ibu.
Aku dan Al-Qur’an
Hubunganku dengan Al-Qur’an kemudian berlanjut ketika aku mulai belajar menghafal Al-Qur’an. Ketika kata demi kata, ayat demi ayat, surat demi surat aku hafalkan, di situlah aku merasakan bahwa Al-Qur’an adalah mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang sepertiku (yang ibunya tidak berbahasa arab) dapat dengan mudah menghafal Al-Qur’an. Maka tidak heran jika kemudahan (membaca, menghafal, dan mempelajari) Al-Qur’an disebutkan empat kali dalam Al-Qur’an,
“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?”
Rasa syukurku semakin bertambah ketika aku diberi kesempatan untuk belajar Al-Qur’an lebih jauh lagi di sebuah perguruan tinggi. Aku mendapat beasiswa S1 untuk program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Di bangku perkuliahan aku tidak diajari tafsir Al-Qur’an ayat demi ayat, melainkan aku diajari tentang metode-metode untuk menafsirkan Al-Qur’an. Aku tidak disuguhi ‘buah-buahan’ yang sudah masak, melainkan aku diajari cara ‘memanjat pohon’ untuk memetik buah, kira-kira seperti itulah perumpamaannya.
Di bangku perkuliahan, aku mulai mengerti. Ketika ditafsirkan, Al-Qur’an seringkali disalahgunakan. Al-Qur’an dijadikan sebagai alat pembenaran bagi masing-masing golongan dan pembenaran tindak kekerasan. Bahkan tidak jarang kita temui Al-Qur’an dijadikan alat kampanye saat pemilu. Fakta ini mengingatkan saya pada sebuah syair yang digugah oleh penyair Urdu, Mahir Al-Qadri (1907-1978) yang melukiskan ratapan Al-Qur’an,
Laksana perhiasan mereka memperlakukan aku.
Mereka menjagaku dan kadang menciumku.
Mereka membacakan aku pada saat-saat pesta.
Mereka bersumpah denganku ketika berselisih.
Didalam diri mereka aku tersimpan rapi.
Hingga datang pesta dan perselisihan berikutnya,
Saat-saat mereka kembali membutuhkanku.
Ya, mereka membaca dan menghafalku.
Tetapi aku hanya laksana perhiasan .
Pesanku diabaikan, keindahanku dicampakan.
Aku tetap polos, yang pernah pancarkan kemenangan.
Mereka sungguh keliru memperlakukan diriku.
Banyak yang kuberi tapi tak seorangpun memahami.
Syair ini benar-benar menggambarkan kondisi kita di negeri ini dan beberapa negeri muslim lain. Para demonstran kerap melambai-lambaikan Al-Qur’an seraya meneriakkan slogan buruk, penuh kebencian, dan permusuhan. Mereka lupa bahwa Al-Qur’an adalah kitab (rahmat) yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Ia diturunkan kepada Nabi pembawa rahmat bagi seluruh alam, tapi cara mereka meneriakan Al-Qur’an sangat jauh dari definisi rahmat.
Fakta adanya serangkaian peristiwa bom bunuh diri yang pernah terjadi di negeri ini menjadikannya semakin ironis. Jika pelakunya ditanya mengapa mereka melakukan bom bunuh diri, maka dengan lantang mereka akan menjawab, ‘bom bunuh diri adalah perintah Al-Qur’an’.
Kita Merindukan Tafsir Al-Qur’an yang Ramah
Menurut Quraish Shihab, tafsir adalah upaya untuk mengungkap maksud-maksud firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Jika merujuk pada definisi ini maka produk tafsir Al-Qur’an sangat beragam sesuai dengan ilmu pengetahuan, latar belakang, dan kecerdasan mufassir (orang yang menafsirkan Al-Qur’an).
Dalam bukunya, Reading The Qur’an: The Contemporary Relevance of The Sacred Text of Islam, Ziauddin Sardar mengemukakan bahwa kita sering kali mengabaikan satu fakta, yaitu hakikat ayat-ayat Al-Qur’an yang rumit, berlapis, alegoris, metaforis, dan multitafsir.
Tafsir yang dikaitkan pada Al-Qur’an sesungguhnya hanyalah hasil pemahaman manusia. Tidak ada satu orangpun yang berhak memutlakan kebenaran tafsirnya. Apalagi memaksa semua orang untuk mengikuti tafsiran mereka yang kaku dan tertutup. Dua sikap inilah yang kemudian menumbuhkan kebencian, dan permusuhan orang lain bahkan disertai kekerasan dan aksi teror.
Hari ini kita memerlukan tafsir yang ramah, yang mau menerima perbedaan, bersedia hidup berdampingan dan saling menghormati. Untuk mewujudkan hal ini maka, para penafsir Al-Qur’an harus mencerna teks-teks ilahi secara objektif, hati yang bersih, dan rasional. Para mufassir juga hendaknya tidak menafsirkan Al-Qur’an secara tekstualis. Namun mereka harus berusaha menagkap pesan dibalik ayat yang oleh kaum sufi disebut makna ‘bathin’.
Menurut Said Aqil Siradj, agama islam akan terasa gersang dan kering, jika ternyata aspek eksoterik dalam islam hanya sebatas legal-formal dan tendensinya tekstualis.
Masih menurut Said Aqil sebuah ayat tentang jihad misalnya, akan terasa gersang dan kering apabila pemahamannya dimonopoli oleh tafsir “perang mengangkat senjata”. Padahal jihad pada masa Rasul saw merupakan satu wujud dan manifestasi pembebasan rakyat untuk menghapus diskriminasi dan melindungi hak-hak rakyat demi terbangunnya sebuah tatanan masyarakat yang beradab.
Itulah sepenggal kisah hubunganku dengan Al-Qur’an dan kerinduanku terhadap tafsir yang ramah.
Editor: Shidqi Mukhtasor


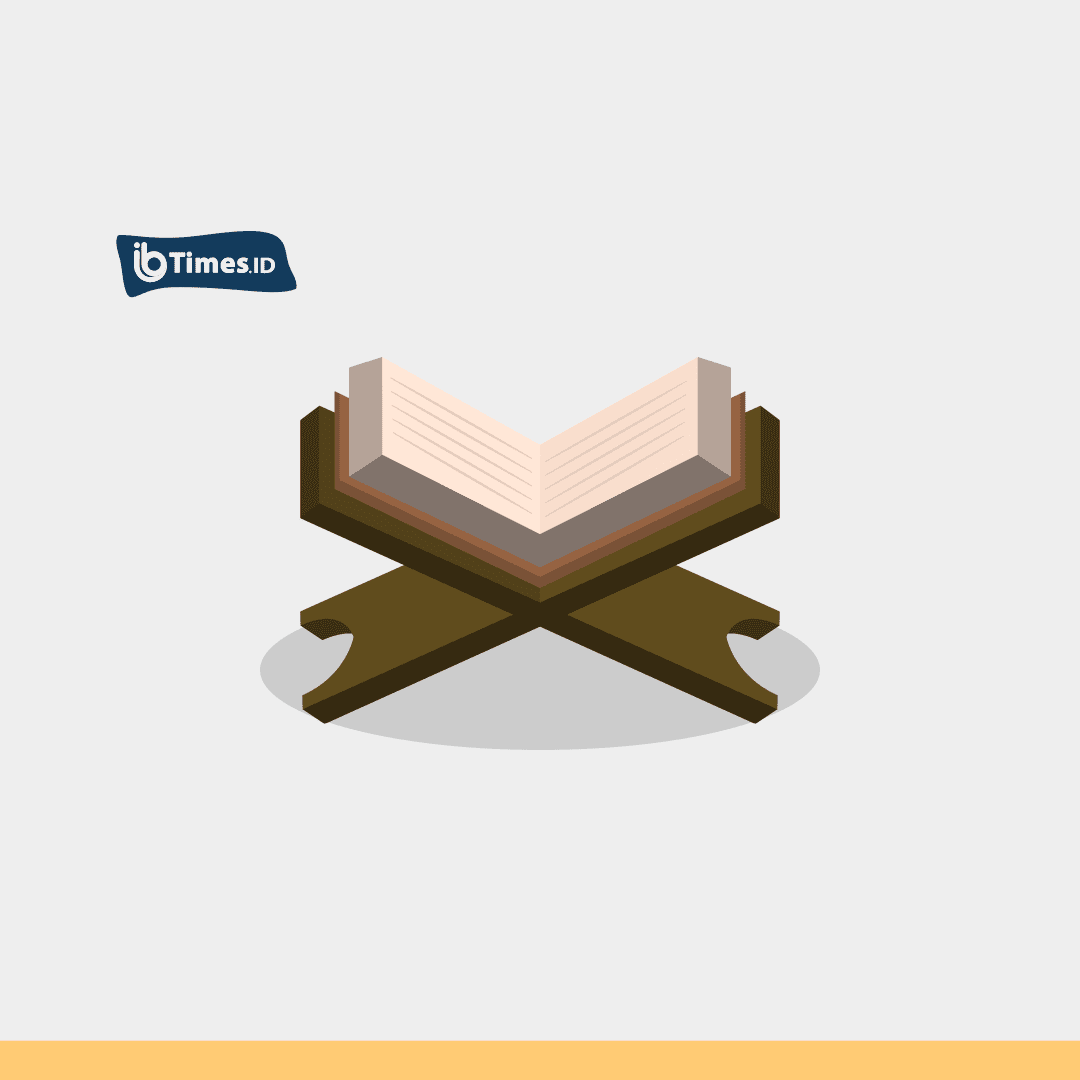

mantab tad