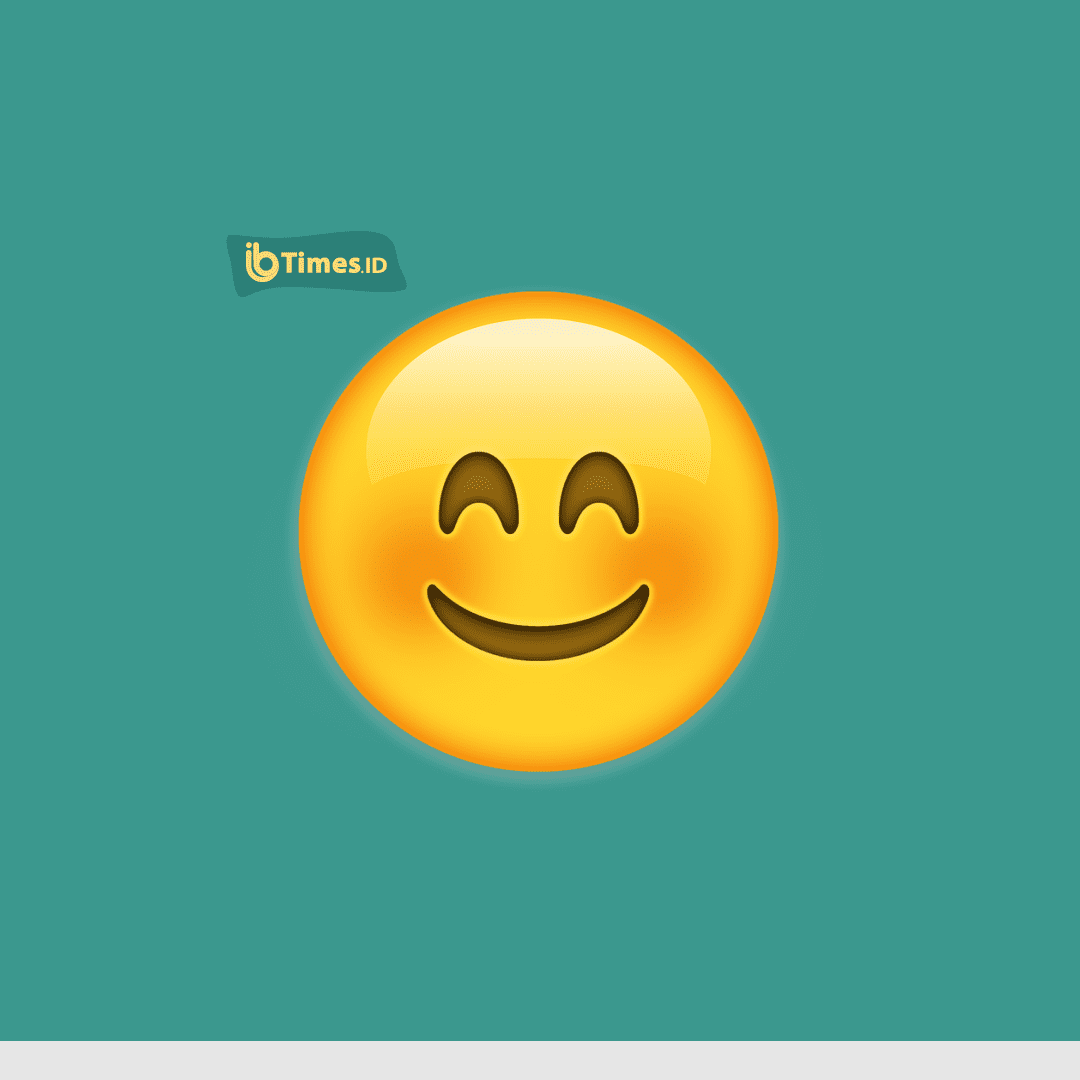Tidak sulit untuk kita menjumpai budaya ‘apa’ di media sosial. Teliti saja bahwa influencer-influencer pencipta konten bekerja dari segala ‘apa’. Semua yang viral, yang ramai adalah yang ‘apa’. Tentu apa-apa yang aneh, berbeda dan baru, atau setidaknya yang diberi kemasan baru.
Masalahnya kemudian yang sering kita tidak sadari adalah ‘apa’ menjadi standar kebahagiaan. Bahwa kita akan bahagia dengan ‘apa’ yang terbatas, berbeda, mahal. Sebaliknya, hidup terasa datar dan hambar bila apa yang kita punya, adalah apa yang orang lain juga punya. Intinya, jiwa kita dikuasai oleh ‘apa’.
Bayangkan saja apa-apa berikut. Liburan ke bali lebih menyenangkan dari berjalan santai dengan keluarga di sore hari. Makan malam di restauran steak mahal lebih sedap dari makan nasi pecel di warung depan rumah. Baju-baju dari brand luar negeri lebih elok ketimbang baju lama di lemari. Selalu saja, terbentang deretan ‘apa’ yang lebih dari ‘apa’ yang lain.
Kita manusia lantas dibuat mengejar apa-apa itu. Bekerja keras dari pagi hingga kembali pagi. Kerja yang berpeluh, berjubel, berdarah-darah. Tak jarang hingga ibadah terlupa. Padahal semuanya hanya demi terbang jauh-jauh ke bali, makan daging sapi yang bisa kita masak sendiri, dan menambah tumpukan kain di rumah yang maksimal dipakai seminggu satu kali.
Di tengah kesadaran akan semua itu jarang kita bertanya, apakah memang bahagia sejatinya ditentukan oleh yang ‘apa’? Mungkinkah terdapat yang lain, yang melebihi, melampaui bahkan meliputi ‘apa’, yang kemudian merupakan dasar bagi bahagia kita yang sebenarnya?
Kesejatian ‘Ada’ dibanding ‘Apa’
Para pembelajar filsafat Islam yang mengenal – dalam Mulla Sadra boleh jadi membedakan antara ‘ada’ dengan ‘apa’. Bagi mereka, ‘apa’ hanyalah batasan artifisial dari pikiran manusia atas ‘ada’. Bahwa ‘ada’ merupakan yang sejati. Buktinya sederhana saja: ‘ada’ bisa berdiri tanpa ‘apa’. Tapi ‘apa’ tanpa ‘ada’, hanyalah bayangan, imajinasi, atau bahkan semata konsep di pikiran.
Bukti lain yang mudah diterima orang kebanyakan adalah bahwa sesuatu itu menjadi ‘apa’ karena kita yang membuat, menamakan atau mendefinisikan demikian. Selembar kertas misalnya, bisa menjadi media untuk menulis atau bisa menjadi bungkus makanan. Dalam kondisi yang manapun, mereka adalah suatu ‘apa’ karena konstruksi pikiran dan intervensi perbuatan manusia.
Meski demikian, dibalik semua ‘apa’ yang relatif itu, mereka ‘ada’. Tanpa ‘ada’, tiada pula ‘apa’. Artinya, tanpa ‘ada’, tiada kertas tulis, tiada pula pembungkus makan, dan bahkan tiada pula segala apa-apa. ‘Ada’ merupakan dasar bagi realitas. ‘Ada’ ialah yang nyata di luar sana dan yang kita rasa, cium, dan dipersepsikan.
Dengan memahami fakta itu maka sekarang kita bisa bertanya: lantas mengapa seringnya kita mendasarkan bahagia pada yang bukan sejati, yaitu pada ‘apa’? Mengapa kita tidak mengembalikan bahagia kita pada ‘ada’?
Apa dan Ilusi Kebahagiaan
Masalahnya memang karena saking dekatnya ‘ada’, ia menjadi yang paling nyata sekaligus tidak kita sadari. Walhasil, kita menyandarkan kebahagiaan pada yang kentara oleh kasat mata atau indra-indra. Jadilah ‘apa’ kita nobatkan sebagai yang nyata dan bisa memengaruhi bahagianya kita karena ia seolah yang nyata.
Pun, ilusi kebahagiaan oleh ‘apa’ bekerja karena manusia gagal memahami hubungan ‘apa’ dan ‘ada’. Bahwa ‘ada’ ialah yang nyata serta kenyataan ‘ada’ berlaku pada ‘apa’ karena mereka satu belaka di realitas. Ilusi terjadi manakala kita melihat ‘apa’ sebagai yang nyata padahal ‘ada’ yang memberi eksistensi kepada ‘apa’ itu.
Sebagaimana kita dapati di keseharian, orang selalu berkeluh tentang ‘apa’. Padahal sebetulnya yang membuat sedih-bahagia mereka ialah ‘ada’. Misal, makan nasi goreng di warung kaki lima tidak berbeda sebagai ‘apa’ dengan makan di restoran bintang lima. Bahwa bukan ‘apa’, melainkan ‘ada’ pada salah satu atau keduanya yang bisa melumat rasa lapar dan memanjakan lidah kita.
Gradasi ‘Ada’ dan Gradasi Bahagia
Dahaga kita pada ‘apa’ tidak akan pernah puas. Sebab, segala ‘apa’ itu nilainya sama saja. Mereka bukan yang sejati di realitas, mereka adalah kosong belaka. Semakin kita melahap ‘apa’, tidaklah kita semakin kenyang olehnya. Kepuasan atau kebahagiaan itu hanya mungkin jika kita mengejar selain ‘apa’. Kebahagiaan itu hadir dari mengejar ‘ada’.
Tentu yang dimaksud disini bukan sekedar ‘apa’ yang ‘ada’. Karena jika begitu, kita akan kembali terjatuh kepada ‘apa’ ketimbang ‘ada’. Maka yang tepat adalah mengejar ‘ada’ dengan dibarengi pengetahuan bahwa dirinya merupakan sesuatu yang bertingkatan. Bahagia kita yang sempurna akan tercapai jika bisa meraih ‘ada’ yang berada di tingkatan lebih tinggi bahkan lebih sempurna.
Faktanya, jiwa kita adalah sesuatu yang tidak menempati ruang serta akan terus hidup selepas tubuh hancur. Berangkat dari kondisi dirinya, maka jiwa mendamba pada ‘ada’ yang lebih sempurna diatasnya. Bahagianya jiwa akan tercapai ketika kita mengejar ‘ada’ yang sempurna dan gagal dicapai jika yang dikejar hanya ‘apa’ yang berbatas dan bahkan sekedar ilusi.
Sepakat dengan gagasan Muhsin Labib, seorang filsuf muslim Indonesia, bahwa untuk bahagia sepenuhnya maka manusia harus memiliki jenis kesadaran yang berbeda. Ketimbang kesadaran esensial-material, atau ‘kesadaran apa’, mereka mesti mencapai kesadaran eksistensial atau ‘kesadaran ada’. Pada yang pertama manusia tertegun dan terjebak pada ‘apa’. Sedangkan pada yang kedua, manusia memahami ‘ada’ sebagai sumber dan tujuan kebahagiaan sekaligus.
Ada Sempurna sebagai Muara Kebahagiaan
Apakah ‘ada’ yang sempurna itu? Pertanyaan itulah yang harus pertama kali kita jawab sebelum kita bisa meraih bahagia yang sempurna pula. Mengetahui ‘ada’ yang sempurna akan membantu kita untuk mengetahui kemana kita harus menuju. Segala daya tenaga dan pikiran pun akan lebih terarah dalam perjalanan menujunya.
Sesungguhnya, ‘ada’ pada dirinya sendiri sudah sempurna. ‘Ada’ tidak memiliki cacat. Segalanya tercakup dalam ‘ada’. Mustahil terdapat sesuatu yang bisa berdiri sendiri di luar ‘ada’. Segala sesuatu harus ‘ada’ maka kemudian bisa dikatakan ia nyata, realitas, atau sejati. ‘Ada’ ialah satu yang tidak memiliki komponen, sehingga tidak bisa dibedah, dipisah. Ia lengkap dan utuh.
‘Ada’ itu sepadan dengan ‘Tuhan’. Kedua konsep itu tidak merujuk kepada dua hal yang berbeda. Melainkan mereka merujuk kepada satu realitas yang sama. ‘Ada’ itu, esa, tidak bersekutu. Demikian pula Tuhan. ‘Ada’ itu melampaui dan meliputi segalanya, begitu pula ‘Tuhan’.
Lantas seseorang mungkin bertanya: bukankah saya, kamu, mereka juga ‘ada’? Apa beda itu semua dengan Tuhan? ‘Ada’nya kita ialah ada yang bersyarat, yang membutuhkan prakondisi sebelum diaktualisasi.
Artinya, kita ialah ‘ada’ yang miskin, lemah, tidak berdaya dan membutuhkan kepada yang lain. Hal itu tidak sama dengan Tuhan. Dialah ‘ada’ itu sendiri. Dia tidak membutuhkan syarat, bantuan, dan tidak memiliki permulaan (telah, sedang dan selalu ada) serta tidak pula akan berakhir (mustahil mati atau musnah).
Sampailah kita kepada kesimpulan: Tuhanlah ‘ada’ sejati dan pada Tuhanlah kita akan mendapat bahagia yang hakiki. Mengenali mana Tuhan yang sejati adalah penting, namun mengenali mana yang hakiki antara ‘ada’ dan ‘apa’ bisa jadi lebih penting. Sebab, dengan memahaminya kita bisa lebih dekat kepada ‘ada’ yang sempurna atau Tuhan itu sendiri.
Editor: Soleh