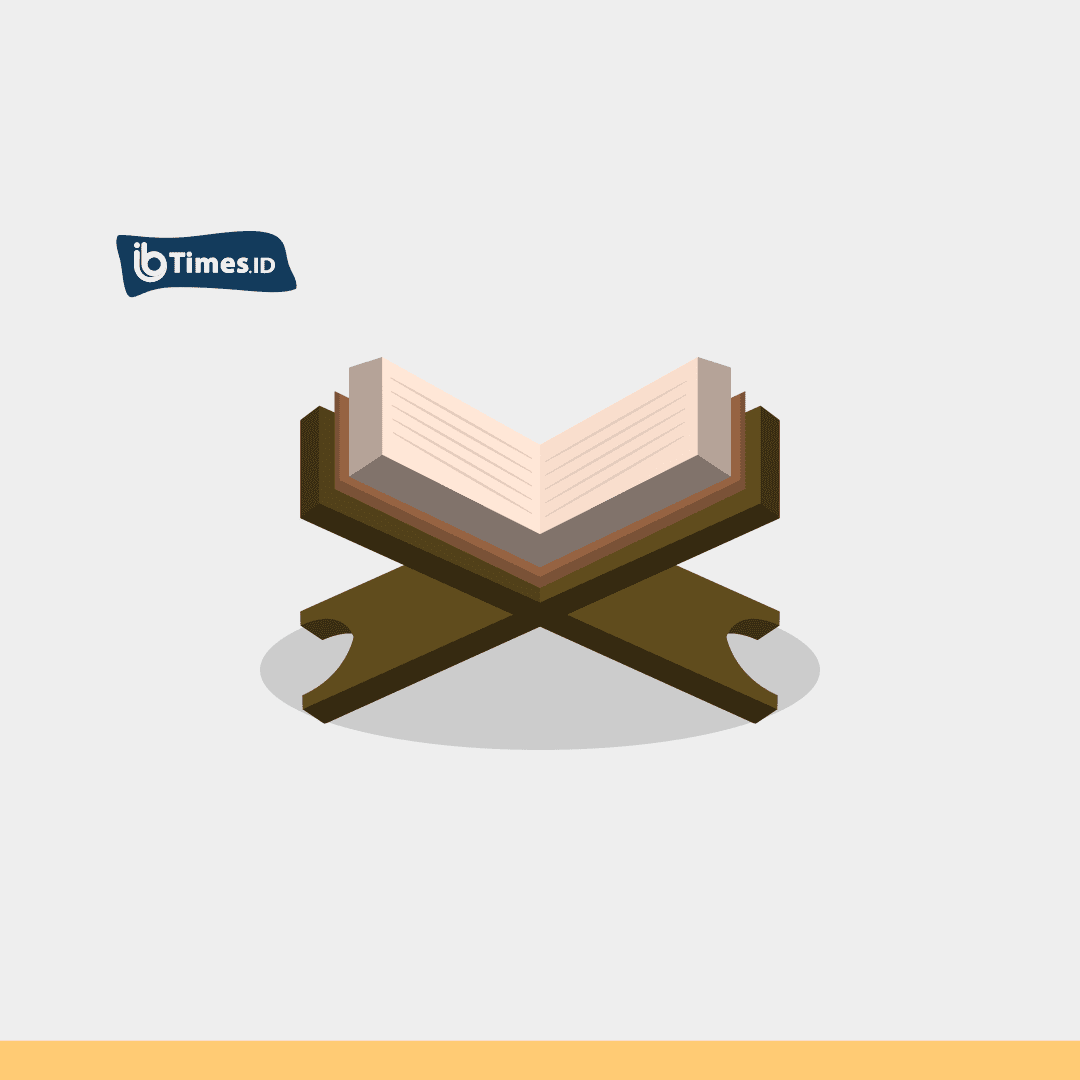Sebagai paradigma, Al-Quran menawarkan berbagai pilihan rasional terhadap manusia sekaligus memberikan hak otonom baginya untuk memilah dan memilih opsi terbaik sesuai kapasitas dirinya, baik sebagai hamba Tuhan maupun makhluk sosial. Al-Quran sebagai paradigma merupakan landasan tradisi keilmuan Islam, sebab Al-Quran inheren dan berdialektika kepada para pembacanya. Namun, dalam beberapa aspek, akhir-akhir ini cara pandang umat Islam terhadap Al-Quran mengalami pergeseran yang amat serius. Pergeseran pemahaman ini menyangkut persoalan bagaimana umat Islam membaca, menginternalisasi, dan mengobjektivikasi teks Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
Al-Quran sebagai Teks
Dalam lintasan sejarah Islam yang diselimuti kabut ortodoksi, begitu Mun’im Sirry menyebutnya, problem teks dan maknanya bukan hanya kabur, melainkan juga menciptakan otoritas teks yang cenderung represif. Teks dipersepsikan begitu otoriter sehingga muncul postulat “tidak ada ijtihad tanpa teks” (la ijtihada ma’a al-nash). Otoritas teks ini, dalam perjalanannya, begitu hegemonik sehingga menguasai alam kesadaran kolektif umat Islam.
Mengarifi persoalan tersebut, Nasr Hamid Abu Zaid membuat distingsi antara teks metafisikal dan teks fisikal. Menurutnya, keadaan teks suci yang orisinal bersifat metafisikal sehingga tidak bisa kita pahami kecuali melalui apa yang dikatakan teks fisikal yang sampai kepada kita melalui dimensi kemanusiaan yang secara historis terus berubah. Atas dasar itulah, Fazlur Rahman, misalnya, mengkritik keras dictation theory yang menyatakan bahwa peran Nabi tidak lebih hanya sebagai penerima pesan (receiver of the message) dan mentransmisikan pesan ilahi kepada manusia.
Dalam teori ini, Nabi Saw dipersepsikan laksana audio recording. Padahal bagi Rahman, konteks pewahyuan Al-Quran merupakan proses yang sangat kompleks, ia harus dibaca secara diakronis, historis, dan sosio-antropologis. Hal senada juga dilontarkan Abu Zaid, tatkala teks Al-Quran yang metafisik diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ia mulai memasuki ruang sejarah dan tunduk pada aturan main sejarah dan sosiologis.
Rahman ingin menunjukkan psikologi kreatif nalar kenabian dalam pewahyuan. Menurutnya, sumber dan asal proses kreatif tersebut adalah human agency (agensi kemanusiaan yang diperankan oleh Nabi. Simplifikasinya, Nabi mendapat inspirasi dari Tuhan, namun alam/ dunia Nabi berikut komunitasnya diperbolehkan untuk membentuk secara dominan produk linguistik yang dihasilkan. Implikasinya, peristiwa yang dialami Nabi dan komunitasnya terefleksikan dalam Al-Quran.
***
Untuk mempermudah memahami hal ini, Rahman yang dikutip Abid Rohmanu, membuat ilustrasi tentang poligami. Poligami, dalam Al-Quran, sesungguhnya mengangkat hak, martabat, dan status perempuan yang sebelumnya disubordinasi oleh budaya Arab. Ini salah satunya direpresentasikan perintah teks, “seharusnya laki-laki tidak menikahi lebih dari seorang perempuan jika tak mampu berbuat adil”. Teks Al-Quran juga menyatakan “mustahil” kiranya bagi kaum laki-laki mampu melakukannya. Pada sisi yang lain, teks juga diyakini memberikan izin untuk berpoligami.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana memahami dua perintah ini? Cara menyelesaikan ini menurut Rahman adalah dengan menyadari bahwa al-Qur’an mempromosikan kebahagiaan yang maksimum bagi keluarga. Perkawinan monogami adalah yang ideal untuk merealisasikannya. Tetapi tujuan moral ini menurut Rahman harus dikompromikan dengan tradisi dan budaya masyarakat Arab kala itu.
Karena itu, Al-Qur’an menerima tradisi poligami pada level hukum, tetapi membatasinya dan menjadikannya sebagai pilihan darurat. Pada saat yang bersamaan, Al-Qur’an mempromosikan idealitas perkawinan monogami, sebuah tradisi perkawinan baru yang diorientasikan Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Al-Quran bukan kitab hukum, yang dapat secara langsung dioperasionalkan dalam tataran praktis. Perlu dibedakan antara aspek idealitas dan kontingensi Al-Quran.
Moderasi Beragama: Dari Sentripetal ke Sentrifugal
Dalam realitas keindonesiaan, persoalan membumikan teks ini juga riuh sekali. Ada yang terlalu tekstual maupun kontekstual. Dua kutub ini terjadi diakibatkan karena memiliki cara pandang berbeda dalam membaca dan memahami teks Quran. Padahal, jika kita cermati, sesungguhnya kontradiksi antara teks asli (Al-Quran) dan teks-teks lain yang dibangun di atasnya sangatlah kompleks. Namun, kesadaran kolektif umat, menurut Sirry, telah tergiring sedemikian rupa oleh klaim otoritas teks sehingga banyak keyakinan umat Islam begitu menyejarah, kendati sebenarnya tidak memiliki landasan kuat dalam teks asli.
Sebagai contoh, selama ini umat Islam Indonesia menggaungkan istilah “moderasi beragama”, yang lambat laun “kehilangan tujuan organiknya” dan cenderung bergerak pada kelompok-kelompok itu saja (baca: NU, Muhammadiyah, misalnya). Padahal semestinya, ia bergerak menyasar di luar kelompok moderat atau kelompok radikal. Dari sini saja, kita dapat memahami bahwa selama ini konsep moderatisme Islam (baca: moderasi beragama) berkembang – meminjam istilah Masdar Hilmy – secara sentripetal.
Artinya, moderasi beragama sebagai sebuah gerakan dan paradigma yang ditargetkan Kementerian Agama dalam hal ini untuk “melunakkan” cara keberagamaan yang radikal, belum efektif. Sebab, pada akhirnya, konsep moderasi beragama pada akhirnya tetap ditentukan oleh cara umat Islam dan umat beragama lain dalam mendekati dan memahami teks suci (baca: Al-Quran dan hadits, Al-Kitab, misalnya).
Patut dicatat, bahwa baik umat Islam radikal maupun moderat sama-sama memperlakukan teks suci pada posisi tertinggi sebagai landasan normatif guna mengembangkan dan memformulasikan cara keberagamaan yang otentik. Namun, istilah “dasar normatif” dapat memiliki arti yang berbeda berdasar konteks yang melatarinya. Dalam konteks inilah, tingkat moderatisme itu dipertaruhkan.
Dari sekelumit contoh tersebut, dapat dikatakan bahwa konsep moderatisme Islam di Indonesia berkembang secara sentripetal. Kini sudah saatnya konsep tersebut harus dikembangkan secara sentrifugal guna memaksimalkan sumber internal Islam sebagai acuan pertama dalam menghasilkan cetak biru (blue print) moderatisme Islam.
***
Dalam konteks inilah apa yang disebut oleh Fazlur Rahman sebagai pendekatan “gerakan ganda” (double movement) patut dijadikan rujukan melalui dialektika diakronik (baca: bolak-balik) dalam rangka merekonsiliasi dan mendialektika antara teks dan konteks dalam spektrum pemikiran Islam. Jika modus pertama mengandalkan fleksibilitas Islam sebagai pihak luar untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lokal negara, maka modus kedua mengandalkan Islam sebagai modalitas internal guna mengembangkan cetak biru moderatisme Islam yang lebih mapan guna menarik relevansinya dengan kondisi lokal Indonesia.
Sebagaimana agama-agama lain, Islam sesungguhnya melintasi tiga episode; 1) episode teologis dan metafisis, 2) episode manusia agung (Nabi dan para sahabat), 3) episode manusia biasa. Episode pertama terpisah dari alam, disusul episode berbentuk teks-teks Al-Quran yang menghubungkan antara Tuhan dan manusia melalui perantara manusia agung (Nabi) dan episode Islam dalam tataran manusia biasa.
Dengan metode ini, sesungguhnya kita bisa memahami mengapa Islam tidak monolitik, dan justru kosmopolit? Karena ia menyerap nilai-nilai historis dan norma-norma kultural di mana ia tumbuh dan berkembang. Tidak berlebihan kiranya jika Islam dipandang sebagai sebuah agama yang sempurna, sebuah agama yang mengedepankan etika kemanusiaan dan menyempurnakan syariat agama terdahulu. Atas dasar itu pula, kita dapat mengatakan sekaligus memahami betapa – dalam bahasa Sirry – naifnya argumen kalangan Muslim ortodoks yang memosisikan Islam sebagai “daftar” kepercayaan yang beku, jumud, stagnan dan terpisah dari ruang historis, antropologis, dan sosiologis.
Al-Quran sebagai Paradigma
Al-Quran, bagi Kuntowijoyo, adalah paradigma. Paradigma yang dimaksud dalam konteks ini ialah sebagaimana yang dipahami oleh Thomas Kuhn, bahwa realitas sosial dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu yang pada gilirannya akan menghasilkan mode of knowing tertentu pula. Dengan mengikuti pengertian ini, paradigma Al-Quran bagi Kunto adalah konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas sebagaimana dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri.
Ini artinya, Al-Quran “mengkonstruksi” pengetahuan yang memberikan dasar bagi kita untuk bertindak, bersikap, dan berperilaku. Kontruksi ini memungkinkan untuk mendesain sistem, tak terkecuali sistem ilmu pengetahuan. Dengan demikian, di samping memberikan gambaran aksiologis, paradigma Al-Quran juga berfungsi memberikan wawasan epistemologis. Tidak berlebihan kiranya, jika Al-Quran ingin “meruangkan” dirinya ke dalam tataran pembaca (manusia) agar tidak berhenti pada tataran doktrinal, melainkan operasional-praktikal. Dalam konteks inilah, menjadikan Al-Quran sebagai paradigma menjadi penting dan diarusutamakan kembali agar umat Islam senantiasa dipandu dalam mengembangkan peradaban yang islami-ihsani.
Editor: Soleh