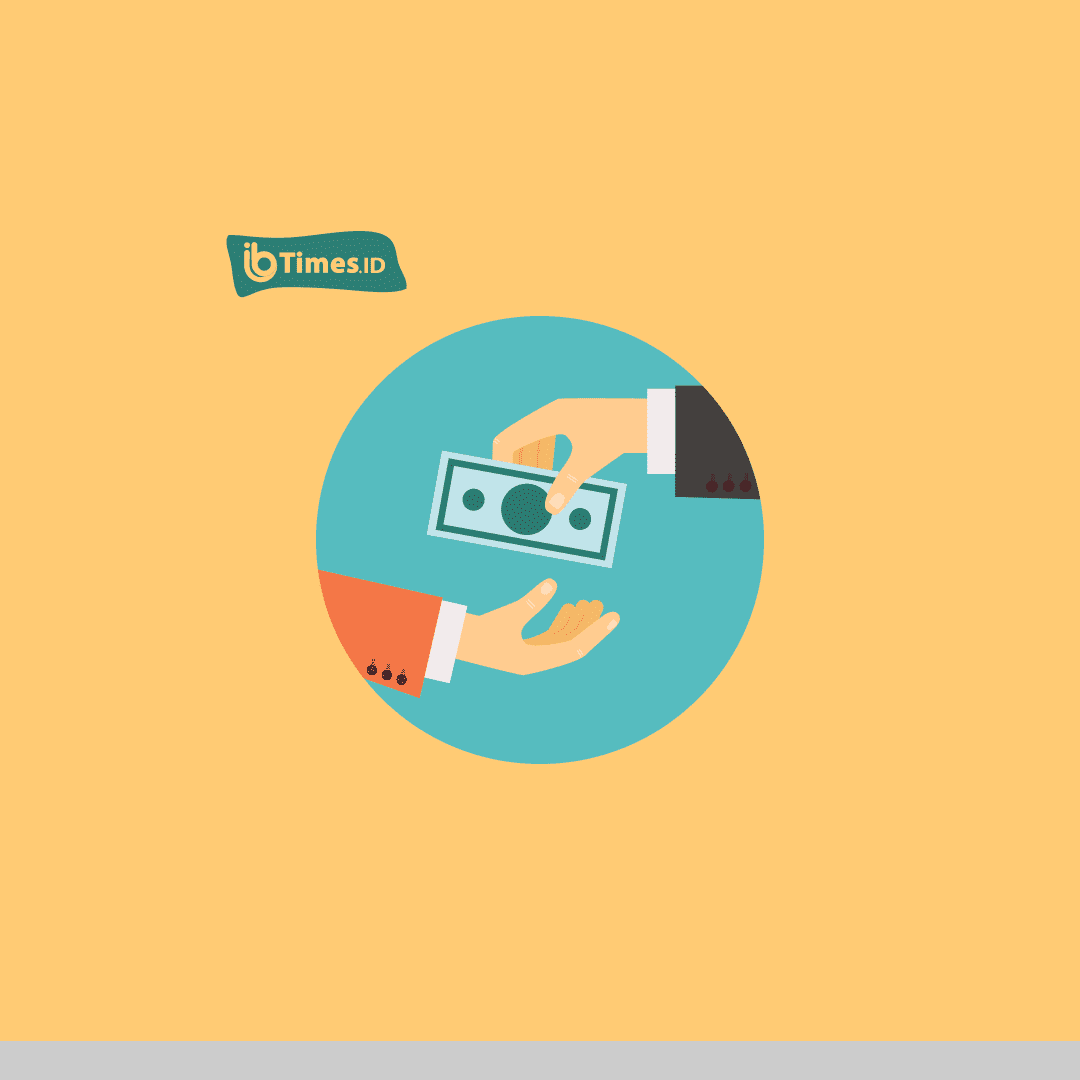Di negeri yang disebut-sebut sebagai Zamrud Khatulistiwa, tempat tanah menjanjikan emas dan rempah, hiduplah Mukidi. Tanahnya memang gemah ripah loh jinawi, tapi perutnya kerap kali hanya gemah ripah oleh angin. Mukidi adalah pemulung, seorang ‘pahlawan kebersihan’ dalam lelucon getir para netizen yang tak pernah ia baca. Istrinya, Sarminah, adalah buruh serabutan, melompat dari satu cucian ke cucian lain, dari satu kebun ke kebun lainnya, dengan upah yang tak pernah cukup untuk melompati garis kemiskinan. Ketiga anaknya, si sulung Bagong, kemudian Joko, dan si bungsu Ngatini, telah lama berhenti sekolah. Sekolah Dasar saja sudah merupakan kemewahan. Kini, mereka menggelinding seperti bola liar, terseret dalam pusaran remaja nakal yang kadang berujung pada aksi-aksi kriminal kecil, sebuah protes primitif terhadap dunia yang telah menelantarkan mereka.
Kondisi Mukidi adalah sebuah lukisan pilu yang terpajang di galeri negeri yang katanya makmur ini. Dan penyebab keadaannya itu sederhana saja: rumahnya telah dijarah. Bukan dijarah oleh maling biasa yang mendobrak pintu di tengah malam, membawa celurit, dan mengambil televisi tua atau tabungan receh. Penjarahan atas rumah Mukidi jauh lebih brutal, lebih sistematis, dan yang paling menyakitkan, dilakukan dengan tampak begitu sopan dan legal.
Para koruptor itulah penjarahnya. Mereka datang dengan setelan jas rapi, duduk di balik meja mahoni, dan menandatangani dokumen-dokumen yang dengan lunak dan elegan menggelontorkan uang rakyat ke dalam rekening-rekening pribadi. Setiap tanda tangan itu adalah sebuah lembaran uang yang seharusnya menjadi tiang penyangga rumah Mukidi. Mereka menjarah dengan senyum, bukan dengan todongan senjata.
Mereka telah menjarah akses kesehatan Mukidi. Uang yang seharusnya membayar BPJS, memberikan Mukidi hak untuk batuk tanpa takut mati, telah raib. Ketika Sarminah demam tinggi, satu-satunya dokter adalah warung yang menjual paracetamol gadungan. Rumah sakit hanyalah sebuah gedung megah yang ia lihat dari jauh, sebuah istana yang pintunya dikunci oleh para penjarah itu.
Mereka telah menjarah akses pendidikan anak-anaknya. Uang yang seharusnya menjadi SPP, membeli seragam, dan buku, telah lenyap dalam proyek fiktif dan markup anggaran. Bagong, Joko, dan Ngatini adalah generasi yang terampas masa depannya. Sekolah bagi mereka adalah kenangan pahit dan sebuah cita-cita yang terlalu mahal. Kini, mereka hanya bisa belajar dari kerasnya jalanan.
Mereka telah menjarah akses ekonominya hingga nyaris sempurna. Harga-harga melambung karena korupsi menggerogoti subsidi dan mendistorsi pasar. Upahnya sebagai pemulung dan istrinya sebagai buruh tak lagi cukup untuk sekadar menapaki anak tangga paling bawah dari piramida kebutuhan. Makan sekali sehari sudah seperti pesta. Selebihnya, perut diakali dengan air putih dan tidur. Penjarahan itu begitu total, begitu brutal, hingga yang tersisa dari Mukidi hanyalah kentutnya.
Ya, kentutnya. Itulah satu-satunya ‘kekayaan’ yang berhasil ia pertahankan dari para penjarah. Suara kentutnya nyaring, menggema di dalam gubuk reyengnya, kadang mengejutkan tetangga. Mereka menertawakannya, membullynya, mengolok-olok si miskin yang kentutnya saja berisik. Mereka tak paham, bahwa nyaringnya suara itu adalah jerit diam dari sebuah perut yang lebih sering diisi angin ketimbang nasi. Itu adalah musik protes dari usus-usus yang keroncongan, satu-satunya ‘bahasa’ yang bisa diucapkan tubuhnya untuk melawan.
Ironinya, para tetangga itu tidak pernah prihatin dengan penjarahan brutal yang terjadi setiap hari di rumah Mukidi. Mereka tidak melihat sistemiknya kejahatan yang membuat Mukidi tersedu. Mata mereka tertuju pada layar gawai, terpana oleh berita viral: rumah Tuan Takur, seorang miliader konglomerat, baru saja dirampok!
Media massa menyiarkannya berhari-hari dengan dramatis. Tuan Takur tampil di televisi dengan wajah sedih, bercerita tentang rasa traumanya. Harta yang hilang, katanya, mencapai miliaran rupiah. Para tetangga berdecak kagum, lalu bersimpati mendalam. “Kasihan sekali Tuan Takur,” ujar mereka. “Hatinya pasti sangat sedih.”
Tak seorang pun yang berpikir kritis. Harta yang hilang dari Tuan Takur itu mungkin tidak lebih dari 2% dari total kekayaannya. Ia tetap kaya raya, tetap bisa makan steak impor tiga kali sehari, dan anak-anaknya tetap bersekolah di luar negeri. Yang lebih mendasar: dari mana sebenarnya harta Tuan Takur yang sebanyak itu? Profesinya tidak jelas, bisnisnya tidak jelas, tetapi kekayaannya melimpah ruah, seolah-olah uang itu jatuh dari langit. Ada yang berbisik, ia dekat dengan kekuasaan, dapat proyek-proyek tender, dan mungkin juga adalah bagian dari para penjarah itu sendiri. Tapi bisikan itu tenggelam dalam euforia belas kasihan yang diproduksi oleh media.
Mereka memuja Tuan Takur yang korup, sambil menertawakan Mukidi yang menjadi korban. Mereka lebih empati pada seorang konglomerat yang kehilangan sebagian kecil harta yang bahkan mungkin haram, daripada pada seorang pemulung yang kehilangan seluruh masa depannya yang sah.
Inilah potret negeri yang sakit. Negeri yang terbuai oleh narasi-narasi viral yang manis dan dramatis, tetapi buta terhadap kejahatan struktural yang terjadi dalam sunyi. Negeri di mana orang lebih mudah meneteskan air mata untuk seorang penjarah yang kecurian, daripada untuk seorang Mukidi yang dijarah hingga ke tulang-tulang rusuknya.
Mukidi hanya bisa duduk di depan gubuknya, memandang langit yang sama yang dipandang oleh Tuan Takur dari balkon rumah mewahnya. Di langit itu, ada janji kemakmuran yang digaungkan sejak ia kecil. Tapi baginya, langit hanyalah atap besar tempat ia melontarkan suara kentutnya yang nyaring, sebagai satu-satunya bentuk perlawanan yang ia kuasai.
Para koruptor itu terus menjarah. Mereka tak hanya menjarah uang di kas negara, tetapi juga menjarah hak hidup warga miskin. Data berbicara: setiap tahun, negara ini kehilangan puluhan triliun rupiah akibat korupsi. Jumlah yang sangat brutal. Dengan uang sebanyak itu, setiap keluarga miskin seperti keluarga Mukidi bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak, anak-anak mereka bisa bersekolah hingga ke perguruan tinggi, dan mereka bisa makan tiga kali sehari dengan gizi yang cukup. Penjarahan itu bukanlah angka statistik belaka; itu adalah beras yang hilang dari piring Mukidi, itu adalah obat yang tak pernah sampai ke tangan Sarminah, itu adalah masa depan yang dipendam untuk anak-anak Bagong, Joko, dan Ngatini.
Namun, teriakan Mukidi hanya terdengar sebagai kentut bagi telinga dunia. Dan dunia lebih memilih untuk mendengar tangis dramatis Tuan Takur yang kehilangan permata. Sampai kapan kita akan terus tertidur dalam buaian narasi yang salah? Sampai kapan kita akan lebih prihatin pada pencurian yang kasat mata, tetapi abai pada perampokan massal yang dilakukan secara sistematis, elegan, dan brutal terhadap rumah-rumah orang papa seperti Mukidi?
Rumah Mukidi masih terus dijarah. Dan mungkin, tanpa kita sadari, kita semua adalah tetangga yang hanya bisa terpana pada layar, sambil menertawakan suara kentut yang sebenarnya adalah jerit kematian yang paling menyedihkan.
Editor: Soleh