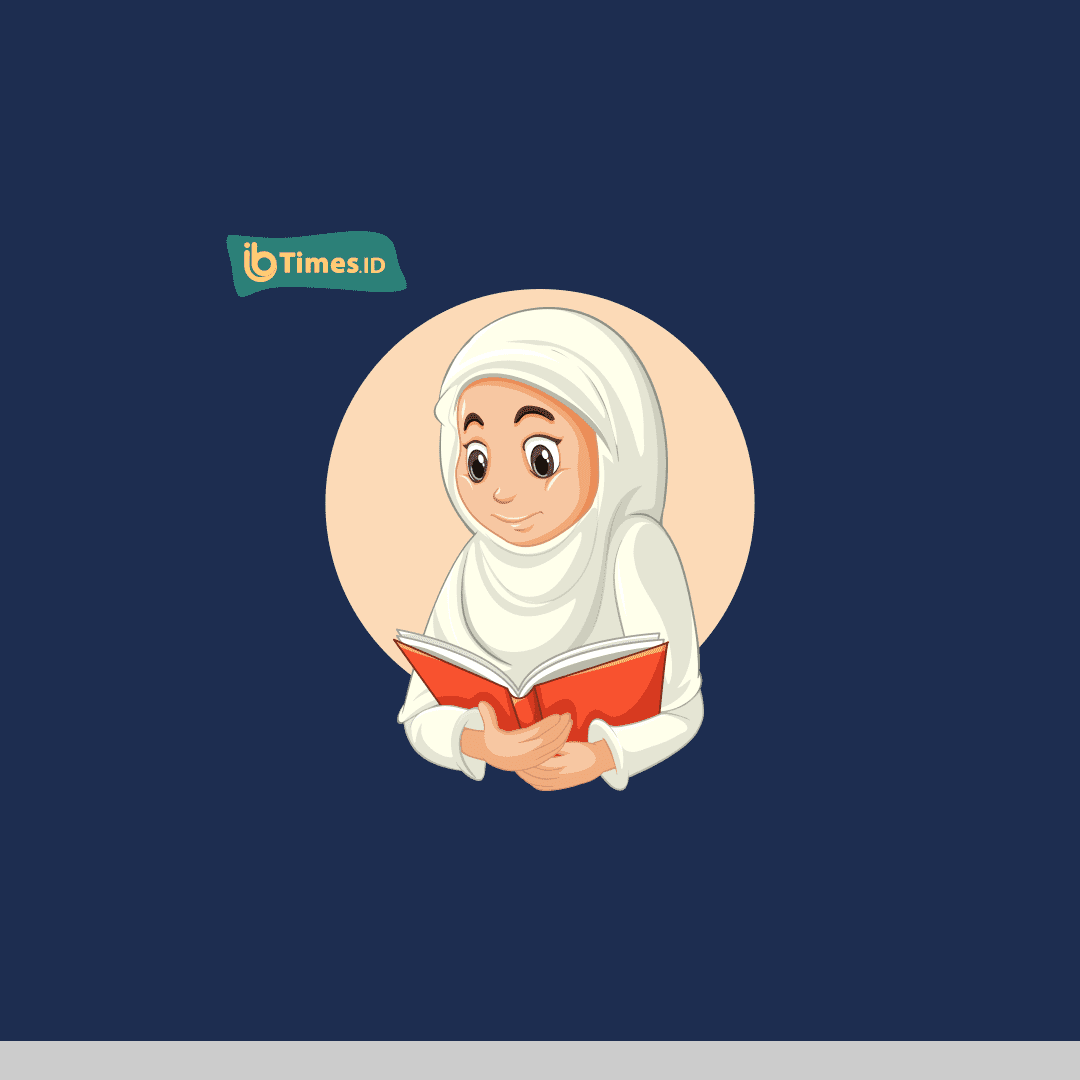Akhir bulan Desember tahun ini memberikan pertanda kepada saya, jika saya sudah menjadi bagian dari manusia Madura selama 20 tahun. Waktu yang bisa dibilang cukup lama dalam mengarungi kehidupan. Selama itu juga, saya menyadari jika darah Madura yang mengalir dalam tubuh saya, tidak bisa dihilangkan meski suatu saat nanti saya harus pergi merantau ke luar Madura.
Bagi saya, menjadi bagian dari manusia Madura merupakan hal yang menyenangkan. Saya bersyukur hidup di daerah dengan karakter masyarakatnya yang masih mau menjaga tradisinya sampai sekarang. Meski kehidupan sudah memasuki era modern, akan tetapi, masih banyak tradisi Madura yang dipertahankan oleh masyarakatnya, misalnya karapan sapi, arebbe, dan sape sonok. Sehingga, ketiga tradisi itu masih mudah untuk dijumpai.
Kebudayaan dan Ketertindasan Perempuan Madura
Bukan hanya itu, kebanggaan saya menjadi manusia Madura disebabkan oleh masyarakatnya yang masih menjalankan nilai-nilai luhur. Nilai luhur masyarakat Madura lebih diarahkan kepada tata krama dalam kehidupan, yang diwujudkan dengan nilai sopan santun kepada orang yang dihormati. Bahkan, nilai luhur masyarakat Madura juga menyentuh perihal ketakwaan kepada Tuhan. Bentuk perwujudannya dengan menjalankan ibadah keagamaan.
Namun, meski saya merasa bangga menjadi manusia Madura. Akan tetapi, terselip keresahan sekaligus kesedihan saya kepada perempuan Madura. Sebab, di balik konstruksi perempuan Madura yang dinilai pekerja keras, tahan banting, dan ulet, ternyata perempuan Madura dalam kehidupannya mengalami ketertindasan.
Ketertindasan perempuan Madura dikarenakan oleh kehidupannya yang selalu mengalami keterasingan. Wujud ketertindasan perempuan Madura dapat terlihat dalam dua bentuk, yakni “tubuh” dan “posisi”.
Ketertindasan dalam bentuk tubuh, dapat dilihat dalam komersialisasi tubuh perempuan Madura dalam aspek ekonomi. Sebagaimana dapat ditemukan dalam penjualan jamu rapet Madura. Dalam proses pemasaran jamu rapet Madura, produsen jamu selalu menggunakan simbol perempuan Madura untuk mempermudah dalam mendapatkan pembeli.
Penggunaan simbol perempuan Madura dalam pemasaran jamu rapet Madura, disebabkan oleh adanya konstruksi mengenai keunggulan seks perempuan Madura. Terutama yang berkaitan dengan alat kewanitaannya. Maka, tidak mengherankan jika gambar perempuan Madura banyak terpampang di kemasan jamu rapet Madura.
Maka tanpa disadari, tubuh perempuan Madura sudah mengalami proses eksploitasi, karena sudah digunakan sebagai komoditas ekonomi. Artinya, perempuan Madura tidak sepenuhnya memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri. Padahal, jika dilihat dalam nilai keagamaan, tubuh merupakan ciptaan dari Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dirawat dan difungsikan oleh pemiliknya.
Subordinasi Perempuan Madura
Bentuk ketertindasan perempuan Madura selanjutnya, yakni posisinya yang mengalami subordinasi. Soalnya, masyarakat Madura masih mempercayai kepada nilai pengetahuan, yang memandang laki-laki memiliki cara berpikir dengan rasional dan perempuan cara berpikirnya hanya mengikuti perasaan. Sehingga, dengan adanya cara pandang tersebut, berdampak kepada kehidupan perempuan Madura dalam aspek politik dan aspek keluarga.
Dalam aspek politik, bisa dilihat dari minimnya jumlah perempuan Madura yang terlibat aktif dalam dunia perpolitikan. Pada tingkat DPRD, kehadiran anggota perempuan masih jauh dari persentase minimal yang diatur dalam undang-undang, yakni 30%, karena mayoritas anggota DPRD diisi oleh laki-laki. Begitu juga dalam tingkat bupati dan calon bupati yang ada di 4 Kabupaten Madura, masih didominasi oleh laki-laki.
Kemudian, dalam aspek keluarga, laki-laki memiliki kuasa kepada istrinya dan kuasa kepada anak perempuannya. Dalam kuasa kepada istri, seorang laki-laki yang menjadi suami, selalu mendominasi dalam membuat keputusan. Dan, keputusan yang sudah dibuat, harus diikuti oleh istri. Soalnya, perempuan Madura sudah terinternalisasi dengan kalimat, “Patorok ocak ka dhabune reng lakek”. Artinya, harus patuh kepada perintahnya laki-laki.
Begitu juga kuasa laki-laki kepada anak perempuannya sebagai seorang ayah, terlihat mendominasi dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Tidak jarang keputusan yang dibuat adalah tidak menyekolahkan anak perempuannya terlalu tinggi, karena jika sudah menikah, tugasnya hanya melayani keluarga di rumah. Dengan begitu, pendidikan tidak akan memiliki arti penting bagi perempuan Madura.
Adanya ketertindasan posisi perempuan Madura pada aspek politik dan keluarga, memberikan gambaran jika masyarakat Madura masih berpegang teguh dengan nilai patriarki. Akibatnya, suara perempuan akan dianggap tidak penting dalam membuat sebuah keputusan.
Saya jadi teringat dengan salah satu konsep pemikiran dari Karl Marx, jika kepribadian manusia sudah terbentuk dari pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan gender, kasta dan kelas. Maka, tidak mengherankan jika perempuan Madura mengalami kondisi yang didiskreditkan, karena perempuan Madura adalah bagian dari masyarakat pasca kolonial, yang selalu dipandang sebelah mata.
Yang menjadi pertanyaan dilematik adalah bisakah perempuan Madura keluar dari ketertindasannya? Dan, bagaimana cara yang bisa digunakan agar perempuan Madura keluar dari ketertindasannya?