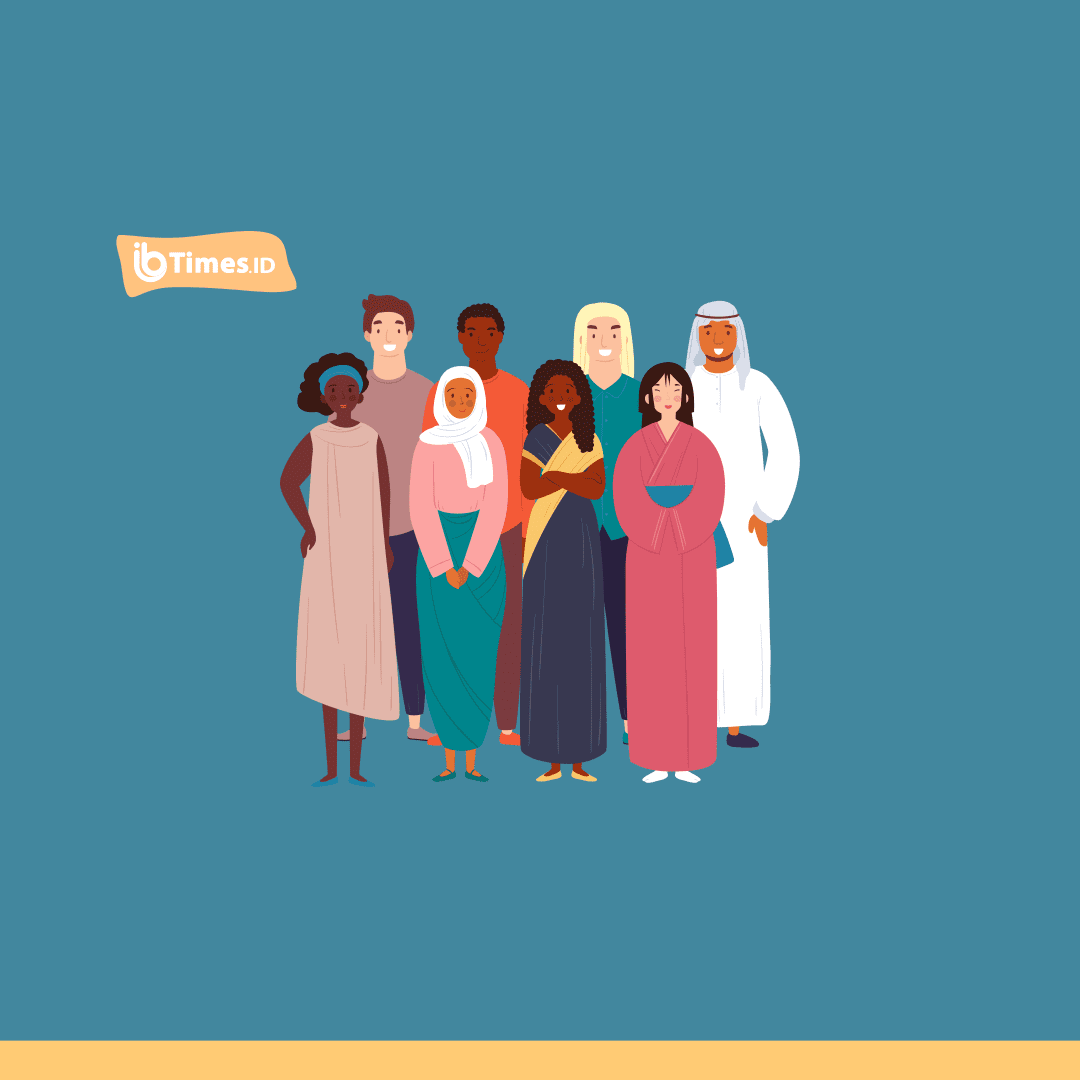Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim yang terbilang sangat tinggi. Bahkan, Islam merupakan agama dengan persentase pemeluk terbesar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data sensus penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang di mana pada tahun 2010 saja, Indonesia memiliki penduduk muslim dengan persentase di angka 87,2% dari total jumlah penduduk atau dalam angka absolut mencapai hingga 207,2 juta jiwa.
Jika tingkat pengaruh dalam suatu negara ditentukan berdasarkan jumlah massa, maka tidak diragukan lagi bahwa Islam adalah agama paling berpengaruh, sekaligus menjadi penentu dalam segala hal di Indonesia.
Namun, jika Islam memang berharap demikian, maka harapan tersebut harus segera diredam. Sebab, Indonesia telah memilih jalannya bukan sebagai negara Islam, melainkan sebagai negara republic. Di mana, terdiri dari unsur masyarakat yang heterogen dalam budaya termasuk dalam agama.
Indonesia pula mengusung konsep welfare state (negara kesejahteraan) yang juga ditegaskan dalam Preambule (Pembukaan) UUD 1945 yang menyatakan bahwa keadilan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, menjadi hal yang mustahil bahwa Islam dapat menjadi raja atas segala hal di Indonesia.
Namun, Islam tentu dapat tetap memberi kontribusi nyata bagi keberlangsungan bangsa dan negara bersama-sama dengan pemeluk agama lainnya, tanpa terkecuali. Kontribusi itu dapat diberikan melalui konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal tersebut cukup jelas menggambarkan bagaimana cita luhur bersatu dalam keragaman benar-benar dijadikan sebagai pondasi berdirinya sebuah negara.
Cita tersebut pun tidak semata berjalan mulus begitu saja. Terdapat banyak halang rintang yang terus mengganggu berbagai upaya untuk mewujudkan cita bersama. Persoalan tersebut seringkali muncul dalam bingkai toleransi, pencarian pembenaran politik melalui dalil-dalil agama, serta berbagai macam seruan tentang radikalisme dan upaya merong-rong NKRI.
Tuduhan-tuduhan tersebut seringkali tidak berdasar. Hanya dibangun atas kecemburuan sosial antar umat beragama, bahkan antar golongan dalam satu agama. Tampaknya, kita tidak benar-benar serius dalam menerjemahkan relevansi dari ultimate values (nilai tertinggi) dalam ajaran-ajaran agama.
***
Dalam konsep negara demokrasi, sejatinya tidak menyaratkan keyakinan atas konsep ketuhanan. Namun, Indonesia sebagai negara yang sedari awal telah berkomitmen terkait ketuhanan yang maha esa, maka agama menjadi salah satu instrumen penting yang menentukan berhasil atau tidaknya tata kelola Indonesia.
Dengan demikian, indeks demokrasi Indonesia pun memiliki keunikan tersendiri dengan agama menjadi salah satu parameter di dalamnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks demokrasi Indonesia dengan indikator “ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama” pada tahun 2019 menyentuh angka 87,79%. Artinya, masih terdapat banyak hal yang harus dibenahi dari satu aspek antropologi Indonesia, dalam hal ini agama.
Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal, dan yang paling menyumbang banyak persoalan adalah kerukunan antar umat beragama. Bukan hanya itu, pemerintah pun terkesan terlalu jauh melakukan represif dengan alat-alat negara untuk menertibkan kekacauan ini. Kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah adalah membenturkan dasar negara (Pancasila) dengan agama serta ideologi-ideologi yang bermunculan di tengah masyarakat.
Pembenturan Pancasila Secara Membabi Buta
Alasan bagi Indonesia untuk memasukkan sila “ketuhanan yang maha esa” dalam rumusan formal dasar negara di samping mencerminkan jiwa bangsa, juga didasarkan atas ultimate values (nilai tertinggi) yang terkandung dalam ajaran-ajaran agama.
Pancasila membutuhkan agama untuk memperoleh rumusan moral dan etika, yang dalam konsep keagamaan dikenal dengan kesolehan sosial. Hal tersebut mengindikasikan bahwa negara belum mampu merumuskan atau setidaknya memiliki pedoman tersendiri untuk merumuskan pengaturan-pengaturan terkait perilaku serta tindak-tanduk warga negara dalam konsep baik-buruk dan benar-salah.
Hubungan demikian adalah hubungan yang kekal. Sebab, negara tentu akan terus memerlukan konsep moral dan etika untuk menciptakan ketertiban dan kerukunan dalam hidub berbangsa dan bernegara.
Tidak akan ada masa di mana suatu negara tidak lagi memerlukan kedua hal tersebut. Jika benar masa itu tiba, maka masa tersebut akan menjadi masa kembalinya umat manusia pada zaman kegelapan. Tidak ada lagi konsep memanusiakan manusia.
Maka, akan semakin mengafirmasi pula pernyataan Plautus tentang manusia dalam bukunya yang berjudul Asinaria sebagai “homo homini lupus” dengan makna yang menempatkan manusia sebagai serigala bagi manusia lainnya.
Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara, selama ini terkesan terlalu dipergunakan secara membabi buta. Berangkat dari Pancasila lah lahir UU Ormas, berangkat dari Pancasila Ahmadiyah dilarang, berangkat dari Pancasila pula segala hal yang berkaitan dengan FPI dilarang, bahkan sebelum kasus penembakan yang melibatkan enam anggotanya sebagai korban belum selesai.
Sehingga menjadi paradoks tujuan awal dilibatkannya ketuhanan dalam dasar negara untuk memformulasi moral dan etika, namun tak pernah mampu memberi penerangan terkait hal tersebut.
Sebagai dasar negara, Pancasila semestinya menjadi bintang penerang, bukan malah menjadi meteor penghantam. Namun fakta menunjukkan bahwa telah banyak entitas yang dihantam oleh meteor Pancasila tersebut.
Beban Moral Islam Sebagai Mayority Entity
Sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia, memberikan beban moral tersendiri bagi Islam dan pemeluknya. Tentu pelimpahan beban ini tidak ada unsur diskriminatif dan telah benar-benar secara proporsional memilih pundak untuk bersandar.
Islam sebagai agama yang memiliki goals “rahmatan lil’alamin”, maka memang benar-benar tepat untuk menjadi suri tauladan sekaligus juru narasi perdamaian dan kerukunan antar warga negara di Indonesia. Hal ini jangan pula diartikan sebagai amanah untuk mendirikan negara Islam.
Solusi atas persoalan Indonesia tidak se-sederhana menyerukan Khilafah. Jangan melulu dilihat dari segi sistem. Sebab, sebaik apa pun sistem, akan tetap bermuara juga pada kemerosotan indeks apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik dari para stake holder. Komitmen memang sangat diperlukan, terlebih dalam hal integritas. Jika kita seringkali berseru terkait integritas pejabat, maka kali ini kita mesti berseru pada diri kita sendiri terkait integritas beragama.
Sekularisme dan Pembaharuan Islam
Pembaharuan Islam seringkali terhambat oleh anggapan-anggapan sekularisme. Jelas bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Hanya sebatas upaya dekonstruksi konservatisme yang selalu melihat pembaharuan sebagai suatu gerbang lunturnya nilai-nilai Islam.
Sebenarnya, jika orang-orang yang berupaya mendekonstruksi tersebut telah melihat secara utuh bagaimana sebuah roadmap pembaharuan dibangun, maka ia akan menemukan sebuah jalan terang bagi persoalan-persoalan selama ini.
Secara sederhana, pembaharuan tidak berarti menghilangkan maupun menodai. Justru di dalamnya terdapat spirit purifikasi yang diiringi dengan semangat dinamisasi. Sebagai upaya purufikasi pembaharuan bertujuan untuk menambahkan akal sebagai alat. Bukan sebagai sumber ajaran, melainkan sebagai alat untuk menggali kembali sumber-sumber yang ada yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Sedangkan, sebagai gerak dinamisasi pembaharuan berupaya untuk melapangkan cakrawala dengan cara membuka selebar-lebarnya gerbang masuk bagi ilmu-ilmu modern yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.
Jelas spirit pembaharuan ini merupakan solusi yang membawa sejuta harapan bagi persoalan masa sekarang. Tidak hanya mengembalikan secara membabi buta, tetapi juga terdapat upaya kontekstualisasi di dalamnya.
Berbicara soal sekularisme, justru agama akan menjadi sekuler apabila agama tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Terkesan eksklusif, tanpa ada kontribusi bagi peradaban. Maka tuduhan sekuler tersebut akan lebih tepat jika diarahkan pada golongan-golongan yang mandeg dalam upaya pengkajian Islam secara dinamis.
Sebenarnya, pembaharuan tidak hanya menjadi narasi yang terus bergulir di tubuh Islam, melainkan juga bergulir di tubuh-tubuh agama lainnya. Prof Stephen (Guru Besar Misiologi) mengatakan bahwa:
“Sebuah Gereja misioner mengakui dunia telah sangat berubah menyusul dua perang dahsyat pada abad ke-20. Kematian paham Komunisme di hampir semua tempat di mana mereka pernah memiliki cengkeraman. Serta kebangkitan agama-agama besar dunia, dan khususnya menyeruaknya Islam sebagai agama yang tumbuh paling pesat di dunia beserta ancaman aneka kelompok radikal di dalamnya.”
***
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa,
“Tatkala orang-orang Kristen Barat kian merosot dalam jumlah, mereka pun mulai menyadari kebutuhan untuk bersaksi dan memberitakan injil dalam cara-cara baru dengan urgensi baru dalam berbagai masyarakat pluralis dan sekuler di mana mereka tinggal. Misi ada di mana-mana”.
Dari pernyataan Prof. Stephen tersebut menunjukkan bahwa narasi pembaharuan bukan saja milik Islam, namun juga menjadi milik agama-agama lain yang turut khawatir akan masa depan agamanya. Dan kita tidak dapat mencegah hal tersebut.
Namun kerapkali kita di Indonesia justru berupaya keras untuk menggagalkan dan memandang hal tersebut sebagai suatu tindakan penyesatan tanpa berfikir kembali bahwa mereka juga merupakan umat beragama yang agamanya turut menyumbang standar moral dan etika dari masing-masing ultimate values yang dimiliki dalam rumusan dasar negara.
Sialnya, Pancasila justru menjadi ancaman bagi golongan-golongan agama dalam mengejawantahkan nilai. Banyak kekhawatiran hinggap di kepala dalam bentuk ketakutan akan dianggap radikal, anti pancasila, dan merong-rong NKRI.
Polemik Negara Islam dan Kebangsaan
Semestinya, dua hal ini tidak perlu menjadi polemik apabila kita betul-betul paham bahwa hakikat yang perlu dicapai adalah suksesi ultimate value. Dan suksesi itu tidak pernah menyaratkan penguasaan atas institusi berbangsa dan bernegara.
Pola pikir yang selalu terbentuk di tengah kita adalah untuk mencapai tujuan maka kita mesti memiliki kuasa struktural. Hal tersebut hanya sebatas keinginan yang cenderung didominasi oleh hasrat. Maka yang akan lahir adalah Islam yang sekadar emosional dan sloganistik.
Ia tentu emosional karena yang ada di kepalanya hanya hasrat untuk berkuasa, dan ia menjadi sloganistik sebab yang didengungkan sebatas doktrin “Al-Islam huwa ad-din wad-daulah”. Sehingga ia lalai akan goals rahmatan lil’alamin dan terkesan menjadi mager (malas gerak) karena merasa tidak punya kuasa apa pun dalam hal kebijakan.
Negara Islam atau kebangsaan juga pernah menjadi polemik antara Soekarno dan A. Hassan. Soekarno berusaha mempertahankan pandangan nasionalitasnya, sedang A. Hassan pun tetap kekeh dengan pandangan keislamannya. Ternyata, yang menjadi soal adalah keduanya memiliki perbedaan referensi.
Soekarno mengira bahwa Negara Islam adalah bentuk teokrasi sebagaimana yang digambarkan buku-buku Barat. Sedangkan A. Hassan mengira Nasionalisme sebagai bentuk sekularisme yang saat itu tengah naik daun di Turki.
Menurut Thomas Aquinas, kemurnian hukum Tuhan hanya berhenti pada wahyu. Ketika mulai merambah pada otoritas rohaniawan dan juru tafsir, maka kemurnian tersebut telah terkontaminasi oleh akal manusiawi.
Jika merujuk pada kerangka pemikiran Aquinas, maka tidak ada alasan untuk mengharuskan berdirinya negara Islam, sebab kuncinya bukan pada otoritas kebijakan, melainkan kejujuran dan kesungguhan menggunakan akal dalam menggali Qur’an dan Sunnah.
Dalam waktu yang lama, Indonesia akan tetap terkurung dalam pertentangan ideologi dan agama dengan meteor Pancasila yang sewaktu-waktu siap menghantam, apabila tidak sesegera mungkin sadar bahwa yang terpenting bukanlah kuasa struktural maupun hal-hal yang bersifat kebijakan semata. Melainkan lebih ditekankan pada kesadaran akan pentingnya perwujudan Islam yang hanif dan rahmah.
Editor: Yahya FR