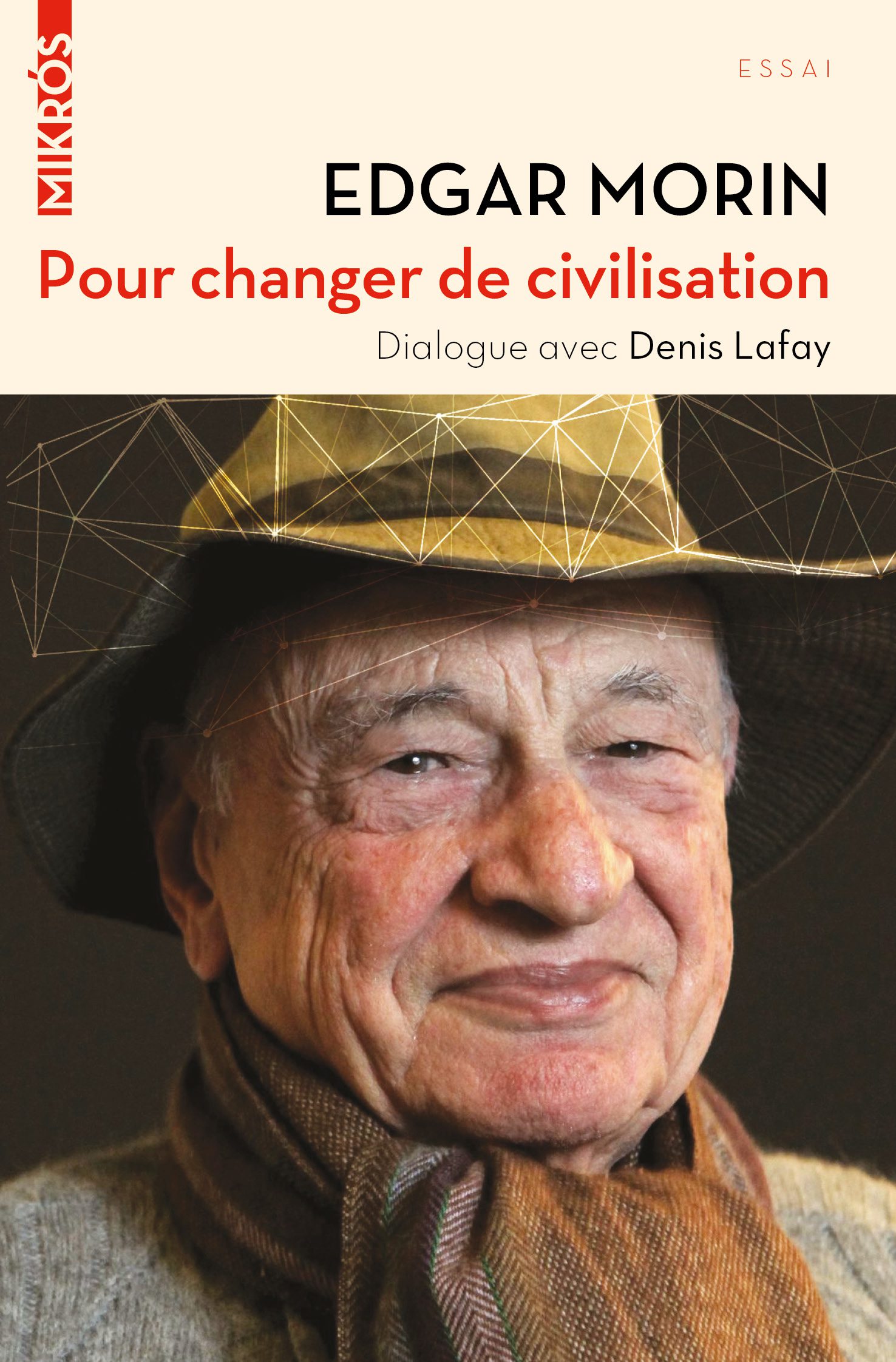Sepuluh tahun lalu, kurang lebih, saya membeli buku bekas di bilangan Quartier Latin, dekat Universitas Sorbonne Paris, Perancis. Buku itu mengolah tulisan dan dialog para cerdik-pandai Perancis tentang filsafat, etika, dan bioteknologi, khususnya tentang teknologi kloning pada manusia, yang pada tahun 1990-an sedang heboh dibicarakan. Dari buku itu, saya mengenal para filosof kontemporer Perancis, di antaranya Marcel Gauchet, Alain Badiou, dan Edgar Morin.
Dari tiga filosof tersebut, saya beruntung, bisa berguru langsung dengan Marcel Gauchet di Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris. Gauchet dikenal sebagai seorang filosof dan sejarawan agama yang fasih membedah hubungan agama, sekularisme dan modernitas. Sayangnya, saya hanya membaca buku-buku Alain Badiou dan Edgar Morin, karena keduanya adalah filosof gaek yang kini usianya hampir satu abad.
Akhir tahun lalu, di Place de Bellecour, Lyon, saya mampir ke sebuah toko buku yang menyediakan buku-buku bekas dengan harga murah meriah. Saya langsung menuju deretan buku-buku filsafat dan ilmu sosial. Di antara deretan buku baru best-seller di Perancis, buku Edgar Morin berjudul, “Pour changer de civilisation: Dialogue avec Denis Lafay ( Editions de l’Aube, 2019) menarik perhatian saya.
Selain takjub, bahwa Morin ternyata masih hidup, produktif menulis buku, dan memberikan analisis tajamnya terhadap isu atau peristiwa aktual lokal dan dunia di media terkenal semisal Le Monde dan Liberation, saya sendiri tertarik butir-butir pikirannya yang objektif, kritis, dan menyerukan solidaritas dan humanisme. Ia yakin, “satu-satunya obat penawar barbarisme adalah humanisme.”
Morin dan Humanisme
Di Perancis, Morin dikenal sebagai pemikir tentang kompleksitas zaman. Sosiolog dan filosof yang lahir 99 tahun lalu itu, seperti Alain Badiou, adalah pendukung Partai Komunis Perancis, pada masa perang dunia. Dikenal agnostik-radikal, ia mempromosikan humanisme tanpa batas –agama, suku, ras, partai politik, golongan, dan kecenderungan seksual.
Sebagai keturunan Yahudi, ia membela bangsa Palestina tanpa lelah dan rasa takut. “Bangsa Yahudi, keturunan dari para korban politik aparteid (geto), saat ini, melakukan getoisasi bangsa Palestina. Kita tidak bisa membayangkan sebuah bangsa buronan, berasal dari rakyat yang paling menderita diburu sepanjang sejarah kemanusiaan, saat ini, bisa berubah menjadi bangsa sinis yang kepuasannya adalah mempermalukan orang lain,” ungkap Morin seperti dikutip Le Figaro-Magazine, 6 Oktober 2017 lalu.
Karena pernyataan tersebut, ia dituduh penyeru antisemitisme dan pembela Islam. Atas tuduhan ini, ia balik menuduh antisemitisme sebagai alat Israel untuk mempertahankan dan membela kepentingan politik nasional dan internasionalnya.
Dalam buku Pour changer de civilisation yang saya beli murah itu, pandangan dan keyakinan Morin pada humanisme tampak terang-benderang. Ia memberikan catatan kritis dan analitis terhadap berbagai persoalan aktual yang terjadi di Perancis, Eropa, Musim Semi Arab, fenomena Al-Qaedah, ISIS, imigrasi, hingga reformasi Islam di Eropa. Catatan dan komentarnya yang dikumpulkan oleh Denis Lafay pada Januari 2016 terasa tetap relevan dengan kondisi Eropa dan dunia setelahnya: keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan naiknya Presiden Donald Trump di Amerika Serikat.
Referendum Brexit pada Juni 2016, baginya, adalah panggung ekspresi demokrasi sekaligus krisis eksistensial dan pembauran bangsa Eropa. Sedangkan terpilihnya Trump di Amerika Serikat menunjukkan runtuhnya ruang demokrasi, hilangnya aturan-aturan etika dasar, diplomasi perang, dan merajalelanya dehumanisasi (penganiayaan, politik uang, materialisme, stigmatisasi dan hirarki etnik dan agama, runtuhnya hak asasi manusia, terutama perempuan, dan hancurnya etika ekologi seperti penambangan sumber daya alam secara brutal (hlm. 8).
Selanjutnya, tanpa ragu-ragu lagi, ia yakin bahwa peradaban modern yang diwarnai barbarisme dalam tata dunia lokal, nasional, maupun global hanya bisa diobati dengan penawar humanisme. Humanisme, dalam pandangannya adalah kesadaran yang dimiliki setiap manusia untuk hidup bersama dalam sebuah “komunitas takdir,” karena sama-sama berbagi krisis ekologis dan ekonomi, bahaya yang ditimbulkan oleh fanatisme agama dan senjata nuklir.
Oleh karena itu, lanjutnya, tidak ada alasan lain bagi umat manusia untuk kembali pada kesadaran kolektif “saling mengukuhkan, memperkuat, dan berbaur satu sama lain.” Jika tidak, ia mengingatkan, manusia akan melakukan hal sebaliknya, yakni saling memangsa, bercera-berai, lebih menyukai kehancuran daripada persatuan, bersembunyi di balik identitas khusus— kebangsaan atau agama (hlm. 16).
Morin dan Barbarisme Modern
Alih-alih menyalahkan agama sebagai penyebab radikalisme dan terorisme yang diusung Al-Qaedah dan ISIS, seperti yang biasa terlihat jelas dalam analisa banyak sarjana dan pengamat radikalisme dan terorisme, Edgar Morin memilih untuk melihat sejarah kolonialisme, dekolonisasi, pemerintahan diktator, Revolusi Iran 1979, Musim Semi Arab pada 2011, dan kekacauan geopolitik di Negara-negara Muslim, terutama Timur Tengah. Faktor internal dunia Islam ini diperparah dengan perilaku bangsa-bangsa besar yang punya kepentingan politik dan ekonomi di sana. Faktor sejarah dan tata hubungan diplomatik yang barbar inilah yang melahirkan Al-Qaedah kemarin lusa dan ISIS sekarang ini.
Morin juga melihat secara objektif bahwa barbarisme dunia modern itu tidak hanya ISIS yang mencitakan Negara atau kekhalifahan Islam, tetapi juga barbarisme yang dilakukan Nazisme, Stalinisme, dan Maoisme. Ia menolak tegas, karena itu, pandangan yang hanya mengaitkan barbarisme dengan abad ke-21 dan Islam. Jutaan orang mati juga terjadi di kamp-kamp Nazi, pembunuhan massal Soviet pada masa Stalin, Revolusi kebudayaan China dan juga genosida yang dilakukan tentara Khimer Merah (hlm. 22-23).
Tipe barbarisme kedua adalah, yang kata Morin paling hegemonik dalam sejarah peradaban kontemporer, barbarisme statistika atau data dan angka. Statistika dan angka (GDP, laba-rugi, pertumbuhan ekonomi, sensus penduduk, dan survey) telah menjadi visi unilateral yang melahirkan tirani profit, spekulasi internasional, dan kompetisi buas.
Atas nama kompetisi, katanya, setiap aturan dibuat untuk meningkatkan daya saing, hingga berakibat pada kebijakan kerja bagi karyawan yang tidak berperikemanusian, di mana kualitas hubungan antar manusia seperti kerja sama, inisiatif, dan rasa tanggung jawab dikesampingkan demi alasan efisiensi kerja dan keuntungan perusahaan atas dasar hitung-hitungan rasio kekuangan, cadangan devisa, dan saham di bursa efek. Situasi ini, analisa Morin, terkait erat dengan sikap penolakan untuk melihat secara komprehensif realitas dunia, masyarakat, dan individu dalam kompleksitasnya. Sebab, sesungguhnya, dunia dan isinya itu tidak bisa disederhanakan dalam tirani dan barbarisme angka, data dan statistika (hlm. 26).
Morin dan Islam
Terkait dengan Islam, baik di Perancis, Eropa, Amerika Serikat dan dunia Muslim yang sedang mengalami krisis multidimensional, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi dan sekularisme, Morin melihat bahwa adalah tidak adil untuk menuntut Islam harus selaras dengan demokrasi dan sekularisme dalam waktu yang singkat saat ini. Padahal, Katolik sendiri butuh berabad-abad untuk bisa menerima demokrasi dan sekularisme.
Sebelum Renaisan pada abad ke-14-17, agama (Kristen/Katolik) dan politik (kerajaan) di Eropa tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan berakibat pada penyimpangan agama dan politik; inquisisi, perang agama, korupsi kewenangan gereja dan politik, dan sebagainya. Gereja baru bisa menerima demokrasi, praktis pada abad ke-20, yang ditandai dengan pemisahan otoritas agama (gereja) dan politik yang di Perancis dikenal melalui UU Laicite (Sekularisme) 1905.
Di pihak lain, Barat juga seringkali terjebak pada sinisme tak berdasar, misalnya ketika Temple Budha Bamiyan di Afghanistan atau Palmyre di Siria dihancurkan oleh Al-Qaedah dan ISIS. Padahal, ratusan tahun silam, untuk alasan penaklukan teritorial sebagaimana para Islamis itu, orang Kristen Barat juga melakukan pembunuhan kaum pagan dan penghancuran situs karya seni kulturalnya kaum pagan, melakukan perang Salib, dan mengkristenkan dunia Islam.
Morin mengakui bahwa Islam adalah agama Yudeo-Kristiani, sebagaimana Yahudi dan Kristen. Ketiganya berakar pada ajaran monoteisme Nabi Ibrahim. Meski dalam teologi dan praktiknya, Islam lebih mirip dengan Yahudi (makanan halal, larangan makan babi dan minuman keras) daripada agama Kristen. Oleh karena itu, supaya Islam dapat selaras dengan demokrasi dan sekularisme, seperti penerimaan Yahudi dan Kristen, maka yang dilakukan sekarang adalah pendekatan pedagogik, yakni mengajarkan substansi ajaran Yahudi dan Kristen pada Islam, sebab titik temu ketiga agama itu adalah pada substansi ajaran yang sama (hlm. 43-48).
Dalam konteks ini, Morin percaya bahwa suatu hari nanti Islam akan menerima demokrasi dan sekularisme seperti takdir sejarah yang ditempuh Yahudi dan Kristen sebelumnya. Morin secara meyakinkan berkata,
Il est l’heure d’organiser et de promouvoir un islam occidental européen, qui sera le théâtre de reconnaissances fondamentales. Reconnaissance du statut des femmes, de l’égalité hommes-femmes, des lois de la République, du monopole de l’État dans l’éducation publique —cohabitant avec des systèmes d’éducation privée-, des non-croyants et des libres penseurs, des mariages mixtes…
(Inilah saatnya menyusun dan dan mempromosikan Islam Barat Eropa, yang akan menjadi panggung bagi pengakuan-pengakuan mendasar. Pengakuan atas status perempuan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, undang-undang Republik (Perancis), monopoli Negara pada pendidikan publik (bersama dengan sistem pendidikan swasta), orang-orang tak beriman dan para pemikir bebas, dan pada kawin campur…).
Pandangan optimis Morin pada Islam Eropa yang tercerahkan ini menegaskan bahwa, secara sosiologis, agama Islam akan bertransformasi seperti agama monoteis Yahudi dan Kristen ketika harus berhadapan dengan fakta sosial dan politik demokrasi dan sekularisme. Selain itu, pandangan humanis Morin pada Islam dan monoteisme, meski ia sendiri mengaku agnostik radikal, bertentangan dengan Islamophobia yang belakangan ini meningkat pesat dijajakan oleh partai politik ultra nasionalis dan kanan Eropa, seperti Front National Perancis-nya Marine Lepen, dan Partai Geertz Wilder di Belanda serta President Donald Trump di Amerika Serikat yang menumbuh-suburkan paham far right nationalism and white supremacy. Ia mengkritik paham ini sebagai “racun yang meracuni semua bangsa” (hlm. 48-49).
Morin dan Politik Kiri
Catatan kritis Morin atas berbagai peristiwa politik, sosial, dan agama berguna untuk melihat dan mempertimbangkan secara jernih peristiwa-peristiwa kekinian yang dikategorikan oleh Morin sendiri sebagai “nafsu barbarisme (tentation barbare). Ia selanjutnya menyatakan perlunya mencari solusi bersama dengan kembali melakukan “rehumanisasi” dan melipatgandakan kesadaran humanis pada setiap upaya untuk membangun kembali “peradaban politik” baru dan sekaligus “politik peradaban”.
Ia sendiri meyakini bahwa obat penawar dari krisis multidimensional manusia modern dalam bentuk barbarisme politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan adalah humanisme itu sendiri. Humanisme mengatasi segala perbedaan dan hambatan psikolologis dan teritorial serta rasial. Dengan humanisme, peradaban manusia akan kembali menawarkan kebajikan-kebajikan bagi umat manusia dan alam semesta. Humanisme yang bertumpu pada pengetahuan dan pemikiran yang mendalam dan menyeluruh juga dapat mengobati kebutaan hati nurani manusia yang dihasilkan oleh pengetahuan yang tercerai-berai, tersekat, bersifat negatif dan Manichean (bi-polar, hitam putih).
Untuk itu, sebagai militan paham “kiri”, Morin mendefinisikan “politik kiri” – baik itu kiri Sosialis atau Komunis, sebagai sebuah paham yang berakar pada banyak hal: Libertarian (perkembangan individu), Sosialis (perbaikan masyarakat), Komunis (komunitas dan persaudaraan), dan sekaligus Ekologis supaya dapat membangun hubungan baru dengan alam. Bagi peneliti CNRS Perancis dan suami dari sosiolog Maroko ini, kemanusiaan adalah sebuah petualangan yang tidak bisa dilepaskan dari politik kiri. Katanya (hlm. 88-93),
Être de gauche invite à prendre part à cette aventure inouïe avec humilité, respect, bienveillance, exigence, créativité, altruisme et justice. Être gauche, c’est aussi avoir le sens de l’humiliation et l’horreur de la cruauté, ce qui permet la compréhension de toutes les formes de misère, y compris sociales et morales. Être de gauche comporte toujours la capacité d’éprouver toute humiliation comme une horreur.
(Menjadi kiri mengundang Anda untuk mengambil bagian dalam petualangan yang luar biasa ini dengan kerendahan hati, hormat, kebajikan, permintaan, kreativitas, altruisme dan keadilan. Menjadi kiri juga berarti memiliki rasa (jijik) pada penghinaan dan kengerian pada kekejaman, yang memungkinkan untuk memahami segala bentuk kesengsaraan, termasuk di dalamnya kesengsaraan sosial dan moral. Menjadi kiri selalu melibatkan kemampuan untuk melihat semua penghinaan sebagai horor).
Dalam tulisannya di Harian Liberation (20/03/20), ia menulis secara gamblang tentang COVID-19, “Virus ini juga menunjukkan kepada kita bahwa saling ketergantungan itu harus memicu solidaritas kemanusiaan dalam sebuah kesadaran komunitas bersama. Virus ini juga mengungkapkan pada kita apa yang saya sebut “ekologi aksi,” namun sebuah aksi yang tidak patuh pada niat, ia akan dibelokkan dan dialihkan dari niat awalnya dan lalu menjadi bumerang yang dapat menyerang orang yang melemparnya itu.”
Menjelang usianya satu abad, ia tak berhenti menyeru pada kita untuk membangun solidaritas dan kemanusiaan global guna merajut kembali “kain kemanusiaan yang telah sobek” dan ekologi global yang luluh lantak.
Wallahu a’lam bis shawab. Tuhan yang Mahatahu kebenarannya.
Editor: Arif