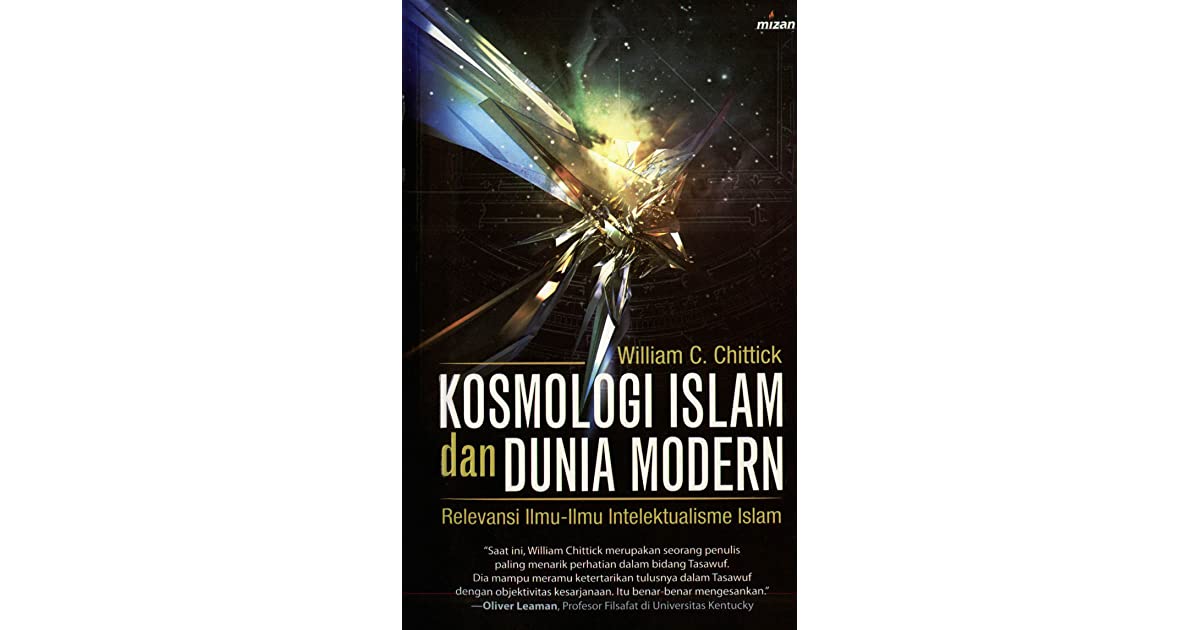“Siapa pun dapat menghafal Al-Qur’an dan hadis, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bisa memahami apa yang Allah dan Nabi bicarakan.”
(Chittick 2010, 6)
Taqlīd | Kalimat di atas ditulis William C. Chittick sebagai contoh dua jenis pengetahuan (ilmu): pengetahuan nukilan (naqlīyyah/nakliyah) dan pengetahuan intelektual (`aqlīyyah/akliyah).
Menghafal Al-Qur’an dan hadis merupakan pengetahuan nukilan. Dalam arti, siapa pun bisa melakukannya selama mendapatkan transmisi (nukilan), baik dari teks mau pun dari orang lain.
Sedangkan ‘hanya sedikit yang benar-benar bisa memahami apa yang Allah dan Nabi bicarakan’ merupakan pengetahuan intelektual. Dalam arti, seseorang telah melakukan proses mencari kebenarannya dengan menggunakan akal atau pikirannya sendiri.
Perbedaan Ilmu Nakliyah dan Akliyah
Apa perbedaan ilmu nakliyah dan ilmu akliyah? Ciri paling umum dari ilmu nakliyah adalah dia harus diturunkan dari orang ke orang. Satu-satunya cara untuk mepelajari ilmu nakliyah, kata Chittick, adalah dengan menerimanya dari orang lain. Contoh dari ilmu ini adalah bahasa, sejarah, hukum, dan lain sebagainya.
Sedangkan ilmu akliyah bersifat sebaliknya. Ia tidak bisa diterima dari orang lain, kendati guru atau orang lain masih sangat dibutuhkan. Seseorang tidak bisa mengatakan bahwa “tiga ditambah tiga sama dengan enam karena guru saya mengatakan demikian”. Ia harus menggunakan daya inteleknya untuk membuktikan kebenaran pernyataannya.
Chittick membawa diskursus ini dengan tujuan menghidupkan kembali budaya pencarian pengetahuan intelektual Islam yang selama berabad-abad telah dianggap mati. Apa yang dilakukan oleh hampir semua muslim adalah menerima apa adanya pengetahuan dari guru atau sumber lainnya, dan tidak berusaha membuktikan kebenarannya dengan mendayakan intelektualitasnya sendiri.
Taqlīd dalam Islam
Dalam Islam, ada istilah taqlīd (mengikuti otoritas). Dalam diskursus ini, Chittick menegaskan bahwa yang akan menjadi lawan kata taqlīd bukanlah ijtihād, tetapi tahqīq (verifikasi). Sebab, ranah ijtihād adalah hukum Islam. Sedangkan yang menjadi diskursus pembahasan adalah ilmu intelek.
Dua intelek masyhur muslim, yaitu al-Ghazali dan Rumi, sebut Chittick, mengecam sikap taqlīd. Tetapi, bukan taqlīd dalam ranah hukum Islam, melainkan taqlīd dalam ranah pemberdayaan intelektualitas pribadi.
Pentingnya Mendayakan Akal
Mengapa tradisi intelektual harus dihidupkan kembali? Alasan utamanya adalah mendayakan akal merupakan perintah langsung dari Allah. Meski tidak semua orang memiliki bakat untuk melakukan refleksi mendalam tentang banyak hal, tetap ada kewajiban moral untuk menggunakan akalnya sendiri.
Mendayakan akal kemudian membawa pada konsekuensi lebih jauh, salah satunya adalah ‘bagaimana cara berpikir yang benar?’ Pertanyaan ini membawa pada banyak pendapat dikemukakan untuk menjelaskan cara terbaik dalam memperoleh pengetahuan. Perbedaan pendapat pun terjadi, sehingga merupakan hal yang lumrah.
Tauhid Sebagai Dasar
Namun, dalam Islam, kata Chittick, ada satu prinsip yang diakui oleh semua orang: Tuhan itu satu (esa), dan Dia adalah satu-satunya sumber kebenaran dan realitas. Dari-Nya segala sesuatu, dan kepada-Nya segala akan kembali. Kita mengenalnya sebagai “Tauhid”. Berbagai cara dalam memperoleh pengetahuan harus berorientasi pada Tauhid.
Tauhid atas dasar ‘meniru’ atau taqlīd terhadap orang lain tidak diterima. Seorang muslim tidak bisa dikatakan sebagai muslim sejati jika dia berkata “Aku beriman kepada Allah karena orangtua saya mengatakan demikian”. Seseorang harus membawa dirinya sendiri (swa-bukti) untuk membenarkan pernyataannya. Karenanya, daya inteleknya harus digunakan.
Dalam hal ini, seseorang harus menjadi muhaqqiq. Kejayaan intelektualisme Islam pernah dicapai ketika para muhaqqiq hidup. Mereka adalah para filsuf muslim dan sufi. Menurut Chittick, peradaban intelektualisme Islam berjalan pada dua bidang di atas: filsafat Islam dan tasawuf, yang pada perkembangannya menelurkan banyak cabang keilmuan lainnya.
Dua bidang di atas menuntut swa-bukti (self-evident) sebagai syarat pengetahuan sejati. Filsafat Islam dibangun di atas metodologi yang logis dan rasional yang dikembangkan oleh para pemikir muslim dengan cara-cara yang benar menurut Islam.
Sedangkan tasawuf merupakan metode mencari pengetahuan sejati yang didasarkan pada teknik-teknik kontemplatif yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.
Dari filsafat Islam dan tawasuf kemudian lahir muslim sejati yang mengenal Allah dengan Tauhid sebagai pokoknya. Kita pun mengenal al-Ghazali, Ibnu Sina, Jalaluddin Rumi, dan nama-nama besar lainnya.
Secara sederhana, tujuan menghidupkan intelektualitas adalah mempersiapkan landasan bagi tercapaiannya manusia sempurna (insān kāmil). Itulah yang sama-sama diperjuangkan oleh para filsuf muslim dan sufi (Chittick 2010, 59).
Editor: Yahya FR
| Judul Buku | : | Kosmologi Islam dan Dunia Modern: Relevansi Ilmu-Ilmu Intelektulisme Islam |
| Penulis | : | William C. Chittick |
| Penerjemah | : | Arif Mulyadhi |
| Penerbit | : | Mizan Publika |
| Tahun Terbit | : | Oktober 2010 (cetakan I) |
| Tebal | : | xvi + 216 hlm; 13 x 20,5 cm |