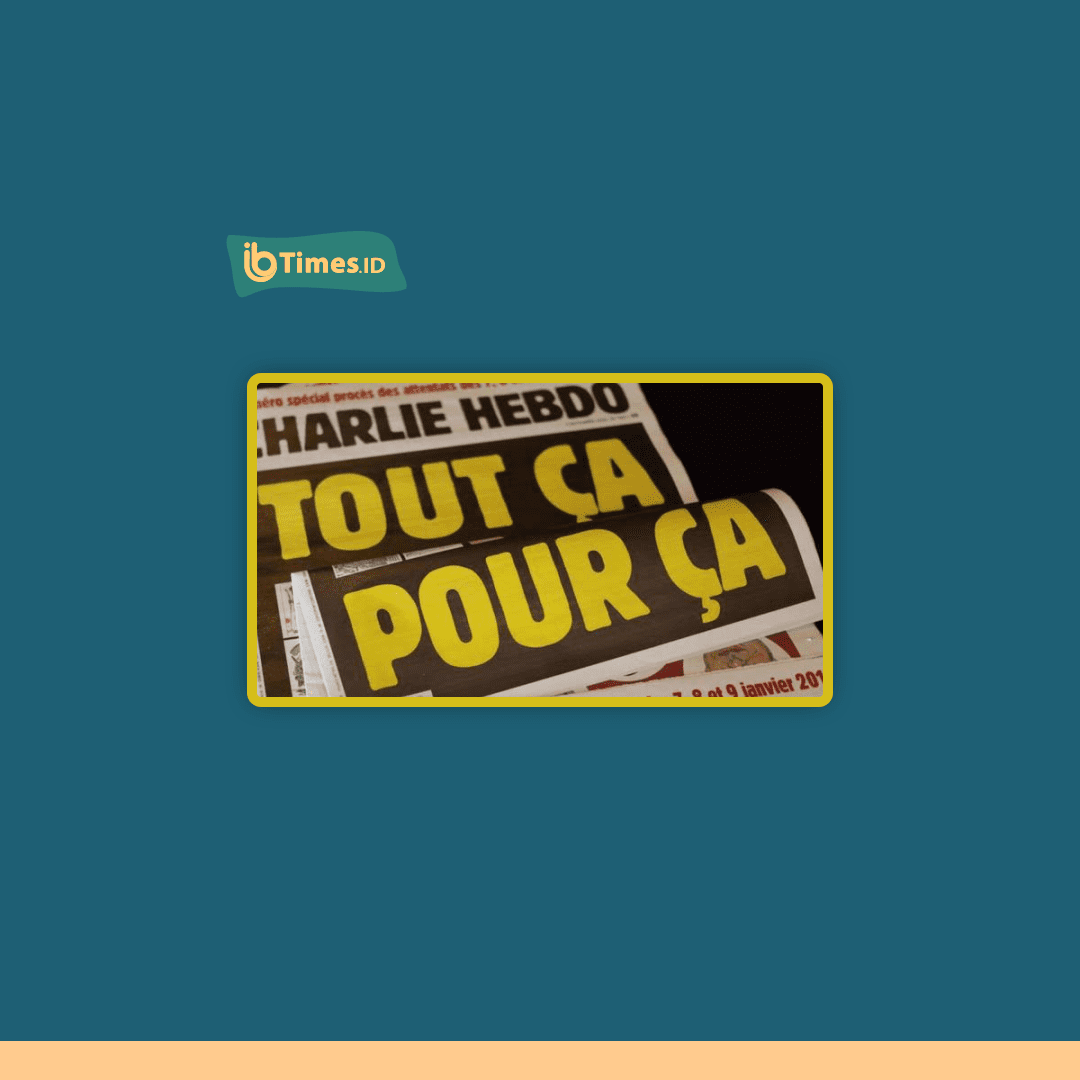Kasus Charlie Hebdo yang membuat karikatur Nabi Muhammad di Perancis menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi ada batasnya. Dengan kata lain, tidak setiap ekspresi, termasuk dalam karya seni dapat dengan mudah diumbar tanpa kendali. Itu artinya, perlu ada toleransi yang ditujukan untuk mengelola ekspresi agar dapat dinikmati secara proporsional dan dijadikan pelajaran penting dalam membangun hidup bersama, misal dengan humor.
Boleh jadi tak banyak orang yang tahu bahwa humor adalah salah satu “barometer” toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam masyarakat berbudaya Jawa, wayang telah menjadi mitologi yang populer dan akrab dengan hal dan masalah humor. Dalam babak yang dikenal dengan “gara-gara”, humor adalah saat dan tempat yang tepat untuk mempertunjukkan segala sesuatu yang dianggap aneh, tidak lazim, bahkan tak terduga.
Itulah mengapa adegan itu selalu menjadi favorit di kalangan penonton wayang lantaran bermuatan lelucon atau guyonan. Namun, tokoh-tokoh yang dipandang berkharisma humoris itu justru begitu dihormati, bahkan disegani.
Menarik, memang. Apalagi dalam bukunya yang berjudul Mitologi dan Toleransi Orang Jawa/2000/2003 (Mythology and the Tolerance of the Javanese/1965). Benedict Anderson menunjukkan bahwa wayang sebagai “agama” bagi orang Jawa begitu berpengaruh dan menentukan. Meski tanpa kitab Suci, Nabi, dan Mesias (Sang Penyelamat). Namun “agama wayang” dipercaya mampu memberi pedoman yang mencerahkan dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu, wayang bukan hanya menjadi tontonan semalam suntuk. Melainkan juga menyajikan tuntunan dan tuntutan yang nyata, termasuk melalui humor-humornya. Tak heran, tokoh-tokoh humoris yang dilakoni oleh para punakawan tidak semata-mata ditampilkan demi penghiburan belaka, tetapi terutama untuk dijadikan sebuah pelajaran.
Toleransi dan Humor dari Wayang
Salah satu pelajaran penting yang jarang mendapat perhatian serius adalah berkaitan dengan toleransi. Dalam wayang, hal itu ditunjukkan lewat tokoh-tokoh yang dipentaskan dalam lakon atau cerita tertentu. Seperti Arjuna dan Bima misalnya, yang secara fisik memiliki perbedaan amat kontras.
Di satu sisi, Arjuna yang ditampilkan tampan, sakti mandraguna, namun lemah gemulai adalah idola atau dambaan bagi para wanita yang berlomba-lomba ingin diperistri olehnya. Di lain sisi, Bima yang tampak begitu besar, kuat, namun tegas dan lugas selalu diandalkan sebagai pembasmi dari segala yang jahat setara dengan anaknya Gatot Kaca.
Dalam konteks toleransi, pelajaran yang diwariskan secara turun-temurun, khususnya pada anak-anak Jawa, adalah siapapun boleh dan berhak untuk menjadi seperti keduanya. Artinya, anak yang kurus kering sekalipun dapat saja mengidolakan Bima, dan sebaliknya, anak yang gemuk tak salah juga jika mendambakan menjadi seperti Arjuna.
Sebab yang ditekankan di sini bukan soal siapa yang paling cepat dan kuat serta bakal menang seperti dalam kisah perlombaan lari antara kelinci dan kura-kura. Tetapi, tekanannya justru pada siapa yang pantas dan layak untuk menjalani apa yang sudah dipelajari, dihayati dan diamalkan oleh kedua tokoh itu. Jadi, toleransi sesungguhnya bukan sekadar berkaitan dengan soal kekuatan, kemampuan, bahkan kekuasaan, namun justru mengenai kepantasan dan kelayakan.
Bagi orang Jawa, dua hal di atas bukanlah sebuah konsepsi, melainkan cara pandang. Dalam arti ini, yang di sebelah kiri tidaklah selalu bermakna jahat atau salah. Begitu pula dengan yang di sebelah kanan belum tentu berorientasi pada kebaikan atau kebenaran.
Seperti dalam wayang, keduanya dapat ditafsirkan secara pantas dan layak tergantung dari mana sudut pandangnya. Dari wayangnya, atau dari bayangannya. Dari situlah dapat ditemukan pandangan atau pemandangan macam apakah yang dihasilkan dari cara memandang wayang yang juga berarti sebagai bayang-bayang.
***
Dalam wayang, humor menjadi tanda bahwa cara pandang yang pantas dan layak bukan ditentukan oleh hasil yang diperoleh dari pandangan atau pemandangan. Tetapi juga berkat kejelian dan kewaspadaan untuk lepas dan bebas dari segala cara pandang yang mudah menipu, bahkan sarat dengan beragam tipuan. Maka, humor dalam wayang mengajari para penontonnya untuk menunda atau menahan segala pandangan, apalagi pemandangan yang didapat dari cara pandang satu sisi atau sepihak belaka. Persis di sinilah humor tidak berpretensi untuk menyalahkan atau membenarkan apa pun yang telah dipandangi selama menonton wayang. Namun, hal itu justru menjadi “bahan bakar” untuk menimbang atau mengukur seberapa tolerankah para penonton wayang dalam me
Pada tataran ini, humor tentang “polisi jujur” sesungguhnya setara dengan babak “gara-gara” dalam wayang. Kesetaraannya terletak pada bagaimana humor itu bukan semata-mata diintensikan untuk menghina, apalagi mencemarkan, identitas atau sosok tertentu, terutama kepolisian. Namun, hal itu justru mau memperingatkan bahwa kejujuran sebagai nilai hidup utama semakin langka, bahkan nyaris terbuang dalam hidup bersama. Pada wayang, kejujuran adalah nilai hidup yang selalu dipertunjukkan dengan perjuangan yang tak kenal lelah. Bahkan jika perlu mengorbankan apapun yang ada. Namun, kejujuran yang sudah semakin menguap dan mengorbankan banyak hal. Sebagaimana diungkap Ronggowarsito bahwa “sing jujur kojur” (yang jujur bakal hancur), tidak perlu terlalu diratapi apalagi ditangisi.
Penawar Kedengkian
Justru obat penawar dari keprihatinan itu adalah dengan menghadirkannya sebagai humor. Dengan demikian, tak ada yang perlu dicemaskan atau dikhawatirkan lantaran kejujuran dan kebohongan ibarat dua sisi yang ada pada mata uang. Keduanya tak terpisahkan dan tak mudah dibedakan sama seperti pagi dan malam, terang dan gelap, senang dan susah. Maka, jalan keluarnya adalah dengan menertawainya saja lantaran yang sesungguhnya .disebut jujur atau bohong hanyalah sebuah cara pandang yang dapat berubah-ubah seiring perkembangan zaman.
Dalam batas-batas tertentu, humor memang hanya sekadar guyonan yang boleh jadi bebas nilai. Tapi, jika diamati dan dihayati secara mendalam, di sana tergurat pelajaran untuk menjadi toleran yang tersurat dalam setiap kata dan perbuatan humoris. Jadi, bukan jargon belaka jika ada slogan yang menyatakan bahwa “semakin humoris semakin toleran”. Lagipula, seperti ditembangkan dalam salah satu lagu dari album Dalbo (Iwan Fals, dkk., 1993) yang berjudul “Hua Ha Ha”, bahwa “tertawa itu sehat” dan “menipu itu jahat”. Bukankah begitu?