ذُكَاءٍ وَحِرْصٍ وَاصْطِبَارٍ وَبُلْغَةٍ # وَاِرْشَادُ اُسْتَاذٍ وَطُوْلِ زَمَانٍ
Entah kenapa tiba tiba penggalan syair di atas terbersit di benak saya, syair di Kitab Ta’lim Muta’allim tersebut menjelaskan syarat syarat murid dalam menuntut ilmu, salah satunya adalah petunjuk guru atau kyai.
Sebagai seorang yang lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren, beberapa isu tentang pesantren akhir akhir ini cukup membuat saya refleksi mendalam entah sebagai kritik sosial atau autokirik untuk diri saya dan lingkungan pesantren.
Di tengah arus modernisasi dan digitalisasi, pesantren tetap eksis sebagai oase spiritual dan tradisi di Indonesia. Pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, melainkan ruang pembentukan jiwa, karakter, dan nilai. Namun, dalam era yang semakin cepat ini, relasi santri dan kyai menghadapi berbagai tantangan baru.
Polemik yang muncul dari tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 pada Oktober 2025 menjadi titik refleksi penting. Tayangan tersebut menampilkan narasi yang dianggap melecehkan kehidupan santri dan kyai, dengan judul provokatif seperti “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan Pondok? Kiainya Yang Kaya Raya, Tapi Umatnya Yang Kasih Amplop.” Tayangan ini memicu gelombang protes dari kalangan pesantren, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo, dan memunculkan tagar #BoikotTrans7 di media sosial.
Kontroversi ini bukan hanya soal etika jurnalistik, tetapi menyentuh akar representasi pesantren dalam ruang publik. Tayangan tersebut menunjukkan minimnya pemahaman terhadap relasi batin yang tumbuh di pesantren relasi antara santri dan kyai yang tidak bisa dipahami dengan logika transaksional atau komersial. Dalam buku Bilik-Bilik Pesantren, Nurcholish Madjid menekankan bahwa pesantren adalah ruang tumbuhnya nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, dan pencarian makna. Kyai bukan hanya guru, tetapi figur yang menjadi cermin akhlak dan penjaga tradisi. Santri bukan hanya murid, tetapi pewaris nilai dan penjaga warisan.
Relasi ini bersifat batiniah, dibangun atas dasar kepercayaan, keteladanan, dan cinta ilmu. Dalam dunia modern yang menuntut efisiensi dan kompetensi, relasi ini sering kali tampak “tidak rasional” bagi mereka yang melihat dari luar. Namun justru di sanalah letak kekuatan pesantren. Pesantren menawarkan alternatif terhadap dunia yang kehilangan arah, dunia yang sering kali mengukur segalanya dengan matriil uang dan status.
Polemik Trans7 menunjukkan bahwa pesantren masih rentan terhadap kesalah pahaman opini publik. Dalam upaya mengejar sensasi dan rating, media bisa saja menyajikan narasi yang bias dan reduktif. Ini menjadi tantangan bagi pesantren untuk membangun narasi alternatif dengann memperkuat dokumentasi, literasi, dan ruang dialog yang menunjukkan kedalaman relasi santri dan kyai. Santri era kini bukan hanya murid, tetapi juga penulis, peneliti, dan pembela nilai. Kyai bukan hanya pemimpin ritual, tetapi juga penjaga nilai moral dalam dunia yang semakin kompleks.
Di sisi lain, pesantren juga perlu melakukan refleksi internal. Modernisasi tidak bisa dihindari, tetapi harus diiringi dengan pembaruan nilai. Kyai dan santri perlu membangun relasi yang adaptif, dialogis, dan terbuka terhadap perubahan. Tradisi tidak boleh menjadi beban, tetapi harus menjadi sumber inspirasi untuk menjawab tantangan zaman. Dalam konteks ini saya mengamini pendapat Cak Nur dalam salah satu bukunya, beliau berpendapat bahwa seyogyanya pesantren harus menjadi ruang pembebasan, bukan pengekangan. Pesantren harus menjadi ruang pencarian makna, bukan sekadar pelestarian bentuk.
Relasi santri dan kyai di era modern setidaknya harus ditopang oleh tiga hal yaitu keikhlasan, keterbukaan, dan keberanian. Keikhlasan untuk tetap menjadikan ilmu sebagai jalan ibadah. Keterbukaan untuk menerima kritik dan perubahan. Keberanian untuk membela nilai dalam ruang publik, termasuk menghadapi narasi yang menyimpang.
Polemik Trans7 bisa menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama bahwa pesantren bukan hanya milik kalangan internal, tetapi bagian dari wajah kebudayaan Indonesia. Ia harus hadir dalam ruang publik dengan narasi yang jernih, mendalam, dan membebaskan. Santri dan kyai harus menjadi subjek, bukan objek dalam pemberitaan. Mereka harus menulis, berbicara, dan membangun ruang yang adil bagi semua kalangan.
Dengan semangat dari Bilik-Bilik Pesantren ala Cak Nur, kita diajak untuk melihat pesantren bukan sebagai ruang tertutup, tetapi sebagai bilik-bilik kesadaran zaman. Relasi santri dan kyai adalah warisan spiritual yang harus dijaga, diperbarui, dan diwariskan. Bukan hanya dalam bilik-bilik fisik, tetapi dalam bilik-bilik pemikiran dan tindakan. Di era modern, pesantren harus menjadi mercusuar nilai, bukan sekedar menara gading tradisi.
Editor: Soleh


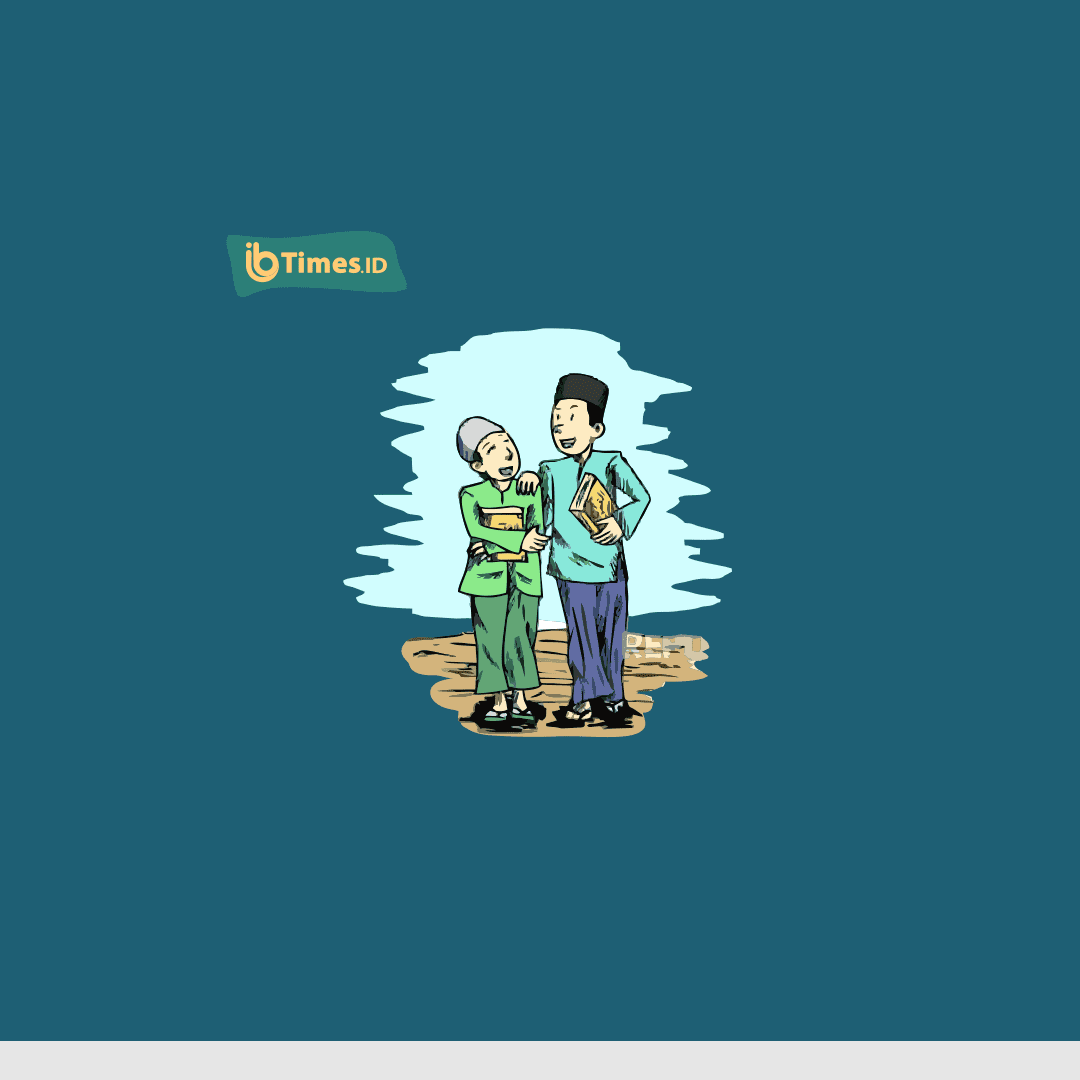

reflektif,