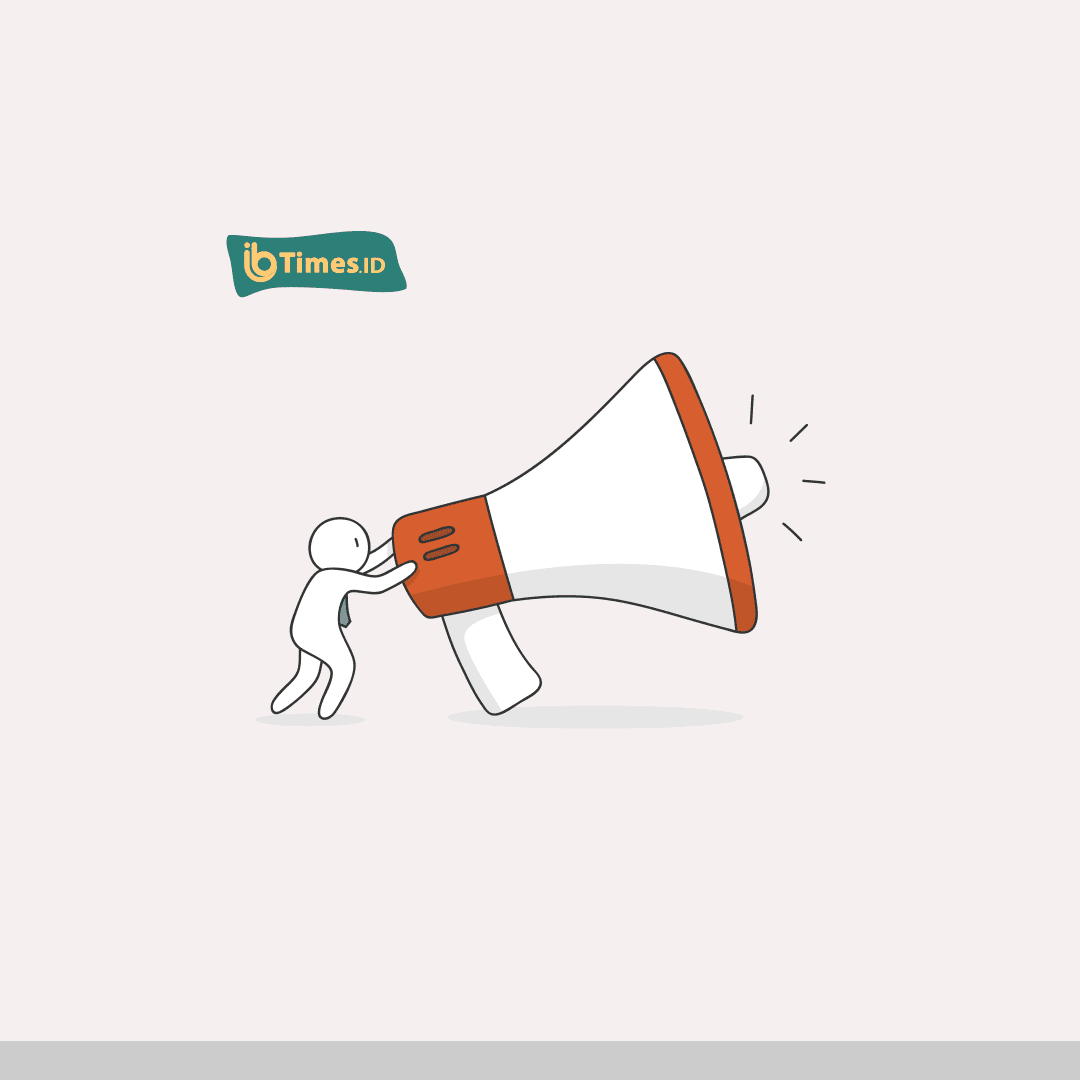Rasanya ada benarnya pepatah yang mengatakan ada dua jenis orang yang susah diingatkan atau “move on” dalam kegagalan, yaitu kegagalan dalam menjalin tali kasih percintaan dan kalah dalam memilih pilihan ideal dalam pilpres. Dalam pengamatan penulis dan menyimak lalu lalang lalu lintas postingan chat atau status di grup-grup media sosial atau platform sosial, begitu berseliweran narasi-narasi kebencian kolektif yang berasal dari kebencian-kebencian dari level individu yang menemukan habitatnya yang sama sehingga terjadilah kapitalisasi kebencian (hatred capitalization) yang membuncah.
Mengapa sebenarnya perbedaan pilihan politik (baca: pilpres) memacu nuansa kebencian yang menjalar dan masif sehingga kampanye hitam dan negatif dengan begitu mudah diposting, disharing dan dimasifkan secara membabi-buta terhadap individu pasangan Capres-Cawapres tertentu.
Narasi Kebencian
Kebencian (hate, hatred) adalah sebuah perasaan mendalam (intense) yang mengandung unsur ketidaksukaan berlebihan dalam waktu yang cukup lama. Sebagai sebuah momentum besar dan kolosal dari sekian banyak proses atau kontestasi pesta demokrasi, maka momentum pilpres merupakan sebuah mozaik preferensi pilihan kolektif individual dengan motif preferensi pilihan yang sangat kompleks dan lintas batas tanpa memandang status sosial dan alasan rasional atau emosional dalam pilihan individu terhadap pasangan capres-cawapres yang mereka pilih sesuai dengan pilihan nurani mereka.
Memang, secara realitas dan efek psikososial, perbedaan dalam pilihan politik (baca: pilpres) bagi sebagian besar individu tertentu menimbulkan efek “othering” atau labelisasi “orang lain”, meminjam istilah Eli J. Finkel, Professor Psikologi dari Northwestern University, AS, (2021). Efek “othering” mengesankan bahwa orang yang berbeda pilihan politik dikesankan sebagai orang lain atau intruder karena berbeda pilihan dan idealisme politik.
Menurut Utami & Darmaiza (2020) ujaran kebencian (hate speech) dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yaitu: sindiran/sarkasme, berita bohong (hoax), makian, distorsi, cacian, dan kritik negatif. Beberapa jenis ujaran kebencian tersebut dapat dengan mudah kita temukan dan terima dari postingan media dan platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok dan YouTube, dalam bentuk cuplikan video-video yang merupakan hasil editan dan “bombastis” judul dan propagandanya.
Kebencian di Dunia Politik
Lantas apa sebetulnya yang menyebabkan individu begitu “benci” terhadap pasangan capres-cawapres tertentu? Seringkali kebencian yang bermula dari perasaan atau emosi/sentimen pribadi berlanjut menjadi sebuah kebencian massal yang dikapitalisasi dan mendapatkan justifikasi kolektif dari individu yang memiliki kesamaan narasi kebencian yang sama.
Menurut Eric Heinze (2016) dalam bukunya yang berjudul “Hate Speech and Democratic Citizenship” dikutip dari Utami & Darmaiza (2020), kebencian dalam dunia politik bisa dijadikan alat untuk propaganda mereduksi dan pencitraan negatif terhadap individu lainnya. Ada dua alasan utama mengapa kebencian timbul dalam pilihan politik, yaitu prasangka buruk (stereotyping) terhadap orang atau kelompok lain dan adanya inferioritas atau perasaan terpinggirkan (marginalisasi) dari kekuasaan yang dominan dan berkuasa.
Kedua alasan tersebut menemukan momentumnya ketika media sosial yang begitu instant, accessible, dan collective-sharing opinion dengan mudah menyebarkan secara masif narasi-narasi kebencian yang disebar dan mendapatkan respon “positif” dengan LIKE, SHARE dan COMMENT yang memiliki afeksi, emosi dan sentimen yang sama.
Kebencian: Dunia Virtual vs Realitas
Media sosial dan media massa sangat berperan dominan dan kontributif dalam menstimulus dan kapitalisasi kebencian. Konstruksi kebencian yang terbangun seringkali secara fokus ditujukan kepada individu tertentu dengan memanfaatkan segala cara dan “angle” negatif atau keburukan paslon lain. Itulah dunia “untouchable” yang seringkali kebenarannya absurd.
Narasi yang dibangun seringkali bukan berupa data dan fakta, tetapi lebih kepada narasi kualitatif yang sentimental dan emosional terhadap individu tertentu. Menurut hemat penulis, fenomena narasi kebencian dapat menjadi fenomena ghibah massal dan kolektif yang sebatas mempertontonkan perbincangan liar, gosip, diskursus parsial dan emosional yang lebih cenderung membicarakan keburukan dan “dosa” individu tertentu, bukan menawarkan gagasan atau ide objektif dan faktual disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan ilmiah dan empirik.
Semuanya kembali bermuara kepada daya literasi dan nalar individu, hanya saja masalahnya di era kebebasan bermedia sosial ini, semuanya dapat menjadi seolah-olah “faham dan menguasai” dengan isu atau permasalahan tertentu yang seharusnya cukup menjadi diskusi atau diskursus ilmiah terbatas dalam sebuah forum ilmiah dan akademik yang objektif dan rasional, bukan mengumbar liar narasi kebencian yang didasari emosi, sentimen, stereotyping dan prasangka-prasangka, yang sebagaimana agama pun menganjurkan umatnya untuk menjauhi prasangka buruk (dzhan) atau sebuah prejudice.
Mari stop narasi kebencian, kalaupun ada kebencian dalam hati cukup disimpan dalam hati, tidak kemudian dikapitalisasi menjadi sebuah diskursus liar yang berujung pada fenomena ghibah di media sosial. Semoga.
Editor: Ahmad