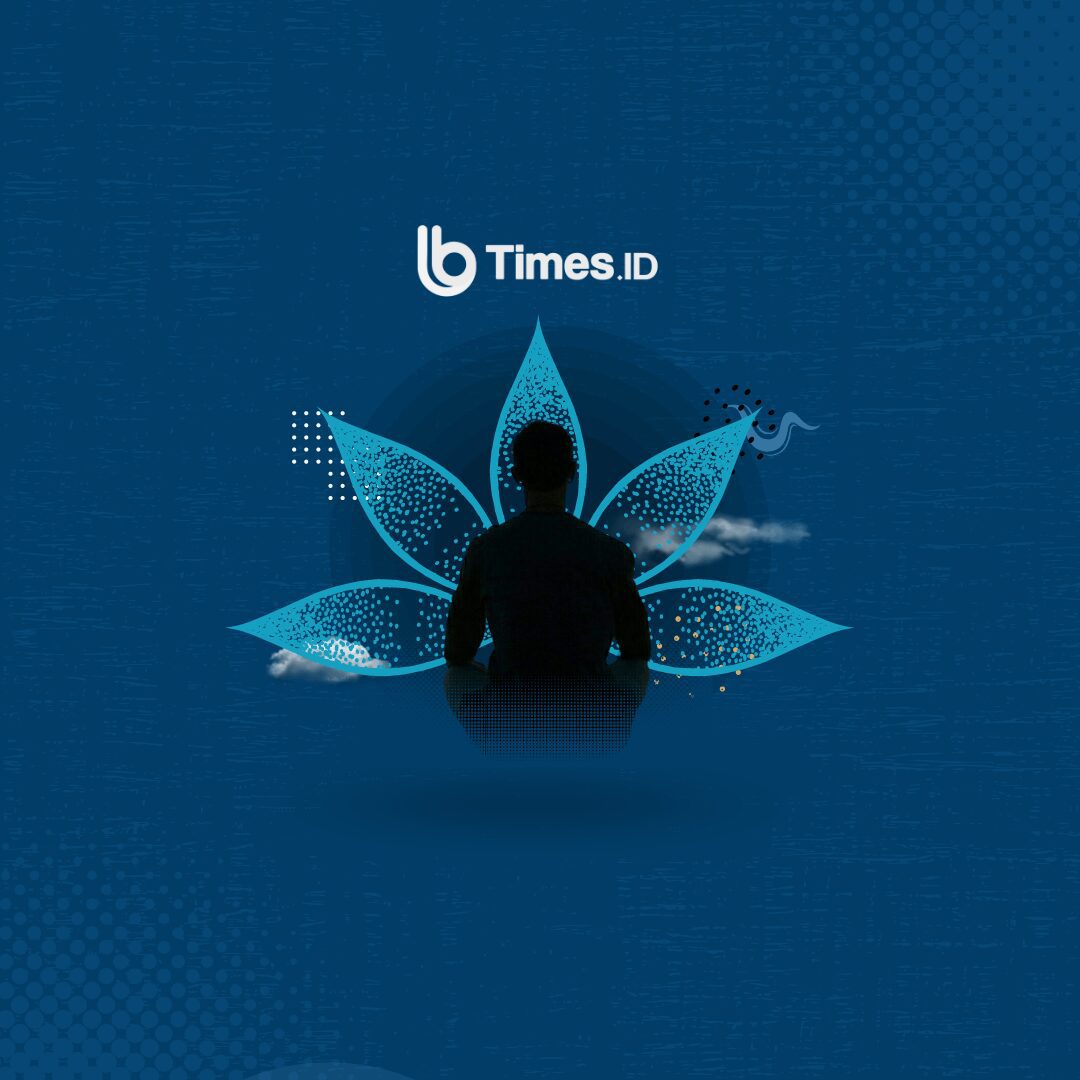Agama adalah suatu kebutuhan dasar manusia, tanpa agama manusia akan mengalami kehampaan akan nilai-nilai spiritual. Hadirnya agama menjadi pelita ditengah kehidupan masyarakat yang terlena karena nilai-nilai materialisme. Agama datang membawa misi pembebasan bagi umat manusia agar terlepas dari belenggu materialisme yang lambat laun telah mematikan moral manusia. Sebagaimana Rasulullah Saw. adalah seorang yang membebaskan masyarakat Makkah dari materialisme pada masa itu (Armstrong, 1993: 211-215).
Beragama sejatinya merupakan fitrah manusia, tidak ada yang bisa lepas dari agama. Kapanpun dan dimanapun kita tidak bisa lepas dari kepercayaan (agama). Tatkala kita berkunjung ke suatu tempat, mungkin kita bisa tidak menemukan pasar ataupun bioskop. Akan tetapi, sangat kecil kemungkinan bagi kita untuk tidak menemukan tempat peribadatan (Shihab, 2011: 75).
Manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dalam setiap hal, entah itu kerabat ataupun koleganya sebagai konsekuensi dalam sosial. Bahkan dalam titik terendah kehidupan manusia, ketika tidak ada yang dapat memenuhi keinginannya. Ia akan memohon kepada Zat yang Maha Mutlak untuk meminta pertolongan atas keterbatasan yang ia miliki.
Kebutuhan Spiritualitas Semakin Meningkat
Deklarasi “Kematian Tuhan” menyebabkan Eropa kehilangan Iman secara dramatis. Kaum beragama mengalama tahun-tahun yang sulit terutama pasca Perang Dunia kedua. Jumlah orang Inggris yang tidak ingin ke Gereja mengalami kenaikan yang drastis, bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya.
Kemerosotan agama juga ditandai dengan perubahan budaya seperti ambruknya sturkutur kelembagaan modernitas, sensor diperlonggar, aborsi, homoseksual, perceraian menjadi lebih mudah, gerakan perempuan mengampanyekan kesetaraan gender, serta anak muda yang mencerca etos modern orang tua mereka. Namun ada hal yang menarik, terlepas dari penolakan stuktur otoritas lembaga keagamaan, budaya kaum muda tahun 60-an menuntut sebuah hidup yang lebih religius.
Spiritualitas timur menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka, alih-alih pergi ke gereja, mereka justru pergi ke Kathmandu atau mencari teknik meditasi Timur. Spiritualisme Timur layaknya “permata yang hilang” karena selama ini dicari oleh mereka, dikarenakan epistemologi barat yang sangat rasionalistik melupakan aspek intuitif dalam kehidupan. Karena hal tersebut Karen Armstrong menegaskan terlalu dini berbicara tentang kematian Tuhan (Armstrong, 2011: 394-395).
Kebutuhan akan spiritualitas senantiasa bertambah, bahkan kebutuhan spiritualitas di negara-negara maju lebih tinggi, ketimbang di negara-negara berkembang. Di Amerika serikat misalnya, sejak tahun 1960-an perkembangan spiritualitas cenderung kuat, hal ini dapat kita lihat dari maraknya budaya hippies yang memberontak terhadap nilai-nilai kemapanan. Arus globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi serta akses informasi yang begitu kentara menjadikan manusia hampa. Kemapanan yang terjadi tidak dapat memenuhi jiwa rohani, menjadikan manusia hampa (Bagir, 2019: 19-20). Fenomena ini menegaskan bahwa harta bukanlah jaminan akan kebahagiaan, namun manusia juga membutuhkan aspek religius dalam kehidupannya.
Bahkan dalam internal agama Islam sendiri, perkembangan spiritualitas semakin banyak. Upaya mengatasi kekeringan nilai spiritual tersebut yaitu melalui jalan Tasawuf. Seyyed Hossein Nasr menjelaskan bahwa Tasawuf layaknya nafas yang memberikan hidup pada tubuh, ia telah memberikan semangatnya pada stuktur Islam, baik dalam perwujudan sosial maupun intelektual (Nasr, 2020: 22).
Tasawuf sebagai gerakan spiritual memilih jalan cinta sebagai upaya memahami agama. Basis epistemologi tasawuf menggunakan pendekatan intuitif, karena seringkali akal dijadikan pusat sentral untuk memahami perkara, padahal akal bukan satu-satunya instrumen pengetahuan, melainkan salah satunya.
Al-Qur’an sendiri mengisyaratkan bahwa hati dapat dijadikan sumber pemahaman yaitu, “mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami” (QS. 7: 179). Namun makna hati disini bukan dalam arti indrawi, tetapi makna majazi (metafora) yang bermakna menggunakan aspek-aspek irasional dalam menentukan perkara.
Aspek-aspek irasional tersebut antara lain sabar, syukur, cinta karena hal tersebut bertentangan dengan rasionalitas. Hati adalah menjadi pertimbangan dalam menentukan perkara agar manusia tidak menjadi kaku serta bertangan dingin. Layaknya seorang hakim tatkala memvonis hukuman diharapkan tidak hanya terpaku terhadap aspek formalitas suatu hukum, namun juga mempertimbangkan aspek-aspek diluar hukum seperti keadaan pribadi seorang terdakwa, maka inilah yang disebut sebagai kebijaksaan melihat situasi maupun kondisi.
Agama Merupakan Aspek Primordial dalam Batin
Agama adalah persaksian seorang manusia kepada Tuhannya, jauh waktu sebelum kita dapat dikatakan menjadi sesuatu, kita telah mengambil sumpah bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang exist. Sebagaimana di Al-Qur’an dijelaskan: Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul kami bersaksi (engkau Tuhan kami)”. (QS. 7: 172).
Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan dua alasan mengapa Allah mengambil persaksian atas manusia. Yang pertama, agar manusia dihari kiamat kelak tidak berdalih dengan mengatakan bahwa mereka tidak tahu atau lengah karena tidak ada petunjuk dari Allah sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur’an: “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini”. Persaksian itu memberikan setiap manusia potensi untuk mengetahui Keesaan Allah melalui fitrah yang telah Allah berikan.
Yang kedua, agar manusia pada hari kiamat kelak tidak berdalih bahwa Iman mereka mengikuti keturunan sebelumnya, sehingga dengan persaksian ini setiap manusia diberikan peluang untuk menolak siapapun walaupun orang tuanya sendiri, apabila mereka mengajak kepada kedurhakaan dan menyekutukan Allah. Sebagaimana dijelaskan Al-Qur’an: “Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan, kami hanyalah anak keturunan mereka”.
Disisi lain beragama juga merupakan aspek paling luhur dalam batin manusia, sangat mustahil bagi manusia untuk meniadakan agama dalam batinnya. Maka dari itu manusia disebut juga sebagai homo religious, yaitu makhluk yang dapat kehidupannya selalu bergantung kepada nilai-nilai spiritual. Hal ini juga menafikkan anggapan bahwa agama merupakan hasil kreatifitas dari pikiran manusia, sejatinya keyakinan akan Tuhan merupakan fitrah manusia “Fitrah Allah yang telah diciptakan-Nya kepada manusia” (QS. 30: 30).
Menurut Karen Armstrong dalam bukunya History of God beliau menjelaskan, “Manusia tidak bisa menanggung beban kehampaan dan kenestapaan; mereka akan mengisi kekosongan itu dengan menciptakan fokus baru untuk meraih hidup yang bermakna” (Armstrong, 1993: 584). Manusia akan mengagungkan apapun yang mereka anggap memiliki potensi lebih, entah karena ketakutan ataupun kekaguman terhadap yang lebih tinggi dari dirinya.
Sejatinya orang-orang atheis itu tidak meninggalkan Tuhan, namun mereka hanya beralih dari tuhan yang satu, menuju tuhan yang lainnya. Dalam hal ini kaum atheis itu menuhankan pemikiran mereka, sehingga itulah yang menjadi apa yang dikatakan Armstrong sebagai “fokus baru” setelah sebelumnya meninggalkan tuhan-tuhan mereka yang lama.
Agama tanpa nilai spiritualitas hanyalah dogma yang hampa, bagaimana iklim beragama kita dewasa ini, apakah penuh dengan aspek spiritualitas ataukah miskin akan spiritualitas. Agama sebagai aspek primordial dalam hidup menuntut manusia untuk hidup dalam kasih dan sayang, serta meninggalkan potensi permusuhan. Spiritualitas dalam beragama adalah wisdom bagi kaum beriman dalam menjalankan perintah-Nya.
Editor: Soleh