Di era media sosial, agama tak lagi sekadar ajaran suci yang menuntun jiwa, tapi juga menjadi “konten” yang bisa diperdebatkan, dijual, bahkan dikomodifikasi. Kita menyaksikan betapa banyak ulama dan tokoh agama saling mengomentari, saling menyindir, bahkan saling menegasikan di ruang publik.
Ironisnya, fenomena itu tidak hanya terjadi antar kelompok yang berbeda ideologi, tapi juga di dalam tubuh yang sama — satu ormas, satu mazhab, bahkan satu manhaj.
Ulama kini bukan hanya menafsirkan teks, tapi juga “mengelola citra.” Media sosial telah mengubah sebagian mereka menjadi public performer — ustaz seleb, kiai viral, pendakwah influencer — yang lebih sibuk membangun pengikut ketimbang memperdalam pengetahuan.
Dalam iklim seperti itu, perbedaan pandangan teologis yang sejatinya biasa dan sehat dalam tradisi keilmuan Islam, berubah menjadi ajang saling serang. Akibatnya, umat yang mestinya tercerahkan, justru terpecah dan bingung: siapa yang harus diikuti, dan mana yang benar?
Namun menariknya, di tengah riuh rendah debat di ruang publik itu, ada satu fenomena yang relatif tenang: Muhammadiyah. Organisasi ini seperti oase di padang gersang perdebatan tak produktif. Para ulama, cendekiawan, dan aktivisnya jarang terlihat saling sindir di media sosial.
Mereka tidak sibuk mengomentari siapa yang paling benar dalam hal furu’iyah, tidak saling menggugat soal siapa yang paling paham manhaj tarjih, dan tidak berlomba tampil paling suci di layar kaca. Mereka tampak “adem” — bukan karena tak punya perbedaan, tapi karena mereka memahami bahwa perbedaan bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk diolah menjadi kekuatan intelektual dan sosial.
Kita Butuh Budaya Ilmiah, Bukan Budaya Debat
Tulisan ini bukan saya maksudkan menyombongkan Muhammadiyah, namun sesekali sebagai kader penting membanggakan para tokohnya, para ulamanya yang lebih mengedepankan tradisi ilmiah dibanding keinginan menonjolkan diri. Keteduhan Muhammadiyah bukan datang dari ketiadaan perbedaan, melainkan dari etika intelektual yang tertanam kuat. Adab di atas ilmu itu saya temukan pada para ulama Muhammadiyah.
Dalam tradisi Persyarikatan, perbedaan pandangan diselesaikan bukan di Facebook, Instagram, Twitter atau TikTok, tapi di forum resmi yang disebut Majelis Tarjih dan Tajdid. Di sana, perbedaan diuji dengan dalil, data, dan argumentasi ilmiah yang terukur. Setiap hasil ijtihad kolektif tidak lahir dari suara paling keras, tapi dari nalar paling jernih. Karena itu, ketika Majelis Tarjih menetapkan fatwa atau pandangan keagamaan, masyarakat Muhammadiyah menerimanya dengan tenang — bukan karena fanatik, tapi karena percaya pada proses ilmiahnya.
Budaya ini berakar dari semangat tajdid — pembaruan. Muhammadiyah mengajarkan bahwa Islam tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus bergerak ke konteks. Inilah mengapa ulama-ulama Muhammadiyah tidak sibuk mengulang debat klasik tentang bid’ah atau tidaknya qunut, tetapi memilih membahas kalender hijriah global tunggal (KHGT), ekonomi syariah progresif, fatwa zakat saham, atau wakaf produktif. Mereka berdebat, tentu saja, tapi dalam ruang-ruang akademik, di jurnal, di simposium, di meja riset — bukan di kolom komentar media sosial.
Kesadaran Kolektif: Ulama sebagai Pelayan Umat, Bukan Pesaing
Ada satu kesadaran penting yang membentuk karakter ulama Muhammadiyah: bahwa mereka adalah pelayan umat, bukan pesaing satu sama lain. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi dalam dunia dakwah hari ini — di mana setiap ustaz ingin menjadi brand — kesadaran seperti itu menjadi langka. Mungkin pandangan saya subyektif karena saya kader Muhammadiyah, namun media sosial menunjukkan karakter ulama Muhammadiyah ini.
Muhammadiyah membentuk ulama bukan untuk menjadi figur karismatik yang dikultuskan, tapi untuk menjadi bagian dari sistem kolektif dakwah yang terorganisir. Karena itu, mereka tidak menonjolkan “siapa saya”, melainkan “apa kontribusi saya”. KH Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa dakwah adalah kerja sistem, bukan kerja personal. Maka tidak heran bila kita jarang mendengar satu ulama Muhammadiyah mencaci ulama Muhammadiyah lainnya — bukan karena mereka semua sepakat, tetapi karena mereka semua kompak dalam orientasi dakwah.
Kekompakan ini lahir dari etos ikhlas beramal. Mereka sadar, kebenaran bukan milik satu kepala, tetapi hasil dari kerja kolektif yang dilandasi iman dan ilmu. Maka, perbedaan ditampung, bukan ditonjolkan. Kritik dibicarakan, bukan dipertontonkan. Semangatnya adalah fastabiqul khairat, bukan fastabiqul debat. Dalam mengusung KHGT misalnya, bukan tidak ada pertentangan dan perdebatan, namun semua diselesaikan pada majelis ilmu bukan diumbar pada media social.
Islam Berkemajuan: Dakwah yang Mencerahkan, Bukan Menyulut Emosi
Muhammadiyah menamai arah gerak intelektualnya sebagai Islam Berkemajuan. Bukan slogan kosong, tapi visi epistemologis. Islam yang tidak menakut-nakuti, tetapi mencerahkan. Islam yang tidak reaktif, tetapi solutif. Islam yang hadir bukan untuk menegur siapa yang salah, tetapi menawarkan jalan bagaimana menjadi benar.
Itulah sebabnya, alih-alih menghabiskan energi untuk membantah sesama dai, Muhammadiyah memilih menghadirkan karya nyata: Fatwa-fatwa yang sejuk berdalil, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang melayani semua golongan, Lembaga ZISWAF yang menyalurkan dana umat untuk pemberdayaan, universitas-universitas Islam modern yang melahirkan intelektual muslim global.
Inilah bentuk dakwah yang berkemajuan: menyalakan lilin, bukan meniup api. Dan mungkin, inilah mengapa umat merasa tenteram ketika mendengar pandangan dari ulama Muhammadiyah — karena mereka bicara dengan tenang, bekerja dengan ilmu, dan bergerak dengan niat tulus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Belajar dari Keteduhan Ulama Muhammadiyah
Umat Islam hari ini perlu belajar dari keteduhan Ulama Muhammadiyah. Bukan untuk menjadi Muhammadiyah, tapi untuk memahami bagaimana perbedaan bisa dikelola dengan akal sehat dan hati lapang. Dunia digital memang menggoda setiap orang untuk tampil, tetapi tidak semua yang tampil memberi manfaat.
Kita perlu kembali menghidupkan etika al-adab qabla al-‘ilm — adab sebelum ilmu. Sebab, ilmu tanpa adab melahirkan arogansi, dan dakwah tanpa etika hanya akan melahirkan perpecahan. Para ulama, kiai, dan ustaz perlu sadar: umat sedang menunggu teladan, bukan tontonan. Umat haus ketenangan, bukan keributan.
Dan mungkin, inilah saatnya kita bertanya jujur pada diri sendiri: ingin dikenal karena debat kita, atau karena kontribusi kita?
Di tengah dunia yang gaduh, Muhammadiyah memilih menjadi tenang. Di tengah umat yang mudah terbakar emosi, mereka memilih menjadi cahaya. Mungkin sederhana, tapi justru karena kesederhanaan itulah mereka besar — dan tetap kokoh sebagai kekuatan moral-intelektual Islam yang berkemajuan.
Umat tidak butuh lebih banyak perdebatan. Umat butuh lebih banyak keteladanan. Dan keteladanan itu, seperti yang ditunjukkan oleh para ulama Muhammadiyah, tidak lahir dari siapa yang paling benar, tetapi dari siapa yang paling tulus bekerja untuk kebenaran.
Editor: Soleh


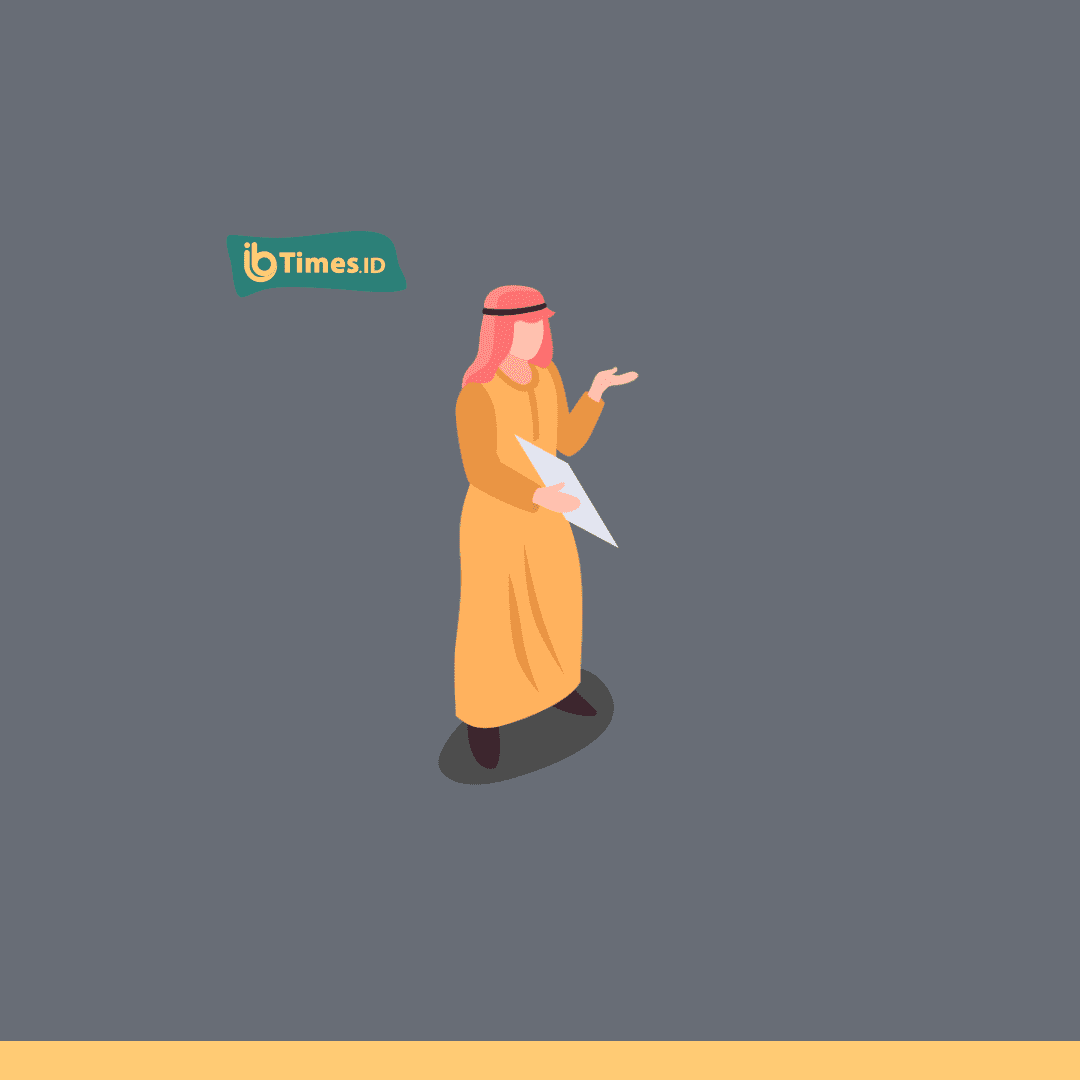

Tulisan yg renyah dan menyadarkan untuk semua. Baik ulama nya maupun jamaahnya.