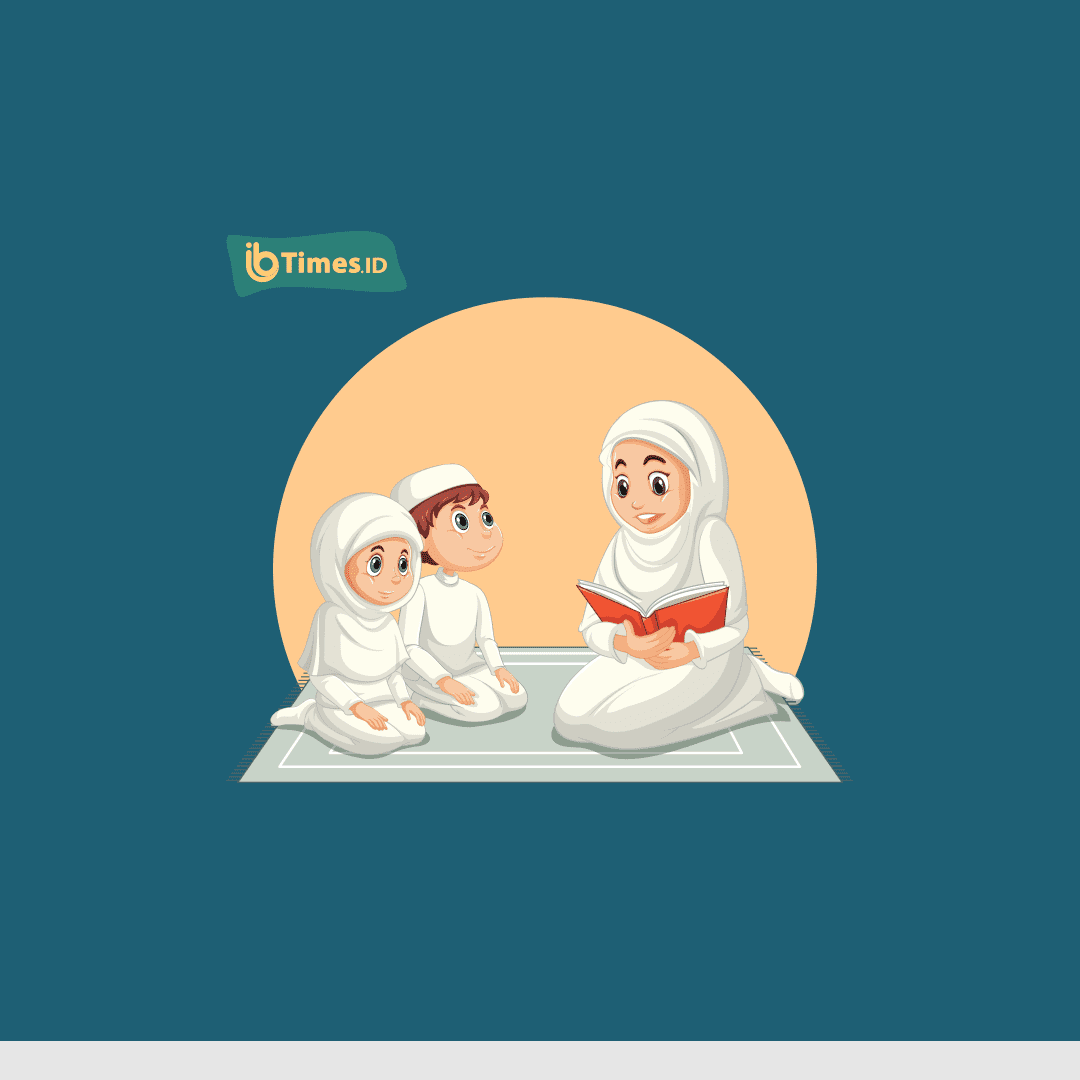Penetapan 22 Desember sebagai Hari Ibu Indonesia, bukan untuk perayaan atas jasa seorang ibu dan istri atas peran domestiknya belaka. Lebih dari itu, ini tentang kebangkitan pergerakan perempuan untuk Indonesia merdeka. Tentang persatuan gerakan perempuan menolak ketidakadilan gender, menolak diskriminasi, dan marginalisasi.
Bermula dari Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 yang membuahkan Sumpah Pemuda dengan salah satu ikrar, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ternyata juga “membakar” semangat di kalangan aktivis perempuan, untuk menggalang persatuan antarorganisasi perempuan yang cenderung bergerak sendiri-sendiri kala itu.
Tanggal 22-25 Desember tahun yang sama, dilaksanakan Kongres Perempuan Indonesia Pertama, di Ndalem Joyodipuran Jogyakarta.
Kalangan aktivis perempuan muda pun ikut memprakarsai kongres tersebut. Ada Soejatien, Ketua Putri Indonesia yang menjadi Sekretaris panitia kongres. Ia belum menikah ketika itu.
Soejatien adalah murid Soekarno dan Ki Hajar Dewantoro. Perempuan muda, berorganisasi, berpengetahuan, memang selalu dapat diandalkan.
Laman wikipedia.org mencatat, Ni Soejatien mendampingi Ibu Ketua panitia, R.A. Soekonto, anggota Wanito Utomo dan guru di HIS (sekolah Hindia Belanda untuk pribumi) dan wakilnya, Nyi Hadjar Dewantara, istri Ki Hajar Dewantara.
Tonggak Kebangkitan Gerakan Perempuan
Kongres Perempuan Indonesia Pertama itu betul-betul menjadi tonggak penting bagi kebangkitan gerakan perempuan. Menunjukkan kematangan pemahaman dan sikap politik (nasionalisme) yang tinggi dari kalangan pergerakan perempuan, untuk ikut mewujudkan Indonesia merdeka.
Berbagai organisasi perempuan bersatu dan bertekad memperjuangkan hak-hak yang adil bagi perempuan. Mereka menolak diskriminasi, marginalisasi, dan ketidakadilan gender. Menolak dipersiapkan (hanya) untuk dikawinkan. Lalu menjadi istri, menjadi ibu, dan mengurus rumah tangga.
Jika dianggap tak becus mengurus suami, dapat dicerai kapan saja lalu dikembalikan (seperti barang) ke rumah orang tuanya. Dianggap tak berguna.
Salinan dari laporan-laporan mengenai Kongres Perempuan pertama ini dimuat dalam edisi perdana majalah Isteri. Oleh Susan Blackburn, Profesor di Universitas Monash Melbourne Australia diterbitkan ulang dalam bukunya “Kongres Perempuan Pertama – Sebuah Tinjauan”.
Blackburn mencatat bahwa peserta Kongres Perempuan pertama itu berasal dari utusan 23 organisasi berbasis keagamaan (Islam, Katolik) dan organisasi non-agama.
Mayoritas peserta datang dari Jawa. Sehingga, masalah keterwakilan peserta dan isu “jawa sentris” menjadi perhatian. Namun demikian, sejumlah organisasi perempuan dari Sumatera rupanya menyatakan dukungan dengan mengirimkan telegram.
Sebagaimana ikrar Sumpah Pemuda, komitmen menjadikan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa persatuan pun ditunjukkan dalam pidato-pidato selama kongres. Hanya satu perwakilan organisasi yang berpidato dengan Bahasa Jawa. Selebihnya menggunakan Bahasa Indonesia.
Kongres membahas berbagai topik yang sangat maju, bahkan masih sangat relevan hingga hari ini. Mengidentifikasi berbagai ketimpangan gender mulai dari pendidikan untuk perempuan, menghentikan perkawinan anak, hingga reformasi undang-undang perkawinan Islam (Wiering, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia).
Lihat beberapa judul pidato berikut misalnya, “Deradjat Perempoean”, “Perkawinan Anak-Anak”, “Doedoeknja Perempoean di Kehidoepan Sama-sama”, “Bagaimanakah Djalan Kaoem Perempoean Waktoe Ini dan Bagaimanakah Kelak?”, “Hal Keadaan Isteri di Europah”, dan sebagainya.
Sungguh sangat progresif dan visioner. Mereka tidak lagi (hanya) membincangkan bagaimana berdandan untuk menyenangkan suami. Atau bagaimana memasak menu-menu spektakuler atau resep tradisional untuk menyenangkan lidah suami, atau bagaimana tips-tips mengurus anak-anak dengan baik, sebagaimana kodratnya sebagai ibu.
Mereka membahas derajat dan kedudukan yang adil bagi perempuan dan kontribusi perempuan untuk Indonesia merdeka.
Menjadi Hari Ibu Indonesia
Tanggal hari pertama Kongres Perempuan Indonesia Pertama (22 Desember) itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu.
Hari di mana perempuan Indonesia menyatakan komitmen dalam satu visi pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Sekaligus untuk kemerdekaan perempuan, dengan kedududukan yang setara dan adil dalam rumah tangga, dalam kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa yang ketika itu bahkan belum merdeka.
Sekali lagi, untuk pergerakan kemerdekaan Indonesia (dari penjajahan) dan kemerdekaan perempuan dari cengkraman diskriminasi dan ketidakadilan gender.
Jadi, Hari Ibu Indonesia adalah hari penghormatan pada perjuangan perempuan untuk kemerdekaan Indonesia. Hari perjuangan perempuan mengakhiri diskriminasi dan ketidakadilan.
Keputusan menjadikan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu, merupakan hasil Kongres Perempuan ketiga (1938) di Bandung. Lalu, Presiden Soekarno meresmikan tanggal tersebut sebagai Hari Ibu Nasional melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1953.
Isu-isu yang Masih Relevan
Setelah 92 tahun berlalu, Hari Ibu Indonesia tetaplah menjadi titik awal kebangkitan gerakan perempuan Indonesia. Titik awal keberhasilan “menerobos” hukum rimba patriarki yang semula tak bisa dilewati.
Tentu saja masih banyak tantangan hingga hari ini. Misalnya, masalah perkawinan anak yang masih tinggi. UNFPA menyebutkan bahwa satu dari lima anak berusia di bawah 18 tahun di seluruh dunia sudah kawin.
Indonesia menduduki peringkat ke-8 tertinggi di dunia. Masa pandemi COVID-19 diprediksi meningkat 13 juta di dunia. Indonesia menjadi penyumbang besar di sana.
Angka kekerasan terhadap perempuan juga makin tinggi. Satu dari tiga perempuan Indonesia mengalaminya (BPS, 2016). Komnas Perempuan bahkan menyebut Indonesia darurat kekerasan seksual. Angkanya mencapai 4.898 kasus pada tahun 2019. Modus kekerasan seksual pun terus berkembang berbasis online. Tak ada payung hukum yang melindungi korban.
Pandemi COVID-19 ternyata juga memperburuk kesetaraan gender, di mana 19% perempuan mengalami peningkatan beban kerja domestik dan pengasuhan tak berbayar, sedangkan laki-laki hanya 11% (UN Women, 2020).
Jadi, Hari Ibu adalah momentum konsolidasi gerakan perempuan dengan gerakan sosial lainnya, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Karena masalah ketimpangan gender bukan masalah perempuan, tetapi masalah bangsa ini.
Tentu kita harus berterima kasih atas peran domestik perempuan sebagai ibu dengan kerja-kerja produksi dan reproduksi yang tak berbayar itu.
Harus menghormati mereka dengan sehormat-hormatnya. Tetapi, menjadikan Hari Ibu hanya sebagai perayaan untuk pemuliaan (glorifying) jasa seorang ibu atas peran domestiknya saja, sungguh telah melenceng dari sejarah ditetapkannya Hari Ibu itu sendiri.
Editor: Lely N