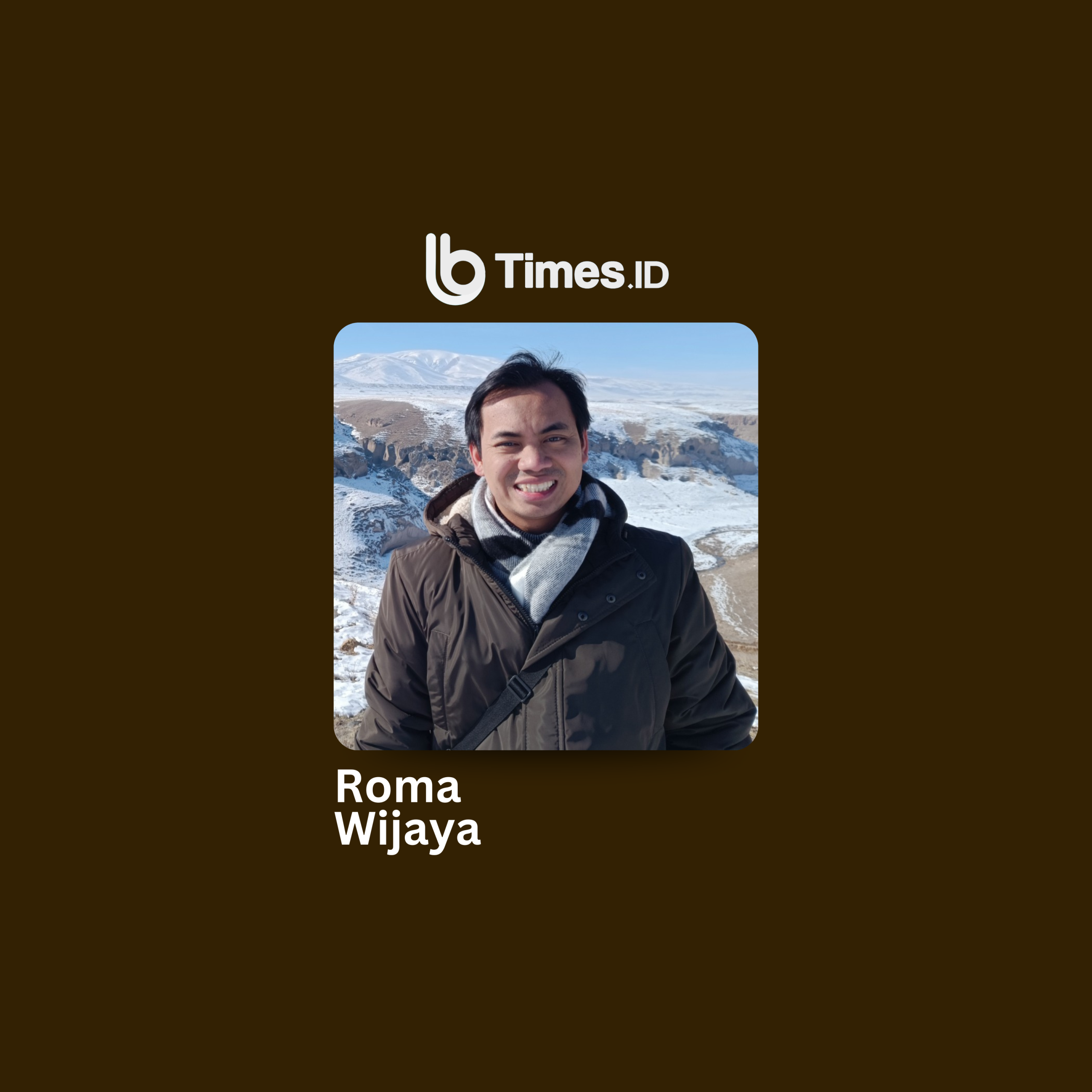Kita sering mendengar dan berucap frasa, “Ini sudah takdir Tuhan” ketika bencana
ekologis melanda Indonesia seperti banjir bandang, longsor, atau kebakaran hutan. Narasi ini,
sayangnya, sering kali berakhir pada penerimaan pasif, menangguhkan tanggung jawab manusia.
Padahal, jika diamati secara jujur objektif akar masalahnya, kerusakan alam yang kita lihat hari ini
adalah akumulasi kerusakan ekologis yang dilakukan oleh tangan kita sendiri seperti buang
sampah sembarangan, deforestasi, dan lainnya.
Inilah mengapa gagasan yang disampaikan oleh Judith Schlehe, seorang Antropolog dan
Sosiolog dari Universitas Freiburg, Jerman, menjadi sangat penting untuk direnungkan oleh
komunitas Muslim Indonesia. Dalam pemaparannya tentang “Rethinking the Role of Indonesian
Moslem Communities in Raising Social Solidarity,” Prof. Judith menyerukan sebuah paradigma
baru yakni solidaritas tidak boleh berhenti pada batas-batas manusia, tetapi harus meluas kepada
semua makhluk dan alam raya.
Mengkritik Modernitas Melalui Bencana
Sebagai permisalan berdasarkan artikel Judith berjudul “Anthropology of Religion:
Disasters And The Representations of Traditionand Modernity” pandangan yang paling luas
terkait Gempa 2006 di Jawa merujuk pada mitos lokal yang terhubung dengan lanskap, di mana
roh dikatakan mengirim bencana sebagai peringatan agar masyarakat Jawa terutama Sultan dan
penguasa mengingat tradisi mereka.
Hal yang menarik adalah bagaimana bencana dan kerusakan alam menjadi arena untuk menegosiasikan makna antara tradisi dan modernitas. Dalam diskursus tentang gempa, muncul kecenderungan polarisasi baru yaitu modernitas dikaitkan dengan sekularisasi, materialisme, kemerosotan moral, dan eksploitasi ekologis. Serta tradisi diidealkan sebagai model spiritualitas dan keharmonisan global.
Banyak orang menganggap gempa sebagai pertanda atau peringatan dari Allah SWT untuk kembali menjalani hidup bermoral sesuai aturan Islam, menghormati alam, dan menjauhi dosa. Namun, interpretasi yang paling umum juga menyalahkan nilai-nilai modern seperti individualisme, korupsi, konsumerisme, dan intervensi serta perusakan alam.
Kerusakan alam tidak lagi dilihat sebagai nasib pasif, melainkan sebagai kritik pedas terhadap gaya hidup modern yang diyakini telah merusak warisan budaya dan nilai-nilai Jawa. Ini adalah pengukuhan teologis dan kultural bahwa bencana bukanlah takdir pasif, melainkan konsekuensi logis dari akumulasi tindakan yang tidak solider.
Dari Antroposentrisme Menuju Solidaritas Universal
Selama ini, konsep solidaritas di ruang publik Indonesia termasuk dalam wacana
keagamaan terlalu berpusat pada manusia (antroposentris). Kita mudah tergerak membantu
sesama korban bencana, tetapi abai terhadap faktor penyebab bencana itu sendiri yang berasal
dari kerusakan ekosistem.
Judith berargumen bahwa kegagalan kita dalam bersolidaritas dengan alamlah yang
memicu krisis alam. Kerusakan hutan, polusi sungai, dan eksploitasi berlebihan adalah bukti
nyata hilangnya empati terhadap entitas non-manusia. Dengan mengutip scripture mistis lokal
seperti legenda Nyi Blorong yang menunjukkan adanya koneksi spiritual manusia dengan
makhluk air ia menunjukkan bahwa secara kultural, kita memiliki warisan untuk menghargai
alam. Namun, pengakuan spiritual ini harus diangkat ke ranah etika publik dan diperkuat dengan
ilmu pengetahuan modern.
Menggugat “Takdir” dengan Actor-Network Theory
Untuk menjustifikasi perluasan solidaritas ini, Judith menyebut dua kerangka teori yang
relevan yaitu;
Actor-Network Theory (ANT)
Teori ini meminta kita melihat alam semesta sebagai sebuah jaringan kompleks di mana
manusia hanyalah salah satu aktor. Sungai, pohon, tanah, dan hewan juga memiliki peran
(agency) dan hak untuk eksis. Ketika kita merusak sungai, kita tidak hanya merugikan manusia
di hilir, tetapi kita juga memutus mata rantai kehidupan aktor-aktor lain dalam jaringan itu.
Solidaritas adalah pengakuan terhadap agency non-manusia ini.
Multispecies Ethnography
Pendekatan ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup manusia bergantung sepenuhnya
pada makhluk lain. Kita hidup dalam keterikatan (interconnectedness) dengan lebah yang
membantu penyerbukan, dengan mikroba yang menyuburkan tanah, dan dengan hutan yang
membersihkan udara. Kesatuan dengan alam adalah solidaritas untuk kelangsungan hidup diri
sendiri.
Dengan lensa ini, kita bisa melihat bahwa bencana alam bukanlah takdir pasif yang murni
diturunkan dari langit. Ia adalah konsekuensi logis dari akumulasi tindakan yang tidak solider:
pembalakan liar, penimbunan sampah plastik selama puluhan tahun, dan pembangunan yang
serakah.
Inilah yang termaktub jelas dalam Al-Qur’an 30: 41:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah SWT membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
Ayat ini merupakan penegasan teologis bahwa manusia adalah agen sentral serta aktor penyebab kerusakan, dan oleh karena itu, harus menjadi agen sentral pula dalam menciptakan/melestarikan solidaritas yang melingkupi seluruh semesta.
Jalan Muslim Indonesia Menuju Khalifah Semesta
Jangan salah kaprah ketika saya menuliskan term “khalifah” ini bukan semata-mata
bermakna “pemimpin” atau konotasi dukungan saya terhadap pemahaman “khalifah” seperti
sistem politik khalifah yang sudah berlalu (Ottoman, Fathimiyyah, Andalusia, Mamluk, Seljuk,
dan sebagainya). Namun istilah khalifah saya tekankan sebagai “penjaga” tidak hanya sesama
manusia tidak luput pula entitas alam semesta lainnya.
Sejatinya komunitas Muslim Indonesia memiliki modal spiritual yang sangat kuat yaitu
pondasi Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam semesta). Ini adalah
platform teologis terbaik untuk menggerakkan solidaritas universal yang diserukan Judith
Schlehe.
Tanggungjawab kita sekarang adalah mengaktifkan serta melestarikan rahmatan lil ‘alamin ini secara ekologis bertoleransi terhadap semua entitas mahkluk yang bernyawa. Bukan hanya peduli pada anak yatim dan kaum duafa, tetapi juga peduli pada kesejahteraan hutan yang tersisa, kebersihan pantai, dan kelangsungan hidup orangutan di Kalimantan khususnya serta hewan-hewan yang terancam punah lainnya. Jangan sampai deforestasi ini semakin meluas menjadikan ketidakstabilan alam.
Ketika Muslim Indonesia mengubah pandangannya dari penguasa menjadi penjaga (khalifah) bagi seluruh alam, kita tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga menegaskan kembali peran kita sebagai umat yang membawa kasih sayang bagi seluruh ciptaan. Dengan langkah ini, kerusakan alam dan bencana yang terjadi di bumi pertiwi bukan lagi hanya diterima sebagai takdir, tetapi dimaknai sebagai panggilan mendesak untuk kembali menjadi manusia yang solider, tidak hanya antarmanusia, tetapi juga solider terhadap all universe.
Editor : Ikrima