“Jangan baca buku filsafat, nanti kamu jadi atheis!”
“Hati-hati kalau gabung kajian filsafat, ntar ninggalin sholat!”
“Buat apa belajar filsafat? Bisa-bisa murtad kamu!”
Cibiran semacam itu adalah suatu yang umum disampaikan kepada rekan-rekan saya ketika akan mulai belajar filsafat. Cibiran itu akan semakin menukik ketika yang mengucapkan bukan orang sembarangan.
Bisa jadi ucapan itu keluar dari bibir orang-orang terdekat seperti orangtua, teman kos-kosan hingga bahkan ustadz dalam majlis-majlis taklim.
Sebagian akhirnya memilih mundur dini dari petualangan filosofis. “Ketimbang dicabut dari KK atau disembelih dibelakang rumah”, kata mereka. Tapi biasanya lebih banyak yang memilih untuk tetap istiqomah.
Dalam pengamatan saya, mereka-mereka yang tertarik belajar filsafat ini punya trait tertentu. Trait itu adalah gak kerasan di rumah dan bosan hidup.
Salah Paham Soal Filsafat
Kebanyakan pelarangan dan penghujatan kepada filsafat serta para pelajarnya bukan lahir dari pengertian yang benar tentang filsafat. Justru, karena salah paham maka filsafat kemudian dihakimi dengan tidak adil. Misal, paling umum filsafat didefinisi sebagai ilmu anti Tuhan karena mempersoalkan doktrin tentang Tuhan.
Yang lain mungkin memberi pengertian filsafat sebagai ilmu rasional yang juntrungnya bikin seseorang berpaham liberal. Jika sudah liberal, dianggap pasti semaunya menafsirkan ajaran-ajaran Islam. Entah nanti merasa ‘satu’ dengan Tuhan, atau merasa sholat bukan lagi kewajiban. Khawatirnya lagi, nanti mengajak yang lain untuk berpikir demikian.
Menariknya, salah paham semacam ini sudah terjadi sejak lebih dari seribu tahun yang lalu. Para ahli kalam sampai memvonis haram dan menyunat bangunan filsafat dari sejarah Islam karena misinterpretasi mereka mengenai ilmu filsafat. Bahwa filsafat membuat muslim menganggap Tuhan tidak mengendalikan takdir atau bahkan Al-Qur’an hanya makhluk, bukan firman Tuhan.
Karena persoalan salah-paham yang sudah sampai derajat salah-kaprah itulah maka para filsuf muslim mengatur siasat. Bahasa filosofis dibuat teknis dengan gaya selingkung unik. Pun, kajian dalam kitab-kitab filsafat Islam klasik sengaja ditulis padat, tidak detail. Mengapa begitu? Agar setiap yang mau belajar kitab filsafat harus langsung bertanya ke para filsuf yang mumpuni.
Makna Filsafat yang Sejati
Lantas apa sebetulnya filsafat? Perkara ini sebetulnya mustahil dibahas dalam tulisan yang teramat ringkas. Apalagi dalam format yang tidak serius-serius amat seperti disini. Namun, setidaknya satu-dua pasal tentang hakikat dan perbedaan filsafat di Barat dan Islam musti dimengerti. Meski sekilasan dan umum sekali.
Filsafat seperti yang sering kita dengar adalah ‘mencintai kebijaksanaan’. Wajar kalau kita teliti banyak akun-akun filsafat yang isinya quotes-quotes inspiratif penuh motivasi. Mereka ini yang biasanya kita unduh dan repost di story. Agar seolah-olah kita bijak. Walau begitulah netizen, yang dipublikasi sering beda dengan yang dieksekusi.
Pengertian ini ada benarnya, tapi ga sepenuhnya juga. Dalam tradisi filsafat Islam dan filsafat Barat terjadi persilangan. Ini dapat ditelusuri dari akar sejarahnya. Filsafat Islam cenderung meneruskan tradisi filsafat yunani yang spiritualis. Sebut saja Socrates, Plato dan Aristoteles. Ketiganya sama-sama meyakini bahwa puncak dari filsafat adalah memahami Tuhan.
Kecenderungan itu bisa ditilik dalam karya-karya filsuf besar Muslim seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. Barat sendiri mengakui mereka sebagai sebagian pengembang dan komentator paling penting untuk karya-karya Aristoteles. ‘Paripatetisme Islam’ ini mati di Sunni, tapi sukses disemai Mulla Sadra melalui hikmah mutaalliyah yang mengintegrasi filsafat, Al-Qur’an dan Tasawuf.
Berbeda halnya dengan di Barat. Renaisans yang kita kenal sangat revolusioner kenyataannya justru melahirkan skeptisisme akut kepada filsafat. Ini gara-gara filsafat terlanjur dikenal luas sebagai bagian dari doktrin dan metodologi keilmuan gereja.
Maka, ketika berbagai doktrin gereja dikritik dan runtuh, para intelektual Barat pembaharu kemudian turut meragukan filsafat secara keseluruhan.
Karena itu kita kini kenyang dengan berbagai pandangan ‘ateistik’ dari para filsuf barat. Mulai dari ‘Tuhan telah mati’ Nietczhe sampai ‘Agama adalah candu’ nya Marx. Sayangnya pandangan ini menjadi dominan dan malah sudah membangun pondasi bagi dasar-dasar pandangan kehidupan Barat yang materialistik. Filsafat yang ‘mbaraat’ inilah yang harus kita antisipasi.
Filsafat Islam adalah Ilmu Akidah
Prof Mishbah Yazdi mengklarifikasi filsafat dalam tradisi Islam sebagai tiga hal yang bersinonim: ilmu utama, metafisika atau ilmu tentang Tuhan (teologi). Semua itu sejalan dengan kitab terakhir Aristoteles yang dijuduli muridnya dengan ‘metathaphysiche’ padahal dirinya menamai ‘teologiche’. Disitu Aristoteles berargumen rinci tentang sang penggerak yang tidak bergerak: Tuhan.
Dari bingkai Aristoteles, filsafat Islam beranjak dan mendefinisikan diri sebagai ‘ilmu yang mengkaji yang Ada, dan yang Ada-sejati dengan bantuan rasio’. Bedanya, jika Aristoteles menggunakan istilah unmoved mover, maka Ibnu Sina menggunakan istilah wajibul wujud (wujud yang niscaya). Bahwa kita semua hanya wujud yang bergantung pada wujud-Nya.
Dengan penjelasan di atas, nampaklah bahwa makna filsafat yang dibangun dalam tradisi Islam ialah suatu ‘ilmu akidah’. Karena itu wajar bila respon terhadap filsafat umumnya juga datang dari para ahli kalam. Sederhananya filsuf dana ahli kalam punya versi masing-masing soal akidah berdasar cara menggali kebenaran. Satu menggunakan rasio, satu menggunakan teks.
Imam Ghazali juga menyadari hal ini kala mengkritik filsafat dalam Al-Munqidh Min ad-dhalal. Kata beliau, filsafat memiliki akidah yang bertentangan dengan Islam. Karena kritik dari ulama sekelas Imam Ghazali maka hingga kini umat Islam banyak yang mendekati filsafat dengan was-was. Jika kita perhatikan banyak ustadz yang salah-paham filsafat mengutip Imam Ghazali.
Padahal ‘akidah’ filsafat tidak melenceng ekstrim seperti yang dikira Al-Ghazali dan para pengikutnya itu. Senada dengan akidah yang kita pahami, bagi para filsuf segala yang ada hanya ilusi, ada yang sejati adalah Allah itu sendiri. Siapa yang mau bilang bahwa Allah itu tidak ada dan terdapat eksistensi lain yang sejati di atas Allah? Yang bilang itu barulah sesat!
Kesimpulan: Islam Butuh Filsafat
Simpul tulisan ini ingin mengatakan bahwa sudah saatnya kita meninggalkan salah-paham akut yang telah bertahan ribuan tahun dalam pemikiran kita. Bahwa Islam justru sangat membutuhkan filsafat, utamanya di tengah hujaman pengaruh westenisasi-modernisasi yang membayangi kita dengan kritik-kritik rasionalis ala Barat.
Respon yang tekstualis tetap dapat diajukan. Tapi pada sisi dialog antar agama dan peradaban, rasionalitas jauh lebih inklusif. Kita bisa jadi tidak percaya Injil atau relativisme, pun mereka tidak percaya Al-Qur’an. Tapi nalar kita masing-masing dapat berjumpa dalam premis-premis.
Mendekati agama atau keyakinan kita dengan rasio juga bermanfaat besar. Pertama, kita memiliki keyakinan yang sifatnya sadar, bukan sekedar taklid atau ikut-ikutan. Kedua, keyakinan yang rasional akan membantu kita mengantisipasi hoax yang mencoba membuat kita serba emosional. Maklum, 2024 sudah semakin dekat.
Memang nalar jauh dari sempurna. Itu jika dibandingkan dengan wujud Tuhan yang Maha Sempurna. Namun jangan lupakan bahwa nalar adalah suatu kesempurnaan pemberian Tuhan. Maka, berfilsafat sejatinya adalah cara kita bersyukur yang paling purna atas karunia Allah yang menjadikan kita—sebagaimana definisi para filosof Muslim–hayawanun nathiq (hewan bernalar).


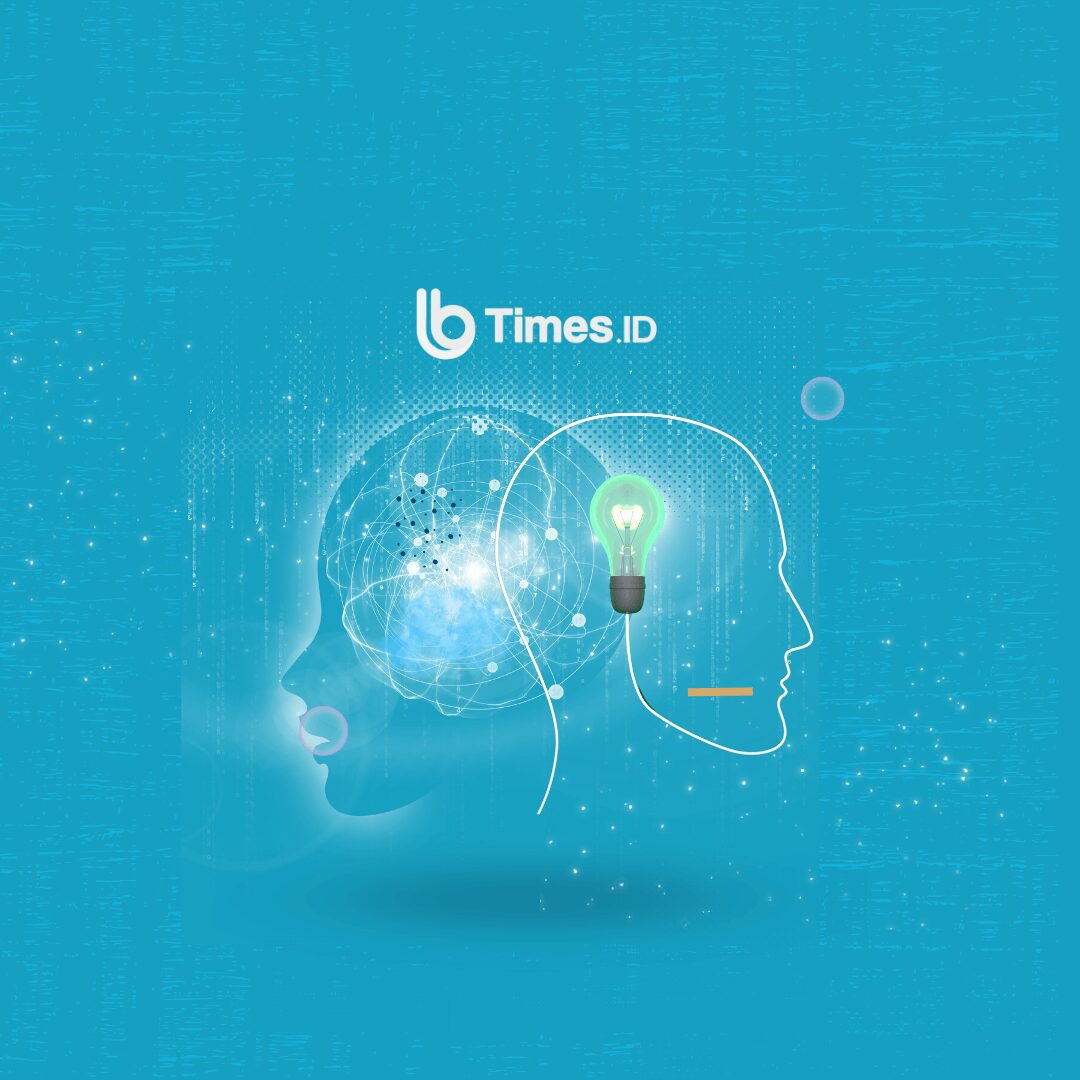

Jangankan filsafat, tasawuf saja banyak yang salah paham hingga mengklaim atas kesesatannya