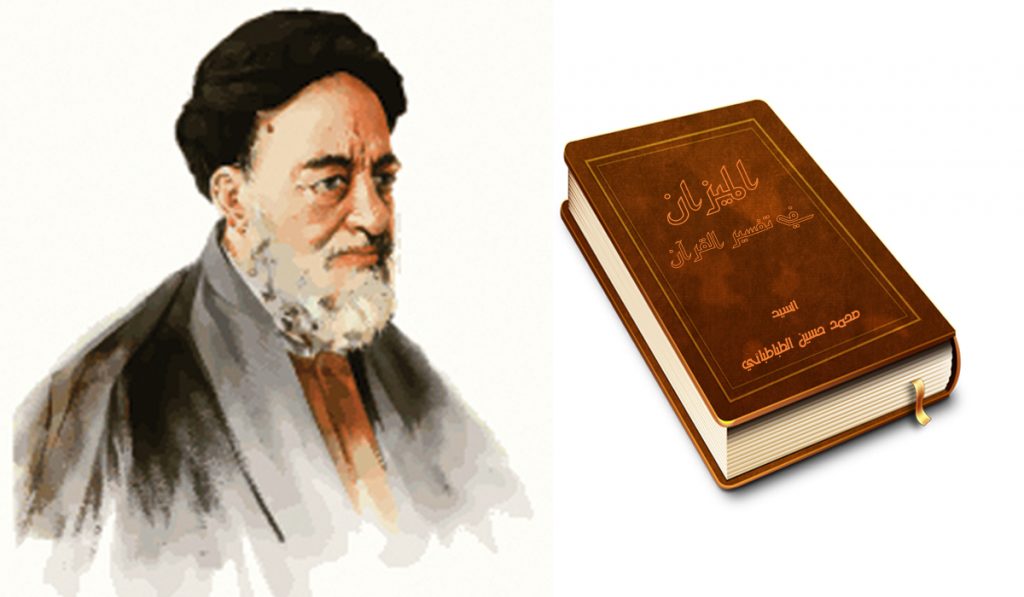Berbeda dengan sementara mufassir yang menilai huruf muqatta’ah sebagai termasuk dalam kategori ayat-ayat mutasyabihat, al-Tabataba’i tidak beranggapan demikian.
Ada sekitar 20 pendapat yang mencoba memberikan takwil atas huruf-huruf muqatta’ah tersebut, al-Tabataba’i menolaknya. Baginya, huruf-huruf muqatta’ah merupakan kode khusus antara Allah dan Rasul-Nya. Di mana, pengetahuan manusia tidak sampai kepadanya kecuali sekedar menduga-duga.
Dalam kasus ini, sikap al-Tabataba’i menjadi kontradiktif dengan pandangannya semula bahwa semua ayat-ayat Al-Qur’an bisa dipahami maksudnya.
Memahami Al-Qur’an Lewat Dua Sisi
Lebih jauh, dalam kaitannya dengan pemahaman Al-Qur’an, al-Tabataba’i berasumsi bahwa setiap ayat Al-Qur’an pada dasarnya bisa dipahami dari dua sisi.
Satu sisi adalah pemahaman makna literal sebagaimana yang tersurat dalam teks-teks Al-Qur’an, yang kemudian dikenal sebagai aspek lahir. Sedangkan sisi yang lain adalah pemahaman terhadap makna yang tersirat. Yakni makna yang terdapat di balik teks ayat, yang kemudian dikenal dengan aspek batin.
Mengenai pemahaman yang demikian, al-Tabataba’i mengutip hadis: “Sesungguhnya Al-Qur’an memiliki makna lahir dan batin. Sedangkan makna batinnya memiliki makna batin lagi hingga tujuh makna”.
Dalam pandangan al-Tabataba’i, baik arti lahir maupun arti batin, keduanya tidaklah saling bertentangan. Ini berbeda dengan yang dipahami oleh kaum pengikut batiniyah.
Pengikut batiniyah hanya memegang makna batin yang bahkan cenderung menyeleweng dari aspek lahiriahnya. Bagi al-Tabataba’i, arti lahir adalah ibarat badan, dan arti batin adalah rumahnya.
Atau, arti lahir adalah merupakan perlambang dari arti batin. Dalam hal ini, arti lahir berfungsi menyampaikan hal-hal yang bisa dimengerti kebanyakan orang. Arti inilah yang, dalam pandangan al-Tabataba’i, bisa diketahui oleh setiap orang yang memiliki kemampuan linguistik.Tidak ada bukti kata-kata al-Tabataba’i bahwa arti Al-Qur’an adalah tidak seperti arti kata-kata Arabnya.
Perenungan Batin terhadap Ayat Al-Qur’an
Berbeda dengan arti lahiriah yang bisa diketahui oleh setiap orang yang memiliki kompetensi linguistik, arti batin hanya bisa dipahami melalui perenungan yang mendalam.
Perenungan ini pun hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, yaitu mereka yang tergolong elite-spiritual. Kemampuan para elite-spiritual dalam mengungkapkan arti batin itu juga tidak sama, melainkan bergantung kepada tingkat spiritualitas masing-masing.
Mereka yang tingkat spiritualistasnya lebih tinggi, maka kemampuannya dalam menyingkap makna batin juga lebih luas dan dalam.
Sedangkan tingkat spiritualitas masing-masing ulama itu sendiri sangat ditentukan oleh kebersihan hati dan kedekatan mereka kepada Allah Swt melalui pengalaman batiniah mereka.
Sebagai “ruh” arti batin memiliki makna yang jauh lebih luas dan dalam dari pada arti lahir. Kalau arti lahir hanya memiliki satu atau dua arti saja, maka arti batin, sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas memiliki sampai tujuh bahkan tujuh puluh makna.
Memberikan contoh mengenai hal ini, al-Tabataba’i menyebutkan bahwa firman Allah, QS. al-Nisa’ [4]: 36) secara lahir menunjuk pada larangan menyembah selain Allah dan menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain.
Firman Allah, QS. Al-Hajj [22]: 30 menegaskan bahwa menyembah berhala merupakan salah satu dari larangan menyekutukan Allah tersebut.
Menurut al-Tabataba’i, melalui perenungan yang mendalam akan diketahui bahwa alasan pelarangan menyembah berhala itu karena penyembahan semacam itu merupakan bentuk kepatuhan kepada selain Allah, bukan semata-mata menyembah berhala namun bahkan menyembah syetan.
Al-Tabataba’i dan Kesyiahan
Selain contoh tersebut, sebagai seorang ulama Syiah terkemuka, pemikiran al-Tabataba’i memang sangat diwarnai ideologi kesyiahan. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai kajian yang dilakukannya sebagaimana tertuang dalam beberapa karyanya. Termasuk dalam kitab tafsirnya al-Mizan ini.
Tampak sekali bahwa kitabnya ini sangat memperlihatkan keteguhan al-Tabataba’i berpegang pada mazhab Syiah. Dalam karya monumentalnya ini, al-Tabataba’i bahkan kelihatan sekali berupaya mengkampanyekan mazhab Syiahnya ketika menafsirkan ayat-ayat yang, menurut kaum Syiah sendiri, berkenaan dengan pandangan-pandangan ideologis kesyiahan mereka.
Dalam menafsirkan ayat-ayat, al-Tabataba’i secara panjang lebar menguraikan tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan dalam Islam, yang mengacu kepada pembelaannya terhadap konsep imamah dalam Syiah.
Dengan tidak saja melakukan kajian-kajian qurani dan riwayat, baik yang berasal dari Sunni maupun dari Syiah sendiri, tapi juga mengkritik pandangan-pandangan ideologis aliran Sunni.
Al-Tabataba’i menyakini hak kepemimpinan itu sebagai milik ahlul bait. Mereka inilah yang dalam pandangan Syiah sebenarnya berhak memegang imamah, menggantikan Nabi Muhammad Saw.
Penafsiran Ulil Amri
Dalam kaitan ini, al-Tabataba’i selalu menolak pendapat mayoritas ulama-ulama Sunni tentang penafsiran ulil amri dalam ayat: Ati’u Allah wa ati’u al-rasul wa uli al-amr minkum.
Kalangan ulama Sunni, seperti Sayyid Rasyid Ridha dan al-Razi dalam penafsirannya atas ayat tersebut menyimpulkan bahwa yang dimaksud ulil amri adalah ahl al-hall wa al-aqd.
Menurut al-Tabataba’i, pendapat yang demikian ini salah besar. Perintah untuk menaati ulil amri memberikan suatu kepastian bahwa mereka adalah orang-orang yang suci. Yang tidak memiliki dosa. Yang ma’sum serta seluruh sikap serta tutur katanya dan perbuatannya selalu mencerminkan kebenaran. Sedangkan, menurut ayat-ayat Al-Qur’an (QS. Al-Ahzab [23]: 3) dan beberapa hadis, orang-orang yang ma’sum itu tidak lain adalah ahlul bait.
Demikian mengenai penafsiran al-Tabataba’i yang memperlihatkan pembelaannya terhadap mazhab teologi yang dianutnya, yaitu Syiah. Dalam berbagai ayat yang lain, khususnya yang terkait dengan pandanganpandangan khas Syiah, al-Tabataba’i hampir-hampir tak pernah beranjak dari bimbingan kesyiahannya. Inilah yang tampak ketika ia menafsirkan ayat.
Kalangan ulama Sunni menafsirkan ayat tersebut sebagai perintah untuk memberikan mahar dalam pernikahan (hubungan seksual). Jamal al-Din al-Qasimi, misalnya, menafsirkan ayat itu dengan: “perempuan yang kamu nikahi yang kamu berhubungan seksual dengannya, maka berilah maharnya dengan sempurna.” Menurut al-Tabataba’i, ayat ini adalah berkaitan dengan nikah mut’ah (pernikahan temporer, dalam jangka waktu tertentu). Sebagaimana maklum, nikah mut’ah adalah jenis pernikahan yang diperbolehkan dalam Syiah.
Kitab Tafsir al-Mizan memang kaya akan pendekatan, yang mencerminkan keluasan pengetahuan penulisnya. Wajar jika kemudian kitab tersebut banyak memperoleh apresiasi dari berbagai kalangan. Hanya saja, bukan berarti kitab tafsir ini tidak memiliki kelemahan.
Kelemahan terpokok dari kitab tafsir ini adalah karena al-Tabataba’i menulisnya dalam kerangka aliran Syiah yang dianutnya. Betapapun al-Tabataba’i berupaya untuk bersikap ilmiah-akademis, namun tampak sekali bahwa ia dibimbing oleh semesta intelektualnya yang sangat ideologis. Wallahu A’lam.
Editor: Yahya FR