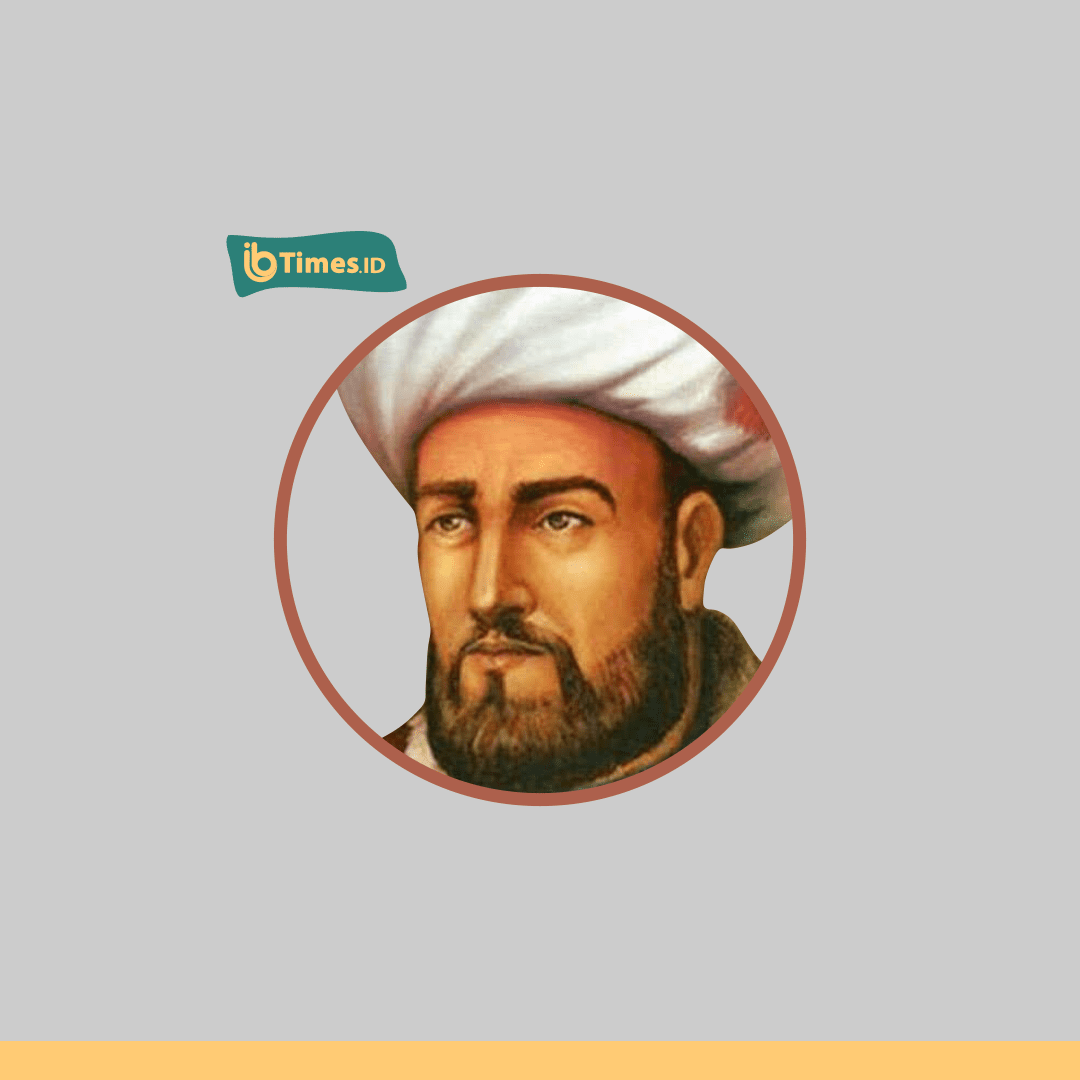Sebagai umat Islam tentu kita sering mendengar pentingnya peran amar ma’ruf nahi munkar dalam ajaran Islam. Nilai amar ma’ruf nahi munkar yang kerap digaungkan di berbagai kesempatan oleh seorang pendakwah dan cendekia adalah upaya untuk mengawal sikap manusia yang kerap lupa dan lalai menjalankan prinsip keagamannya.
Dalam bukunya yang berjudul Panduan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Ali Mustafa Yaqub menekankan bahwa kedudukan hisbah (perilaku amar ma’ruf nahi munkar) dalam Islam adalah sangat besar. Ia merupakan bagian dari dasar-dasar pokok agama yang signifikan (Ali Mustafa Yaqub, 2012: 9).
Hal serupa disampaikan oleh Imam al-Ghazali dalam Muktashar Ihya Ulum al-Din. Menurutnya, tindakan amar ma’ruf nahi munkar (al-ihtisab) merupakan salah satu asas agama (ashlun min ushul al-din) dan merupakan salah satu misi kenabian. Tidaklah seorang nabi diutus melainkan mereka menerapkan amar ma’ruf nahi munkar. Dalam ayat di bawah ini, ditegaskan hal tersebut (Imam al-Ghazali, 1990: 118).
Allah Swt berfirman,
وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung [Al ‘Imran104].
Dalam tafsir fenomenalnya, Tafsir al-Azhar, Buya Hamka menyampaikan ajakan kepada yang m’aruf dan menjauhi yang munkar itulah yang dinamai dakwah. Dengan adanya ummat yang berdakwah, agama menjadi hidup, tidak menjadi seolah-olah mati (al-Azhar, 2000: 866).
Sebagaimana kita ketahui, tugas para Nabi adalah menghidupkan agama-agama yang diamanahkan oleh Allah Swt untuk disebarkan ke muka bumi. Jika demikian, maka tentu mereka para nabi berupaya amat keras untuk menghidupkannya dengan melakukan amar ma’ruf nahi munkar.
Empat Rukun Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Dalam bahasan khusus mengenai amar ma’ruf nahi munkar, Imam al-Ghazali merumuskan bahwa dalam perkara ini terdapat empat rukun yang harus diperhatikan, yakni subjek penyeru amar ma’ruf nahi munkar (al-muhtasib), objek yang diserukan (al-muhtasab alaihi), bahan/materi yang diserukan (al-muhtasab fihi) dan teknis pelaksanaan penyeruan itu sendiri (al-Ihtisab nafsuhu).
Seorang penyeru kebaikan dan penghimbau kemunkaran, menurut Imam al-Ghazali, disyaratkan seorang muslim dan mukallaf. Pensyaratan seorang muslim sebagai pelaku penyeruan meniscayakan bahwa objek yang didakwahi adalah orang muslim juga, sehingga tidak mungkin jika hal ini diserahkan kepada orang non-muslim.
Sedangkan penunjukkan mukallaf sebagai syarat pelaku dakwah berpacu pada keharusan seorang penyeru untuk mengetahui ihwal yang didakwahi. Hal ini tidak mungkin diserahkan kepada kelompok yang belum mempunyai keahlian membedakan yang salah dan yang benar (belum tamyiz).
Sebagian ulama mensyaratkan kepemilikan integritas yang tinggi (al-‘adalah) bagi seorang penyeru, sebagian lagi tidak. Yang mensyaratkan perlunya integritas tinggi, sebuah syarat yang mengandaikan bahwa seorang penyeru harus melaksanakan terlebih dahulu semua yang diperintahkan, berpacu pada surat al-Shaff ayat 2 yang berbunyi “Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu sesuatu yang tidak kalian kerjakan?”.
Sedangkan yang tidak mensyaratkan integritas tinggi sebagai syarat berpacu pada realitas, bahwa sejatinya tidak ada manusia yang benar-benar sempurna tanpa sedikitpun melakukan kesalahan. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Imam al-Ghazali. Bahwa seorang penyeru tidak disyaratkan baginya memiliki sebuah integritas tinggi untuk mengamalkan amaliyah penyeruannya. Kendati demikian, tentu ia harus berupaya semaksimal mungkin menerapkan terlebih dahulu idealitas bidang yang akan didakwahinya.
Terkait objek yang menjadi sasaran seruan adalah mereka yang melakukan sesuatu tidak pada semestinya (al-irtikabu man la yanbaghi lahu). Sebagai contoh adalah apa yang terjadi pada seorang Khalifah Bani Umayyah, Marwan bin Hakam (w. 65 H).
***
Saat itu beliau menyelenggarakan khutbah shalat Id sebelum pelaksanaan shalat Id. Kemudian, ada seseorang yang menegur dan mengatakan bahwa Khutbah Id dilaksanakan setelah shalat. Menurut pengakuan Abu Said al-Khudri r.a. kemudian Marwan bin al-Hakam melaksanakan anjuran dari orang yang menegur tersebut.
Selain itu, seorang penyeru kebaikan dan pencegah kemunkaran haruslah memahami detail permasalahan yang diserukannya. Masalah yang diperkarakan haruslah hal-hal yang prinsipil yang sisi kekeliruannya bisa diketahui secara terang-terangan tanpa perlu ijtihad lagi.
Permasalahan yang diperkarakan juga tidak dalam hal-hal yang bersifat khilafiyah (yang bersifat cabang/furu). Hal ini dicontohkan dari apa yang terjadi dalam interaksi Fikih Syafi’i dengan Fikih Hanafi.
Mazhab al-Syafi’iyyah tidak mengingkari fatwa mazhab Syafi’I yang melegalkan minum perasan Anggur selama ia tidak memabukkan. Sebagaimana mazhab al-Hanafiyyah tidak memperkarakan fatwa mazhab al-Syafi’i tentang kebolehan memakan anjing hutan dan biawak.
Yang terakhir, terkait teknis yang perlu dilakukan untuk melakukan penyeruan kebaikan dan pencegah kemunkaran adalah dibarengi dengan karakter kealiman, sifat wara’, dan akhlakul karimah. Karakter kealiman yang dimiliki oleh seorang penyeru mengandaikan bahwa dirinya memahami batas-batas syariat sehingga mampu menegur jika ada yang melakukan kekeliruan.
Sifat wara’ (sifat berhati-hati dan proporsional) yang dimiliki oleh seorang penyeru diharapkan mengatur seorang agar berhati-hati dan proporsional dalam upaya preventif atas sesuatu yang ingin dibenarkannya. Mengetahui duduk permasalahan dan mengadakan dialog dalam menyelesaikan permasalahan merupakan perwujudan sifat wara’.
Yang ketiga adalah pembersamaan penyeruan dengan akhlakul karimah. Prinsip semacam ini meniscayakan terciptanya suasana yang efektif dan solutif dalam menuntaskan permasalahan. Yang menjadi gol dalam prinsip ini adalah sebuah penyadaran akan ketidakberesan yang terjadi. Bagaimanapun, seorang melakukan kekacauan lantaran dua hal, perilaku tersebut dilakukan karena disengaja atau karena hal tersebut belum diketahuinya.
Pendasaran penyeruan yang didasarkan pada akhlakul karimah mensyaratkan seorang penyeru agar bersikap bijak, dialogis, dan menghadapi permasalahan dengan kepala dingin. Tujuannya adalah satu, agar penyeruan atas suatu keburukan tidak mendatangkan keburukan yang lain.
Jika tidak dilakukan dengan bijak, tidak sedikit upaya pemberantasan kemunkaran, karena ia tidak dilakukan dengan proporsional dan bijak, malah mendatangkan kemunkaran serupa bahkan yang lebih besar. Demikian yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali dalam nasihatnya tentang cara melakukan penyeruan menuju kebaikan dan pencegahan dari kemunkaran dengan cara yang bijak.
Amar Ma’ruf Nahi Munkar Bersifat Fleksibel
Tentu hal ini tidak bersifat mutlak, utamanya terkait dengan ihwal yang akan kita serukan pembenarannya. Melihat standar kemunkaran yang sangat multitafsir dalam negeri yang kaya dengan keragaman ini, kita perlu bersikap bijak dan hati-hati. Dalam hal ini, kita perlu berpijak pada landasan undang-undang dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Mengingat hal inilah yang bisa kita jadikan patokan paten dalam menilai benar tidaknya sebuah permasalahan, tentu dibarengi dengan kebijakan dan kearifan lokal yang membersamainya (baik yang bersikap aturan adat atau pakem keagamaan tertentu).
Dan ihwal penegakan penyeruan perbaikan juga perlu berpacu pada konstitusi yang mewajibkan seserang agar tidak melakukan persekusi atau main hakim sendiri, melainkan perlu pendampingan dari pihak berwajib (polisi dan penegak hukum resmi negara lainnya), kendati dalam hal-hal yang yang lebih lokal (seperti peraturan adat, kesepakatan warga, tradisi sosial yang sudah lama berjalan di satu masyarakat, dan praktik nasihat keagamaan yang bersifat damai tanpa unsur pemaksaan) tetap diperkenankan diberlakukan sesuai dengan kode etik yang sesuai dengan Hak Asasi Kemanusiaan dan Hukum Konstitusional yang berlaku.