Dalam sebuah diskusi di grup alumni salah satu kampus luar negeri (yang namanya sengaja disensor) tiba-tiba jadi ramai gara-gara satu pertanyaan “sepele” tentang gelar akademik. Kehebohan itu berawal dari salah satu anggota grup bertanya soal gelar apa sebenarnya yang layak disandang oleh para lulusan sarjana dari kampus tersebut.
Pertanyaan ini dilemparkan oleh salah satu anggota grup dan langsung memicu percakapan panjang. Ternyata, banyak alumni yang selama ini merasa bingung. Apakah gelar resmi mereka adalah Bachelor of Science (B.Sc), sebagaimana tercantum dalam regulasi negara tersebut, atau bahkan dengan Licentiate (Lc)?
Secara aturan, jelas, gelar B.Sc adalah hak akademik yang sah dan diakui. Tapi faktanya, sebagian besar alumni malah lebih nyaman memakai Lc, entah karena alasan identitas, gengsi, atau mungkin karena “ketidaksengajaan”. Mungkin juga karena sejak awal mereka lebih akrab dengan gelar itu, tanpa pernah merasa perlu mempertanyakan asal-usulnya.
Gelar Lc, Prestise, dan Kepercayaan Masyarakat Indonesia
Di Indonesia, gelar Lc tampaknya bukan hanya sekadar penanda akademik. Ia telah seolah menjadi semacam “label kepercayaan” di tengah masyarakat. Gelar tersebut kini seakan menjadi daya ‘jual’, khususnya yang terjun dalam dunia dakwah.
“Bukan sebagai gagah-gagahan, namun untuk menarik kepercayaan masyarakat atas ilmu yang disampaikan dalam dakwahnya. Toh, sama-sama lulusan jurusan Agama Islam, jadi apa salahnya pakai gelar itu?” begitu alasannya.
Masalahnya, narasi seperti ini pelan-pelan membentuk pola berpikir bahwa otoritas keilmuan bisa diwakili cukup oleh dua huruf di belakang nama. ‘Lc’, lalu selesai urusan. Seolah-olah begitu gelar itu disematkan, maka otomatis isi ceramahnya valid dan ilmunya terpercaya, tanpa perlu ditinjau lebih jauh.
Fenomena ini barangkali tak lepas dari pengaruh para da’i yang dulu mendominasi ruang dakwah, mayoritas memang bergelar Lc. Akhirnya, publik terlanjur menyamakan ‘keilmuan’ dengan ‘gelar’, dan bukan dengan substansi.
Padahal, gelar Lc itu sendiri sebenarnya bukan eksklusif milik lulusan studi Islam. Banyak lulusan bidang lain—dari ekonomi hingga teknik—juga menyandang gelar Licentiate, tergantung regulasi akademik negara tempat mereka kuliah.
Padahal, kalau mau jujur, dunia keilmuan tak sesederhana itu. Ilmu tak selalu melekat pada gelar, dan gelar tak otomatis menjamin kapasitas. Tapi begitulah realitasnya.
Di tengah masyarakat yang masih memuja simbol, Lc kini bukan hanya gelar, tapi juga “branding”. Maka jadilah Lc sebagai simbol prestise baru. Mudah dikenali, cepat dipercaya, dan cukup 2 huruf untuk membuka pintu undangan ceramah.
Dakwah dan Kebutuhan Masyarakat
Dunia dakwah itu luas, jauh lebih luas dari sekadar mimbar, sorban rapi, atau dalil-dalil yang dikutip tanpa henti. Tapi sayangnya, kita hidup di tengah masyarakat yang sudah terlanjur membelah realitas menjadi dua kubu: ‘ustadz’ dan ‘jama’ah’. Yang satu dianggap tahu segalanya soal agama, yang lain cukup duduk manis, manggut-manggut, dan ikut tanpa banyak tanya.
Padahal, kalau mau dikembalikan ke makna aslinya, kata ustadz itu berarti guru, titik. Tapi entah sejak kapan, ia berubah menjadi label sakral.
Hari ini, begitu seseorang disapa ‘ustadz’, seolah otomatis dia maksum: tak bisa salah, tak boleh dikritik, dan jauh dari dosa dekat dengan surga.
Padahal, merekapun yang menyandang gelar ‘ustadz’ juga masih tersandung-sandung keluar dari lubang kemaksiatan. Sama-sama pendosa hebat. Tapi toh masyarakat tetap percaya. Karena di kepala banyak orang, kalau sudah pakai baju koko dan bisa mengutip satu dua ayat dengan fasih, maka dia pasti alim. Selesai urusan.
Jadi, jangan terlalu kaget kalau hari ini kita temukan ‘ustadz’ yang terjerat kasus sosial, moral, bahkan kriminal. Kita sendiri yang menciptakan mitos itu, lalu kecewa saat realitas tak sesuai imajinasi.
Yang sering dilupakan adalah: yang wajib itu bukan jadi ustadz, tapi jadi da’i. Menyampaikan kebaikan adalah tugas setiap muslim, tak peduli latar belakang atau panggungnya.
Maka jika ada seseorang yang berdiri di kolong jembatan dan berhasil mengajak berbuat kebaikan, maka secara fungsional, dia sudah lebih “berdakwah” daripada mereka yang berceramah panjang di atas mimbar tapi lupa mempraktikkannya.
Dakwah bukan soal gelar. Bukan soal tampilan. Dan jelas bukan soal reputasi. Ia soal kejujuran menyampaikan dan ketulusan mengajak. Sisanya, hanya kosmetik sosial.
Dakwah itu tentang kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga kadang tidak peduli gelar. Jika yang disampaikan memvalidasi pemahamannya hari ini, itu yang diakui. Jadi, yang butuh validasi bukan hanya ‘da’i’, tapi juga jama’ah. Rumit memang, tapi, serumit apapun, dakwah harus tetap berjalan.
Takutnya, hari ini kita peduli terhadap gelar bukan karena kapasitas keilmuan kita itu, namun untuk kepentingan ‘validasi’. Mencari panggung sosial, puja-puji jama’ah, terangnya lampu sorot dan tepuk tangan khalayak, na’udzubillah.
Ingat, bahwa Nabi Muhammad menyebut dirinya nabi bukan untuk gaya-gayaan dan kebanggaan. Dalam setiap penyebutan “Anā Rasūl” atau “Anā Nabī” tidak pernah keluar dalam konteks pameran spiritual atau ajang pembuktian status.
Setiap penyebutan itu selalu muncul dalam momen-momen krusial. Ketika wahyu harus disampaikan, ketika umat mulai ragu, atau ketika misi kerasulan perlu ditegaskan.
Nabi tidak pernah menjadikan gelarnya sebagai alat untuk meninggikan dirinya di atas manusia. Tidak pernah menyebut statusnya sebagai rasul demi popularitas atau pengaruh sosial.
Bahkan saat beliau menyatakan, “Anā sayyidu waladi Ādama walā fakhr”, (Aku adalah pemimpin anak cucu Adam, namun aku tidak menyombongkan diri), beliau menegaskan posisi itu sebagai amanah, bukan pencapaian.
Penyebutan gelar nabi atau rasul oleh Nabi Muhammad bukanlah bentuk kebanggaan pribadi, tetapi merupakan pernyataan fungsi dan tanggung jawab risalah; berbeda dengan sebagian da’i masa kini yang menyebut gelar ‘mungkin’ untuk membangun otoritas pribadi atau status sosial.
Namun, tidak semuanya begitu. Masih banyak yang da’i yang diam-diam terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri. Tulisan ini hanya bentuk refleksi pada diri sendiri di antara riuh-riuh pujian dan gelar. Tapi, bukan berarti gelar juga tidak penting. Bagi sebagian kalangan, gelar juga harus ditunjukkan, untuk kepentingan akademik, misalnya.
Tapi ya begitulah, kadang urusan gelar bukan cuma soal legalitas, tapi juga soal “selera” dan “prestise semu” yang diwariskan turun-temurun. Penggunaan gelar ini akhirnya jadi semacam pilihan gaya hidup. Mirip seperti memilih antara kopi tubruk atau latte, masing-masing punya pembela fanatiknya, meskipun biji kopinya sama saja.
Editor: Soleh


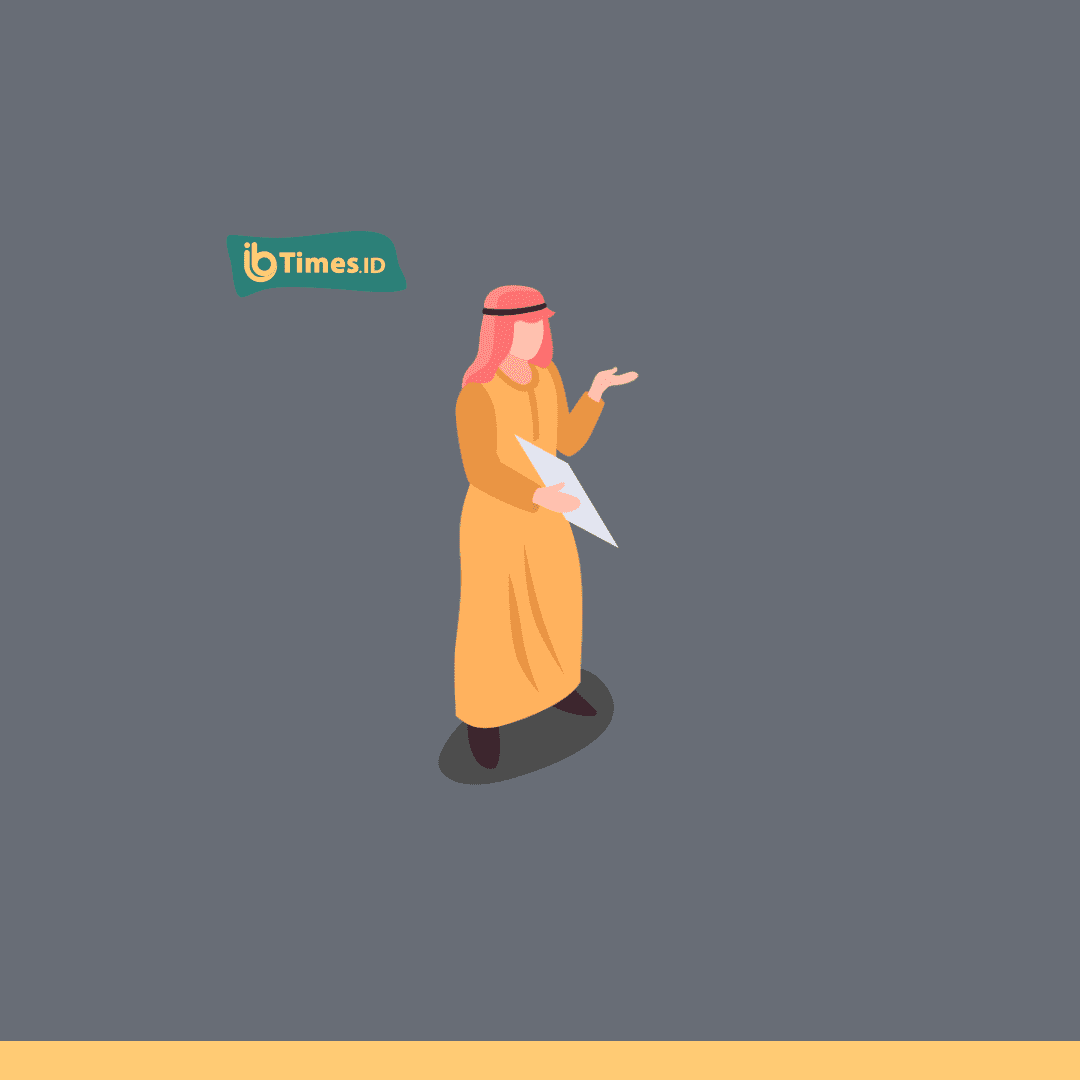

Kok yang dibahas cuma gelar lc?
Kalau gelar Kyai, Gus, Habib, nggak dibahas?
jika gelar tidak menjamin kapasitas keilmuan, bagaimana cara efektif bagi para da’i yang berintegritas untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendapatkan validasi tanpa harus bergantung pada prestise gelar tertentu, terutama di tengah maraknya informasi digital?