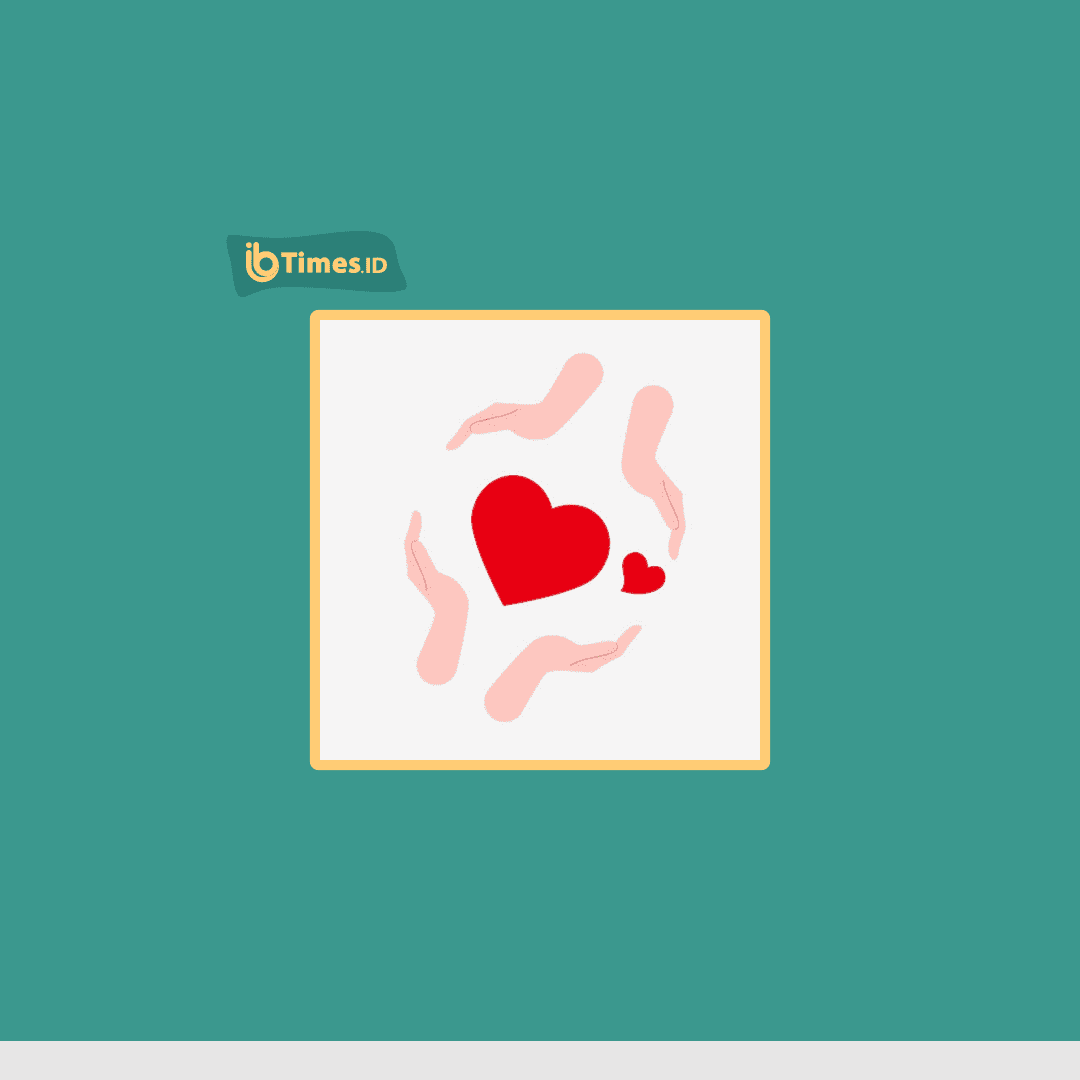“Karena aku mencintaimu dan kamu mencintaiku, maka kita harus saling mengekang agar cinta kita tetap utuh dan abadi tanpa gangguan manusia lain” kurang lebih demikianlah alegori cinta manusia-manusia modern. Manusia yang “cemburuan” dalam menjalin relasi cinta. Relasi yang seharusnya membebaskan dan memanusiakan karena berasaskan cinta. Namun, kenyataan yang berkeliaran justru sebaliknya. Hubungan cinta banyak merenggut kebebasan manusia, kebebasan bermain, nongkrong, mendengarkan musik tertentu, dan bahkan kebebasan untuk memiliki tubuhnya sendiri.
Cinta yang Abstrak
Cinta akhirnya menjadi suatu hal abstrak yang seringkali disalahartikan. Keabstrakannya menjadikan pikiran manusia berkeliaran mencari esensi cinta yang sejati. Beberapa dari pencarian tersebut justru berujung pada pendangkalan makna cinta dan menjerumuskannya pada pelepasan eksistensi satu sama lain.
Dengan dalih cinta, maka manusia yang satu merebut kebebasan manusia lain. Dengan dalih cinta, tubuh-tubuh terbuai begitu mudah. Dengan dalih cinta, kebohongan demi kobohongan tercipta. Kasus kekerasan, depresi, dan bunuh diri karena masalah hubungan asmara menjadi fakta tak terbantahkan relasi cinta yang salah kaprah. Nursalikah (2021) dalam wawancaranya dengan Komnas Perempuan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan kasus ketiga terbanyak yang paling sering dilaporkan.
Kasus bunuh diri terbaru dialami oleh mahasiswi dari Malang karena dipaksa menggugurkan bayi di perutnya oleh pacaranya (Hutasoit, 2021). Relasi cinta yang salah kaprah bertumpu pada perenggutan tubuh suci dengan dalil cinta yang palsu. Kekeliruan dalam menempatkan eksistensi cinta dan pemahaman yang salah kaprah tentang cinta mengindikasikan kedangkalan seni mencintai. Fromm (2018) secara tegas membentangkan narasi bahwa cinta adalah seni. Dengan begitu, perlu penerapan, latihan, dan pembahasan komperhensif yang seringkali dinafikan oleh manusia modern.
Cinta yang Mengekang
“Sekolah dulu. Jangan cinta-cintaan dulu” menjadi kalimat sakti salah arti tentang cinta. Cinta dianggap hal tabu yang tidak layak diperbincangkan oleh kalangan pelajar (anak-anak). Padahal, anak-anak dibesarkan oleh cinta dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Namun, mereka dibatasi untuk mengenal cinta. Seakan-akan, cinta akan menghasilkan petaka bagi masa depan mereka. Reproduksi pembatasan pemahaman tentang cinta menghasilkan ujung kegagapan dalam mencintai yang akhirnya berdampak pada tindakan cinta yang mengekang, sebuah tindakan yang sebenarnya bukanlah asas dari cinta (Malinowski dkk, 2009).
Kekangan menghasilkan alienasi. Alienasi artinya terasing. Manusia yang terkekang ataupun mengekang menjadi makhluk yang asing dengan dirinya sendiri dan terasing dengan orang lain (Widodo, 2005). Di satu sisi, manusia yang terkekang merasa seperti burung dalam sangkar.
Burung yang memiliki sayap jelajah luas melingkari langit, namun harus terkurung termenung menyaksikan sayapnya melepuh. Akhirnya, ia menjadi asing dengan kata “terbang”. Di sisi lain, manusia sang pengekang juga menjadi asing dengan dirinya sendiri. Dirinya yang sadar akan eksistensinya. Namun, karena tindakannya yang mengekang orang lain dengan dalih cinta, maka sejatinya ia sedang mengalami kritis eksistensi (Russel, 2004).
Jika disederhanakan, maka sesuai dengan narasi populer Dilan bahwa “manusia yang sedang cemburu adalah manusia yang sedang tidak percaya diri (krisis eksistensi)”. Tindakannya dalam mengekang memberikan konsekuensi kekangan untuk dirinya sendiri. Alhasil, berujung pada kontrak yang irasional “tidak boleh berteman dengan lawan jenis selain aku. Akupun juga sama, tidak akan berteman dengan lawan jenis selain kamu”. Niatnya, membangun romantisme. Namun, sejatinya sedang menghasilkan keruntuhan kehidupan sosial dan saling mengasingkan diri satu sama lain. Selain terasing satu sama lain, maka akan berlanjut pada terasing dengan dunia dan segala isinya, bahkan orang tuanya sendiri.
Cinta, Kekangan, dan Pemberontakan
Dari sudut yang lain, kekangan dalam relasi cinta manusia modern dapat membangkitkan gairah pemberontakan. Akan tetapi, gairah pemberontakan ini hanya akan muncul ketika manusia yang terkekang mulai menemukan hal yang diinginkan. Camus (2009) mendefinisikan sang pemberontak sebagai manusia yang berkata ‘tidak’ atas perintah yang ditujukan padanya, tapi tidak berbanding lurus dengan keinginannya.
Artinya, sang pemberontak adalah perempuan yang selama ini berkata ‘iyaa’ kepada pacarnya yang melarangnya datang ke kafe untuk sekadar mengobrol bersama teman-temannya, lalu kemudian di suatu waktu tertentu sang perempuan dengan tegas berkata ‘tidak’ dan memilih menemui teman-temannya serta bersenandung bersama kebebasannya sebagai bagian dari makhluk yang otentik.
Sang pemberontak adalah laki-laki yang setiap hari berkata ‘iya’ Ketika perempuannya melarangnya untuk pergi dengan teman-temannya dan harus mendengarkan celotehnya setiap saat. Hingga, suatu waktu sang laki-laki dengan tegas berkata ‘tidak’ dan memilih lepas dari kekangan cinta yang memilukan. Sang pemberontak adalah manusia-manusia sabar yang mulai menemui limit batas kesabarannya. Dan, pemberontakan tidak lain adalah simbol dari batas kesabaran yang terus ditekan (Camus, 2009).
Namun, persoalan kekangan seringkali merujuk pada pembenaran yang irasional. Pembenaran yang mengerdilkan arti emansipasi dalam prinsip humanisme. Seringkali, kekangan dalam relasi asmara anak muda modern didasarkan pada bias gender.
Seorang laki-laki melarang kekasihnya (dalam hal ini perempuan) untuk berteman dengan laki-laki lain. Baginya, sebagai seorang laki-laki ia merasa paham apa yang ada di pikiran masing-masing laki-laki lain. Pembenaran ini berdasar pada prasangka (prejudice). Dan, prasangka memicu krisis kepercayaan yang akhirnya menghasilkan tindakan egoistik. Pandangan bahwa setiap laki-laki atau perempuan memiliki pemikiran yang sama sejatinya telah menciderai narasi emansipasi. Narasi yang berupaya memperjuangkan keunikan masing-masing individu.
Manusia yang Unik dan Pentingnya Kebebasan
Bauman (2000) menegaskan bahwa masing-masing manusia, tanpa memisahkan gender apapun, merupakan entitas yang unik dan memiliki perbedaan mendasar atas dirinya dengan orang lain di seluruh jagat raya. Dalam konteks selera perempuan, laki-laki yang satu lebih suka dengan perempuan bergigi gingsul, laki-laki lain lebih suka dengan perempuan berpipi tebal, beralis tebal, bertutur kata lembut, bertutur kata tegas, berparas sendu, berkulit hitam, berkulit putih, bertato, bertindik, berwawasan luas, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya, tidak ada manusia yang benar-benar sama dan mentalitas penyamaan persepsi yang berlebihan akan menghasilkan pengkhianatan kemanusiaan (Addams, 2021).
Cinta bukanlah tentang keseragaman rasa dan cara perlakuan. Namun, tentang cara menghargai perbedaan dan memberi ruang kebebasan atas perbedaan yang ada.
Kebebasan artinya melawan berbagai bentuk kekangan yang membuat tubuh tidak nyaman dan menghasilkan ketidakbebasan. Secara praktis, kebebasan bersifat relatif. Tergantung bagaimana sebuah batas-batas anatara yang bebas dan tidak bebas dikomunikasikan. Hebermas (1929-sekarang) menawarkan paradigma komunikasi yang mengedepankan 4 (empat) prinsip dasar, yaitu bahasa yang perlu dimengerti (intelligibility), mengarah pada kebenaran (truth), dijelaskan dengan jujur (truthfulness), dan mudah dipahami orang lain (appropriateness) (Kurniawan, 2020).
Dengan pondasi komunikasi yang utuh dan saling memberikan pengertian, kebenaran, kejujuran, dan kemudahan untuk dipahamai akan menghasilkan relasi cinta dengan pemahaman cinta dan kebebasan yang otentik. Lalu, kebebasan otentik akan menghasilkan cinta yang membahagiakan para pecinta.
Jika demikian, apakah kekangan tidak mampu menghasilkan kebahagiaan? Renungi bersama doimu, tretan.
Editor: Nabhan