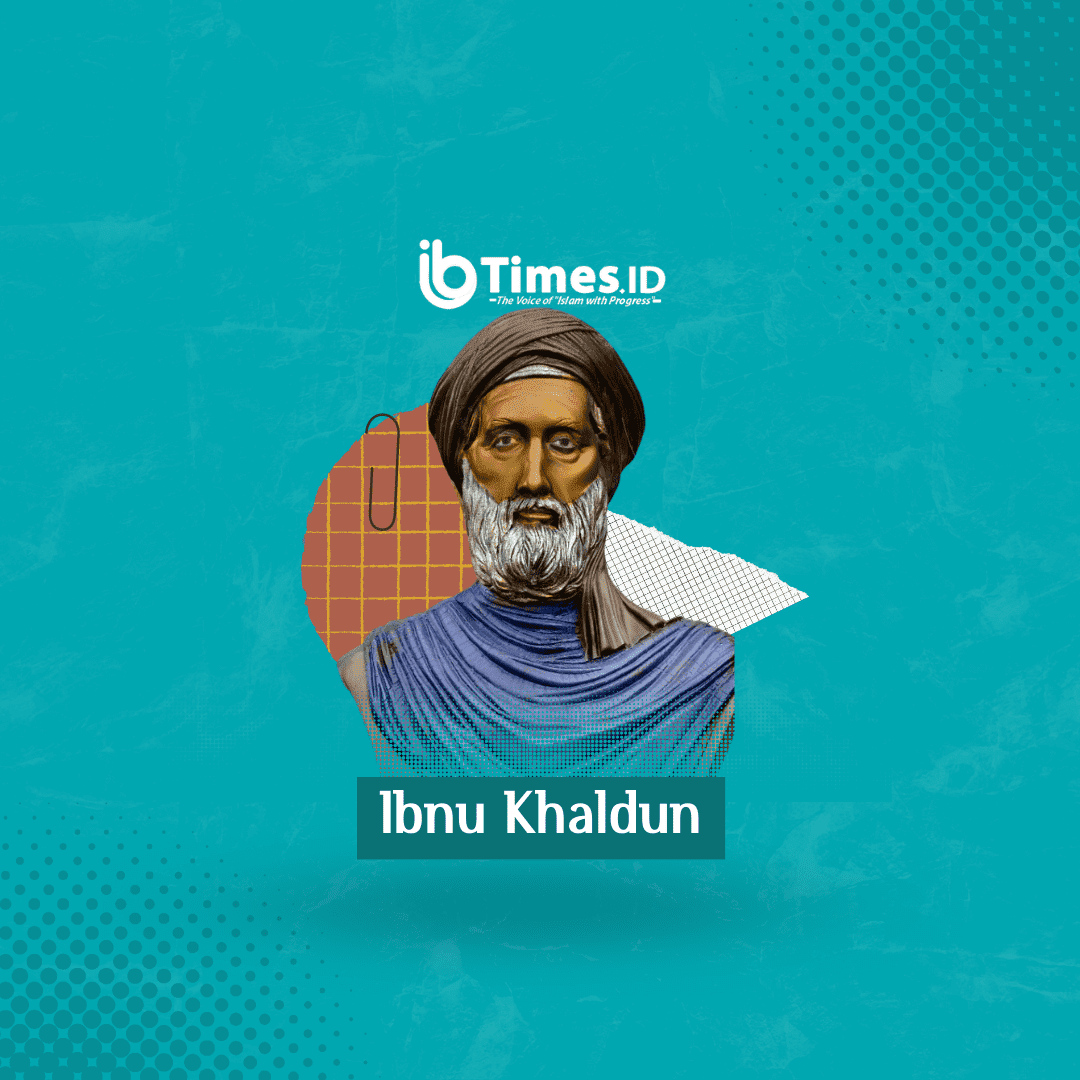Tema etika adalah salah satu topik filsafat Islam yang belum cukup dipelajari. Kajian etika saat ini hanya berfokus pada etika individu dan tidak mencakup etika publik seperti etika politik (Iqbal, 2019). Ibnu Khaldun merupakan sedikit dari tokoh-tokoh Muslim yang berbicara topik tersebut.
Nama lengkapnya adalah Wali al-Din ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin ‘Abd al-Rahman Ibnu Khaldun. Dia lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332, bertepatan dengan bulan Ramadan tahun 734 H. Ia dibesarkan dalam keluarga Andalusia yang pindah ke Tunisia pada pertengahan tahun 700-an. Keluarganya berasal dari keturunan Khaldun dari Arab Selatan yang datang ke Spanyol pada tahun-tahun awal kedatangan orang Arab Muslim ke Spanyol. Keluarga Ibnu Khaldun menduduki berbagai posisi penting di bawah kekuasaan Ottoman, Umayyah, al-Murabitun, dan al-Muwahhidun, mereka dianggap sebagai tokoh terkemuka (Enan, 2007).
Memahami Ashabiyah Ibnu Khaldun
Imam Iqbal, seorang dosen di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, di dalam disertasinya menyatakan bahwa Ibnu Khaldun tidak menulis sesuatu yang khusus tentang etika politik. Muqaddimah, karya utamanya, bukanlah tentang etika politik. Begitu juga karyanya yang lain. Namun, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa prinsip-prinsip moral dan kebijaksanaan harus digunakan untuk menjalankan kekuasaan politik (Khaldun, 2001). Menurut Iqbal, ungkapannya itu dapat menjadi sarana untuk menyelidiki dan merekonstruksi perspektif etika politik tokoh ini (Iqbal, 2019).
Iqbal mengatakan bahwa ada dua sistem etika politik yang dominan dalam perspektif Ibnu Khaldun. Salah satunya adalah sistem etika politik kesukuan, yang dibangun di atas nilai-nilai ashabiyah (Iqbal, 2019). Kata ashabiyah secara harfiah berasal dari kata ashaba yang berarti “mengikat” (Saumantri & Abdillah, 2020). Ashabiyah dapat didefinisikan secara fungsional sebagai ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, ashabiyah juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan, dan persatuan kelompok (Khudayri & ’Utsmani, 1987).
Konsep ini memiliki dua interpretasi, yaitu destruktif dan konstruktif. Ashabiyah menjadi destruktif apabila cenderung digunakan untuk menjatuhkan pemerintah atau penguasa dengan berbagai cara. Ashabiyah jenis ini dapat ditemukan dalam sistem sosial politik yang alamiah atau kesukuan (badawah) dan dalam sistem sosial politik yang lebih modern (hadarah). Sementara ashabiyah berfungsi sebagai kekuatan konstruktif ketika digunakan untuk mengawasi dan mengontrol, mereka juga mendorong pemerintah untuk melakukan tugas dan fungsinya.
***
Secara sosiologis, klasifikasi masyarakat badawah dan hadarah ini didasarkan pada ashabiyah yang berkembang dalam masyarakat dengan asumsi bahwa ashabiyah dalam masyarakat badawah masih sangat kuat, sedangkan dalam masyarakat hadarah sebaliknya. Masyarakat badawah dengan ashabiyah yang kuat cenderung sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi memiliki perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang kuat dan keinginan untuk bekerjasama.
Berbeda halnya dengan masyarakat hadarah, mereka cenderung memiliki hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik di mana masing-masing individu dalam masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain.
Ibnu Khaldun menggambarkan situasi di mana sebuah kelompok badawah yang dipimpin oleh seorang individu yang dihormati oleh komunitas ashabiyah yang kuat memiliki kemampuan untuk melumpuhkan kelompok hadarah yang sekarat. Setelah masyarakat badawah mengambil alih budaya dan kekuasaan golongan hadarah, mereka lambat laun akan bertransformasi menjadi masyarakat hadarah itu sendiri. Masyarakat badawah kehilangan ashabiyah-nya setelah mengambil alih kekuasaan dan mereka menjadi masyarakat hadarah yang juga akan digeser oleh golongan badawah berikutnya (Amin, 2018).
Tingkatan Ashabiyah Menurut Ibnu Khaldun
Atas dasar penggambaran tersebut, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa sebuah bangsa mengalami perubahan sebanyak tiga tahapan. Tahapan metamorfosis tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, ketika sebuah bangsa memiliki tingkat ashabiyah yang kuat untuk berusaha membentuk sebuah bangsa, mereka berada dalam keadaan masyarakat. Pada tahap awal, masyarakatnya adalah masyarakat badawah yang sedang mempersiapkan diri untuk berkembang menjadi masyarakat hadarah.
Kedua, adalah tahap keberhasilan di mana tingkat ashabiyah yang kuat mampu “merebut” sebuah negara dari usaha tersebut, yang kemudian mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Pada tahap ini, masyarakat badawah mulai berubah menjadi masyarakat hadarah. Masyarakat ini akan beralih ke masyarakat hadarah dan kemudian kehilangan identitas aslinya. Sebagai hasil dari ashabiyah yang kuat, mereka hidup dalam kemewaahan atas usaha yang telah mereka lakukan.
Ketiga, tahap kehancuran terjadi. Negeri yang mereka “rebut” dengan kekuatan ashabiyah akhirnya runtuh karena gaya hidup modern yang menghilangkan semangat ashabiyah. Hal ini karena kemewahan dan ketakutan kehilangan berbagai fasilitas hidup mewah.
Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tahap-tahap tersebut menghasilkan tiga generasi, yaitu generasi pembangun (badawah), generasi penikmat (proses menuju hadarah), dan generasi yang tidak lagi memiliki ikatan emosi dengan negara (hadarah). Jika suatu negara mencapai generasi ketiga ini, negara itu akan runtuh.
***
Menurut Ibnu Khaldun, peradaban besar dimulai dari masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, perjuangan, dan kesulitan. Mereka berusaha keras untuk mencapai cita-cita mereka melalui perjuangan yang keras karena keinginan mereka untuk hidup makmur dan terbebas dari kesusahan hidup, serta memiliki ashabiyah di antara mereka. Impian tercapai kemudian menghasilkan peradaban baru. Biasanya, peradaban baru ini muncul di belakang peradaban lain. Selanjutnya, tahapan-tahapan yang disebutkan di atas terulang terus-menerus, sehingga teori ini dikenal sebagai Teori Siklus.
Oleh karena itu, menurut Khaldun dalam Muslim (2012), maju-mundurnya suatu masyarakat tidak disebabkan oleh kesuksesan atau kegagalan sang penguasa, tetapi oleh ashabiyah-nya. Dengan demikian, teori Ibnu Khaldun menegaskan bahwa faktor solidaritas sosial memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan sosial (Muslim, 2012).
Editor: Ahmad