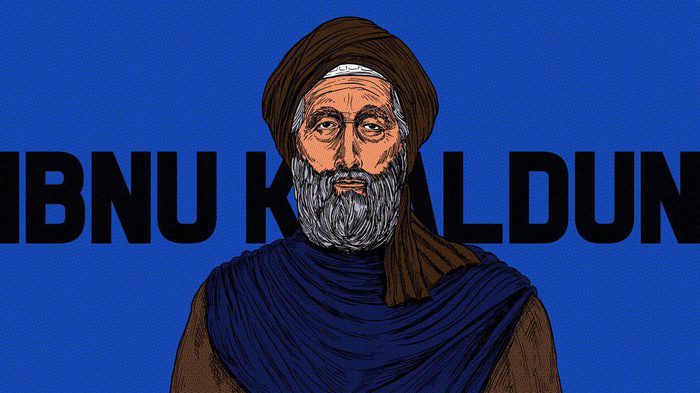“Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya”. Pepatah ini mengingatkan kita pada tokoh sosiolog terbesar abad pertengahan yang banyak dikagumi di kalangan intelektual, baik di Barat maupun di Timur. Ya, Ibnu Khaldun namanya.
Sosok Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami. Ia dilahirkan pada tanggal 1 Ramadhan 732 H, atau yang bertepatan pada 27 Mei 1332 M di Tunisia dan wafat pada 17 Maret 1406 di Kairo (Abdurrahman Kasdi, 2014: 293).
Nama “Ibnu Khaldun” sendiri dapat dilacak dari garis keturunan kakeknya yang kesembilan yaitu Khalid bin Usman. Dari kakeknya inilah Abdurrahman lebih dikenal sebagai Ibnu Khaldun (huruf waw dan nun diakhir sebagai bentuk penghormatan dan kebiasaan orang andalusia). Dan selanjutnya keturunan Khalid lebih dikenal dengan Bani Khaldun, termasuk Abdurrahman.
Dalam silsilahnya, Ibnu Khaldun secara gamblang menguraikannya dalam al-Ta’rif, yaitu: “’Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khalid (dikenal Khaldun-cikal bakal keluarga besar Andalusia dan Maghribi) bin Usman bin Khani’ bin Khattab bin Kuraib bin Ma’ad Yakrib bin Haris bin Wail bin Hujr.
Wail bin Hujr merupakan salah satu sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diberkahi oleh Allah SWT, anaknya dan cucunya sampai hari kiamat. Menurut Ibnu Hazm dalam kitab Jumhurul Ansabil-Arab, Wail bin Hujr juga seorang sahabat Nabi yang terkenal meriwayatkan 70 hadist dan pernah diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman untuk mengajarkan Islam. Dengan para leluhur yang demikian luar biasa, maka tidak heran jika Ibnu Khaldun juga sangat luar biasa dalam bidang keilmuan.
Intelektual Muslim Memandang Peradaban
Ibnu khaldun juga merupakan tokoh pemikir yang mengkaji fenomena sosial, di samping setumpuk keilmuan dan gelar atas prestasi yang diperolehnya. Keinginannya tersebut tentu tidak terlepas dari konteks history dan kekacauan di zamannya. Sehingga mendorong Ibnu Khaldun untuk mengkaji fenomena sosial dengan mendasarkan atas pandangan filosofis-realis.
Sikap ini sebagai upaya Ibnu Khaldun, lantaran para pengkaji fenomena sosial sebelumnya cenderung idealis. Dan kebanyakan, metode yang digunakan banyak dipengaruhi oleh Plato dan Aristoteles seperti yang tampak pada al-Kindi dan al-Farabi. Di mana mereka menjelaskan bahwa gejala sosial seperti apa yang seharusnya untuk mewujudkan masyarakat yang baik. Tunduk pada aturan-aturan sesuai dengan konsep dan teori. (Hafidz Hasyim, 2010: 341).
Akibat atau dampak dari pola tersebut ialah akan terjadi ke tidak-objektif-an pada gejala sosial. Dan parahnya lagi akan menimbulkan penggalian sejarah yang diwarnai kesalahan bahkan kebohongan. Demi menghindari hal-hal semacam ini, Ibnu Khaldun merasa memiliki tanggung jawab untuk menyingkap realitas sosial itu dengan apa adanya, bukan sebagai ada apanya.
Ini didasarkan pada metode yang dibawa oleh al-Kindi dan al-Farabi tersebut tidak lagi memadai dalam menyingkap hakikat realitas, malah cenderung jauh atau idealistik. Makanya Ibnu Khaldun bermaksud untuk mengungkapkan fenomena itu apa adanya dengan meletakkan sistem sosio-politik berjalan sesuai dengan watak alamiahnya. Artinya, kebenaran objektif dalam fenomena sosial harus dapat dibuktikan secara empiris dan dapat diterima oleh nalar logis. Inilah yang tidak terjadi pada intelektual Muslim sebelum Ibnu Khaldun dalam membahas fenomena sosial.
Peradaban dalam Pandangan Ibnu Khaldun
Kebaruan pemikirannya ini tak lepas dari penyandarannya atas pandangan filosofis, bahwa setiap benda dan juga manusia yang ada dalam kesemestaan ini memiliki ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi termasuk gejala sosial pada hakikatnya berjalan sesuai dengan undang-undang yang ada dan tidak pernah sedikitpun melenceng daripada undang-undang tersebut.
Salah satu pandangan Ibnu Khaldun dalam memahami fenomena sosial, yakni konflik antara Ali dan Mu’awiyah. Bagi Ibnu Khaldun, persoalan Ali dan Mu’awiyah bukanlah persoalan benar dan salah. Tetapi kekalahan Ali atas Mu’awiyah, hanya karena tingkat solidaritas para pendukung Mu’awiyah lebih solid, dibanding pendukung Ali.
Dan seandainya saja, Mu’awiyah tidak melakukan perlawanan terhadap Ali, maka Mu’awiyah sendirilah yang akan dihancurkan oleh pendukungnya dan kekuasaan Ali pun akan dihancurkan oleh orang lain. Sekalipun begitu, Ibnu Khaldun tetap saja mengakui Mu’awiyah hanya sebagai seorang raja bukan seorang Khalifah. Dan hal itu tidak menjadi masalah, karena masalah kerajaan adalah hal yang relatif. (Hafidz Hasyim, 2010: 342).
Ibnu Khaldun juga berkeyakinan, diturunkannya syari’at itu pun juga memiliki suatu tujuan, yakni demi keberlangsungannya peradaban itu sendiri. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, tidak ada teks (Al-Qur’an) satu pun yang bertentangan dengan hukum-hukum watak peradaban. Pandangan ini tentu tidak hanya bualan semata, akan tetapi telah mendalami dan melakukan beberapa interpretasi terhadap teks-teks tentang perubahan-perubahan peradaban.
Kesimpulan
Dari sini, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa Ibnu Khaldun memiliki semangat untuk menyingkapi realitas fenomena sosial dengan apa adanya sesuai dengan watak peradaban. Berbeda dengan para intelektual Muslim sebelumnya yang cenderung memungkiri realitas, sebab belum memahami watak peradaban kata Ibnu Khaldun. Akhirnya, merasa bahwa romantisisme zaman Nabi SAW adalah suatu peradaban yang terbaik dan berkeinginan untuk melakukan tradisi yang sama.
Akibatnya, pola-pola pemikiran seperti ini malah cenderung idealis, sebab ada konteks zaman yang sama sekali berbeda. Ibnu Khaldun dengan keberaniannya menggagas suatu pemikiran yang benar-benar baru. Sehingga menghantarkan dirinya sebagai pendiri dan peletak dasar sosiologi pertama yang bernuansa realis.
Editor: Saleh