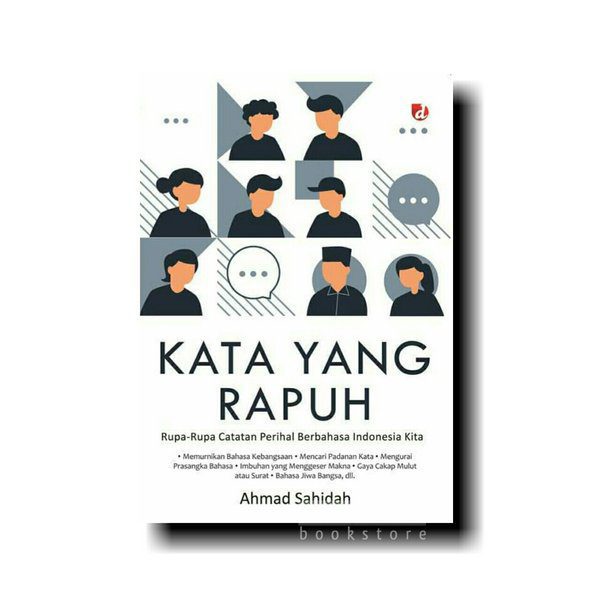Status manusia sebagai makhluk sosial turut mengait anasir-anasir lain di luar dirinya. Dari rambatan ini kemudian lahir proses interaksi antara manusia satu dengan liyan lewat perantara bahasa. Tentu, bahasa yang dipakai lumrah menyesuaikan lingkungan di mana interaksi berlangsung.
Bahasa adalah soal kesepakatan, demikian yang sering disitir. Satu kelompok masyarakat sah-sah saja berdialog dengan mitranya menggunakan simbol-simbol tertentu yang saling dipahami sebagai konsep yang diinginkan.
Suatu kota di Turki, misalnya, hampir seluruh penduduknya menggunakan bahasa siul untuk menyambung komunikasi jarak jauh karena letak geografi tidak mendukung mereka berinteraksi antar tebing.
Dalam Islam, yakni Al-Qur’an, sejarah lahirnya bahasa tidak hanya berdasar dari konsesus masyarakat, melainkan sebuah paket matang dari langit untuk bekal manusia hidup di bumi atau disebut tawqīfi. Kata al-asmā (bentuk plural ism, nama) dalam al-Baqarah ayat 31 adalah konsep mengenai pernak-pernik ciptaan yang dihadiahkan kepada Adam dalam wujud yang “siap saji”, taken for granted.
Menjenguk Bahasa Indonesia
Membaca Kata Yang Rapuh, anggitan Ahmad Sahidah, kumpulan tulisan yang pernah tersiar di beberapa media seperti Majalah Tempo, Jawa Pos, dan Suara Merdeka, rasanya seperti sedang menjalani pijat refleksi sambil menyimak kegundahan si tukang menghadapi otot-otot bahasa yang kaku karena lama tak digerakkan.
Sebagai anak yang lahir-tumbuh di Indonesia, kita sepatutnya bangga dengan ragam buminya. Mirip pertanyaan klise yang acapkali dilontarkan, jika bukan kita, siapa? Tetapi apakah kebanggaan itu terus kita rawat atau tidak, adalah persoalan menantang. Hidup di zaman serba canggih, beberapa bidang kita telah ditindih produk asing.
Termasuk kaitannya dengan bahasa yang lumrah menandai dari mana ia bermuasal. Bahasa Indonesia, sebagai lingua franca, bahasa pengantar kita, dewasa ini bernasib kurang menguntungkan.
Kondisi itu dapat dengan mudah kita amati di beberapa masyarakat di kota besar. Di mana, terjadi ragam interaksi yang kompleks baik secara verbal atau perantara gawai. Di sana, bahasa Indonesia bertaruh eksistensi dengan bahasa asing.
Bahasa Indonesia tidak lagi megah di mulut-mulut pejabat yang merasa lebih berwibawa bicara dengan bahasa asing. Virus ini, agaknya, telah merembes ke ruang-ruang televisi publik. Dari penamaan program tayangan, misalnya, memilih judul “Talk Show” dirasa lebih gagah ketimbang Dialog Muka.
Sematan Presenter, Host, terdengar lebih mewah (meski tidak terdaftar dalam KBBI) ketimbang penyampai. Padahal sekitar tahun 2000-an, kita menyaksikan program Televisi Rakyat Indonesia (TVRI) dimulai oleh Pembawa Acara (bukan MC) wanita bersanggul yang menyampaikan agenda tayangan beberapa jam kedepan.
Kecenderungan kita memakai istilah kebarat-baratan patut dibatasi hanya pada kebutuhan teknis, yakni ketika pengandaian makna bahasa asal tidak sepenuhnya ditangkap oleh bahasa Indonesia.
***
Meminjam misal Ahmad Sahidah, being-in-the-world (atau Dasein)-nya Martin Heideger yang dalam bahasa Indonesia artinya “mengada di dunia”, semata dimakfu untuk kebutuhan membeber hakikat istilah itu.
Tetapi dalam istilah lain yang dapat ditemukan padanannya, alangkah baik padanan itu digunakan senyampang tidak mereduksi makna awal. Seperti dekonstruksi dalam wacana Filsuf Jacques Derrida yang mengandaikan arti proses menjadi hancur, bisa menggunakan pola pe -an dalam bahasa Indonesia.
Malangnya, elit kita tendensius mengatakan dekonstruksi alih-alih penghancuran. Jika narsis semacam ini terus berlanjut, bahkan tak pelak diwarisi golongan muda, bahasa Indonesia tidak diharapkan bernafas lebih panjang.
Dengan laju teknologi demikian dahsyat, agaknya sulit membendung ragam bahasa yang melingkar dalam jejaring dumay (dunia maya). Dalam banyak judul tulisannya di buku yang terbit 2019 ini, Ahmad Sahidah mencatat hasil pengamatannya dari ruang Twitter. Bahwa jutaan pengguna aplikasi berlogo burung itu, terutama warga Indonesia, senang mencampurkan bahasa pengantar dengan bahasa Inggris.
Dikarenakan Twitter membatasi jumlah karakter pada kicauan yang akan diunggah, pengicau merasa harus berhemat kata karenanya mengimpor bahasa Inggris atas pertimbangan jumlah huruf lebih pendek.
Pola semacam ini, jika dilepastangan, akan semakin membengkak dan rumit. Ahmad Sahidah, yang juga pernah mengajar di Universitas Sains Malaysia, kerap menyandingkan realitas kesadaran berbahasa di dua negara serumpun.
Ia menilai, semangat berbahasa di Indonesia masih loyo terbukti dengan nomenklatur acara-acara televisi dengan nama asing atau selebriti yang suka menghambur-hamburkan kata Inggris sepanjang wawancara. Entah karena malas mencari kata kembaran yang tercantum di KBBI, atau karena lidahnya merasa pas mengucap kata-kata asing, atau demikian ini besar dipengaruhi tradisi setempat?
Apapun itu, merasa gagah sewaktu melontarkan bahasa asing dan mengerdil saat berbahasa Indonesia, menyitir kiasan Ahmad Sahidah, adalah upaya penguburan khazanah kita. Bahwa mewujudkan Saya-Indonesia dimulai dengan menata kata.
Judul: Kata Yang Rapuh
Penulis: Ahmad Sahidah, Ph.D
Penerbit: DIVA Press
Tahun Terbit: 2019 (cetakan pertama)
Tebal: 184 hlmn; 14 x 20 cm
Editor: Yahya FR