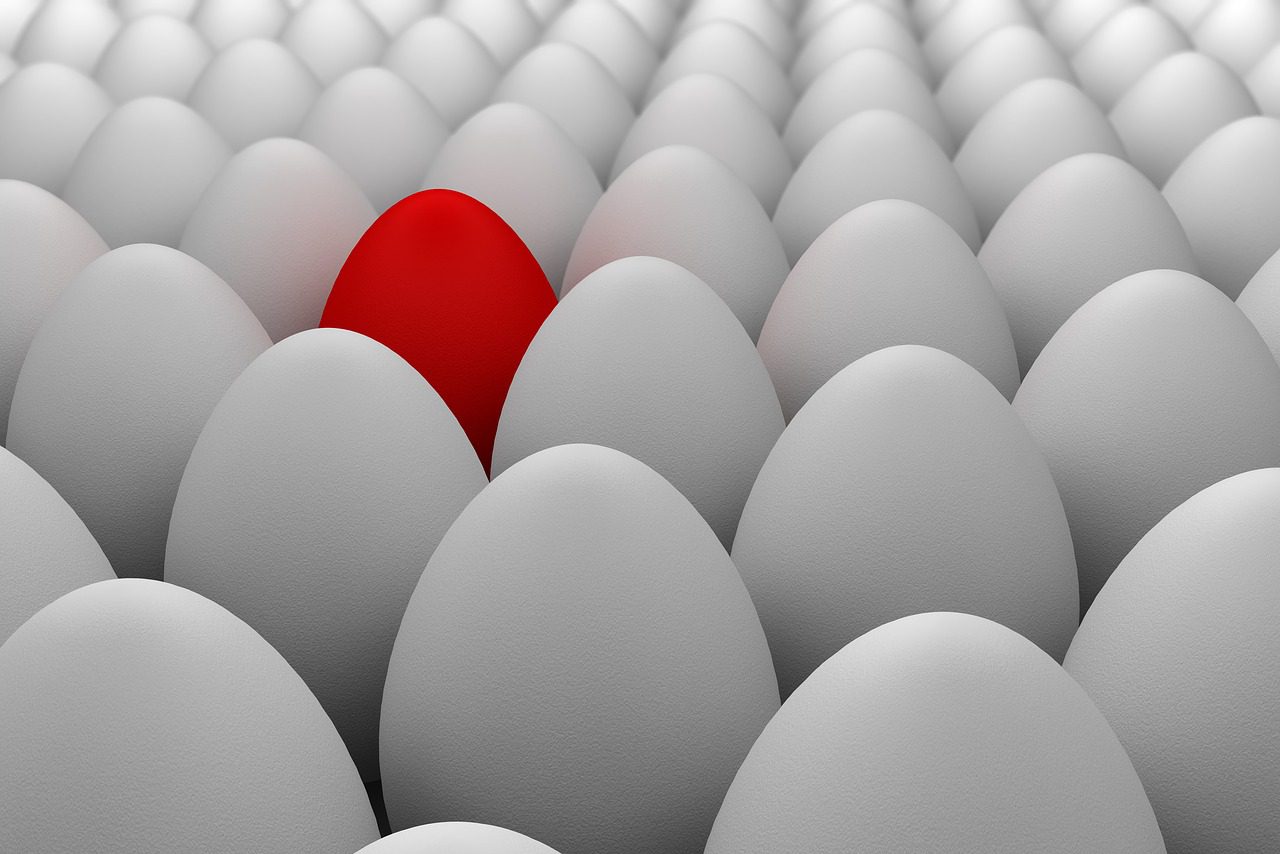Sebelum membahas bagaimana menyikapi perbedaan secara bijak, izinkan penulis bercerita suatu kejadian. Malam itu, suasana pengajian rutin menjadi heboh. Salah seorang penceramah menjelaskan bahwa seorang muslim boleh memelihara anjing. Beliau merujuk pada pendapat Imam Malik Ibn Anas, seorang ahli fiqih dari Makkah.
Menurut semua jamaah di sana, memelihara anjing hukumnya haram. Dengan dalil, dulu saat menerima wahyu, Jibril enggan masuk ke rumah Nabi Muhammad dikarenakan ada seekor anjing yang sedang bersembunyi di sana. Atas dasar itulah memelihara anjing dianggap haram. Setelah kejadian itu, si penceramah tidak pernah diundang mengisi pengajian. Hanya karena perbedaan pendapat, boleh tidaknya memelihara anjing di rumah.
Menyikapi Perbedaan Fikih
Contoh perbedaan pendapat dalam masalah furu’iyah, terutama masalah fikih sangat banyak. Antara satu ulama dengan ulama lain, bahkan antara mayoritas ulama (jumhur ulama) dengan minoritas ulama (ba’dul ulama) sering kali terjadi.
Contoh pertama seperti kasus di atas. Mayoritas ulama mengharamkan seorang muslim untuk memelihara anjing dengan banyak dalil. Tidak sekadar kisah malaikat Jibril yang enggan masuk ke rumah Nabi Muhammad S.A.W karena di dalamnya ada anjing. Sedang Imam Malik Ibn Anas yang merepresentasikan minoritas ulama membolehkan seorang muslim memelihara anjing. Tentunya dengan syarat dan koridor tertentu.
Kedua, mayoritas ulama menyatakan bahwa memakan daging unta tidak membatalkan wudhu. Sedangkan Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan bahwa memakan unta menyebabkan batal wudu.
Ketiga, mayoritas ulama menyatakan bahwa qunut hanya dianjurkan ketika terjadi peperangan atau musibah. Dilain sisi, Imam Idris As-Syafi’i menyatakan bahwa qunut juga dilaksanakan saat menegakkan sholat subuh.
Keempat, mayoritas ulama menyatakan bahwa nabidz (perasan selain anggur) itu haram. Namun, Imam Abu Hanifah membolehkan nabidz asal tidak sampai mabuk.
Kelima, mayoritas ulama sepakat bahwa seluruh tubuh babi haram dimakan, sedang Imam Daud Al-Zahiri menyatakan yang haram dimakan hanya dagingnya (lahm).
Adanya perbedaan pendapat dalam masalah fiqih, tidak membuat para ulama saling mengkafirkan, menyesatkan, dan membid’ahkan. Apalagi saling berperang karena menganggap pendapatnya yang paling benar. Justru dengan rendah hati mereka berkata:
“Pendapatku benar, tapi bisa jadi salah.”
Andai mereka masih hidup, mereka akan saling tersenyum dan berpelukan di kala bertemu. Bahkan muncul bahasa perumpamaan kekinian:
“Kalau mereka masih hidup dan bertemu, mereka bakalan ngopi-ngopi bareng di angkringan,” Artinya, perbedaan bukan menjadi masalah besar terhadap masalah-masalah furuiyah yang profan dan penuh dengan perdebatan, serta dialektika panjang.
Sepanjang tradisi Islam, perbedaan dalam masalah fikih adalah perbedaan yang saling melangkapi (ikhtilaf at tanawu’), bukan perbedaan saling menafikan (ikhtilaf al tadhod).
Meredam Konflik
Dalam Islam, perbedaan adalah hukum alam (sunnatullah) yang tidak bisa dipungkiri dan dinafikan. Menentang perbedaan sama dengan menentang takdir dari Allah. Dengan kata lain, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan mutlak yang ada di alam raya.
Realita mengamini bahwa di alam raya tak hanya ada manusia. Tapi ada pula gunung, hewan, laut, sungai, pohon, dan lain-lain. Tentunya masing-masing mereka memiliki perbedaan dari segi visual, dan fungsional. Yang menjadi pertanyaan: “Apakah dengan perbedaan tersebut, mereka saling menyalahkan? Tentu saja tidak!”
Justru mereka saling melengkapi. Manusia akan senantiasa membutuhkan bantuan gunung untuk menjaga keseimbangan alam di bumi. Begitu juga bagi gunung, manusia mempunyai peran sentral sebagai pemimpin di muka bumi (khalifah fil ardi) yang mengendalikan maju dan tidaknya sebuah peradaban di sana.
Bayangkan jika hidup manusia tanpa dibersamai gunung, tentu setiap hari manusia akan cemas. Bisa jadi sewaktu-waktu bumi akan mengeluarkan lahar panas karena tak punya tempat penyimpanan. Begitu pula dengan kehadiran gunung tanpa adanya manusia. Tentu akan seperti anak ayam kehilangan induknya.
Sama halnya dengan masalah furuiyah maupun masalah keagamaan lain. Yang perlu ditonjolkan bukan malasah perbedaannya, namun sikap kedewasaan seseorang dalam menyikapi perbedaan tersebut.
Menganggapi hal ini, penulis sepakat untuk menyikapi perbedaan lewat gagasan fiqih kebhinekaan yang diluncurkan oleh Maarif Institute dalam bentuk buku sebagai respon maraknya konflik salah paham akibat perbedaan. Buku tersebut berjudul: “Fikih Kebinekaan Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim.”
Buku itu merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang ditulis dari berbagai penulis handal. Salah satu buku yang sangat relevan dengan realita saat ini. Di mana perbedaan masih dianggap sebagai hal tabu dan menyimpang.
Belajar Kebhinekaan dari Piagam Madinah
Secara historis, Islam tidak pernah alergi dengan perbedaan. Buku tersebut menjelaskan bahwa perbedaan telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W hidup. Hal itu dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah.
Di mana piagam tersebut menjadi simbol modern dalam menanggapi kemajemukan, keragaman, kebhinekaan, dan pluralitas agama saat itu. Melalui Piagam Madinah, semua umat setara di ranah sosial. Mereka semua saling tolong-menolong dalam urusan sosial, seperti peperangan. Hal ini termaktub dalam pasal 18:
“Setiap pasukan yang berperang bersama, harus saling bahu-membahu satu sama lain”
Piagam Madinah memberikan pelajaran kepada kita, meski interakasi sosial dilakukan multi agama, namun tidak menafikan adanya persatuan dan kesatuan di ranah sosial.
Rasulullah S.A.W sudah memberikan contoh berinterakasi lintas agama yang baik melalui Piagam Madinah. Kita sebagai umat Islam, seharusnya juga bisa menyikapi perbedaan secara arif dengan mengedepankan tasamuh (toleransi).
Perbedaan dalam masalah furuiyah, terutama dalam masalah fiqih tentunya sangat dimaklumi. Apalagi terhadap masalah-masalah kontemporer yang belum ada di masa lalu. Selama masih merujuk kepada maqashid syariah dan maslahah tentunya itu bukan masalah. Wallahu a’alam
Editor: Sri/Nabhan