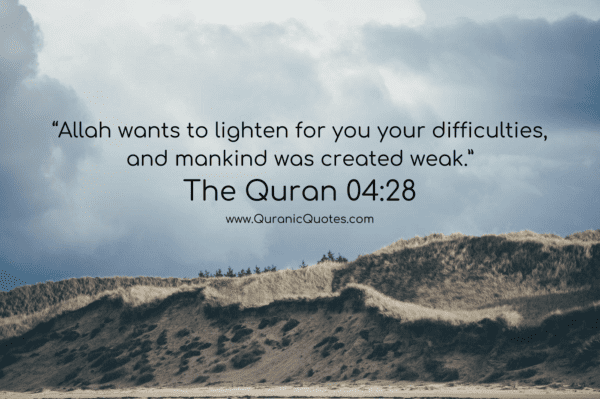Oleh: Fathor Razi*
Barangkali sejenak kita renungkan tindak-tanduk kita selama ini. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang kita lalui tak mungkin luput dari kesalahan dan kekhilafan. Baik perilaku maupun ucapan saat berinteraksi sosial baik di dunia maya dan nyata, seperti menilai buruk orang lain.
Kebaikan dan keburukan selalu menyertai kita. Di mana dan kapan pun, selama nyawa dikandung badan. Setiap orang tentu memiliki sifat baik dan buruk. Jika sifat baik menjadi prioritas, maka sifat buruk tak memiliki tempat bagi kehidupan kita hingga menjelang kematian.
Jika sifat buruk mendominasi laku kita sehari-hari, bukan tidak mungkin, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan permasalahan baik lahir maupun batin. Salah satunya menilai diri kita lebih baik dan sempurna dari orang lain, dan orang lain lebih buruk kehidupannya dibanding kita sendiri.
Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita termasuk makhluk yang lemah (wakhaliqal insanu dha’ifa (Q.S. An-Nisa’ : 28), yang tak memiliki kuasa dan berhak menilai orang sesuai pikirian kita. Merasa diri kita paling baik, paling suci, namun understimate pada orang lain.
Kita Bukan yang Paling Benar
Sebagaimana kita ketahui, tatkala kita menginjak masa baligh, maka kita menanggung dosa atas apa yang kita mulai dalam hal apapun bentuknya. Yang tampak, maupun yang dosa amat samar sekali. Namun yang terbersit dalam benak selalu mempertanyakan, apakah noda dan dosa yang kita mulai tak luput dari ampunan-Nya?
Ini lantaran penilaian kita yang terbatas seolah memutlakkan kebenaran, bahwa yang berdosa tak akan memiliki ruang untuk bertobat. Bahkan mungkin ada ucapan yang tidak enak diperdengarkan:
“Ah kau tetap saja dalam pandanganku. Kau tetap harus hina hingga akhir hayatmu. Aku tak percaya. Mau pontang-panting pun usaha untuk jadi menjadi orang baik dan taat beribadah. Penilanaiku sama tetap saja, sama saja: Kau seperti yang dulu.” Bahkan mungkin ada nada yang tak pantas terucap: “Kau hanya manis di lidah, namun busuk di hati.”
Kedahsyatan isi pikiran kita amatlah berbatas. Jangkauan pikiran kita terlalu jauh melampaui ketentuan serta rahmat-Nya. Kita pun tak semaksum Nabi Muhammad SAW. Amat disayangkan jika seolah-olah kitalah yang paling benar dalam hidup ini. Na’dzubillah…
Menuduh Fasik
Oleh karena itu, rasa-rasanya tidak begitu sulit bagi kita untuk menghilangkan rasa benar sendiri, paling suci, dan berhak melabeli orang tersebut telah melakukan dosa yang sangat besar-–di masa lalu maupun di masa akan datangnya.
Apakah amal ibadah orang lain–baik ibadah transendental maupun horizontal, yang kita anggap rendah dan nista–diterima atau ditolak, bernilaikan pahala atau dosa, kita tak tahu pasti. Wallahu a’alam bish-shawab.
Sebaliknya, amal ibadah yang kita lakukan, benar-benar bernilaikan pahala atau justru kitalah–secara tidak sadar–mentransfer pahala kebaikan kita untuk orang yang berdosa, dan kita hanya menanggung dosa orang lain yang kita anggap munafik.
Sebagaimana dalam sebuah hadits:
ﻻﻳﺮﻤﻲ ﺮﺠﻞ ﺮﺠﻼ ﺒﺎﺍﻠﻔﺴﻖ ﺍﻭﺍﻠﻜﻔﺮﺍﻻ ﺍﻠﺘﺪﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻦ ﻠﻢ ﻴﻜﻦ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻜﺬﺍﻠﻚ ﴿ﺭﻮﺍﻩﺍﻠﺒﺨﺎﺭﻯ﴾
Tidak sepatutnya kita sebagai manusia menuduh seseorang telah fasik (tidak mentaati perintah Allah dan telah dianggap berdosa besar), dan mengatakan seseorang telah keluar dari Islam (kafir), melainkan tudingan atas kata fasik dan kafir akan terpulang kepada si penuding apabila tudingan itu tidak sesuai dengan apa yang ia sangkakan kepadanya (HR. Bukhari)
Maka dari itu, ada masanya orang berpaling dari perbuatan dosa. Jadi, berdosalah dan merugilah kita, jika orang yang kita anggap berdosa dan hina sehina-hinanya, namun sebelum kematiannya ia telah secara totalitas bertobat. Maka, berhentilah menilai buruk orang lain.
Menilai Buruk Orang Lain
Merujuk ungkapan Ahmad Musthofa Bisri (Gus Mus), “Jadi, anda tidak bisa mengatakan seseorang munafik, kenapa? Karena anda tidak tahu dalamnya, kalau anda bisa berarti anda terlalu berani, mengaku seperti kanjeng Nabi Muhammad.”
Akan hangus secara percuma ibadah yang kita tunaikan, lantara kita sibuk menilai buruk orang lain. Kita semestinya dianjurkan melakukan hal-hal yang–meminjam istilah Komaruddin Hidayat–mencerahkan kehidupan sosial. Melalui tindakan terpuji dan amalan-amalan ibadah yang mulia.
Oleh karena itu, bagi hamba-Nya yang memiliki kepekaan rohani yang mendalam, di saat tengah malam, dijadikannya ajang perserahan diri (waminal-laili fatahajjad bihi nafilatallak), menyibukkan diri dengan aktivitas ibadah yang bersifat keduniaan sepantasnya, dan menjalankan ibadah yang berhubungan dengan akhirat. Semestinya kita patuh dalam menjalankan perintah-perintah-Nya.
Pertanyaannya kemudian, apakah kita terlalu sulit untuk sejenak merenung di tempat sunyi, menyisiri deretan kesibukan pekerjaan yang kita kerjakan serta interaksi sosial melalui ucapan yang kita sampai sepanjang hari?
Jawaban yang sejujur-jujurnya tentu ada dalam benak diri kita masing-masing. Wallahu ‘alam bish-shawab
*Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.