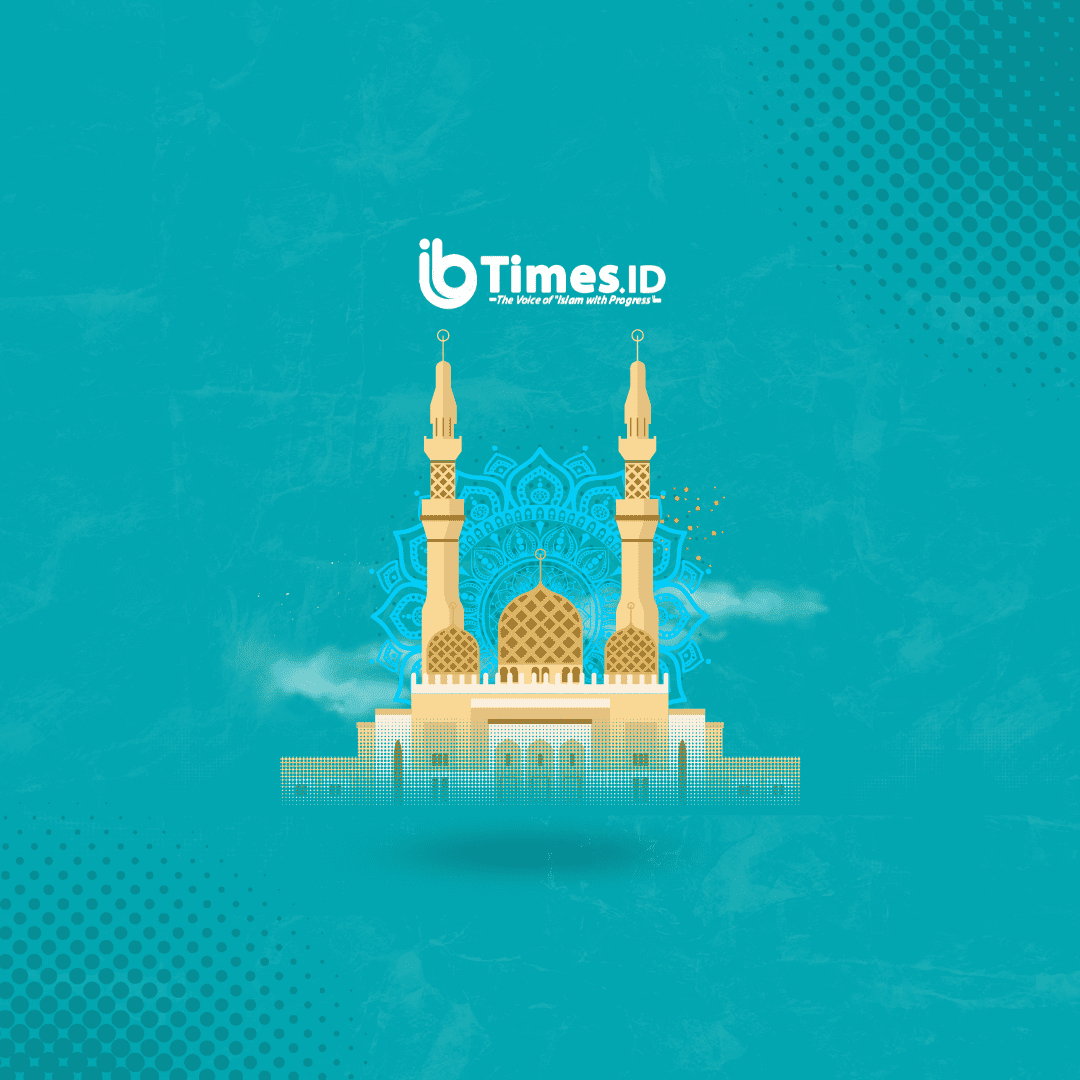Sebagaimana diketahui, sebagai gerakan dakwah Islam Muhammadiyah tidak mengikat diri pada mazhab tertentu. Baik secara fikih maupun akidah. Meski begitu, tidak berarti Muhammadiyah anti mazhab. Berbagai mazhab yang ada itu diakomodir, lalu dipilih atau ditarjihkan sesuai manhaj yang dianut oleh Muhammadiyah.
Sikap tidak mengikat diri pada mazhab tertentu ini sering dikaitkan dengan sifat Muhammadiyah yang modernis dan pembaru. Artinya tidak terlalu taklid atau mengekor kepada tradisi terdahulu, melainkan mencoba menawarkan hal baru tanpa mengabaikan khazanah terdahulu. Konsekuensinya, tidak bisa kita mengatakan bahwa Muhammadiyah itu Asy’ari misalnya, sebagaimana tidak bisa kita menghukumi Muhammadiyah itu salafi. Bahwa ada banyak persamaan atau kedekatan, itu lain hal. Sudah banyak tulisan atau kajian yang melakukan pendekatan antara Muhammadiyah dengan Asy’ari maupun Salafi.
Yang ingin penulis soroti ialah dampak sikap tidak bermazhab ini dalam bidang fikih. Berbeda dengan NU yang mengikuti mazhab Syafii, Muhammadiyah dalam urusan fikih menggunakan manhaj tarjih. Kitab- fikih klasik digantikan dengan HPT sebagai panduan ibadah. Akibatnya, kajian fikih mazhabi dan berbagai literatur fikih klasik tersebut kurang populer bagi warga Muhammadiyah.
Selain itu, sering ada anggapan bahwa pengajaran fikih mazhabi—yang menggunakan kitab fikih para ulama (bukan langsung Al-Qur’an dan sunah)—di persyarikatan dinilai kontra-produktif dan berseberangan dengan nilai modernitas dan pemurnian yang dianut Muhammadiyah.
Benarkah demikian?
Pengertian Mazhab Fikih
Dalam khazanah keilmuan Islam, istilah mazhab fikih tentu bukan barang asing. Secara bahasa, mazhab berarti jalan yang dilalui atau dilewati. Adapun secara istilah, para ulama mengartikan mazhab sebagai jalan atau metode yang dipakai setelah melalui penelitian, kemudian orang menjadikannya sebagai pedoman.
Hingga saat ini, ada empat mazhab fikih yang populer dan terjaga ajarannya; Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali. Dikatakan populer karena 4 mazhab ini, dibanding puluhan mazhab lainnya, ajarannya paling tersebar ke seluruh penjuru dunia dan banyak memiliki pengikut yang melestarikan ajarannya sampai saat ini.
Berbicara soal mazhab bukan hanya soal pendapat sang Imam saja, melainkan juga berkaitan dengan pendapat rijalul mazhab, dasar-dasar mazhab (ushulul mazhab), kitab-kitab yang dipelajari, dan madrasah diajarkannya mazhab itu sendiri.
***
Mazhab ialah satu kesatuan dari berbagai komponen di atas. Tidak semua pendapat Imam Syafii misalnya, dianggap sebagai bagian dari mazhab Syafii. Ada 20 pendapat Imam Syafii ditinggalkan atau tidak diamalkan dalam mazhab.
Meski begitu, bukan berarti terjadi inkonsistensi dalam mengikuti pendapat sang Imam. Justru ini bukti bahwa dalam mazhab terjadi proses filter ilmiah yang panjang selama ribuan tahun oleh berbagai ulama dalam lintas disiplin keilmuan.
Jika kita tengok literatur usul fikih terdahulu, mungkin kita akan susah menemukan istilah tamazhub (menganut mazhab). Namun jika kita perhatikan literatur sejarah Islam, kita dapati para ulama terdahulu menisbatkan dirinya kepada mazhab tertentu, sebagaimana sering kita baca nisbah tersebut di belakang namanya. Tidak terhitung banyaknya ulama terang-terangan mengikuti mazhab fikih tertentu.
Imam Tajudin al-Subki (w. 771 H) dalam Kitab Jam’ul Jawami’ menyebutkan pengertian bermazhab ialah, “berpegang teguhnya orang selain mujtahid kepada mazhab tertentu yang diyakininya lebih kuat atau setara dengan selainnya.”
Tidak bisa dimungkiri, berpegang teguh atau memilih satu mazhab tertentu dalam fikih ialah sunnatullah atau tradisi para ulama terdahulu. Mereka saat belajar fikih pasti memulai dengan suatu mazhab tertentu, urut dan berjenjang dari level dasar sampai expert. Tradisi ini terbukti mampu mencetak para ahli fikih mumpuni yang bukan saja mampu menjawab persoalan fikih ibadah-muamalah klasik, namun juga mampu menjawab masalah kontemporer.
Bermazhab Bukan Anti Modernitas
Belakangan, di beberapa cabang dan daerah Muhammadiyah, kajian fikih mazhabi mulai banyak diminati. Hal ini tidak lepas dari pengaruh sebagian alumni Timur Tengah yang pulang, lalu mengajarkan fikih kepada masyarakat dengan metode mazhabi komparasi HPT. Metode ini membuka mata bahwa cukup banyak persoalan fikih mendetail belum dibahas di HPT, namun terdapat di kitab fikih klasik. Akhirnya perlahan mereka mengenal khazanah fikih klasik dan tertarik mempelajarinya betapapun tidak sederhana.
Meski begitu, bagi sebagian orang, mempelajari atau menganut fikih mazhabi masih dianggap terlalu kolot. Mereka menganggap pembelajaran fikih klasik terlalu rumit, ketinggalan, dan tidak mampu menjawab persoalan kontemporer. Apalagi Muhammadiyah sendiri sudah mendeklarasikan dirinya tidak bermazhab.
Padahal orang yang bermazhab itu sejatinya mencoba memahami fikih sesuai dengan nalar berfikir para ulama terdahulu. Mengikuti satu mazhab tertentu tidak berarti selalu mengikat diri dengan pendapat sang imam. Dalam kondisi tertentu, boleh saja ia memilih pendapat lain dengan aturan yang telah ditetapkan. Artinya ini tidak rigid atau membelenggu sebagaimana dipahami sebagian orang. Mengikuti mazhab seperti memasuki sebuah sekolah dengan kurikulum yang sudah baku, namun sama sekali tidak mengikat alumninya untuk seratus persen mengikutinya.
Bermazhab juga tidak anti modernitas sehingga gagap menjawab persoalan kekinian. Justru dengan mempelajari mazhab secara mendalam, ketika sudah menguasai ushul-ushul (dasar-dasar) pendapat sang Imam, mudah saja persoalan tersebut dicarikan jawabannya. Baik dengan takyif fiqhi maupun “berijtihad” dengan dalil.
Bermazhab Bukan Berarti Tidak Kembali ke Al-Qur’an dan Sunah
Yang tidak kalah nyaring ialah suara yang mengatakan bahwa bermazhab itu bertentangan dengan semangat ar-ruju’ ila Al-Qur’an wa as-sunah. Slogan yang selalu digaungkan ini menjadi semacam landasan bahwa dibanding mengikuti perkataan imam mazhab yang berpotensi salah, tentu lebih baik dan lebih aman mengikuti Al-Qur’an dan As-Sunah Al-Maqbulah yang pasti benar.
Mudah saja, jika kita baca dan lihat sejarah para imam mazhab, akan kita saksikan bagaimana kuat terikatnya mereka dengan Al-Qur’an dan sunah. Sejak kecil sudah menghafal Al-Qur’an, mencari hadis, menghafalkannya, dan berguru untuk memahaminya. Mereka memiliki semua klasifikasi seorang mujtahid. Jauh perbandingannya dengan kita. Maka tidak lagi relevan perkataan “hum rijal wa nahnu rijal” kita terapkan sebagaimana dulu dikatakan Imam Abu Hanifah.
Adapun jika terdapat sebuah pendapat mazhab yang menyelisih hadis sahih, itu bukan karena pendapat sang imam lebih baik dibanding hadis. Melainkan karena sang imam lebih memilih dalil hadis lain atau memang hadis tersebut saat itu belum dijumpainya.
Al-Hafidz Ibn Katsir dalam kitab Al-Baits Al-Hatsis mengutip Syaikh Waki’ yang mengatakan, “hadis yang diriwayatkan dan dibahas oleh ahli fikih lebih baik dari hadis yang dikaji oleh ulama ahli hadis.”
Syahdan, tulisan ini tidak lain hanya mencoba memberi sudut pandang lain terkait kajian fikih mazhabi atau gelagat sebagian warga persyarikatan yang mulai mempelajari fikih mazhab. Dengan tetap mempelajari HPT sebagai pedoman persyarikatan, kajian fikih mazhabi di kalangan persyarikatan akan tetap menemui relevansinya bahkan akan saling mewarnai dan melengkapi satu sama lain.