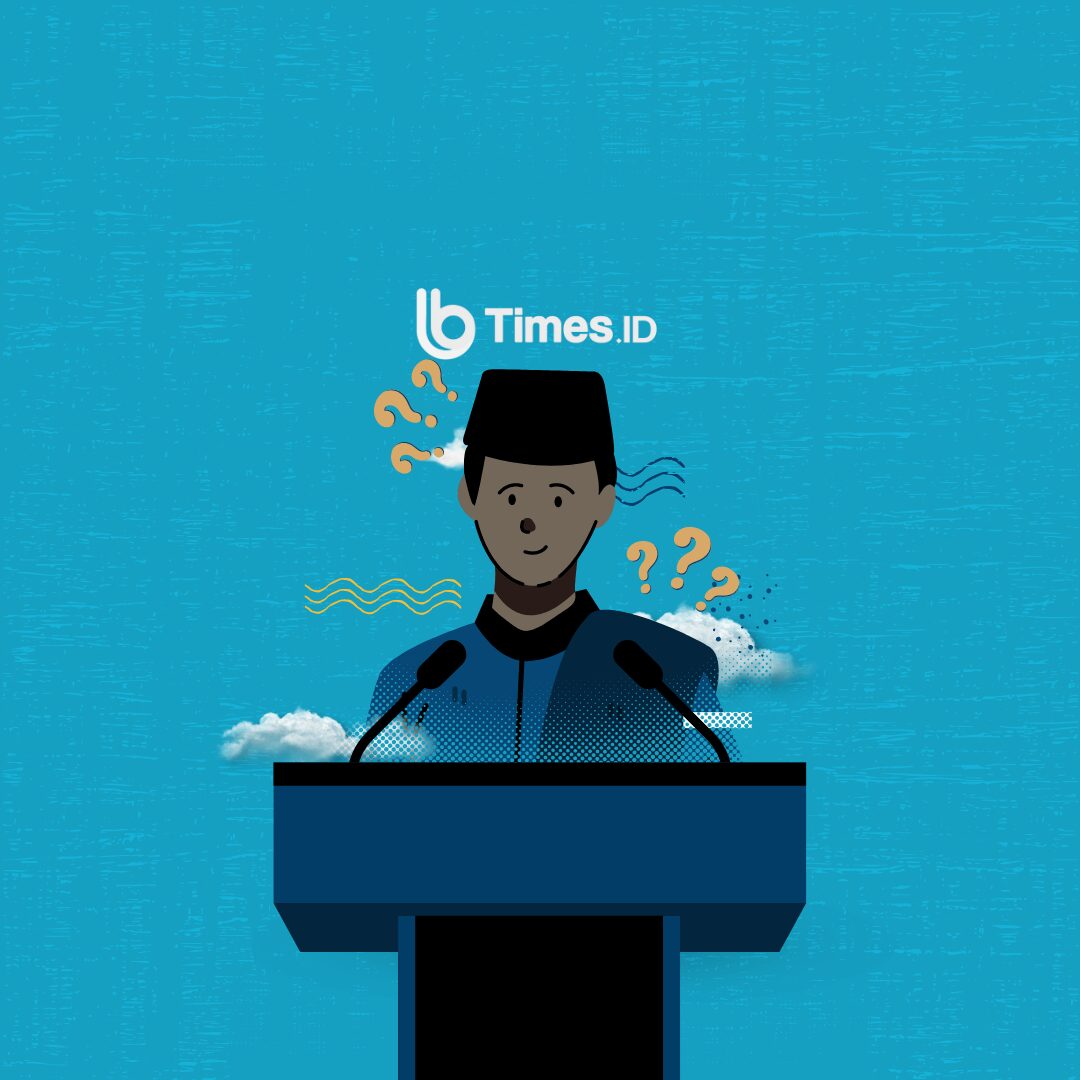Purnama malam itu menggantung di langit Hastinapura, pucat seperti wajah para guru yang kehilangan kata di hadapan dadu kekuasaan yang digenggam para penguasa. Angin berdesir membawa aroma mesiu masa depan yang terbakar. Di balairung agung, lantai batu berkilau oleh cahaya obor, tetapi kilau itu tidak menyingkap kebenaran—hanya menyoroti wajah-wajah yang membeku di antara kemewahan dan kebisuan.
Perang Mahabharata, kata orang, terjadi karena benturan dua kekuatan besar. Namun, sejarah yang jujur tahu bahwa bara itu bukan dinyalakan oleh musuh luar, melainkan oleh api yang menyala di dapur kekuasaan sendiri—api yang disiram oleh ludah serakah, oleh judi politik di atas papan dadu nasib rakyat.
Di sudut aula, Sangkuni tersenyum. Ia bukan sekadar penasihat licik; ia adalah arsitek kehancuran, penulis naskah sandiwara besar. Duryodana duduk di singgasananya, mata menyala penuh ambisi, memandang Pandawa seperti seekor harimau lapar melihat rusa yang terikat.
Sunyi di Tengah Kemewahan: Kebisuan Para Ulama dan Guru
Dadu pun dilempar—bukan sekali, bukan dua kali—melainkan berkali-kali, hingga yang dipertaruhkan bukan lagi tanah atau harta, melainkan kehormatan itu sendiri.
Hari itu, di depan mata para ksatria, seorang wanita—simbol martabat keluarga, lambang suci negeri—dilucuti kehormatannya. Drupadi, dengan kain sari yang ditarik tanpa malu, menjadi saksi bahwa kekuasaan dapat menelanjangi apa saja: tubuh, harga diri, bahkan iman.
Namun, yang mengerikan bukan hanya peristiwa itu, melainkan sunyi yang mengikutinya.
Resi Durna, guru agung yang mengajarkan dharma kepada Pandawa dan Kurawa, hanya terdiam. Bisma, panglima besar yang dijuluki Mahaguru Kebenaran, memalingkan wajah. Widura, menteri bijak, menggenggam lengan kursinya, tetapi tak berkata. Kripacarya, guru rohani, menunduk dalam doa yang tak sanggup mengubah kenyataan.
Sunyi itu lebih mematikan daripada seribu pedang. Sunyi itu menegaskan bahwa kejahatan telah mendapat restu dari keagungan yang membisu.
Dadu Kekuasaan: Pengkhianatan Moral di Hastinapura Modern
Riwayat ini bukan sekadar dongeng purba. Ia adalah cermin retak yang memantulkan wajah negeri kita hari ini.
Bukankah kita juga menyaksikan, di balairung politik modern, para penguasa melempar dadu kekuasaan di atas punggung rakyat? Bukankah kita menyaksikan kehormatan bangsa dilucuti secara vulgar di layar kaca—kehormatan wanita yang dijadikan komoditas, kehormatan akademis yang dijual demi proyek, kehormatan agama yang diperdagangkan dalam paket politik?
Lembaga pendidikan—konon benteng terakhir peradaban—kini bagai padepokan yang merelakan pintunya digembok oleh para pemilik modal. Akademisi kehilangan marwahnya; ilmuwan menjadi penggembira proyek kekuasaan. Mereka diberi gelar dan jabatan, bukan karena ilmunya yang menyala, melainkan karena kesediaannya memadamkan api nurani.
Para ulama? Banyak yang memilih menjadi tamu kehormatan di istana, membaca doa untuk meresmikan kebijakan yang mencederai rakyat, ketimbang berdiri di tengah jalan bersama mereka yang lapar. Sebagian menjual legitimasi agama dengan harga kontrak politik.
Sunyi itu kembali hadir, memekakkan telinga.
Di masa lalu, Sangkuni menjual liciknya untuk merusak tatanan Hastinapura. Di masa kini, Sangkuni berwujud para manipulator opini, konsultan politik yang memutar fakta, dan pemilik media yang menukar kebenaran dengan rating. Mereka pandai menciptakan cerita, memoles penguasa sebagai pahlawan meskipun di baliknya ia merobek-robek keadilan.
Duryodana zaman ini adalah para penguasa yang membungkus keserakahan dengan jargon pembangunan, para pemilik modal yang membangun istana di atas tanah rakyat yang digusur. Dan kita, rakyat biasa, adalah Pandawa yang terpasung—panca moral yang terpaksa membisu karena seluruh panggung telah dibeli.
Resi Durna masa kini mungkin adalah guru besar universitas yang lebih sibuk melobi anggaran daripada membimbing murid. Bisma adalah para tokoh senior yang dulu gagah melawan penindasan, tetapi kini mengunci mulut demi pensiun yang aman. Widura adalah birokrat bijak yang memilih aman di tengah badai, dan Kripacarya adalah pemuka agama yang memohon damai, tetapi melupakan tegaknya kebenaran.
Semua ini membentuk lingkaran sunyi yang mematikan. Dan seperti di Hastinapura, keheningan itu bukan netralitas—ia adalah keberpihakan pada yang zalim, yang melempar dadu kekuasaan demi memenangkan ambisi, mengorbankan kebenaran dan keadilan di atas papan nasib rakyat.
Kurukshetra Zaman Kini: Perang Tak Terlihat dalam Krisis Moral
Di Mahabharata, semua ini berujung pada perang besar di Kurukshetra, sebuah perang yang memusnahkan hampir seluruh generasi ksatria. Semua hancur atas nama keadilan—meskipun keadilan itu sendiri lahir dari rahim kehancuran.
Kita, di zaman ini, mungkin belum menyaksikan Kurukshetra dalam bentuk pedang dan panah. Namun, kita sudah menyaksikannya dalam bentuk perpecahan sosial, krisis moral, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan struktural.
Perang itu sedang berlangsung, perang yang tak terlihat, tetapi memakan korban jiwa, pikiran, dan iman setiap hari.
Dari sudut pandang ilmu politik, Mahabharata memberi pelajaran tentang bahaya moral collapse dalam tata negara. Teori klasik menyebutkan bahwa legitimasi negara tidak hanya lahir dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dari moralitas pemimpin (virtue politics). Ketika moralitas runtuh, kekuasaan menjadi alat penindasan yang sah secara hukum, tetapi batal secara nurani.
Dalam perspektif sosiologi agama, diamnya para ulama adalah fenomena religious co-optation, ketika otoritas keagamaan diintegrasikan ke dalam struktur kekuasaan untuk meneguhkan status quo. Akibatnya, fungsi profetik agama—yang seharusnya menegakkan amar ma’ruf nahi munkar—berubah menjadi stempel halal bagi kebijakan yang menindas.
Sementara itu, dari kacamata pendidikan, kematian kehormatan akademik adalah contoh nyata academic corruption: universitas kehilangan peran kritisnya sebagai penyeimbang negara dan berubah menjadi pabrik legitimasi kebijakan.
Mahabharata berakhir dengan kehancuran, dan dari puing-puing itu muncul kesadaran bahwa perang sebenarnya tidak pernah membawa kemenangan sejati. Di negeri kita, cerita ini seharusnya menjadi alarm keras: jika para penjaga moral terus membisu, jika lembaga pendidikan terus dipasung, jika ulama terus menjadi pelengkap seremoni istana, maka kita sedang berjalan menuju Kurukshetra kita sendiri.
Dan ketika itu tiba, jangan berharap ada pemenang. Akan ada yang duduk di singgasana, tetapi ia hanya memerintah di atas reruntuhan moral, ekonomi, dan iman bangsanya.
Dalam bayangan purnama Hastinapura, aku melihat dua dunia yang bertemu: dunia purba dan dunia kini. Di keduanya, pengkhianatan terhadap moral selalu dimulai dari ruang-ruang megah, tempat suara nurani ditukar dengan keheningan yang mahal.
Dan sejarah selalu menulis hal yang sama: diamnya para ulama, bungkamnya para guru, dan mati surinya lembaga pendidikan adalah undangan terbuka bagi datangnya kehancuran.
Editor: Assalimi