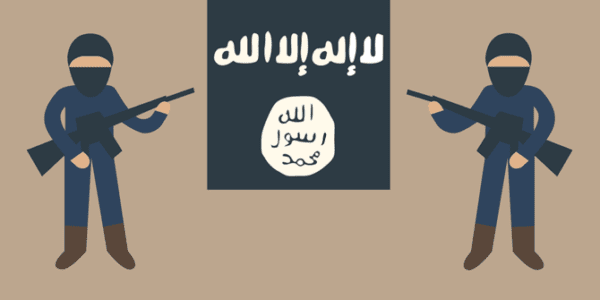Perbincangan tentang Radikalisme
Episteme Radikalisme – Radikalisme, hari ini masih menjadi salah satu topik yang seksi di mata masyarakat Indonesia. Perbincangan mengenai ideologi yang rigid dan dianggap menjadi ancaman bagi kedaulatan negara, selalu menghiasi belantika diskursus publik.
Mulai dari perbincangan ringan di warung-warung kopi sampai ke diskusi elite di media mainstream. Pasalnya, definisi konseptual dari istilah radikalisme sendiri masih sangat rancu dan tidak ada indikator pasti yang bisa disepakati, tentang apa dan bagaimana seseorang bisa dilabeli sebagai radikal.
Sebagian, pihak menilai bahwa pemahaman yang radikal dalam konteks ini pemahaman beragama, memiliki ciri rigid dan cenderung tekstual. Hanya saja, pengertian semacam itu masih bersifat prematur.
Kita bisa menempatkan beberapa ayat sebagai satu hal yang netral, multitafsir dalam suatu dalil adalah hal yang biasa, sehingga menjadikan tafsir atau pemahaman agama yang tekstual sebagai indikator radikalisme masih prematur secara logika.
Ciri yang bisa disepakati mungkin adalah eksklusifitas, individu, atau sekelompok orang yang karena pemahaman agamanya, menjadi anti atau tertutup dengan dunia sosial dan membatasi pergaulan hanya karena sikap in-group berdasar pemahaman agama, bisa dikatakan sebagai titik awal pemahaman radikal.
Tindak Radikalisme
Beberapa waktu yang lalu, peristiwa-peristiwa semacam bom bunuh diri di gereja katedral Makassar, penyerangan mabes polri oleh seorang wanita, dan pembatalan penceramah dengan dalih radikalisme, semakin memperkuat posisi radikalisme dalam wacana publik.
Sebagai orang Islam, tentu kita tidak perlu denial bahwa memang ada sebagain kaum muslim yang memiliki pemahaman agama yang radikal. Radikalisme agama memang ada dan perlu menjadi perhatian penting bagi umat muslim dan aktivis Islam moderat untuk terus berikhtiar membumikan praktik-praktik moderasi Islam.
Namun, seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan narasi radikalisme mengalami pergeseran dari sisi konseptual dan berdampak pada implementasi usaha deradikalisasi. Bahwa radikalisme sekarang sering diidentikkan dengan kelompok yang mengkritik pemerintah.
Terakhir, upaya pelemahan KPK melalui skema tes wawasan kebangsaan dan sebelumnya melalui revisi undang-undang tak luput dari labelling bahwa terdapat Taliban (baca: istilah lain untuk radikal) di tubuh KPK yang dianggap akan merongrong status quo NKRI.
Rezim Wacana
Bicara soal kekuasaan, seringkali kita melihatya dengan model hubungan dominasi dan subordinasi atau antara yang kuat dan yang lemah.
Misalnya, paradigma Marxian yang menyebut bahwa kekuasaan adalah ketika seseorang memiliki modal (alat produksi). Dengan modal tersebut, mereka (kaum borjuis) mampu menguasai kalangan pekerja, atau kekuasaan menurut pandangan 3 dimensi ala Weber, yakni dimensi kelas, status, dan partai.
Namun, pendekatan tersebut hanya melihat konsep kekuasaan konvensional. Pergeseran dari era modern ke post-modern memberikan pandangan lain tentang konsepsi kekuasaan.
Pandangan Marxian dan Weberian tidak mampu menjelaskan secara komprehensif sebab-sebab kekuasaan era post-modern. Misalnya, Marx yang alpa dalam pembahasan tentang kemuncul kelas menengah borjuis kecil yang memiliki modal tetapi tidak mempunyai kuasa akibat perkembangan kapitalisme.
Salah seorang pemikir post-modernisme, Michael Foucault dengan cermat melihat pergeseran konsep kekuasaan dari modern ke post-modern.
Manurut Foucault, kekuasaan bukanlah hubungan antara kepemilikan modal atau privilige tertentu. Namun, lebih kepada adanya keterlibatan relasi-relasi beragam yang membentuk suatu jaringan strategis. Menurut teori kekuasaan Foucault, bahwa kekuasaan tidaklah sentralistis atas satu kekuatan otoritas atau lembaga tertentu melainkan menyebar dalam relasi sosial.
Pergeseran pola kekuasaan menjadi relasional, berdampak pada bagaimana implementasi kekuasaan tersebut. Pola kekuasaan post-modernisme yang dipandang Foucault dari sebelumnya Sovereign Power menjadi Disciplinary Power.
Sederhananya, sovereign power mengatur kekuasaan berdasarkan hukum yuridis dan cenderung represif, sedangkan disciplinary power melihat bahwa penguasa memiliki wewenang dalam menormalisasikan pengetahuan atau nilai untuk tujuan tertentu.
Pengetahuan dan nilai yang terorganisasi menjadi sebuah pengetahuan yang otoritatif dan normal dalam masyarakat disebut dengan Episteme.
Dari episteme yang terlembaga, menjadi dasar motivasi praktik sosial baik cara pikir maupun manifestasinya memunculkan apa yang disebut rezim wacana. Rezim wacana mencoba mendapatkan otoritas dari relasi kuasa yang diciptakan sendiri.
Episteme Radikalisme
Konsep episteme Foucault sangat berkorelasi dengan pendapat Nietzche yang menyatakan bahwa kebenaran tidak bersifat final.
Episteme menunjukkan bahwa kebenaran akan suatu pengetahuan itu bersifat tidak tetap, tergantung upaya-upaya rezim wacana dalam melanggengkan konsepsi tentang benar-salah, normal-abnormal.
Menggunakan pengetahuan (Episteme) sebagai alat kontrol sosial memang lebih efektif dibanding cara-cara represifitas hukum. Karena pengetahuan yang sudah terlembaga dalam diri seseorang akan berdampak pada praktik sosial tanpa adanya pertentangan.
Pada masa Orde Baru, episteme bahwa komunisme adalah ideologi terlarang dan setiap mereka mengkritik pemerintah akan dianggap sebagai seorang komunis yang anti-pancasila.
Episteme itu bertahan hingga hari ini. Meskipun mulai banyak orang tercerahkan untuk kembali meninjau sejarah dan epistemologi komunisme untuk meluruskan episteme tersebut.
Hari ini, setelah lebih dari 2 dekade reformasi, narasi anti-pancasila dan anti-kebhinekaan muncul kembali dengan episteme berbeda yakni radikalisme.
***
Mereka yang tidak sepakat dengan langkah serta kepentingan pemerintah, dianggap sebagai orang-orang yang terpapar radikalisme. Stigma-stigma tersebut muncul layaknya pada masa Orde Baru. Bahkan, stigma tesebut tidak pandang bulu. Meski seorang tokoh yang memiliki latar belakang luar biasa dalam membumikan Islam moderat, pemerintahan yang bersih, dan anti-korupsi, jika tidak sejalan dengan apa yang dikatakan pemerintah, akan mendapat label radikal.
Episteme tersebut perlahan mencapai taraf “normal” setelah semakin banyak pihak yang merasa bahwa narasi radikalisme nir-politis, seperti pada kasus “Taliban” dalam KPK, di mana sebagian orang yang dahulu kritis terhadap upaya pelemahan KPK menjadi sepakat karena anggapan semacam itu.
Hal ini semacam de ja vu dari apa yang terjadi pada masa Orde Varu. Monopoli pancasila sebagai yang benar dan radikalisme sebagai yang salah.
Model relasi kuasa yang sedang berkembang dan coba untuk melembaga hari ini, tentu akan berdampak pada kehidupan demokrasi kita ke depan. Demokrasi yang tanpa stigmatisasi kepada mereka yang berbeda pandangan.
Mencoba mengembalikan posisi pancasila pada tempatnya sebagai dasar sikap bernegara tanpa membeda-bedakan pandangan politik.
Stigmatisasi dan labelling radikalisme kepada para watchdog pemerintah harus segera dihentikan untuk keluar dari iklim pseudo demokrasi.
Editor: Yahya FR