Dalam diskursus kajian hadis, masalah autentisitas selalu jadi perhatian utama. Bagaimana tidak, dalam konstruksi hukum Islam sendiri menempatkan hadis pada posisi yang tinggi, kedua setelah Al-Qur’an. Hal ini otomatis menjadikan hadis sebagai sumber rujukan utama terhadap sunnah Nabi, sehingga keaslian dan kemurniannya selalu dipertanyakan, apakah benar bersumber dari Nabi?, dan sevalid apa?. Sanad atau mata rantai perawi menjadi objek kajian atau penelitian hadis, untuk mengetahui jalur transmisi hadis dari Nabi Muhammad Saw sampai mukharrij secara ilmiah.
Pembagian Hadis dari Segi Kualitas
Dalam kajian ilmu hadis, terdapat klasifikasi untuk mengetahui kualitas hadis, yang hasilnya menyebutkan hadis terbagi menjadi sahih, hasan, dan daif dilihat dari sisi diterima dan ditolaknya, sekaligus menjadi peringkat otoritatif bagi seorang Muslim dalam merujuk ketika disodorkan hadis.
Dari segi sanad, paling tidak ada lima unsur yang menjadi acuan untuk menetapkan kualitas suatu hadis. Pertama, sanadnya harus bersambung. Para periwayat dalam suatu sanad harus dipastikan saling menerima dan menyampaikan hadis satu sama lain, barulah bisa dikatakan sanad itu memang berasal dari Nabi yang diriwayatkan lewat para periwayat tersebut.
Kedua, tidak cukup sanadnya bersambung, para periwayat dalam sanad hadis itu juga harus adil. Maksud adil di sini periwayat harus memiliki integritas moral dan keagamaan agar bisa dipercaya dia menyampaikan hadis dengan jujur dan semestinya, tidak berbohong atau memalsukannya.
Ketiga, periwayat harus dhabith. Jika adil adalah integritas keagamaan, maka dhabith adalah integritas intelektual, maka seorang perawi disamping orang yang baik akhlaknya juga harus punya kapasitas intelektual yang mumpuni, periwayat haruslah merupakan orang cerdas dan kuat dalam hafalan maupun dokumentasi.
Keempat, tidak memiliki illat/cacat. Maksud illat di sini ialah kecacatan yang bisa tersembunyi dalam sanad, illat bisa saja terjadi dalam sanad yang tempaknya sahih tetapi terdapat cacat tersembunyi. Illat bisa berbeda dalam setiap hadis, untuk mengetahuinya haruslah dilakukan penelitian atau kajian terlebih dahulu.
***
Kelima, tidak memiliki syadz, artinya sanad hadis tidak bertentangan dengan sanad lain yang lebih tsiqah, hal ini juga baru bisa diketahui setelah mengkaji atau menelitinya.
Jika lengkap kelima unsur di atas dalam suatu hadis, maka hadis tersebut akan dihukumi sahih. Apabila dalam suatu hadis melengkapi unsur tersebut, tapi periwayat dinyatakan kurang dhabith (khaff al-ruwah), maka akan dihukumi hasan. Tetapi jika dalam suatu hadis lima unsur di atas tidak dipenuhi, barang satu saja (apalagi semua), maka akan dihakimi hadis daif. Hadis sahih dan hasan tergolong hadis maqbul yang bisa digunakan sebagai sumber hukum atau ritual keagamaan dalam kehidupan, sedangkan hadis daif tidak bisa karena tergolong hadis mardud.
Meskipun begitu, penggunaan hadis daif dalam kehidupan masih dipersoalkan dan menjadi bahan perbedaan oleh para ulama. Ada yang menerima dengan memberi syarat yang sangat hati-hati (Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Ibn Hajar al-Asqalany), ada juga yang menolaknya secara mutlak (Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Bakr bin Al-‘Araby). Tentu menjadi pertanyaan, “Walapun hadis daif sudah disepakati tertolak, mengapa masih diupayakan untuk penggunaannya?.” Bukankah jika suatu hadis tidak memenuhi syarat diterimanya maka tertolaklah ia untuk dijadikan sumber rujukan, tidak perlu ada upaya untuk “menyelamatkan” hadis daif tersebut, toh tertolak.
Hadis Daif Tetap Menjadi Perhatian Ulama
Walaupun tertolak, hadis daif tetap menjadi perhatian oleh para ulama. Argumennya, dalam mushthalah al-hadits misalnya, terdapat kaidah yang bisa mengangkat derajat hadis daif ke hasan, dengan status hasan li ghairihi, dikarenakan hadis hasan tersebut mulanya hadis daif yang sanadnya terputus kemudian naik derajatnya dikarenakan terdapat jalur periwayatan lain yang semisal, maka hadis ini juga berubah menjadi hadis maqbul, dapat digunakan sebagai sumber rujukan dalam kehidupan beragama. Ternyata, hadis daif tidak begitu saja ditinggalkan oleh para ulama, tapi tetap diperhatikan kemungkinannya untuk dikompromikan dan didialogkan. Apresiasi tentu untuk para ulama yang telah menyusun dan merumuskan kaidah ilmu ini dengan sangat baik dan hati-hati.
Penilaian Terhadap Hadis yang Subjektif
Pengetahuan akan hadis erat kaitannya dengan proses sosial. Kerja-kerja periwayatan dilakukan melalui interaksi sosial. Penilaian seorang periwayat oleh kritikus juga merupakan tindakan sosial. Maksud saya, penilaian terhadap suatu hadis itu benar-benar subjektif, satu kritikus punya pendapat berbeda antara satu dan lainnya.
Ada tiga karakter yang biasanya dimiliki oleh kritikus periwayat hadis. Tasyaddud, yang bersikap ketat (Imam Bukhari, Yahya bin Ma’in, Abu Hatim al-Razy). Tasahul, yang bersikap longgar (Imam Tirmidzi, Ibn Hibban, Hakim al-Naisabury). Tawassuth, yang bersikap antara ketat dan longgar/tengah-tengah (Amir al-Sya’by, Muhammad bin Sirrin).
Penilaian suatu hadis bisa berbeda karena perbedaan karakteristik penilainya. Kenapa Imam Bukhari berani mengklaim hadis dalam kitab Jami’-nya kualitasnya sahih semua karena beliau menerapkan standarisasi yang tinggi dalam memberi penilaian hadis-hadis yang diseleksinya. Tetapi bukan berarti hadis yang didaifkan Bukhari otomatis tak layak pakai, jika kita hanya mengambil hadis yang disahihkan Bukhari saja, alangkah sempitnya cara pandang kita dalam beragama, karena keterbatasan referensi.
Sebelum pembagian hadis ke dalam sahih, hasan, dan daif, menurut keterangan ‘Ajjaj al-Khatib hadis hanya sahih dan daif saja. Barulah Imam Tirmidzi yang merupakan murid Bukhari mempopulerkan hadis hasan yang kemudian masuk dalam pembagian hadis yang kita kenal sekarang ini. Artinya, bisa saja, boleh jadi iya, hadis hasan yang maqbul menurut Imam Tirmidzi adalah hadis daif yang mardud karena tidak lolos seleksi super ketat sebagai calon hadis sahih oleh Imam Bukhari. Inilah subjektifnya penilaian hadis.
Penggunaan Hadis Daif untuk Dalil dengan Syarat dan Kondisinya
Mayoritas ulama meperbolehkan penggunaan hadis daif sebagai dalil, seperti hanya untuk fadha’il amal (menjelaskan keutamaan suatu amalan), anjuran, ataupun nasehat-nasehat. Tentunya dengan syarat yang sudah dirumuskan dengan hati-hati, yakni: daifnya tidak parah (tidak dhaif jiddan apalagi maudhu’/palsu), ditopang oleh nash yang lebih kuat, dan tidak meyakini sepenuhnya hadis tersebut dari Nabi, mengamalkannya pun dengan penuh kehati-hatian.
Pada akhirnya, hadis daif walaupun mardud, tetap tidak boleh diabaikan. Jelas ada hadis daif yang tidak bisa ditolerir, seperti daif karena perawinya berdusta, kapasistas intelektuanya parah, banyak lupa dan salah, atau hadis tersebut merupakan hadis matruk. Jika hadis tersebut daif karena terputusnya sanad atau perawi yang majhul (tidak dikenal), maka masih dikategorikan ringan. Seperti Abu Hanifah lebih memilih mendahulukan hadis mursal daripada ra’yu dan qiyas, jika tema permasalahan tidak ada di hadis sahih.
Baiknya, melihat hadis daif ialah dengan sikap berhati-hati, seperti yang dilakukan oleh para ulama, dengan turut memperhatikan kemungkinan bisa dikompromikannya dan didialogkan, agar rujukan referensi kita terhadap sunnah Nabi bisa lebih luas, karena tidak semua tema permasalahan yang dihadapi bisa tertutupi dengan hadis sahih atau hasan, dan dasarnya masyarakat Muslim akan selalu merujuk Nabi sebagai teladan.
Editor: Soleh


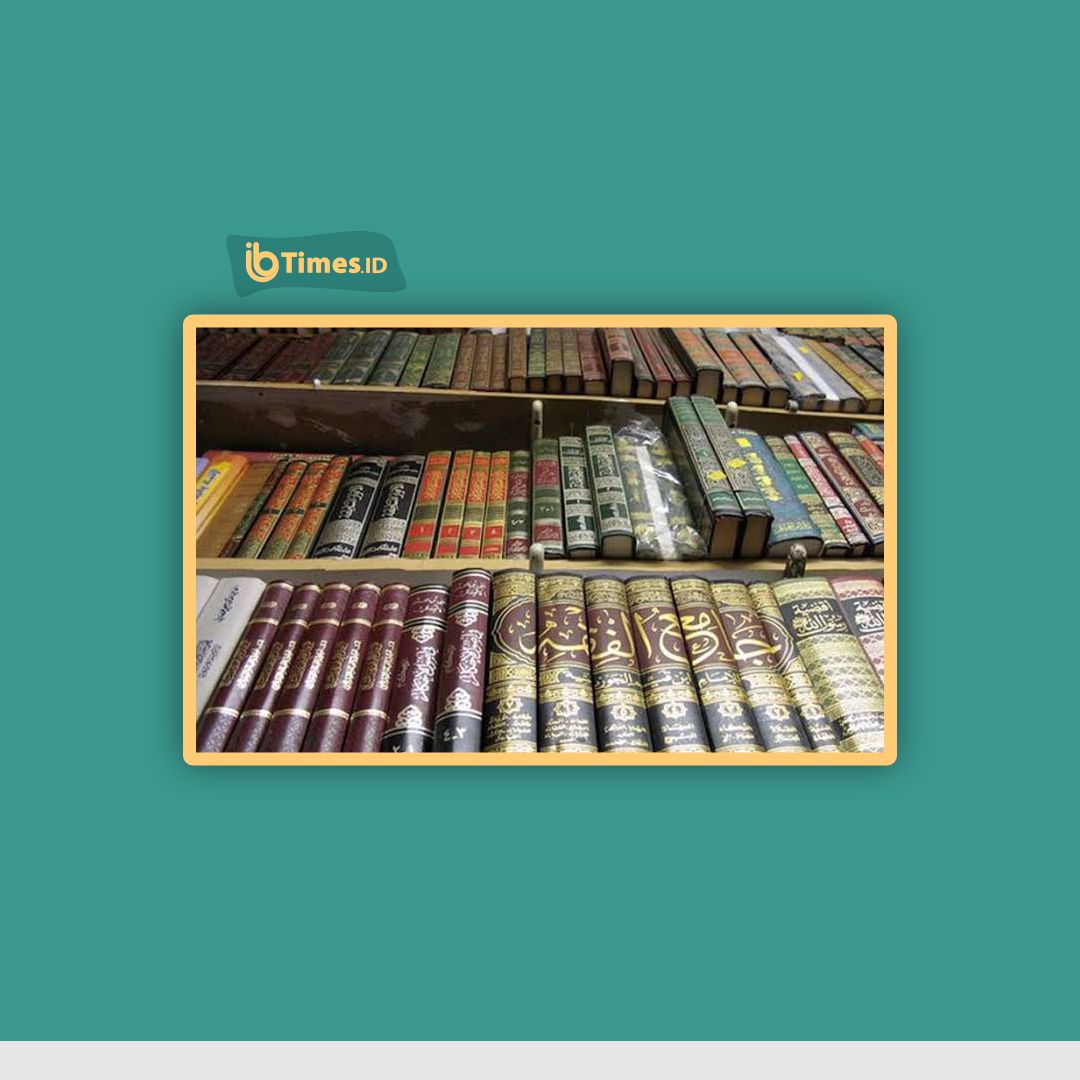

Apakah ada contoh hadis spesifik yang awalnya daif, kemudian dikompromikan oleh ulama dan digunakan sebagai sumber rujukan?