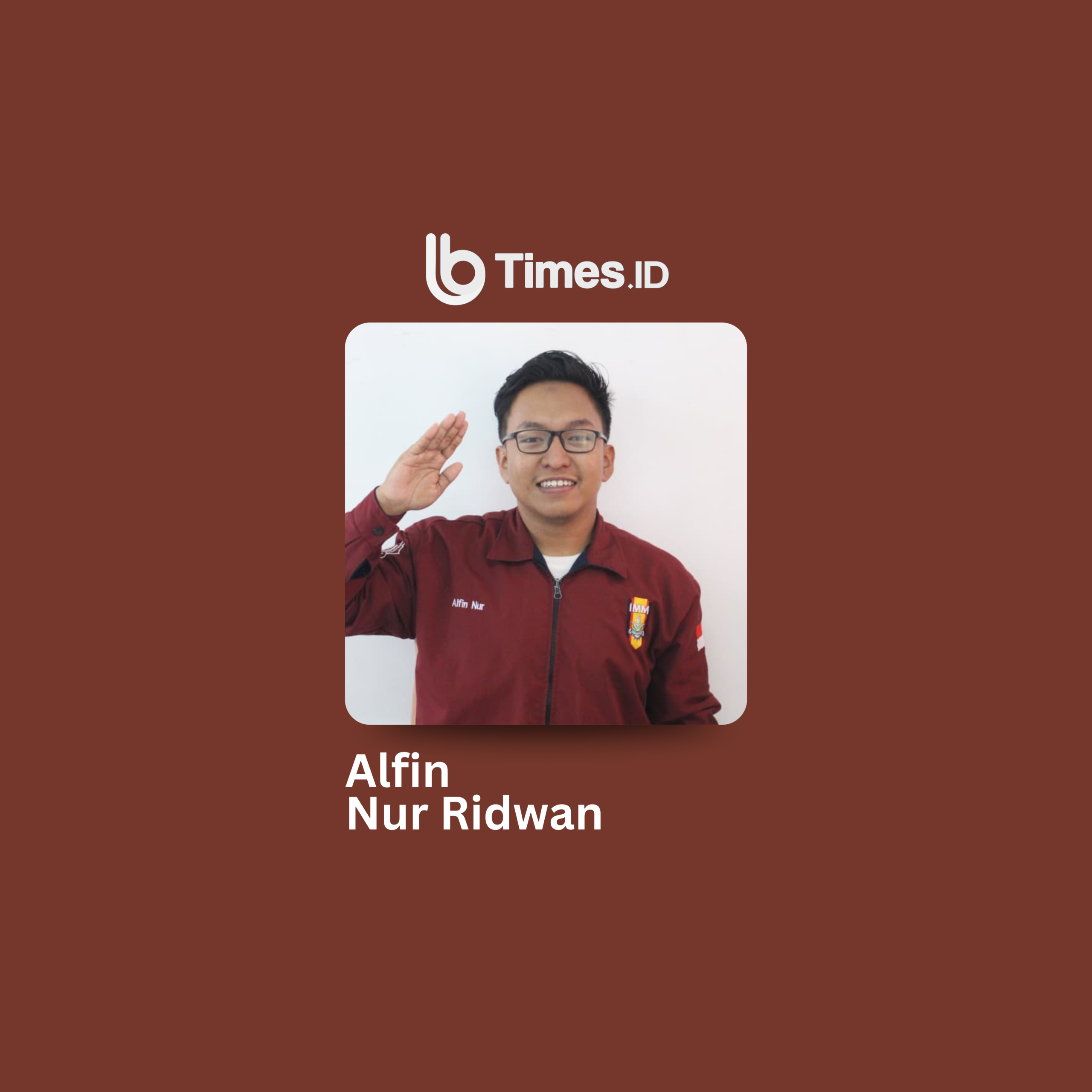Bencana kini tidak lagi sekadar fenomena alam yang tak terelakkan. Di Indonesia, negeri dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan hutan tropis yang luas. Kita tengah menyaksikan sesuatu yang jauh lebih serius: bencana yang diundang oleh tangan sendiri (invited disaster).
Istilah tersebut belakangan disebut dalam forum “Jagongan Akhir Tahun” yang diadakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada 30 Desember 2025.
Forum ini menandai bagaimana kebijakan eksploitasi sumber daya alam oleh negara berkontribusi pada meningkatnya kerentanan ekologis dan sosial. Bukan hanya soal alam yang “marah”, tetapi tentang keputusan manusia yang menciptakan kondisi bencana.
Secara faktual, Indonesia bukan hanya sering dilanda bencana, tetapi jumlah kejadian bencana terus tinggi. Pada 2025, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran lahan tetap menjadi ancaman nyata di banyak provinsi.
Data BNPB menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat ada 3.225 kejadian bencana, yang didominasi oleh banjir dan tanah longsor. Namun data statistik semata tak cukup menangkap esensi yang hendak diingatkan oleh invited disaster.
Invited disaster bukan sekadar banyaknya kejadian bencana. Namun kita juga sedang berbicara mengapa tingkat kejadian ini terus substansial, dan mengapa dampaknya semakin parah dan sistemik. Ini terkait langsung dengan pola pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang belum mempertimbangkan dampak ekologis dan risiko sosial secara mendasar.
Ambil contoh banjir dan longsor besar-besaran yang baru-baru ini melanda Sumatera Utara, Aceh, dan sekitarnya, yang disebut sebagai salah satu bencana terparah dalam beberapa tahun terakhir dengan data korban yang mencapai ratusan jiwa dan kerusakan besar.
Deforestasi Mengubah Bahaya Alam Menjadi Bencana
Melansir dari theguardian.com, para ilmuwan bahkan menyebutnya sebagai “disturbance” yang tidak hanya menghancurkan permukiman, tapi juga habitat spesies kritis seperti orangutan Tapanuli, yang kehilangan ribuan hektar hutan. Sebuah pukulan besar bagi populasi yang sudah sangat terancam.
Penyebabnya bukan hanya cuaca ekstrem. Meski fenomena iklim seperti Siklon Tropis Senyar memang meningkatkan intensitas curah hujan hingga rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, implikasi kerusakan ekosistem membuat dampaknya lebih buruk.
Deforestasi akibat pertambangan, perkebunan sawit, dan proyek-proyek besar telah mengikis fungsi hutan sebagai penyangga alami, sehingga air hujan deras tak lagi tertahan, merembes ke permukiman dengan kekuatan destruktif.
Inilah hakikat invited disaster, ketika alam hanya bertindak berdasarkan hukum-hukum fisiknya, sementara manusia telah mengubah lanskap ekologis dan sosial sedemikian rupa sehingga ketika bahaya itu datang, ia berubah menjadi bencana besar yang sesungguhnya dapat dihindari atau dikurangi dampaknya.
Menelusuri Akar Teoritis: Risiko Sosial dan Politik Ekologi
Dalam perspektif political ecology yang dipopulerkan Frank Thone, risiko bencana tidak independen dari struktur sosial, politik, dan ekonomi. Ia bukan entitas natural semata. Invited disaster adalah fenomena sosial-terkonstruksi dimana kerentanan dihasilkan melalui kebijakan publik, hubungan kuasa, dan pola pembangunan yang mengutamakan eksploitasi.
Ulrich Beck dalam “Risk Society” menjelaskan bahwa masyarakat modern menciptakan risiko yang bersifat global dan sistemik, bukan sekadar ancaman alamiah, tetapi juga konsekuensi dari modernisasi itu sendiri. Risiko-risiko ini bersifat tak terlokalisir, berdampak lintas batas sosial, kelas, dan wilayah.
Dalam konteks Indonesia, proyek ekstraktif besar seperti perkebunan sawit, tambang mineral (termasuk nikel untuk industri baterai global), dan megaproyek infrastruktur membuka celah bencana yang bukan hanya bersifat lingkungan tetapi juga sosial-ekonomi.
Ada juga gagasan slow violence milik Rob Nixon, yang menunjukkan bagaimana kerusakan ekologis dan sosial berlangsung perlahan, namun berujung pada puncak bencana yang spektakuler.
Deforestasi yang berlangsung bertahun-tahun, erosi tanah yang tak terpantau, serta degradasi habitat akhirnya terakumulasi menjadi sesuatu yang meledak secara destruktif ketika dikelola tanpa mitigasi yang serius.
Di Indonesia, problem struktural ini diperparah oleh aturan hukum dan pengawasan lingkungan yang lemah atau tidak efektif. Kajian terhadap undang-undang pertambangan misalnya menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan masih kurang kuat dan kurang mampu mencegah dampak kerusakan dari kegiatan ekstraktif.
Negara, Kapitalisme Ekstraktif dan Bencana yang Diundang
Pemerintah sering kali membenarkan proyek pembangunan besar dengan retorika pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi. Namun kenyataannya, melanggengkan model pembangunan ekstraktif tanpa perhitungan risiko ekologis telah membuat negara ini seringkali “mengundang” bencana. Program deforestasi besar untuk bioetanol dan pangan, misalnya, memperlihatkan bagaimana kebijakan dapat mengesampingkan nilai ekologis demi target ekonomi.
Selain itu, ketergantungan energi fosil yang masih tinggi serta kecenderungan membuka lahan hutan untuk ekspansi industri menunjukkan bahwa risiko bencana bukanlah kesalahan semata alam, melainkan akumulasi keputusan manusia yang sistematis.
Istilah invited disaster tidak hanya sekadar frasa retoris. Ia adalah cermin tajam tentang bagaimana negara, elite ekonomi, dan kebijakan pembangunan berkontribusi terhadap kerentanan ekologis dan sosial.
Ia memanggil kita untuk bertanya: Apakah kita ingin menjadi bangsa yang hanya menunggu bencana, atau bangsa yang secara sadar mengubah pendekatannya terhadap pembangunan dan lingkungan?
Kita perlu transformasi paradigma, dari pembangunan yang mengundang bencana menjadi pembangunan yang menghormati batas-batas ekologis dan meminimalkan kerentanan warga.
Ketika negara masih membiarkan eksploitasi tanpa mitigasi risiko serius, maka bencana akan terus kita undang. Bukan sebagai satu-dua kejadian, tetapi sebagai warisan struktural yang melekat pada cara kita mengelola negeri ini.
Editor: Najih