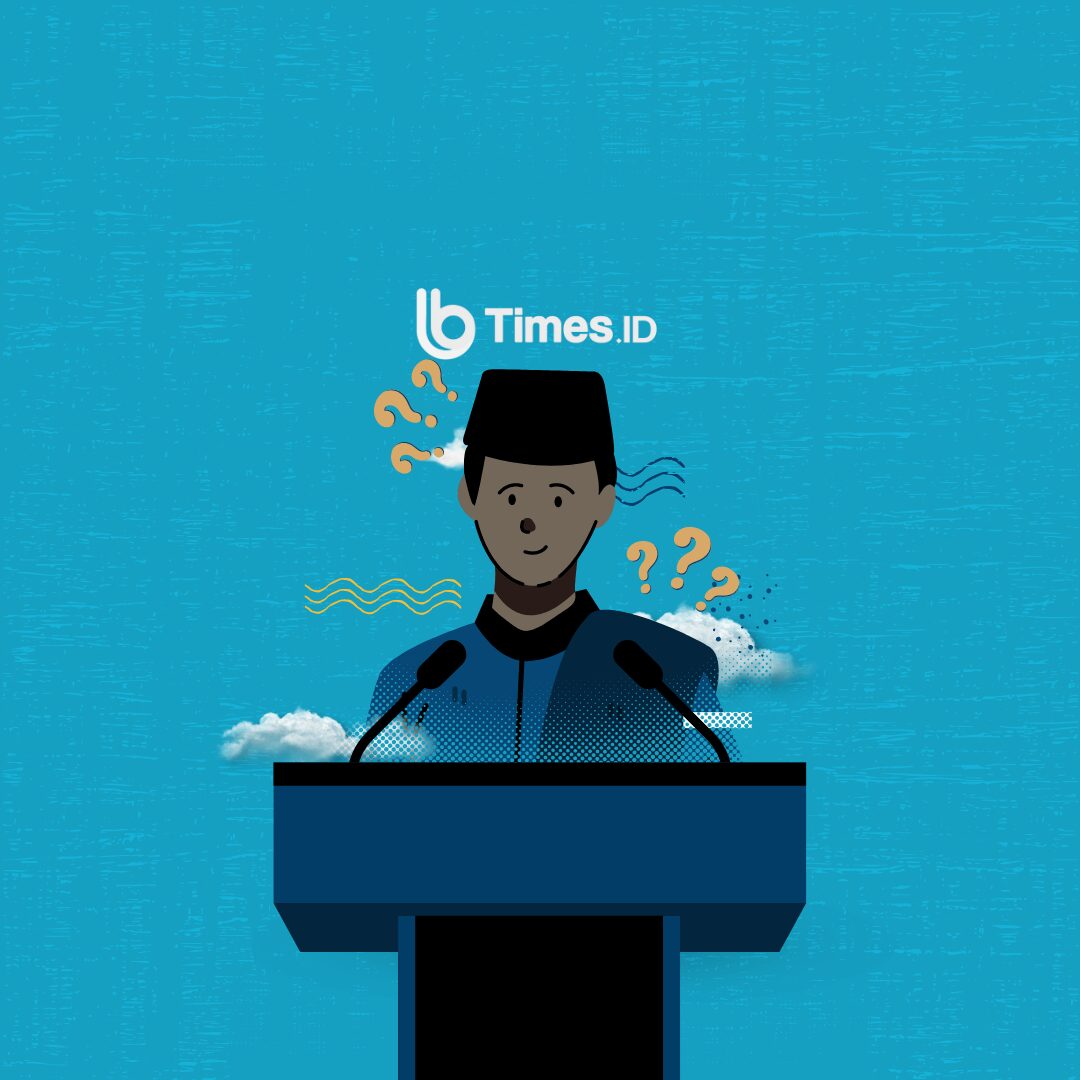Beberapa waktu belakangan ini, semakin sering ditemukan pemuka agama atau ulama yang diduga atau bahkan terbukti melakukan tindakan kriminal berupa pencabulan. Misalnya, kasus Herry Wirawan selaku pimpinan Madani Boarding School Bandung, kasus Moch Subchi Al Tsani dari Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Jombang, dan kasus Kiai Fahim Mawardi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Djaliel 2 Jember.
Peristiwa-peristiwa tersebut membuat masyarakat terbagi menjadi dua. Satu pihak menyerukan bahwa pemuka agama atau ulama tersebut harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku oleh pihak yang berwenang, yakni pemerintah.
Satu pihak lainnya, justru mereka membela dengan keyakinan bahwa pemuka agama atau ulama tersebut tidak mungkin melakukan tindakan kriminal. Lalu mereka berlindung di balik jargon “kriminalisasi ulama” saat menghadapi orang-orang yang tidak sepaham dengan kelompoknya. Bahkan lebih dari itu, ada pula yang menyerang ketika pihak yang berwenang ingin menindak ulama mereka.
Fenomena pembelaan terhadap pemuka agama atau ulama ini membuat penulis bertanya-tanya: Apakah ulama perlu dibela? Jika iya atau tidak, mengapa perlu dibela dan tidak perlu dibela?
Definisi Ulama
Secara normatif, Al-quran menyebut ulama sebagai orang yang takut pada Allah, pada surah Fathir ayat 27-28: “Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu Kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah, yang takut kepada-Nya hanyalah para ulama.”
Dari ayat tersebut, bisa dilihat bahwa ulama adalah orang-orang yang menjadi takut kepada Allah disebabkan pengamatan dan penghayatan mereka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah.
Bisa diperkirakan, ayat di atas adalah penjelasan sekaligus anjuran oleh Al-Qur’an agar manusia khususnya umat Islam mampu menjadi ulama. Apapun pekerjaan dan profesi mereka, yang ciri-cirinya adalah takut pada Allah. Dengan definisi ini, semua orang apapun latar belakangnya, berpotensi sama untuk menjadi ulama; entah itu dokter, politisi, petani, dan lain-lainnya. Asalkan pengamatan dan penghayatan mereka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah membuat mereka takut pada-Nya.
Namun, sekarang apa yang pertama kali terlintas di benak kita ketika mendengar kata “ulama”? Jika yang terlintas adalah orang-orang yang berada di bawah lembaga keagamaan, seperti Muhammadiyah, NU, MUI, dan sebagainya dengan status sosial tersendiri dan bahkan atribut atau busana tersendiri, maka hal ini memperlihatkan bahwa definisi ulama mengalami transformasi dengan ditandai adanya “pelembagaan ulama” secara resmi.
Dengan begitu, ketika terjadi kasus kriminalitas oleh seorang ulama, kita patut bertanya pada diri masing-masing, apa definisi ulama yang tepat bagi orang yang kita “ulama-kan” tersebut? Orang-orang yang takut kepada Allah ataukah hanya orang-orang yang berada di bawah lembaga keagamaan? Apakah perilaku mereka mencerminkan orang yang takut kepada Allah? Kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara jujur untuk menyikapi ini, agar kita sadar apakah yang terjadi adalah “kriminalisasi ulama” ataukah “ulama-isasi kriminal”.
Subjektivitas Pendefinisian Kriteria Ulama
Selain memikirkan definisi ulama, menurut penulis, kita juga harus menyadari bahwa ketika menentukan seseorang sebagai ulama, kriteria yang kita gunakan bersifat subjektif. Di suatu tempat ada yang mengatakan untuk menjadi ulama harus bisa membaca kitab suci, berbahasa Arab, dan seterusnya. Di tempat lain, belum tentu demikian.
Di kalangan lain, bisa saja kemampuan-kemampuan tadi tidaklah cukup untuk membuat seseorang diakui sebagai ulama jika perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai luhur yang diperjuangkan oleh agama.
Jadi, tidak usah heran ketika terjadi peristiwa penolakan ceramah seorang ulama tertentu oleh masyarakat tertentu. Disebabkan, kriteria yang dimiliki ulama tersebut tidak sama dengan kriteria yang dipedomani oleh masyarakat itu.
Lantas bagaimana sebenarnya kriteria yang tepat untuk menentukan seseorang sebagai ulama? Menurut penulis, itu semua kembali pada masyarakat itu sendiri. Semakin cerdas suatu masyarakat, maka ulama yang diakui adalah ulama yang juga cerdas.
Jika masyarakat berpijak pada nilai-nilai universal kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, dan sebagainya, maka ulama yang mereka akui tentu ulama yang juga memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Bahkan, jikalaupun pada akhirnya ulama yang mereka akui terbukti melanggar nilai-nilai yang mereka pegang, mereka tidak akan segan untuk menyerahkannya pada pihak yang berwajib. Sejatinya, yang harus mereka pegang adalah nilai-nilai itu sendiri, bukan “diri” ulama-nya.
Hukum Positif Negara: Aturan Bersama
Dengan beragamnya identitas masyarakat di negara ini, titik temu atau aturan yang disepakati bersama ketika terjadi permasalahan, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah hukum positif negara. Jadi, ketika terjadi kasus kriminalitas oleh seorang ulama, serahkan saja pada pihak yang berwajib. Masalah benar atau salahnya ulama tersebut diserahkan saja pada aturan yang disepakati bersama.
Jika seseorang yang diakui sebagai ulama tersebut memang benar-benar ulama, dirinya pasti akan mengikuti aturan yang ada dengan penuh tanggungjawab. Karena hal tersebut sesuai dengan nilai yang diperjuangkan oleh agama yaitu kesetaraan di depan hukum. Bukan justru menggalang massa untuk membelanya seolah-olah dirinya mempunyai keistimewaan di depan hukum.
Di sisi lain, pihak yang berwenang juga mempunyai tugas yang tak kalah penting, yaitu optimalisasi pemberlakuan hukum di negara ini. Jika pemberlakuan hukum di negara ini adil dan bijaksana, maka publik dengan sendirinya akan percaya sepenuhnya pada pihak yang berwenang. Sehingga fenomena pembelaan membabi buta terhadap tokoh tertentu yang sering kali menguras waktu dan tenaga tidak akan terulang lagi.
Sebaliknya, jika pemberlakuan hukum di negara ini jauh dari kata adil dan bijaksana. Maka bisa saja pembelaan membabi buta terhadap ulama yang terduga atau terbukti berlaku kriminal akan semakin menjadi-jadi.
Ulama Tidak Perlu Dibela
Alhasil, apakah pemuka agama atau ulama perlu dibela? Menurut penulis, karena definisi ulama di zaman ini sudah bertransformasi menjadi orang yang “bekerja” di lembaga keagamaan yang memiliki status sosial tersendiri dan setiap masyarakat bisa saja memiliki kriteria berbeda-beda tentang ulama. Maka, sejatinya ulama tidak perlu dibela jika dirinya melakukan tindakan kriminal atau serahkan saja pada pihak yang berwenang.
Pun seandainya ulama didefinisikan sebagai orang yang takut kepada Allah, juga tidak perlu dibela. Sebab, pendefinisian tersebut tetap subjektif dan spekulasi sepihak saja. Karena tidak ada satu orangpun yang bisa mengkonfirmasi secara objektif rasa takut kepada Allah secara langsung.
Di samping itu, optimalisasi hukum positif negara tetap harus terus diupayakan agar publik percaya bahwa negara mampu bersikap adil dan bijak terhadap semua warganya tanpa memandang status sosial apapun termasuk ulama. Tabik.
Editor: Soleh