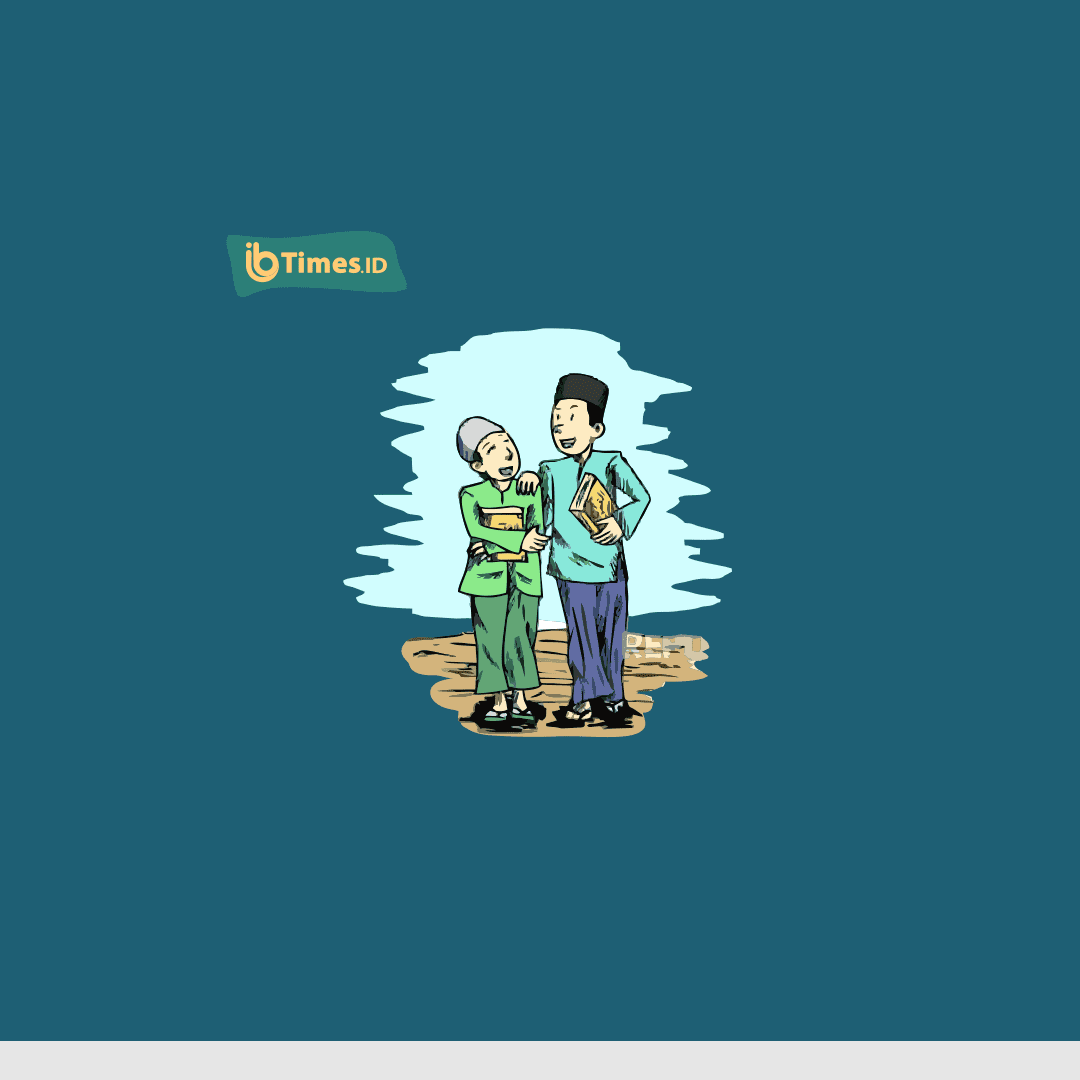Sebagai sebuah lembaga pendidikan tertua, asali, dan khas Indonesia (Dawam Rahardjo, 1985), pesantren memiliki peran sentral dalam menunjang pencapaian visi Indonesia ke depan—menjadi aktor perdamaian dunia. Cita-cita itu akan menjadi sulit terwujud bila pesantren tidak memperbaharui substansi kurikulum yang ada di dalamnya.
Martin van Bruinessen misalnya, dalam Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat mengungkap bahwa kurikulum pesantren cenderung lebih banyak secara substansi diisi oleh kitab-kitab tradisional dengan haluan akidah Asy’ari (yang mengacu pada Sanusi), fiqh Syafi’i dan tasawuf Ghazali. Kitab-kitab itu dibaca dengan metode alat (nahwu) daripada dibaca dengan membenturkannya pada konteks. Pemahaman yang dihasilkan fokus pada makna teks an sich.
Dengan proses pemaknaan teks seperti di atas, teks ditempatkan menjadi dogma. Maksudnya, sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan ulang relevansinya. Kewajiban bagi peserta didik hanyalah menerapkan secara langsung apa yang didapat dari teks. Tanpa pertanyaan, tanpa proses berpikir dialektis. Di sini, peserta didik tidak terlatih untuk bertanya, melainkan menerima begitu saja seluruh perangkat keyakinan; teks selalu kontekstual. Padahal tidak.
Substansi dari teks-teks yang dibaca dan dipelajari di pesantren dan metode pengajaran yang dipakai—yang memiliki kecenderungan tidak dialektis-dialogis menjadikan siswa (baca: santri) tidak terbiasa berpikir kontekstual atau kritis. Pendekatan dan cara membaca teks yang mono-perspektif adalah penyebab utama dalam produk pengetahuan yang sepi dari proses dialektis dan dialogis itu.
Masukkan Filsafat dalam Kurikulum Pesantren
Meski pesantren-pesantren di Indonesia telah banyak mengadopsi metode modern dalam pengajaran—seperti penggunaan teknologi dalam pengajaran, memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulum di dalamnya, mayoritas pesantren di Indonesia memiliki kecenderungan tidak memasukkan filsafat ke dalam kurikulum mereka. Kalau pun ada, hanya sedikit pesantren yang memasukkannya sebagai kurikulum. Misalnya, pada pesantren- pesantren yang memang memfokuskan tema pendidikannya khusus kepada pendidikan filsafat.
Pesantren modern saja, sebut saja Gontor—tidak memasukkan filsafat secara eksplisit sebagai kurikulum. Di sana, logika, teori pendidikan dan ilmu perbandingan madzhab dijadikan kurikulum. Tetapi ini sangatlah awal—sebatas di wilayah pengantar. Bandingkan misalnya dengan kurikulum pendidikan sekolah menengah atas di Perancis sejak akhir abad ke-19 yang sudah mewajibkan siswa-siswanya untuk membaca buku-buku filsafat dan menulis esai tentang pemikiran tokoh-tokoh filsafat (Arendt, Hume, dll.) sebelum mereka menginjak bangku perguruan tinggi (K. Bertens, 2019).
Bukan tanpa sebab, filsafat tidak masuk ke dalam kurikulum pesantren; Pertama, sebab dominasi paradigma tradisional pesantren yang masih dipertahankan—mencakup hubungan akidah-fiqh-tasawuf Sunni. Di mana Al-Ghazali menjadi titik sentral paradigma bagi produk pengetahuan di sana. Implikasi dari dominasi tersebut adalah filsafat dijauhi. Al- Ghazali meletakkan batu pertama bagi penolakan dan legitimasi terhadap pengasingan bagi filsafat dalam Tahafut al-Falasifah.
Kedua, keengganan para guru di pesantren atau pembuat kurikulum di sana untuk merekonstruksi produk pengetahuan mereka. Ada keyakinan yang terus-menerus dipelihara bahwa produk teks dari masa lampau sudah siap pakai secara instan. Generasi selanjutnya tidak perlu bersusah payah merancang ulang bangunan epistemologisnya bagi pemecahan problem modern. Ini yang disebut oleh M. Natsir bahwa pesantren dapat melahirkan orang berperilaku baik tapi buta terhadap wawasan dunia (Fuad Jabali, 2002).
Wawasan dunia; pada umumnya tidak terbentuk dengan paradigma yang monolitik. Maksudnya, problem modernitas atau global tidak dapat didekati dan diurai menggunakan satu kacamata atau satu pendekatan. Problem modernitas yang kompleks juga memerlukan pendekatan dan cara melihat yang kompleks; multi-interdisiplin.
Kebutuhan akan paradigma yang multi-interdisiplin ini sangatlah mendesak. Kasus- kasus sosial semacam toleransi, perdamaian (isu-isu yang dekat dengan agama) tidak dapat dilihat lagi dengan sudut pandang agama an sich—apalagi hanya dalam konteks normatifnya saja.
Dari sana, problem pendidikan di pesantren adalah kurang atau tidak diberikannya ruang yang cukup bagi tumbuhnya kritisisme dan kemandirian berpikir. Seluruh produk pemikiran santri lebih banyak adalah kelanjutan dari apa yang disampaikan atau salin- menyalin saja dari teks atau guru di sana. Pada situasi ini, sulit membayangkan pemikiran yang otentik dari seorang peserta didik.
Bila demikian, tujuan pertama pendidikan untuk membuat peserta didik dapat berpikir mandiri sesuai kebutuhan dan problem zamannya tidak dapat dicapai. Terhalang oleh ketidakmampuan menangkap realitas (problem) sosial yang sesungguhnya. Bagaimana tidak? Bila alat analisis untuk pemecahan masalah masih memakai alat yang lama, sementara realitas sosial terus berubah dan terus baru.
Dalam kebuntuan dan kemandegan alam pikiran pesantren, filsafat dapat menjadi sumber mata air bagi keringnya kreatifitas berpikir produk pengetahuan keislaman- keindonesiaan di sana. Kita tidak dapat berharap akan lahir Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid baru di tingkat pemikiran keislaman bila pesantren tidak bertransformasi pula dalam paradigma berpikirnya.
Pesantren-pesantren mula-mula dapat mengawali kurikulum filsafatnya melalui pemikiran-pemikiran tokoh muslim Indonesia—yang lebih banyak berbicara fakta riil kebudayaan Indonesia beserta tantangan-tantangannya (filsafat sosial-kritis; bukan yang melangit dan mengambang) daripada sekadar mengulang teks-teks tradisional yang tidak merangsang dan menumbuhkan kepekaan; kesadaran kritis terhadap kehidupan sosial dan masyarakat secara umum.
Bila itu dijalankan, kita akhirnya dapat berharap kontribusi pemikiran keislaman produk pesantren bagi penyelesaian problem sosial kontemporer Indonesia—bahkan problem dunia hari ini secara keseluruhan. Itu.
Editor: Soleh