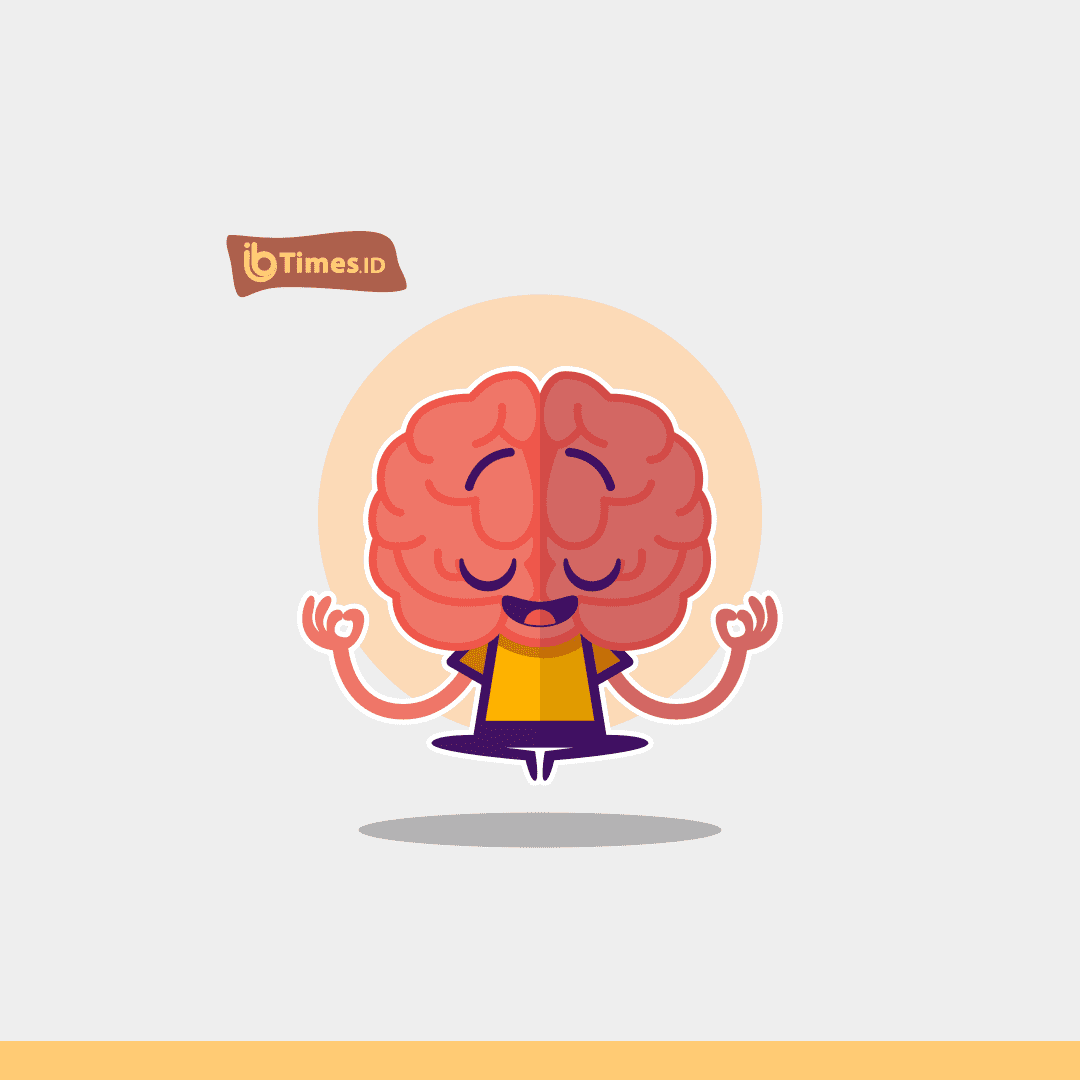Kata “intelektual” sering kita dengar sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir yang tajam. Secara historis, konsep tentang intelektualitas ini kali pertama dikemukakan oleh seorang psikolog asal Perancis, yaitu Alfred Binet. Ia mengemukakan konsep bahwasannya intelektualitas itu merujuk pada sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang seiring dengan proses kematangan diri seseorang.
Sejauh ini, kata “intelektual” masih kerap diasumsikan sebagai kemampuan berpikir yang hanya tersemat pada orang-orang tertentu saja, seperti misalnya pada akademisi, ilmuwan, ataupun peneliti. Padahal, kalau merujuk pada konsep Alfred Binet tadi, artinya secara implisit semua manusia yang berakal adalah seseorang yang memiliki intelektualitas.
Hanya saja, mengapa ada asumsi bahwa intelektualitas seakan hanya tersemat pada orang tertentu saja? Ya, karena selama ini kita belum tahu, bahwa perihal intelektualitas itu bersifat hierarkis dan terus berkembang. Kita menganggap diri sendiri tidak punya intelektualitas, itu karena belum pernah tahu kadar intelektualitas kita ini seberapa.
Oleh karenanya, dalam upaya memperlihatkan kapasitas diri seseorang, pembahasan mengenai cara mengukur kadar intelektualitas ini dimungkinkan. Di satu sisi juga untuk instrospeksi diri, dan di sisi yang lain untuk saling mengingatkan apabila ada kawan atau seseorang yang kadar intelektualitasnya itu perlu ditingkatkan.
Pada tulisan ini, penulis melansir dari sumber internet dan buku-buku logical fallacy, lalu merangkumnya menjadi poin-poin yang memungkinkan seseorang melihat kadar intelektualnya.
Intensitas ‘Pokoknya’ dan ‘Menurut’
Pertama-tama adalah dengan melihat seberapa sering seseorang menggunakan kata “pokoknya” dan “menurut” pada sebuah argumen. Seperti misalnya: pokoknya dari berita yang beredar di tahun 2023 nanti akan ada resesi, pokoknya menurut dosen itu benar demikian, pokoknya menurut bukunya seperti itu.
Kalau melihat kalimat di atas, secara data kita memang bisa bilang bahwa argumen itu benar. Tetapi jika pada konteks intelektualisme, kalimat di atas tidak mempunyai nilai mutu dari pikiran seseorang. Bagaimana kita melihat nilai mutu pikiran seseorang jika ia hanya membaca informasi yang ada di sumber, tanpa adanya penalaran antar informasi dengan logika dari suatu pemahaman? Yang ada ia hanyalah pengepul informasi; membaca, mengingat, lalu menyampaikan dengan asumsi bahwa pemikirannya sudah tepat.
Bukan berarti sebuah referensi sebagai penyusunan argumen atau ber-intelektualitas itu diharamkan. Referensi memang sangat penting sebagai penopang argumen, tetapi jika seseorang penuh dengan kata “pokoknya” dan “menurut”, maka seseorang itu hanyalah pengepul informasi, bukan pengolah informasi.
Respon Ketika Dikritik
Kita mungkin sudah familiar dengan pernyataan, “orang yang enggan menerima kritik itu berarti tidak open minded; belum bisa menerima keberagaman pendapat”. Pernyataan itu memang bisa dibenarkan, akan tetapi kurang lengkap. Sebab, semua orang pasti akan menerima kritik, tapi yang jadi persoalan itu bukan menerima atau tidaknya, tetapi bagaimana respon seseorang itu ketika menerima kritik.
Setidaknya ada dua jenis respon ketika dikritik, yaitu kooperatif dan konservatif. Maksud dari kooperatif dalam hal ini adalah ketika seseorang itu merespon suatu kritik dengan cara yang diskusional. Meskipun orang itu benar ataupun salah, sebuah kritikan akan selalu diambil dan diperbincangkan hingga menemukan titik temu kebijaksanaan.
Sedangkan seseorang dengan kepribadian konservatif akan selalu pongah ketika dikritik. Kendatipun ia menerima kritik; meresponnya dengan bahasa-bahasa halus yang terkesan open minded, orang konservatif akan beretorika semaksimal mungkin untuk menunjukkan bahwa sebuah krtikan yang ia terima itu sepenuhnya salah. Orang semacam ini tidak akan melihat sebuah kritik sebagai sesuatu yang bisa diperbincangkan secara konstruktif.
Mengapa yang konservatif menandakan rendahnya kadar intelektualitas? Sebab, intelektualitas itu perihal kecerdasan untuk menghubungkan sesuatu yang sebelumnya tidak terpola, sehingga menjadi pola.
Hal itu berkaitan dengan oposisi binernya De Saussure yang menyatakan, “sesuatu menjadi ada karena perbedaan karakteristik antar objeknya”. Jadi, orang yang intelektualitasnya rendah, ia akan memunafikan pandangan-pandangan lain yang sebetulnya saling berhubungan.
Mem-framing Tanpa Adanya Argumentasi
Secara definitif, framing adalah pembingkaian atas cara pandang seseorang. Orang yang kadar intelektualitasnya rendah, ia akan mem-framing sesuatu tanpa adanya argumentasi yang logis. Misalnya: ah, kamu mengkritisi kayak gitu mah karena iri sama dia; ah, kamu sering aktif di kelas mah supaya dipuji sama dosen; ah, kamu berlagak seperti aktivis mah karena mau jadi politisi.
Framing semacam itu adalah bentuk penalaran yang tidak logis. Dalam kajian logika, itu disebut sebagai argumentum ad hominem, yaitu argumen yang menyerang sisi personal pembuat argumen, bukan pada substansi argumen.
Orang-orang semacam ini biasanya di forum diskusi atau perdebatan selalu menitikberatkan sentimennya ketimbang kapasitas intelektualnya.
Pengambilan Kesimpulan yang Sempit
Point kelima, bisa dilihat dari bagaimana seseorang mengambil kesimpulan. Dalam hal ini, saya menggaris bawahi orang-orang yang mengambil kesimpulan secara sempit. Misalnya: wah, pemikiran orang itu bagus, sama kayak pemikiranku; ah, korona sekarang mah udah nggak ada, buktinya aku sampai sekarang nggak terpapar; merokok itu tidak apa-apa, buktinya kakekku menghabiskan tiga pak rokok setiap hari dan usianya bisa sampai 90 tahun.
Contoh pengambilan kesimpulan sempit di atas, itu biasa disebut sebagai subjektivitas. Dengan kata lain, pengambilan kesimpulan yang hanya berdasarkan pengalaman pribadi, bukan berdasarkan fakta yang terjadi. Sedangkan pengambilan kesimpulan yang berdasarkan fakta, itu disebut dengan objektivitas.
Sebagai contoh dari pengambilan kesimpulan objektif: pemikiran orang itu bagus, karena representatif dengan realitas yang ada; corona sekarang sudah mulai hilang, karena berdasarkan data dan informasi dari kemenkes; merokok itu potensial membahayakan kesehatan, karena ia mengandung banyak bahan kimia yang berbahaya untuk kesehatan.
Pengambilan kesimpulan yang sempit di atas merupakan kesesatan berpikir yang biasa disebut sebagai availability bias, yaitu penalaran yang berdasarkan contoh yang tidak relevan dengan kuantitas dan kualitas dari sebuah substansi.
Tirani Konsekuensi
Poin terakhir adalah orang yang selalu menitikberatkan konsekuensi secara tunggal dari suatu proposisi. Misalnya: buku adalah jendala dunia, kalau kamu sering membaca buku, maka kamu akan sukses di kemudian hari; orang yang mainnya jauh itu kenal dengan banyak orang, kalau kamu mainnya di situ-situ saja, maka pengetahuanmu ya hanya itu-itu aja.
Pernyataan-pertanyaan di atas adalah sebagian contoh dari hasil intelektualitas yang masih rendah. Karena ia menyatakan proposisi yang selalu berbanding lurus dengan konsekuensi.
Perihal konsekuensi memang bisa jadi disebabkan karena suatu proposisi, namun proposisi tidak selalu menghasilkan konsekuensi yang sama. Antara proposisi dengan konsekuensi itu ‘potensial’ berhubungan, namun harus ada bukti-bukti kuat yang mendukung suatu proposisi.
Benar dan salahnya suatu proposisi itu bergantung atas karakteristik; koherensi dari proposisi itu sendiri, bukan atas konsekuensi.
Misalnya salah satu contoh di atas tadi: buku memang jendela dunia, namun bukan berarti orang yang tidak membaca buku itu tidak sukses di kemudian hari, buku hanyalah salah satu modal yang bisa dimanfaatkan untuk menuju kesuksesan.
Artinya, konsekuensi sifatnya masih hipotesis jika disandarkan pada proposisi. Gaya intelektualitas semacam ini dalam diskursus logika disebut argumentum ad consequentiam, yaitu mentiranikan sebuah akibat dari suatu proposisi tanpa adanya bukti-bukti yang memadai.
Catatan Kaki
Sebenarnya masih banyak jenis-jenis kesesatan berpikir yang ada dalam literatur logika. Namun menurut penulis, setelah membaca dan mencermati literatur logika, berbagai macam jenis kesesatan yang ada itu bisa dirangkum setidaknya dalam enam poin ini.
Dan juga, enam poin yang ada pada tulisan ini merupakan kesesatan yang paling umum kita temui di kehidupan sehari-hari, termasuk ketika di ruang diskusi. Maka dari itu, semoga setelah membaca ini, kawan-kawan bisa sadar akan kemampuan intelektualitasnya dan segera mengeksplorasi lagi. Di bagian akhir, penulis menawarkan referensi yang mungkin berguna untuk keberlanjutan belajar logika.
Referensi
Dobelli, Rolf, 2013, The Art of Thinking Clearly, London: Sceptrebooks.
Rossow, GJ, (ed.), 1994, Skilful Thinking: An Introduction to Philosophical Thinking, Pretoria: HSRC Publishers.
Faiz, Fahruddin, 2020, Ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika: Membincang Cognitive Bias dan Logical Fallacy, Yogyakarta: MJS Press.