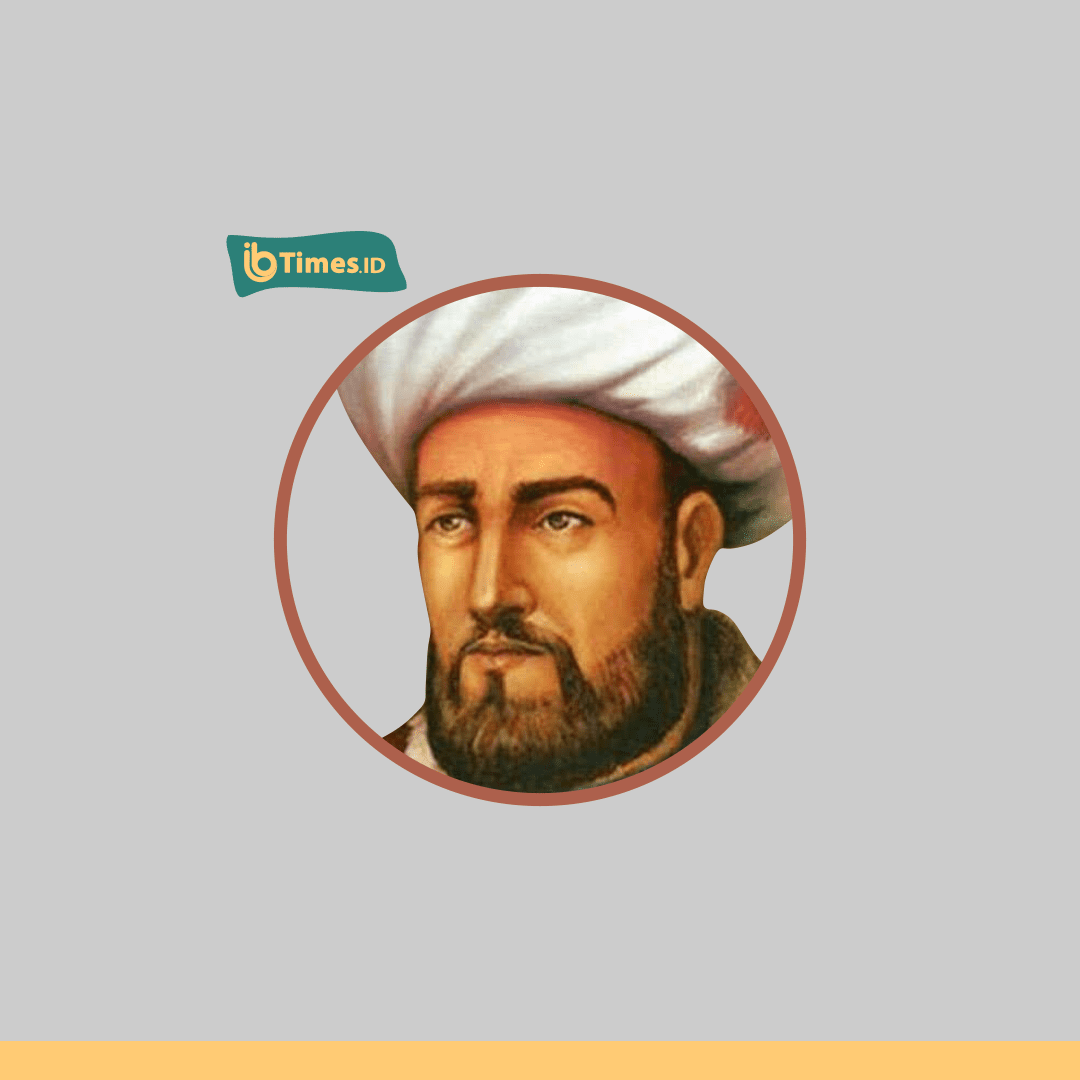Imam al-Ghazali adalah tipikal ulama yang aktif mengajak untuk berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Hal ini terbukti dalam karya-karya fenomenalnya seperti al-munqidz min ad-dlalal, misykat al-anwar, faishal at-tafriqah, dan banyak lainnya.
Beliau menginginkan agar umat Islam mampu mengenali hakikat kebenaran secara mendalam, tidak parsial, apalagi hanya bermodalkan taklid semata. Metode inilah yang kelak akan mengantarkan al-Ghazali melakukan pengembaraan panjang dalam menyingkap hakikat ilmu dan kebenaran. Pengembaraan yang juga membawa al-Ghazali melabuhkan jalan pencarian terakhirnya ke dalam samudera tasawuf.
Ilmu Yaqini
Setelah melakukan pencarian panjang tentang hakikat ilmu dan berbagai upaya penyelidikan untuk terlepas dari jerat-jerat ketaklidan (rabithah at-taqlid), maka sampailah al-Ghazali pada sebuah titik kesimpulan bahwa ilmu yang harus diikuti dan diyakini kebenarannya hanyalah al-‘ilmu al-yaqiniy.
Beliau menjelaskan bahwa al-‘ilmu al-yaqiniy adalah huwa alladzi yankasyifu fiihi al-ma’luumu inkisyafaan laa yabqaa ma’ahu raibun, walaa yuqaarinuhu imkaanu al-ghalathi wa al-wahmi, wa la yattasi’u al-qalbu li taqriiri dzalika (ilmu yaqini adalah ilmu yang dapat menyingkap perkara yang maklum, sebuah penyingkapan yang sama sekali tidak menyisakan keraguan, tidak diiringi kemungkinan terjadinya kesalahan dan terlepas dari pengaruh khayalan dan kebimbangan yang diragukan kebenarannya). Al-‘ilmu al-yaqiny inilah yang akan digunakan al-Ghazali dalam menyingkap hakekat segala perkara.
Namun, apa yang terjadi setelah itu? Imam al-Ghazali mengalami pergolakan yang dahsyat di dalam batin dan pikirannya. Pergolakan yang membawa al-Ghazali ke dalam sikap skeptis (keraguan) terhadap beragam ilmu.
Muncul pertanyaan, “Kenapa bisa sampai demikian? Bukankah harusnya dengan ilmu yaqini muncul keyakinan yang mantap, bukan keraguan?”
Konsekuensi dari meyakini kebenaran ilmu yaqini adalah hanya akan menerima segala ilmu yang telah pasti kebenarannya, ilmu yang tidak menyisakan zhan (dugaan). Padahal kita tahu bahwa ilmu-ilmu syariah semacam fikih, tafsir, dan penilaian derajat hadis adalah sebagiannya bersifat ijtihadi atau zhanni alias tidak pasti.
Di dalam ilmu-ilmu tersebut, sangat memungkinan adanya multi-interpretasi dari para ulama dan memunculkan berbagai ragam pendapat. Apakah kemudian ilmu-ilmu semacam ini mesti ditinggalkan karena tidak sampai ke derajat yaqiniy?
Periode Kebimbangan
Di awal tahap kebimbangannya, Imam al-Ghazali hanya mempercayai dua ilmu, yaitu ilmu khissyiyyat dan ilmu dlaruriyyat.
Ilmu khissiyyat adalah ilmu yang bertumpu pada kemampuan inderawi, seperti penglihatan oleh mata. Misalkan mata kita melihat ada batu besar di tengah lapangan, maka hasil tangkapan penglihatan mata terhadap objek batu adalah contoh dari ilmu khissiyyat.
Sedangkan ilmu dlaruriyat merupakan ilmu yang bersifat aksiomatik, ilmu yang sudah pasti kebenarannya dan tidak memerlukan penelitian serta pengujian, seperti api itu panas dan es itu dingin.
Pada tahap selanjutnya, serangan keraguan itu mulai memasuki periode meragukan ilmu khissiyyat (ilmu inderawi). Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa seringkali pandangan mata itu menipu. Bintang-bintang yang ada di langit jika dilihat oleh mata hanyalah seukuran uang dinar. Namun ternyata setelah dibuktikan melalui ilmu astronomi atau perbintangan ternyata bintang-bintang yang terlihat kecil oleh mata tersebut lebih besar berkali-kali lipat dibanding dengan bumi. Kemudian Imam al-Ghazali menyatakan bahwa hakim akal (ilmu ‘aqliyyat) dan aktivitas observasi telah menggugurkan ilmu khissiyyat.
Di dalam batin al-Ghazali, ilmu khissiyyat mengajukan semacam banding. Ilmu khissiyyat melakukan protes, “Anda meninggalkanku dan berpaling setelah datang hakim akal (ilmu ‘aqliyyat). Apakah anda akan merasa aman dengan berpegang kepada hakim akal sebagaimana dahulu anda sangat yakin denganku (ilmu khissiyyat) sebelum datang hakim akal? Bagaimana jika kelak datang hakim lain yang mendustakan hakim akal sebagaimana hakim akal mendustakanku?”
Al-Ghazali tercenung sejenak kemudian tertidur dan bermimpi. Mimpinya tersebut akan membawa al-Ghazali ke periode kebimbangan berikutnya yaitu meragukan ilmu inderawi dan ilmu akal.
Beliau menyatakan bahwa segala hal yang dialami dan dilihat di alam mimpi terkesan nyata dan sesuai penalaran akal, namun begitu seseorang yang bermimpi tadi terjaga maka pudarlah semua yang ada di mimpi itu. Periode keraguan inilah yang kelak akan mengantarkan al-Ghazali menyelami dalamnya samudera tasawuf.
***
Berbagai keraguan tersebut berusaha diatasi oleh al-Ghazali. Beliau berasumsi bahwa segala keraguan tersebut dapat diusir dengan menyusun argumen-argumen yang sistematis sebagai penangkalnya.
Fase keraguan ini dialami al-Ghazali selama dua bulan lamanya. Selama dua bulan itulah beliau terombang-ambing dalam mazhab sofistik (safsathah) dalam tataran penentuan tindakan (hal), bukan pada tataran penetapan logika serta ucapan.
Akhirnya, Allah memberikan kesembuhan kepada Imam al-Ghazali dan mengembalikan jiwanya seperti sedia kala. Itu semua terjadi bukan melalui struktur pembuktian secara sistematis dan ilmiah sebagaimana lazimnya. Tetapi itu semua berkat cahaya yang Allah curahkan ke dalam dada al-Ghazali (nuurun qadafahullah).
Al-Ghazali menyatakan bahwa periode kebimbangan yang dialaminya tidak hanya menimpa dirinya secara khusus, tetapi juga dialami oleh semua pembesar orang-orang yang arif (ahli ma’rifat). Maqam inilah yang dikenal dengan istilah periode kebimbangan (maqam al-hirah), hingga akhirnya seseorang yang berhasil melewati fase ini akan menemukan ketenangan dan kelezatan di dalam ma’rifat billah.
Bahan Bacaan
Al-Munqidz min ad-Dlalal wa al-Mufshih bi al-Ahwal karya al-Ghazali terbitan Daarul Minhaj.