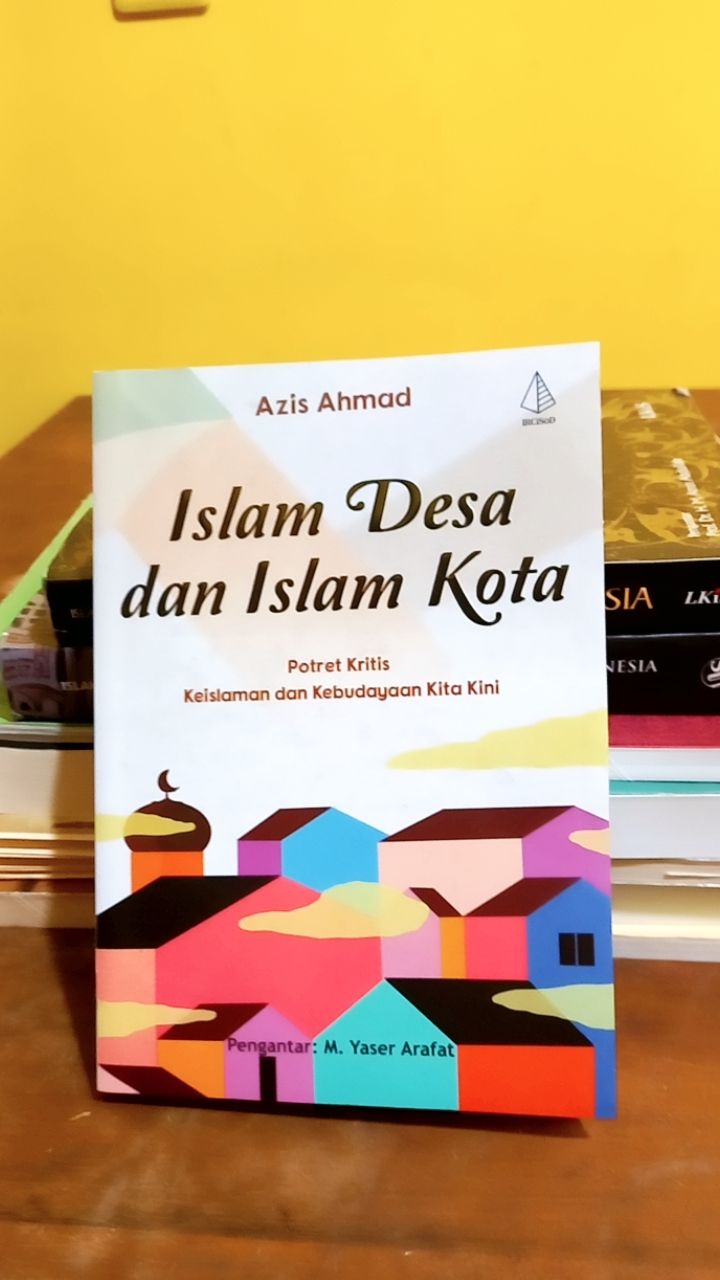Membaca buku berjudul Islam Desa dan Islam Kota, saya langsung membayangkan bagaimana laku-laku beragama antara di desa dan di kota; yang tentu berbeda satu sama lain. Meskipun mungkin Mas Azis tidak ada niatan untuk mendikotomikan desa-kota; tapi pada kenyataannya problem-problem yang ada di desa dengan di kota memang berbeda, bahkan berkebalikan.
Kuntowijoyo (2017) sendiri pernah menulis bahwa budaya desa itu bersifat statis, mistis dan lokal; lain halnya dengan budaya kota yang mobil, rasional dan kosmopolitan. Tambahnya, Pak Kunto mengatakan bahwa kejatuhan Islam adalah pada saat Islam di-desa-kan, di-petani-kan; yang erat dengan budaya-budaya di atas.
Namun dalam buku ini, seakan Mas Azis ingin membantah anggapan sebelah mata Pak Kunto terhadap kebudayaan desa. Bahwa budaya desa tidak selalu sedemikian buruk, mundur atau terbelakang; melainkan ada hal-hal yang mungkin justru tidak ditemukan di kota, baik secara sosial maupun spiritual.
Melalui pengalamannya, Mas Azis mencicipi dua ekosistem yang berbeda sekaligus: menjadi cah ndeso, sebagaimana pekerjaannya sebagai suplayer sayuran yang memaksanya bolak-balik ke kampung halamannya yang berada di Kaliangkrik, Magelang; di lain pihak menjadi cah kutho, dengan pengalamannya menempuh pendidikan S1 dan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan hiruk-pikuk kota pendidikan tersebut.
Buku ini merupakan kumpulan tulisan Mas Azis untuk merespon berbagai fenomena sosial-keagamaan, yang terjadi di desa maupun di kota yang ia tinggali. Namun sebelum membahas buku ini, alangkah baiknya kita mengerti dahulu bagaimana tipologi desa dan kota.
Memahami Tipologi Desa dan Kota
Seorang antropolog bernama Robert Redfield menganggap desa sebagai tempat yang diisi sekelompok masyarakat yang bermata pencaharian petani dan mengembangkan tradisi kecil; sebaliknya kota adalah masyarakat yang berada di dalam pusat kebudayaan dan mengembangkan tradisi besar [Surur, 2020].
Adapun seorang pemikir evolusionis, E.E. Bergel, berpendapat bahwa pada awalnya kota adalah sebuah desa; yang mengalami perubahan terus menerus [Basundoro, 2012].
Dari situ dapat ditarik kesimpulan, bahwa kota dengan segala kemajuan dan kecanggihannya, awalnya adalah desa dengan kesederhanaan dan kesahajaannya. Namun karena adanya perkembangan dan perubahan (dan menjadi kota), maka seakan desa dianggap sebagai terbelakang; yang memunculkan dikotomi desa-kota.
Maka dari itu, sepatutnya masyarakat kota tidak bersombong atas kemodernannya; karena kemajuan turut pula membawa permasalahan yang lebih kompleks seiring dengan bertambahnya masyarakat yang heterogen.
Begitu juga dengan masyarakat desa, tidak perlu berkecil hati dengan ke-desa-annya; karena pada dasarnya desa tetap indah dengan keasrian dan keaslian alamnya, serta sahaja penduduknya.
Shalat dan Manajemen Waktu Masyarakat Desa
Suasana keberagamaan di desa dipotret melalui cerita bagaimana suasana beragama di kampung halamannya. Seperti dalam esai berjudul Berislam dan Melawan ala Petani Nepal van Java, yang membahas ihwal waktu shalat di desa.
Bagi masyarakat desa, waktu shalat bisa diubahnya menjadi manajemen waktu kegiatan sehari-harinya. Jadi, pembagian shalat lima waktu sekaligus merangkum pembagian waktu yang lainnya: bekerja, istirahat, bermasyarakat.
Seperti biasanya setelah Subuh, masyarakat mulai mengawali aktivitasnya: pergi ke pasar, ke sawah, atau mencari rerumputan untuk ternak mereka, dll.
Menjelang Dzuhur, mereka akan pulang untuk istirahat sejenak, makan siang, atau tidur. Kemudian setelah Dzuhur, mereka akan beraktivitas kembali sampai pada waktu Ashar. Namun, adzan Ashar di pedesaan tidaklah pada pukul 15.00, sebagaimana dalam jadwal waktu shalat di kalender-kalender.
Akan tetapi disesuaikan dengan waktu pulang masyarakat desa dari berbagai aktivitas dan pekerjaannya. Sehingga tak jarang di desa ditemui adzan Ashar jam 16.00 atau 16.30; bukan maksud untuk mengundur-undur shalat, melainkan disesuaikan agar masyarakat ikut sholat berjamaah di langgar-langgar mereka.
Jeda waktu Ashar sampai Magrib atau Maghrib sampai Isya biasanya digunakan untuk berkegiatan sosial atau sekadar bercengkerama dengan tonggo teparo. Bagi anak-anak, waktu tersebut biasanya merupakan waktu untuk mengaji, belajar al-Qur’an di langgar-langgar dekat tempat tinggal.
Bagi kaum laki-laki, biasanya waktu ba’da Maghrib diisi dengan tahlilan atau rutinan yasinan bergilir. Dan setelah Isya` adalah waktu untuk keluarga, waktu istirahat dan tidur, sebelum kembali memulai aktivitasnya kembali di esok hari.
Dari situ, Islam di desa tidak nampak sebagai kemunduran. Alih-alih kemunduran, Islam malah mampu me-manajemen kegiatan sehari-hari masyarakat desa; tanpa berat sebelah antara hubungan vertikal (Tuhan) maupun horizontal (masyarakat); spiritual maupun sosial.
Sebagaimana kata Mas Azis, bagaimana kita akan menyematkan kata malas kepada mereka (masyarakat desa) sementara tidur di pagi hari saja dianggap sebagai hal yang tabu? (hlm. 92).
Fenomena Hijrah Pemuda Kota
Kota yang merupakan pusat urbanisasi tentunya menjadi tempat di mana berbagai golongan, suku dan agama menyatu. Maka sangat mungkin terjadi gesekan antar masing-masing latar belakang.
Terlebih di zaman serba canggih ini, arus informasi tak terbendung. Ambil contoh konten-konten keagamaan, sangatlah mudah diakses dengan cuma-Cuma tanpa harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli buku atau kitab.
Dari situ pula muncul paham-paham keagamaan yang bermacam-macam, yang dalam konteks perkotaan adalah radikalisme. Sebagai mahasiswa, Mas Azis sering menjumpai kegiatan dakwah Islam oleh kelompok ekstremis di kampus-kampus. Ya, sasarannya adalah para pemuda.
Salah satu budaya yang sedang tren kurun dasawarsa terakhir adalah budaya hijrah. Saya pribadi merasakan betul ketika masih duduk di bangku SMA perihal fenomena berhijrah. Hanya berbekal kata “hijrah”, mereka langsung mencap dirinya sebagai ‘yang paling’: Islam, benar, halal, syar`i, dll; dan menganggap yang di luar pahamnya adalah salah, bid`ah, buruk, dll.
Itu mungkin masih di bangku SMA, belum lagi jika menginjak perguruan tinggi, dengan masyarakat yang beragam latar belakang keagamaan, dan kajian-kajian yang Islam yang menjamur; bukan tidak mungkin malah akan memperkokoh paham eksklusivisme beragama.
Dalam hal ini, Mas Azis menguraikan bagaimana fenomena hijrah itu terjadi. Seorang yang berhijrah biasanya mulai lengah dengan hiruk pikuk (budaya) perkotaan, hasrat meninggalkan masa lalu yang kelam, dll.
Sedang di lain pihak, terdapat agamawan-agamawan dengan berbagai latar belakang, yang ingin menawarkan paham keagamaannya. Dalam konteks ini, yang paling bisa menggaet pasar adalah paham-paham Islam yang eksklusif, yang mungkin berhasil mengambil hati para pemuda; salah satunya melalui tren ‘berhijrah’.
Dalam menarik hati kalangan pemuda, kelompok-kelompok Islam eksklusif menggunakan media yang beragam: mulai dari kajian-kajian yang lebih modern dan dekat dengan kaum muda, buku-buku, media digital dengan berbagai konten yang disuguhkan, dll.
Maka bukan tidak mungkin jika seseorang telah mengaku ‘berhijrah’ tiba-tiba sangat getol terhadap kesalahan-kesalahan orang lain yang tidak sesuai dengan paham yang diajarkan.
Apakah berhijrah salah? Tentu saja tidak. Yang salah adalah paham eksklusivisme beragama: yang menganggap selain golongannya, salah; merasa surga adalah milik golongannya sendiri.
Tentunya ini adalah PR besar bagi kelompok-kelompok Islam moderat, untuk menjawab tantangan zaman: menyajikan Islam yang lebih dekat, yang kekinian dan kompatibel dengan generasi muda.
Kesimpulan
Tentunya buku ini merupakan sebuah fragmen yang memotret kebudayaan Islam di desa dan kota, sebagaimana pengamatan, pengamalan dan pengalaman Mas Azis.
Desa dan kota memiliki kulturnya masing-masing. Kita tidak bisa antipati terhadap modernitas yang ada di kota; di lain pihak juga jangan sampai kita beranjak ‘meninggalkan’ desa.
Kota adalah lambang kemodernan, di mana inovasi dan kreasi tumbuh di sana; sedangkan desa adalah lambang kesederhanaan, kekeluargaan, kesahajaan; di mana kebijaksanaan lahir di sana.
Justru dari kedua kebudayaan tersebut kita harus pandai menempatkan diri. Karena yang kuno belum tentu usang, dan yang baru belum tentu baik. Kita harus bijaksana seperti desa, sekaligus terbuka seperti kota.
Daftar Buku
Judul buku : Islam Desa dan Islam Kota
Penulis : Azis Ahmad
Penerbit : IRCiSoD (2022)
Tebal buku : 200 hlm.
ISBN : 978-623-5348-36-0
Editor: Soleh