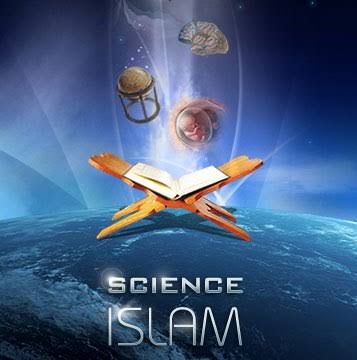Ketika Louis Leahy memberikan kata pengantar dalam buku yang bertajuk Sains dan Problem Ketuhanan karya Greg Soetomo (1995), ia sangat prihatin melihat kenyataan ketika agama sering dikonfrontasikan dengan Sains dan Kosmologi dalam konsepsi modern. Agama dan Sains seringkali juga dipandang dengan sangat dikotomis, apakah merupakan suatu harmoni atau justru pertentangan? Benarkah bahwa kemajuan Sains dan teknologi bisa menjadi ancaman bagi agama?
Leahy menuturkan, sikap konfrontatif atau kecurigaan itu disebabkan oleh defisit pengetahuan dan kompetensi masing-masing tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam riset-riset ilmiah dan apa yang khas bagi monoteisme otentik. Leahy justru sangat meyakini bahwa Sains dan agama sejatinya bersedia untuk berdialog secara intensif dan saling menunjang (Soetomo; 1995: 1).
Namun sebelumnya, secara pribadi saya ikut prihatin sekaligus berbelasungkawa atas jatuhnya beberapa korban yang positif terjangkit virus Corona. Beberapa bulan terakhir ini virus Corona menjadi isu sentral hampir di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.
Tanggal 14 Maret Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr H Haedar Nashir, MSI mengeluarkan maklumat sebagai upaya preventif Muhammadiyah dalam mencegah bahaya Covid-19. Dua hari sesudahnya, tepatnya pada 16 Maret, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah saat pandemi virus Corona. Sebagaimana Muhammadiyah dan MUI, 20 Maret Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU juga mengambil langkah preventif di tengah mewabahnya Covid-19 ini.
Setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan ilmiah, dengan tetap mengedepankan dalil-dalil naqli dan aqli serta sesuai dengan metodologi hukum Islam (ushul fiqh). Maka menghasilkan satu keputusan yang sama, ialah bahwa mencegah kemafsadatan (baca: Covid-19) merupakan tugas setiap individu yang harus ditegakkan. Ketiganya, baik Muhammadiyah, MUI maupun PBNU pada prinsipnya menyatakan sikap yang sama tentang Covid-19. Anjuran pencegahan ini bukan saja menyangkut ibadah-ibadah sosial (ghairu mahdah), akan tetapi juga menyangkut ibadah mahdah yang pada dasarnya tidak memiliki ruang-ruang inovasi (ijtihad) dalam konsepsi filsafat hukum Islam.
Hal ini bisa kita lihat, misalnya, bagaimana ketika kemudian MUI dan dua Ormas Islam washathiyah Indonesia ini menangguhkan shalat Jumat, dan menghimbau agar sebaiknya kegiatan-kegiatan masjid yang melibatkan banyak orang-termasuk shalat jamaah dilaksanakan di rumah masing-masing untuk sementara waktu. Nah, keputusan Muhammadiyah, MUI dan NU ini tidak berangkat dari ruang kosong. Ini penting saya garis bawahi, sebab, belakangan mulai bermunculan pandangan-pandangan peyoratif bahwa keputusan ini sangat profan dan dikaburkan orientasinya. Tetapi, maaf, tulisan ini secara spesifik tidak mengarah ke sana!
Sekurang-kurangnya, ada dua poin mendasar yang saya potret dari apa yang ditempuh Muhammadiyah, MUI dan NU dalam upayanya menyikapi desas-desus Covid-19.
Pertama, kini menjadi sangat jelas bahwa Islam merupakan agama yang luwes, toleran, tidak mengekang terhadap para penganutnya. Islam juga menyediakan banyak dispensasi bagi siapa saja yang tidak mampu menjalankan syariat sebagaimana mestinya. Dan sebagai organisasi keagamaan-kemasyarakatan, Muhammadiyah, MUI, dan NU dalam hal ini sudah menyampaikan pesan itu.
Kedua, fatwa-fatwa atau keputusan ini sesungguhnya menjadi angin segar pertemuan agama dan Sains. Pertemuan ini berangkat dari keprihatinan umat beragama terhadap wabah Covid-19 yang oleh World Health Organization (WHO) dinyatakan sebagai pandemi yang menjadi masalah global dan sangat membahayakan. WHO adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional. WHO berpusat di Jenewa, Swiss, dan didirikan pada tanggal 7 April 1948.
Sementara Muhammadiyah, MUI dan NU yang cukup otoritatif dalam bidang ilmu keislaman terlihat sangat kooperatif dengan keputusan pakar virus dan tim medis yang secara rumpun keilmuan sudah pasti berbeda. Kenyataan ini, sekali lagi, merupakan ajang pertemuan antara agama dan Sains yang oleh sebagian kalangan selalu dikonfrontasikan sebagaimana ungkapan Louis Leahy.
Dalam kaitannya dengan poin kedua, ada catatan menarik dalam buku Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah karya Jasser Auda. Ia seorang pakar maqasid syariah terkemuka, yang selalu mengarusutamakan pendekatan multidisipliner untuk mengintegrasikan pengetahuan yang relevan dari berbagai ranah keilmuan dalam disiplin-disiplin umum hukum Islam, filsafat, dan sebagainya dari cabang ilmu lainnya. Auda hendak mengatakan, bahwa tanpa menggabungkan ide-ide yang relevan dari rumpun keilmuan lain, riset dalam teori dasar hukum Islam akan terkungkung dalam khazanah keilmuan klasik, yang pada gilirannya hukum Islam akan ketinggalan zaman baik dalam ranah teoritis maupun praktis (Jasser Auda; 2007: 28).
Pendekatan ini hendak mempertemukan kembali ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum dengan harapan, tercapainya kesatuan ilmu yang integratif dan interkonektif. Proyek keilmuan ini diharapkan menjadi solusi dari berbagai krisis (baca; Covid-19) yang melanda manusia dan lingkungan sekitar dewasa ini, yang diakibatkan oleh ketidakpedulian suatu ilmu terhadap ilmu lainnya.
Dalam kasus Covid-19, sebagai problem baru yang muncul dan berkembang jauh setelah al-Quran diwahyukan di satu sisi, dan sunnah-sunnah Nabi disabdakan di sisi yang lain. Maka, klasifikasi kasus ini sebagai problem kontemporer yang berada di luar jangkauan teks-teks agama menjadi sesuatu yang tak terbantahkan. Di sinilah ijtihad memainkan peranannya.
Sebagaimana dalam terminologi klasik, ijtihad adalah sebuah aktivitas seorang faqih yang mencurahkan segala kemampuan berfikirnya, untuk menetapkan hukum syara’ yang dzanni (Al-Hajib; 1985: 43) (al-Hammam; 1983: 4/178). Hemat saya, definisi yang dikemukan oleh ulama-ulama klasik tentang ijtihad ini bersifat domestik sehingga, para ilmuan lainnya yang bukan ahli fiqh, tidak termasuk dalam kategori mujtahid. Asumsi tersebut sejalan dengan cita-cita ideal Asy-Syaukani yang mengharuskan adanya diksi al-faqih dalam definisi ijtihad (Asy-Syaukani; 1992: 296).
Pendapat Asy-Syaukani ini jika boleh saya katakan sudah sangat kehilangan relevansinya dengan konteks masa kini. Apalagi, kita hidup pada masa dimana wabah Corona benar-benar telah mengancam peradaban manusia dan alam sekitar yang, jika ulama, umara, ekonom, cendekiawan, ahli medis dan para pakar lainnya tidak saling bergandengan tangan mencegahnya, maka besar kemungkinan jumlah angka kematian korban Covid-19 akan terus bertambah setiap harinya. Dan kita tidak ingin hal itu terjadi.
Sinergitas NU, Muhammadiyah, dan MUI sebagai organisasi atau lembaga keislaman dan ahli medis dengan ilmu kedokterannya (sains) sangat besar kontribusinya terhadap pencegahan Covid-19. Penangguhan shalat Jumat, dan gerakan ibadah di rumah masing-masing adalah bukti riil dari pertemuan agama dan Sains. Qaidah fiqh yang sangat populer di kalangan pelajar Muslim, “dar’ul mafaasid, awlaa min jalbil mashooleh”, dan argumentasi Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H/1388 M) bahwa Allah SWT menetapkan hukum semata-mata untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat (al-Syathibi; 2003:4), tampak terekam jelas dalam keputusan NU, Muhammadiyah, dan MUI ini.
Wal hasil, kita patut bersyukur bahwa pada akhirnya otoritas keagamaan kita sangat mendukung supremasi Sains. Karena sejatinya agama dan sains itu ada untuk kemanusiaan. Toh, agama memiliki tugas ekstra, misi ketuhanan, tetapi dalam praktek, ia tidak boleh dijauhkan dari basisnya, yaitu kemanusiaan.
Mari untuk sementara waktu kita hindari kerumunan, sembari memohon; semoga kondisi Indonesia dan dunia segera kembali normal, seperti dahulu kala. Wallahu a’lam!
Editor: Arif