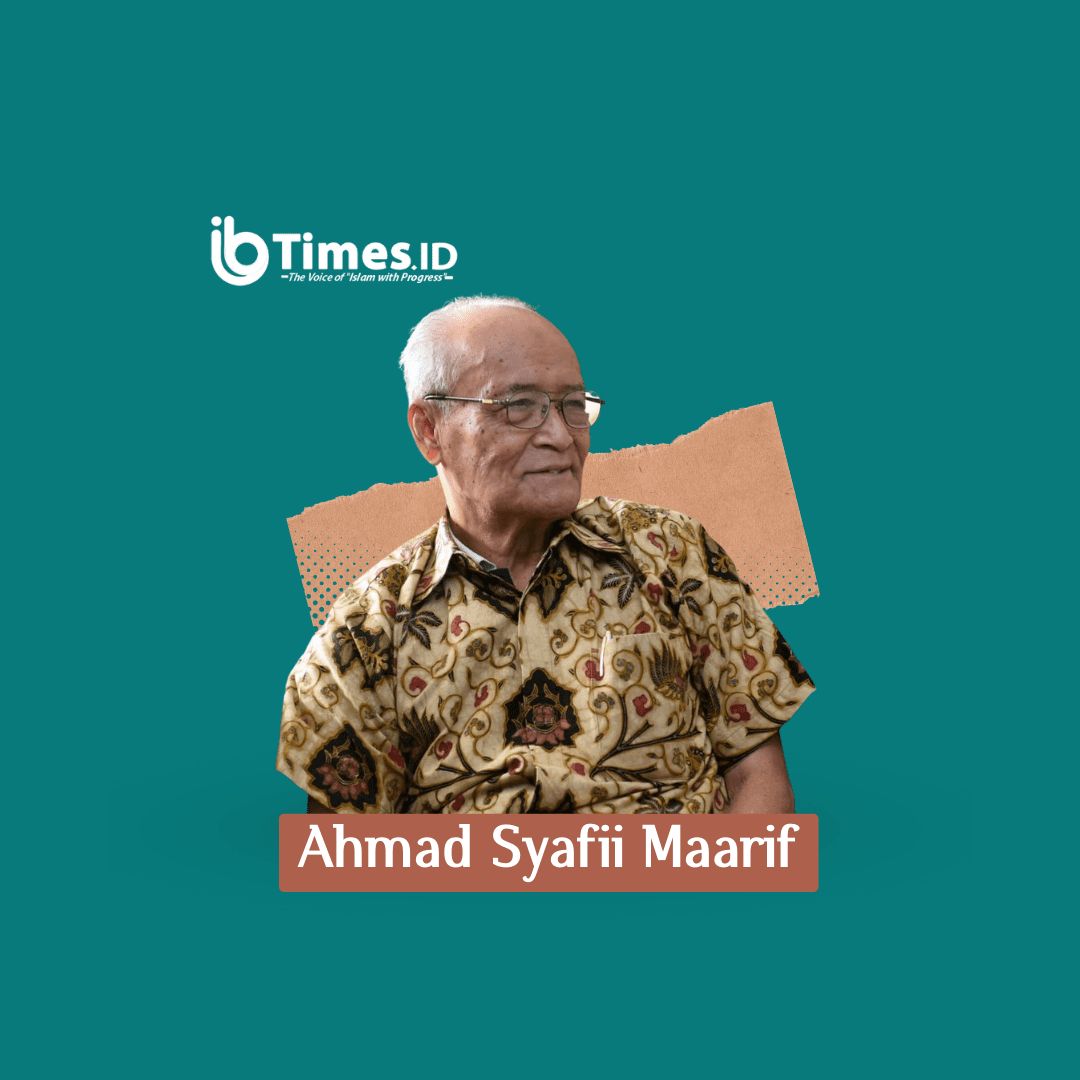Fundamentalisme |Tahun 2022 ini hari sumpah pemuda memasuki usia yang ke- 94 tahun, pada tahun yang sama pula kita kehilangan tokoh gerakan intelektual yang kita kenal dengan sebutan Buya Syafi’i, dimana telah menginspirasi banyak anak muda seperti saya, tentu secara normatif dalam konteks perjalanan intelektual ada banyak proses yang telah dilalui Buya Syafi’i yang perlu untuk kita gali ide, pemikiran dan semangat kebangsaanya sebagaimana semangat para pemuda era tahun 1928.
Sejarah peradaban kepemudaan di Indonesia seharusnya telah cukup matang baik secara emosional maupun intelektual, mengingat telah banyak catatan tinta emas yang telah ditorehkan kepada bangsa ini khususnya pada masa penjajahan.
Dalam sejarah pergerakan perjuangan melawan penjajah, kebaradan kaum muda menjadi bagian penting yang sulit terelakan, ada fakta menarik yang dipublikasikan sejahrawan Ahmad Mansyur Suryanegaratentang peranan pemuda, selama ini tokoh – tokoh seperti Endang Saefudin Anshori, Harry J Benda, John Igleson dan Clifford Geertz menyangka bahwa para tokoh agama di era kolonialisme itu sebagai golongan kaum tua, mengingat gelar haji atau kiai yang di sandang para tokoh agamawan tersebut, padahal mereka sesungguhnya masih berumur tidak lebih 30 tahun, sebut saja misalnya Muhammad Darwis alias Ahmad Dahlan yang pada usia 26 telah memiliki lembaga pendidikan, HOS Tjokroaminoto menjadi pemimpin Serikat Islam pada usia 30 tahun, Mas Mansur saat usianya 20 tahun telah mampu mendirikan Nadhatul Wathon, Wahid Hasyim yang pada usia belum genap 29 tahun telah menjadi tim 9 dalam meletakkan dasar negara dan masih banyak yang lainnya.
***
Semangat nasionalisme para pemuda tahun 1928 pada puncaknya akhirnya melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, nasionalisme tersebut yang oleh Adiyaksya Dault disebut sebagai nasionalisme politik Indonesia yang diperkenalkan oleh para intelektual dan para kaum terpelajar pada awal abad ke 20 yang diawali dengan titik tumpu lahirnya kebangkitan nasional melalui perkumpulan pergerakan Budi Oetomo tahun 1908.
Soekarno juga menjelaskan Nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme “ngelamun” bukanlah nasionalisme “kemenyan” bukanlah nasionalisme “melayang” tapi ialah nasionalisme yang dengan dua kakinya berdiri dalam masyarakat, memang maksudnya sosio-nasionalisme ialah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat itu, sehingga keadaan yang kini pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada kaum yang tertindas, tidak ada kaum yang cilaka, tidak ada kaum yang papa-sengsara.
Nasionalisme Ahistoris
Seirama dengan Soekarno, Prof. Dr. Ahmad Syafi’i Maarif juga mengatakan bahwa proses pembentukan nasionalisme kebangsaan Indonesia belum usai. Meski nasionalisme di era merebut kemerdekaan merupakan kekuatan dahsyat yang telah berhasil meluluhlantakkan sistem kolonialisme.
Namun demikian, nasionalisme yang berkembangan saat ini bukan lagi melawan kolonialisme namun melawan kekuatan asing dan domestik yang bisa menghambat tujuan pembangunan kemerdekaan tanah air. “Tidak peduli apakah kekuatan penghambat itu adalah saudara kita sendiri,” pemahaman nasionalisme yang awalnya ditujukan untuk meruntuhkan sistem kolonial dan sistem feodal menuju terwujudnya sebuah bangsa merdeka.
Namun nasionalisme yang semula tajam kini berangsur-angsur menjadi tumpul bersamaam dengan lumpuhnya hati nurani dan akal sehat sebagian elite bangsa, “Ujungnya yang banyak berkeliaran kemudian adalah nasionalis-nasionalis gadungan yang telah mati rasa dan tidak hirau lagi dengan tujuan kemerdekaan bangsa, oleh karena itu perlu kiranya kita membangunkembali semangat nasionalisme yang telah mampu membawa bangsa ini untuk mewujudkan satu kehendak yakni perlawanan terhadap keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan yang sesungguhnya adalah perlawanan terhadap kolonialisme, lalu bagaima dengan potret generasi muda saat ini?
Di era masyarakat informatif saat ini, diakui atau tidak para remaja dan pemuda dewasa ini mengalamai degradasi dalam banyak hal, ada semacam keterkejutan budaya, saat arus informasi sudah tak memiliki batas bahkan menjadi situasi yang serba digital hampir di ruang paling privasi, alih-alih menjadikan keterbukaan sebagi akses dalam menemukan pengetahuan baru, malah yang terjadi justru keterbukaan menjadi ekses hilangnya identitas budaya sejarah bangsanya sendiri.
***
Tentu ini menjadi hal yang bertentangan dengan semangat sumpah pemuda, yang konon menjadi tonggak semangat kebangkitan kaum muda khususnya dalam mewujudkan rasa nasionalisme, maka dari itu di era kemutakhiran teknologi informasi saat ini kita perlu mendefinisikan kembali makna nasionalisme agar sesuai dengan konteks zamanya mengingat nasionalisme yang sekarang terkesan sekedar hanya simbol dan slogan yang aktualisasinya masih banyak dipertanyakan kejelasan kontribusinya untuk bangsa sehingga menjadi alpha dari nilai-nilai kesejahrahan yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa.
Semangat nasionalisme saat ini tidak hanya lahir dari romatisme sejarah saja, tapi perlu di artikulasikan dalam menjawab tantangan lokalitas yang sejatinya merupakan masalah klasik seperti kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, bedanya semua masalah itu bukan berkenaan dengan penjajahan secara fisik tetapi penjajahan dengan wajah-wajah baru mengatasnamakan Agama, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Nilai-nilai demokrasi, HAM begitu juga agama mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan bukanlah penyebab permusuhan. Apalagi sebagai poros perpecahan tetapi sebagai khazanah kearifan untuk saling melengkapi dan menghormati. Buya Syafi’i Maarif menyebutkan, ke-bhinneka-an harus dipahami sebagai sebuah kekuatan pemersatu bangsa yang keberadaannya tidak bisa dimungkiri.
***
Ke-bhinneka-an juga harus dimaknai sebagai sebuah keragaman yang mempersatukan, menerima perbedaan sebagai sebuah kekuatan, bukan sebagai ancaman ataupun gangguan, semua budaya, agama dan suku yang ada tetap pada bentuknya masing-masing, di mana yang mempersatukan semua itu adalah rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
Buya Syafi’i Maarif juga mempertegas suatu perbedaan itu dipahami dan dibiarkan dalam rangka mewujudkan persatuan kesatuan bangsa. Dengan kata lain keanekaragaman bangsa dihormati dalam wadah kesatuan bangsa Indonesia oleh karena itu Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa dianggap hanya sekedar semboyan, melainkan harus dihayati, disimpan pada sanubari, dan dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara.
Pada prinsipnya, semboyan bangsa adalah sebuah keharusan. Tetapi di era disrupsi ini, nasionalisme bisa jadi barang yang mahal bila tidak pula ada penguatan banyak keteladanan dari para publik figur baik politisi, pengusaha, negarawan, agamawan, budayawan, aktris dan juga tokoh-tokoh lokal agar nasionalisme kita tidak ahistoris.
Fundamentalisme Baru
Demokrasi kini telah menjadi industrialisasi sebagaimana ideologi kapitalisme, maka menafsir ulang kembali semangat nasionaisme melalui kebangkitan kaum muda adalah sebuah kebutuhan. Yang mana, dibutuhkan kesadaran kolektif (bersama) kaum muda, agar tiga rumusan sumpah pemuda tidak hanya menjadi kata-kata yang sifatnya sakral dan hanya untuk di hafal. Tetapi lebih dari itu, dapat menjadi pijakan dalam mempertegas identitas sebagai agent of change, tiga kata tersebut yakni satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa Indonesia.
Dalam era disrupsi saat ini, penulis bersepakat dengan pemikiran Buya Syafi’i Maarif soal fundamentalisme yang patut diwaspadai oleh seluruh entitas masyarakat, tapi tidak cukup hanya fudamentalime agama dan pasar saja. Penulis ingin menambahkan satu lagi fundamentalisme yang perlu diwaspadai khususnya kaum muda agar tidak terjadi keterasingan (alienasi) terhadap identitas budaya bangsa. Yakni fundamentalisme pragmatisme politik yang mana di era disrupsi ini ketiga fundamentalisme tersebut perlu ditafsir ulang sesuai situasi zamannya.
Yang pertama yakni fundamentalisme agama. Di mana, peran agama yang seharusnya sebagai pencerahan umat, lambat laun bergeser menjadi pemicu konflik. Telah banyak kekerasan yang terjadi di negeri kita dengan mengatasnamakan agama yang semakin lama justru dipolitisir. Untuk itu, kaum muda tidak sekadar menjadikan ruang dialog dalam menjernihkan masalah tetapi juga patut memberikan keteladanan bagaimana agama juga mengajarkan toleransi. Memberikan contoh bahwa agama juga mendorong umatnya untuk memperdalam aspek keilmuan, mengajarkan kedisiplinan, menumbuhkan optimisme, dan juga beragam nilai-nilai yang secara riil perlu dibuktikan.
***
Kedua fundamentalisme pasar yang saat ini telah merasuk hampir di segala lini dimensi kehidupan kita. Tidak saja melalui sistem ekonomi neoliberalisme, tapi juga pegaruhnya dalam bidang budaya, pendidikan sampai pada gaya hidup. Ini semua patut disadari oleh kaum muda agar mewaspadai fundamentalisme pasar sebagai ancaman yang sesungguhnya.
Tidak ada jalan lain bagi entitas masyarakat khususnya kaum muda kecuali dengan cara melakukan perlawanan segala bentuk fundamentalisme pasar. Mengingat pada akhirnya nanti, kekuatan pasar akan melibas negara kita melalui sistem neoliberalisme. Maka, kaum muda sedini mungkin harus melakukan perlawanan secara sistematis dan masif baik melalui aksional dengan menjadikan hasil karya anak bangsa sebagai pilihan utama dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya dapat menggairahkan ekonomi berbasis kerakyatan, penolakan kepada kebijakan yang pro-pasar dan serba impor, ketergantungan terhadap utang luar negeri, serta melalui internalisasi dan penguatan ideologi koperasi. Atau jika perlu, melakukan revolusi ekonomi dengan meminta pemerintah melakukan nasionalisasi aset-aset yang dianggap strategis seperti telekomonikasi, pertambangan, dan perbankan sekaligus melakukan revolusi budaya dengan cara merubah budaya hidup konsumtif menjadi produktif, menggeser kebiasaan sebagai pengguna menjadi pembuat.
***
Dan yang terakhir adalah fundamentalisme pragmatisme politik. Diakuai atau tidak, sistem demokrasi saat ini telah mendorong manusia menjadi gila kekuasaan dan tidak sungkan-sungkan menghalalkan segala cara, mengingat demokrasi telah menjadi industri untuk menumpuk kekayaan.
Perilaku menyimpang dalam pemilu yang pragmatis dianggap wajar dan sah-sah saja bagi jamak orang. Sekalipun sesungguhnya dalam norma masyarakat dan hukum adalah pelanggaran yang mesti untuk dieliminasi, baik di alam pikiran ataupun aktivitas. Tetapi nyatanya, justru tumbuh subur dalam setiap musim pemilihan.
Mengapa demikian? Apakah ini karena sistem demokrasi yang telah menjadi liberal? Atau karena masyarakatnya yang cenderung belum melek politik? Atau justru sebaliknya, masyarakat yang terlampau cerdas memanfaatkan momentum? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu telah menjadi dialektika di ruang publik. Tetapi tidak cukup ruang untuk mampu menemukan rumusan yang tepat, mengingat pemahaman tentang demokrasi sendiri oleh masyarakat masih cenderung parsial sehingga yang terjadi adalah kegagalan dalam pelaksanaan demokratisasi sebagai laku terapan dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian, tidak hanya berakhir pada lemahnya legetimasi kepemimpinan, tetapi lebih jauh, yang terjadi adalah krisis keteladanan di berbagai level kepemimpinan, baik vertikal ataupun horisontal dalam struktur masyarakat.
Pelaksanaan demokrasi sesungguhnya berperan sebagai jembatan dalam memberikan pilihan alternatif jawaban atas permasalah yang tengah terjadi dalam kehidupan masyarakat baik dengan dialog, fasilitasi pembuatan kebijakan publik, penyerapan aspirasi, kampanye gerakan moral, diskusi publik, pemberdayaan potensi masyarakat, edukasi, sampai dengan penegakkan hukum adil dan tidak diskriminatif yang arahnya adalah mendorong tumbuhnya kesadaran dan pasrtisipasi masyarakat akan hak sekaligus kewajibanya sehingga demokratisasi menemukan legetimasinya.
***
Pelaksanaan demokrasi justru akan kehilangan peranannya bila ia pada akhirnya hanya menjadi rutinitas lima tahunan atau menjadi komoditas untuk meraih dan mendapatkan kekuasaan saja. Demikian pula demokrasi hanya ada di atas kertas bila partisipasi atau keterlibatan warga dalam proses pembangunan tidak diberikan tempat sebagaimana mestinya.
Oleh karena itu, arena partisipasi publik/masyarakat dalam pembangunan tidak hanya mewujud dalam sebuah konstestasi aspirasi semata, tetapi menjadi mekanisme partisipasi yang memungkinkan setiap orang dan kelompok mampu berkomunikasi secara inklusif dan setara untuk membangun kesepahaman sekaligus kesepakatan bersama.
Ijtihad Demokrasi
Pemilu dan Pilkada tidak berbedah jauh dengan Pilkades dalam praktiknya, dimana pragmatisme politik menjadi poros orientasi. Oleh karena itu, tidak perlu heran jikalau kemudian sistem yang demikian justru melahirkan pemimpin terpilih yang ternyata tidak mampu menjalankan amanah, tidak lain karena proses “menjadi” (to be leader) dilalui dengan cara-cara manipulatif. Tanpa sadar pun, masyarakat juga menikmati sistem politik yang sedemikian rupa. Slogan NPWP (nomor piro wani piro) tanpa sungkan telah menjadi realita politik. Maka, di sinilah peran pemuda dituntut sebagai ujung tombak membendung pragmatisme politik dengan mempertegas artikulasi politik yang mandiri, berintegritas, dan smart sehingga mampu melakukan perubahan sosial dalam tatanan politik.
***
Entah itu sebagai penyelenggara pemilu, peserta pemilu, atau penentu kesuksesan pemilu bersih, jujur, dan adil. Maka, Pemilu dan Pilkada tidak seharusnya disuarakan sebagai pesta demokrasi yang jauh dari maknanya tapi penulis lebih setuju sebagai ijtihad demokrasi dalam menentukan pemimpin yang maknanya jelas dan terukur.
Di akhir refleksi ini penulis ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Pradana Boy (baca: kepemimpinan kaum muda) bahwa ada satu logika yang kadang-kadang sulit dipahami dalam konteks masyarakat Indonesia berkenaan peranan kaum muda. Di satu sisi, terdapat pengakuan bahwa golongan muda diidentikkan dengan progresifitas, mobilitas, penuh kreativitas dan pantang menyerah, tetapi pada saat bersamaan pengakuan tersebut hanya berlangsung pada dimensi kognitif saja, sehingga terjadi disparitas antara pengakuan dan aktualisasi dari pengakuan tersebut.
Intinya pengakuan telah menjadi slogan yang jamak diberikan kepada kaum muda tetapi kesempatan jarang diberikan. Oleh karena itu, besar harapan kita melalui Sekolah Kebudayaan dan Kemanuasian yang diadakan oleh Maarif Institute mulai tanggal 13-17 Nopember 2022 di Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi sarana konsolidasi kaum muda di berbagai lintas pergerakan untuk membumikan sekaligus membuktikan, kalau memang kesempatan itu masih digantung, mari kita rebut dengan semangat tafsir baru nasionalisme yang menghargai kebhinnekaan yakni dengan mempertegas kembali identitas pemuda sebagai penentu perubahan di era tantangan baru fundamentalisme yang dapat membahayakan intregitas sebagai bangsa yang satu bangsa Indonesia. Anda setuju?
Editor: Yahya FR