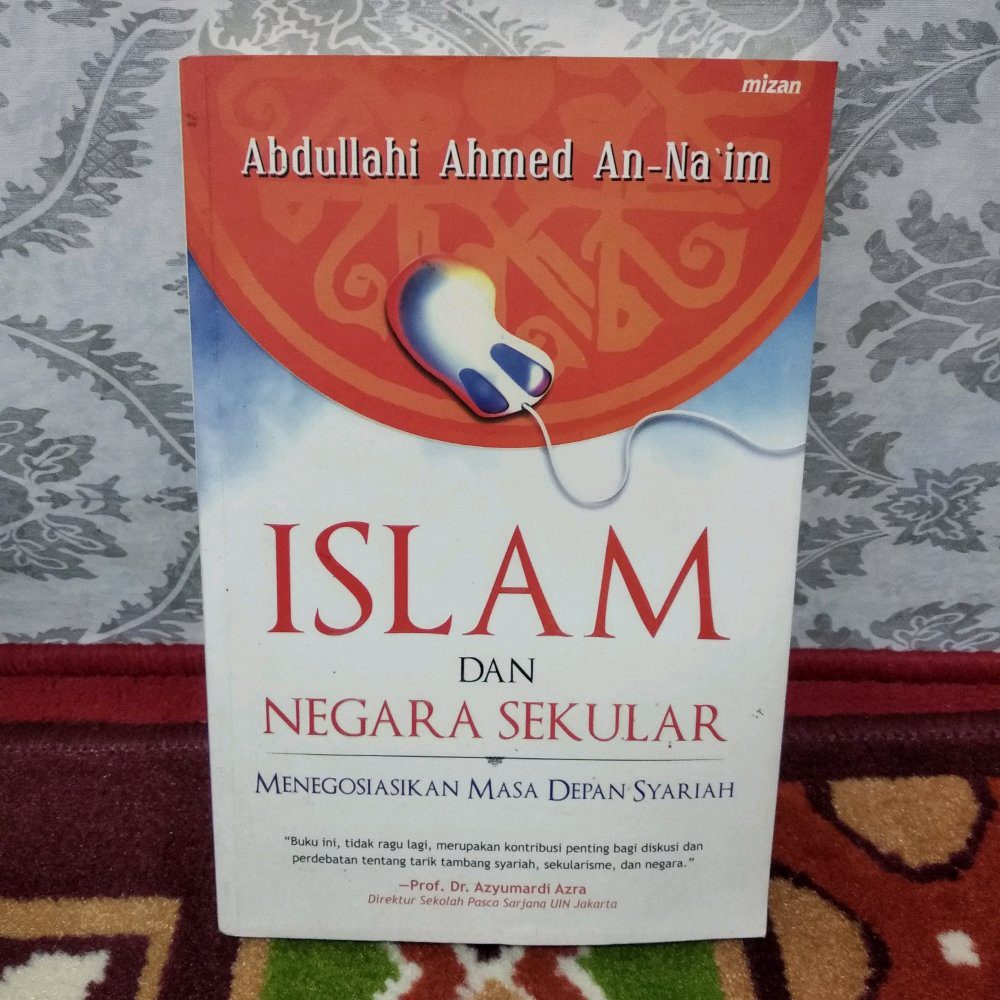Oleh: Muhamad Rofiq*
Ketegangan dan tarik ulur mengenai paham sekulerisme di dunia Islam sampai hari ini masih menjadi topik yang terus didiskusikan oleh para sarjana muslim. Banyak gagasan, baik yang pro maupun yang kontra, tentang paham ini telah digulirkan. Di antara intelektual muslim yang secara percaya diri menunjukkan dukungan kepada paham pemisahan agama dan institusi negara adalah Abdullah Ahmad an-Naim, seorang professor ahli hukum kelahiran Sudan yang saat ini mengajar di Universitas Emory, Georgia, Amerika Serikat.
An-Naim menempuh pendidikan di bidang hukum di Universitas Khurtum Sudan, Universitas Edinburgh dan Universitas Cambridge di United Kingdom. Gagasannya tentang sekulerisme ia tuliskan dalam bukunya yang berjudul Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari‘a yang juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
Argumen an-Naim: Civic Reason
Pikiran pokok An-Naim dalam bukunya tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. An-Naim berargumen bahwa sebuah negara tidak boleh bercorak relijius (a state can never be a religious). Negara manapun, termasuk negara mayoritas muslim, harus menjadi sekuler. An-Naim mendefinisikan negara sekuler sebagai negara yang mengambil posisi netral terhadap doktrin agama dan persoalan keagamaan secara umum.
Semua nilai-nilai normatif yang berbasiskan agama harus dikeluarkan (excluded) dari ruang publik. Wacana yang boleh masuk ke dalam ruang umum milik bersama dan kemudian menjadi hukum publik (public law) adalah wacana non-agama. An-Naim menyebutnya sebagai civic reason (nalar sipil).
Dalam konsep kewarganegaraan (citizenship) dalam sistem demokrasi, untuk memastikan kesetaraan posisi seluruh warga negara, kata an-Naim, semua diskursus berbau agama harus tetap berada di luar ruang publik. Dengan kata lain, ruang publik harus seinklusif mungkin dan dapat diakses oleh seluruh elemen bangsa.
Penggunaan istilah agama tertentu di ruang publik hanya akan mengakibatkan terjadinya dominasi agama, khususnya agama mayoritas terhadap agama minoritas. Keberadaan agama di ruang publik pada akhirnya dapat menegasikan eksistensi pemeluk agama minoritas di negara tersebut.
An-Naim kemudian beranjak pada diskusi tentang posisi Syariah di negara mayoritas muslim. Menurut an-Naim, negara muslim tidak bisa mengelak dari tuntutan logika demokrasi dan sistem kewarganegaran modern. Naim menyebutnya sebagai “the Islamic desirability of a secular state”.
Negara muslim, jika ingin konsekwen dengan sistem yang telah mereka pilih, harus menjadi sekuler dan menghindarkan diri dari penerapan Syariah oleh institusi negara. Menghindar dari penerapan Syariah secara institusional, menurut a-Naim, selain konsisten dengan sistem demokrasi, juga lebih sesuai dengan karakter Syariah itu sendiri.
Sifat dasar syariah adalah multitafsir. Hal ini secara kasat mata bisa dilihat dari kemunculan beragam mazhab fikih dalam sejarah Islam. Penerapan Syariah oleh negara justru hanya akan mempersempit pluralitas Syariah. Negara harus mengambil posisi interpretasi tertentu dan kemudian memaksakannya kepada warganya. Interpretasi yang lain menjadi tidak sah. Ini sesuai dengan karakter negara modern itu sendiri yang bersifat hirarkikal, sentralistik, absolutis dan birokratis.
Selain itu, Syariah juga memiliki sifat indeterminacy (ketidak-kakuan) yang tidak sejalan dengan sifat dasar negara yang mengharuskan adanya uniformity (keseragaman). Naim berpendapat sistem sentralistik yang memaksakan interpretasi seperti ini tidak memiliki presedennya dalam sejarah Islam. Penerapan syariah oleh negara adalah praktek modern yang muncul setelah lahirnya konsep negara bangsa (nation-state).
Namun demikiran, terlepas dari idenya tentang negara sekuler dan syariah yang tidak perlu diterapkan negara, an-Naim menolak untuk mengatakan bahwa Syariah tidak penting. Syariah penting tapi penerapannya ada pada level praktek dan keyakinan individual. Syariah yang ingin diterapkan di ruang publik, harus diobyektifikasikan atau diformulasikan dalam bahasa yang netral, dan melalui proses legislasi yang melibatkan institusi demokrasi modern yang terlepas dari nilai-nilai agama tertentu.
Kritik Khaled terhadap An-Naim
Pandangan An-Naim sebagaimana disebutkan di atas telah banyak didiskusikan dan dikritisi oleh para intelektual muslim. Tariq Ramadan, pemikir muslim terkemuka dari Swiss, misalnya pernah berdebat secara langsung dengan an-Naim di sebuah channel youtube. Tariq juga menulis artikel menanggapi ide negara sekuler an-Naim. Kritik lain pernah ditulis oleh Mohammad Fadel, professor hukum Islam dari Universitas Toronto. Talal Asad, antropolog paling serius yang menekuni topik sekulerisme, juga pernah menyampaikan kritik langsung kepada an-Naim dalam sebuah dialog di Universitas Berkeley.
Bagi pembaca yang ingin melihat bagaimana argumen an-Naim didiskusikan oleh para intelektual tersebut, saya melampirkan tautan di ujung tulisan ini. Pada esai ini saya akan fokus mendeskripsikan kritik yang disampaikan oleh Khaled Abou el-Fadel, professor hukum Islam di Universitas California Los Angeles. Saya memilih Khaled dengan pertimbangan karena ia memiliki kesamaan latar belakang keilmuan (bidang hukum) dengan an-Naim.
Secara umum dapat dikatakan bahwa Khaled menolak perlunya sekulerisasi di dunia Islam. Hanya saja Khaled tidak seratus persen berbeda pendapat dengan An-Naim. Khaled bahkan dapat disebut berada dalam satu tipologi dengan-Naim dalam hal perlunya menjaga epistemologi hukum Islam yang bersifat plural dan indeterminate (tidak kaku).
Khaled juga sepakat dengan penolakan peran koersif negara dalam pelaksanaan hukum Islam. Apa yang ditolak oleh Khaled adalah gagasan negara sekuler dan perlunya menjauhkan agama dari ruang publik. Khaled tidak setuju jika agama hanya ditempatkan pada aras individu tanpa memiliki peran sedikitpun di ruang publik.
Secara konseptual, kata Khaled, sekulerisme sendiri ada dua macam. Pertama, konsep yang diajukan oleh Jean Jacques Rousseau yang menjadi inspirasi model sekulerisme di Perancis hari ini. Dalam konsep ini, agama didefinisikan, dikontrol, dan diatur oleh negara. Hanya agama dalam pandangan negaralah yang bisa diterima di ruang publik. Model seperti ini belakangan di Perancis disebut lacite.
Kedua, konsep yang diajukan oleh John Stuart Mill yang hari ini diterapkan di negara Amerika Serikat. Institusi negara menjaga netralitas atau jarak yang sama kepada semua agama. Negara tidak boleh mencampuri urusan agama, tapi memberikan kebebasan seluas-luasnya tanpa intervernsi.
Konsep sekulerisasi yang diajukan oleh An-Naim mungkin mengacu kepada praktek yang diterapkan di Amerika. Namun demikian, menurut Khaled, menganjurkan sekulerisasi dalam bentuk apapun hanya akan membawa banyak harm (kerusakan) dan menimbulkan turmoil (kekacauaan) daripada manfaat jika diterapkan di dunia Islam. Implikasi gagasan an-Naim sangat monumental dan penuh resiko.
Jalan Sejarah yang Berbeda
Di antara implikasi dari sekulerisasi, menurut Khaled, adalah hilangnya nilai moral dan nilai etis berbasis agama dari ruang publik. Apapun yang berbau agama akan lenyap. Dengan logika ini maka secara praktis tidak akan ada pengajaran agama di sekolah, tidak boleh ada siaran-siaran agama di televisi dan radio dan banyak konsekwensi lainnya.
Tidak hanya itu, hal-hal yang dianggap sebagai tindakan buruk, seperti penggunaan obat-obatan terlarang, prostitusi, pembunuhan, pornografi harus diartikulasikan dalam bahasa dan penalaran non-agama. Ini sama seperti mengatakan bahwa perbuatan itu terlarang, tapi bukan karena agama melarangnya, tapi karena publik menyepakatinya sebagai sesuatu yang berbahaya bagi orang banyak. Jika tidak merugikan publik, sekalipun dilarang agama, ia tetap bisa dilakukan. Ini berarti melahirkan cara pandang dualistik dan dikotomistik dalam pikiran manusia.
Bagi Khaled, konsep sekulerisasi an-Naim sama sekali tidak tepat untuk diterapkan di dunia Islam. Hukum Islam telah menjadi nilai dan kesadaran kolektif yang mengakar di tengah masyarakat. Menawarkan gagasan sekulerisasi sama saja dengan mengosongkan nilai di tengah masyarakat. Sama artinya membentuk masyarakat tanpa nilai atau membentuk masyarakat dengan nilai yang baru akan disusun dari nol.
Menurut Khaled, konsep sekulerisasi an-Naim hanya bisa diterima oleh muslim yang tinggal sebagai minoritas di negara-negara Barat yang menganut sistem demokrasi liberal. Karena sistem seperti itu sudah taken for granted (sistem yang sudah jadi) dan sudah diaplikasikan. Khaled menyayangkan an-Naim mentransplantasi secara mentah-mentah ideologi sekulerisme demokrasi liberal Barat yang memiliki sejarah politik dan kultur hukum yang berbeda dengan negara muslim. Khaled juga mengkritik an-Naim yang tidak menjadikan tradisi Islam (turas) sebagai titik pijak untuk formulasi setiap gagasannya.
An-Naim, kata Khaled, semestinya menyadari bahwa sekulerisme adalah produk spesifik barat yang tidak transferable ke dunia Islam. Di Barat, paham sekulerisme tumbuh secara organik melalui tahapan sejarah yang bersifat natural: reformasi gereja, perang Katolik-Protestan, zaman pencerahan, dan modernisasi.
Dunia Islam memiliki trajektori sejarah yang berbeda. Umat Islam mengalami fase peralihan ke zaman modern melalui pintu gerbang kolonialisasi yang menyisakan trauma dalam ingatan mereka. Pasca kolonialisasi, umat Islam juga mengalami fase dictatorship.
Di sebagian besar negara muslim, fase ini belum berakhir dan bahkan tampaknya belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Mengajukan gagasan sekulerisasi bukan saja akan mencerabut umat Islam dari tradisi intelektualnya (turas) yang sudah berusia belasan abad, tapi juga melahirkan persoalan turunan yang lebih kompleks.
Khaled menyebut kasus di Mesir. Pasca lengsernya Husni Mubarak selama the Arab Spring (Musim Semi Arab), publik di Mesir berdebat keras tentang bentuk negara. Intelektual sekuler liberal Mesir mengajukan gagasan sekulerisasi. Mereka mengusulkan agar penggunaan simbol-simbol Islami selama masa kampanye tidak diperkenankan.
Sebagian sekuleris lain yang lebih ekstrim bahkan menyatakan bahwa kalimat “Assalamualaikum” tidak perlu diucapkan lagi di kegiatan publik yang bersifat non-keagamaan. Pada kenyataannya, ide ini justru kontraproduktif dan memecah belah masyarakat Mesir. Akhirnya revolusi yang berhasil menumbangkan rezim diktator harus berakhir tragis. Karena negara tidak dicapai kohesi ideologis antar anak bangsa. Mesir harus mengalami set back dengan kembalinya rezim militer yang bertindak jauh lebih represif dan brutal dari rezim sebelumnya.
Puritanisme Relijius
Implikasi lain dari gagasan sekulerisasi menurut Khaled adalah lahirnya reaksi ekstrim dari sebagian umat Islam yang tidak setuju. Dengan kata lain, diskursus sekulerisasi justru menciptakan polarisasi baru di tengah masyarakat muslim. Gagasan an-Naim ini, Khaled menyebutnya sebagai sekulerisme puritan, akan memicu reaksi tidak kenal kompromi dari kelompok yang disebut Khaled sebagai “relijius puritan”. Jadi pandangan ekstrim hanya akan memicu lahirnya pandangan ekstrim lainnya yang sama-sama negatif.
Khaled mengatakan bahwa sekuleris puritan dan relijius puritan memiliki persamaan dan perbedaan sekaligus. Persamaannya adalah keduanya melakukan esensialisasi dan simplifikasi terhadap tradisi Islam (turas). Dengan kata lain, kedua kelompok ini memahami syariah secara artifisial. Perbedaannya adalah jika kelompok pertama memarjinalisasi Syariah dari ruang publik dan mengurungnya dalam ruang individu, kelompok kedua justru mengabaikan peran syariah pada dimensi individu. Perhatian mereka diberikan sepenuhnya pada aspek publik.
Maka jika sekuleris puritan membatasi syariah pada aspek kesalehan personal, dan menghapus peran syariah dalam mempengaruhi norma dan nilai moral di ruang publik, kelompok relijius puritan justru sebaliknya: beranggapan bahwa individu sangat potensial terjebak pada hawa nafsu, sehingga kontrol negara harus diperkuat. Bagi kelompok kedua ini, peran negara harus bersifat total pada setiap individu.
Walhasil, kita akhirnya hanya dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak ideal: melakukan sekulerisasi dengan menghilangkan peran syariah di ruang publik atau menerima hegemoni negara dan membiarkan lemahnya masyarakat sipil.
Mengenai alasan sekulerisasi untuk menjaga watak hukum Islam yang bersifat plural dan indeterminate (tidak kaku), Khaled juga mengajukan keberatan. Menjaga ‘orisinalitas’ hukum Islam menurutnya bukan dengan menolak peran moral dan etiknya di ruang publik, tapi dengan meminimalisir peran negara yang berpotensi merusak hukum Islam. Dalam tulisannya yang lain, ia menyebut contoh praktek kodifikasi hukum sebagai bentuk peran negara yang bisa mendekonstruksi epistemologi dan institusi syariah. Sementara nilai-nilai agama yang bersifat etis tetap harus dipertahankan berada di ruang publik.
Menutup kritiknya terhadap an-Naim, Khaled mengatakan bahwa melakukan sekulerisasi dengan membatasi ruang gerak Syariah pada ranah individu sama saja artinya menolak potensi moral yang ada di dalam Syariah itu sendiri. Padahal potensi ini jika dipahami dengan sebaik-baiknya justru akan menjadi kekuatan moral yang kuat (powerful moral force) bagi umat Islam yang sedang melakukan pencarian jati diri di zaman posmodernisme ini.
* Penulis adalah Alumni PCIM Mesir dan Anggota PCIM Amerika Serikat
Lampiran:
- Dialog antara Talal Asad dan Abdullah Ahmad an-Naim (https://www.youtube.com/watch?v=TiTaE863jBI)
- Dialog antara Tariq Ramadan dan Abdullah Ahmad an-Naim: (https://www.youtube.com/watch?v=TiTaE863jBI)
- Review Buku Abdullah an-Naim oleh Mohammed Fadel: (https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-law-and-religion/article/islamic-politics-and-secular-politics-can-they-coexist/70FB8345D463B8FD73F7B58EA666889A