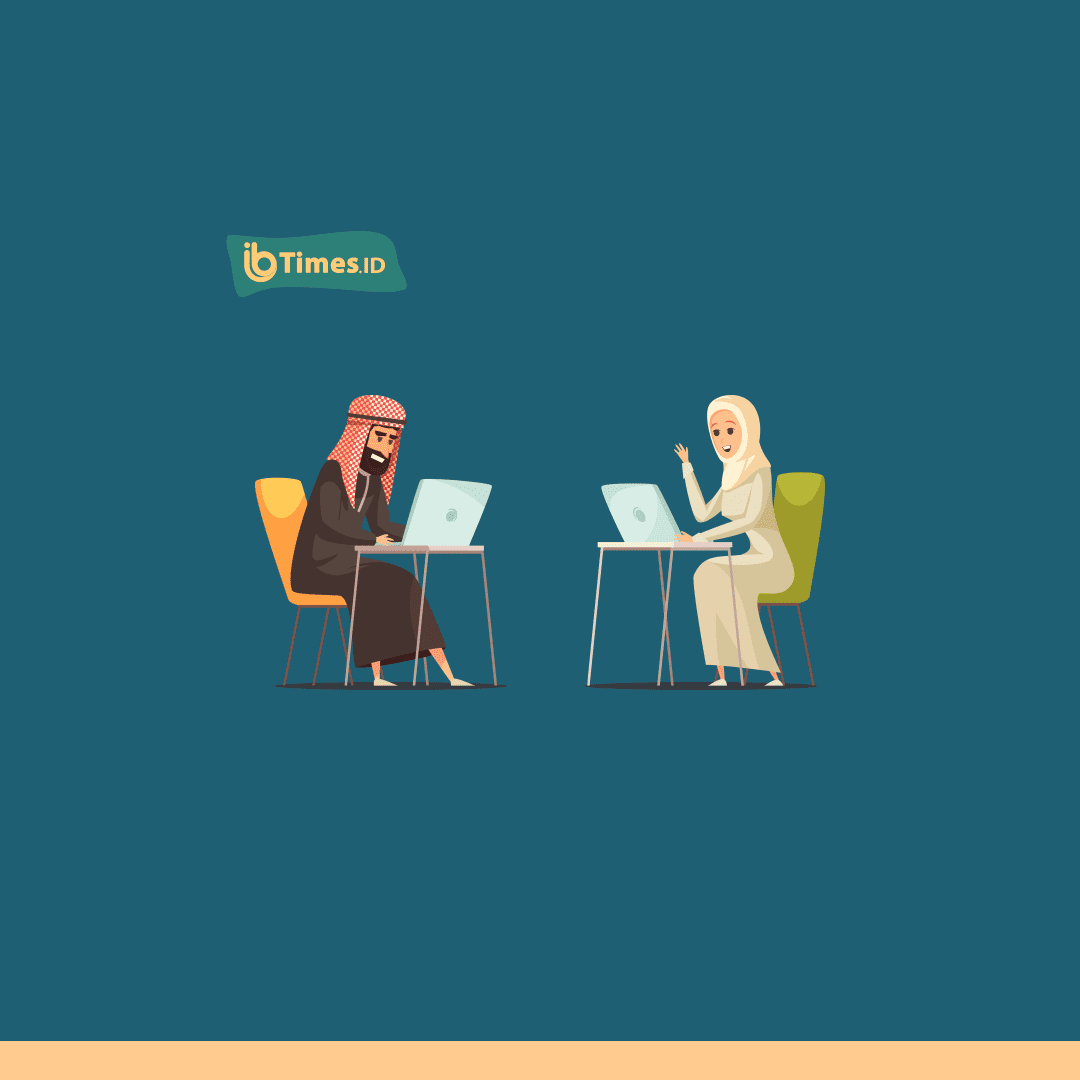Perkembangan teknologi informasi pada saat ini telah berlangsung demikian cepat dan merubah banyak aspek kehidupan dan interaksi manusia sehari-hari. Salah satu produk utama dari perkembangan teknologi informasi adalah munculnya Internet. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh “We Are Social” pada tahun 2021, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk pengakses internet terbanyak di dunia. Dari total 274,9 juta penduduk Indonesia, sebanyak 73,7% adalah pengguna aktif internet.
Data tersebut menunjukkan tingginya penetrasi internet dan bagaimana ia telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat saat ini. Dengan internet, orang-orang dapat saling terhubung serta mengakses informasi dengan cepat tentang berbagai hal, mulai dari pendidikan, hiburan, olahraga, ataupun berita. Bahkan kegiatan pembelajaran dan pengkajian agama pun saat ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh internet.
Dengan munculnya berbagai platform media sosial, terdapat pergeseran pola konsumsi materi keagamaan yang dapat kita temui dalam masyarakat kita saat ini.
Almarhum Prof. Kuntowijoyo dahulu pernah mempopulerkan istilah dalam bukunya, “muslim tanpa masjid”. Yaitu sekelompok muslim yang mempelajari agama tidak dengan cara-cara konvensional dengan datang ke masjid, mengadakan ta’lim di pesantren, dan bertemu dengan ustadz dan kyai untuk mendapatkan ilmu. Tapi dengan mendengarkan kaset rekaman, televisi, atau radio yang berisi materi-materi keagamaan. Metode-metode ini populer digunakan pada periode tahun 90-an hingga 2000-an akhir. Fenomena ini merupakan sebuah interaksi yang unik dan timbul sebagai respon terhadap perkembangan teknologi saat itu.
Dalam perkembangannya, platform tersebut kini semakin berkembang menjadi semakin beragam dengan munculnya YouTube, Instagram, ataupun aplikasi web conference semacam Zoom. Perkembangan teknologi ini menyebabkan terjadinya pergeseran makna “masjid” yang lazimnya kita kenal secara fisik dengan berbagai bangunan dan ruangnya menjadi “masjid” secara virtual atau digital.
Pola konsumsi keagamaan seperti ini umumnya lebih banyak kita temukan di kalangan generasi muda, terkhusus mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Mulai dari anak sekolah, kuliah, hingga orang-orang yang telah bekerja. Hal ini kemudian berpengaruh dalam membentuk identitas dan pemahaman muslim generasi kita saat ini.
Gejala Neo Sufisme
Gejala ini telah dimulai sejak tahun 1980 hingga 2000-an awal dengan munculnya gerakan “New Age” di negara Amerika serta kawasan negara-negara eropa. Munculnya kelompok-kelompok ini juga dicatat dan diklasifikasikan oleh Prof. Fazlur Rahman sebagai kelompok Neo-Sufisme. Yang mayoritas gerakannya berada di daerah perkotaan.
Di Indonesia sendiri, neo sufisme atau besarnya ekspresi keagamaan di ruang publik yang kita saksikan saat ini sedikit banyak dipengaruhi latar sosial pada saat masa orde baru. Dalam Intelegensia Muslim & Kuasa (2006), Yudi Latif menjelaskan bagaimana pembatasan ekspresi politik keislaman dalam ruang publik pada saat itu menyebabkan terjadinya peralihan aktivisme dalam bidang politik kepada bidang pendidikan.
Hal ini kemudian menjadi latar belakang munculnya berbagai macam lembaga keislaman dalam institusi pendidikan di sekolah, kampus, dan lainnya. Semangat yang mengalami represi ini kemudian meluap keluar, ketika reformasi bergulir. Dengan akses dan partisipasi politik yang lebih terbuka dan akomodatif terhadap ekspresi keislaman dari periode sebelumnya.
Di kalangan muslim perkotaan kita dapat melihat bahwa gairah dan semangat untuk mempelajari agama sangat tinggi. Fenomena ini muncul sebagai respon masyarakat kota terhadap arus modernisasi yang membuat hidup menjadi serba cepat dan tidak pasti. Akibatnya, orang-orang modern saat ini mengalami kekosongan dan kehampaan. Mereka kemudian mencoba menemukan dan mengisi kekosongan itu dengan berpaling kepada agama dan spiritualitas, terutama ajaran-ajaran yang berasal dari belahan bumi bagian timur.
Inilah kemudian yang menjelaskan mengapa segmentasi dan penetrasi konten keagamaan itu lebih banyak di kalangan generasi muda dan muslim perkotaan sehingga memunculkan gejala neo sufisme. Pertama, karena mereka cenderung lebih banyak mengalami kegelisahan spiritual yang telah dijelaskan di atas. Kedua, karena secara demografi, pengguna media sosial saat ini didominasi oleh kelompok ini. Dalam bahasa yang lebih populer, kita mungkin lebih familiar menyebut kelompok ini sebagai kelompok “hijrah”. Yang merupakan hasil produk dari pertemuan antara dakwah dan perkembangan teknologi informasi.
Salah satu dampak positif yang muncul dengan hadirnya media sosial adalah memberikan akses yang mudah dan cepat untuk orang dalam mempelajari materi agama. Bagi orang yang tidak memiliki waktu banyak untuk belajar agama secara formal serta tidak memiliki latar belakang pendidikan agama sebelumnya, cara ini merupakan salah satu metode yang praktis dan terjangkau untuk tetap dapat meningkatkan pemahaman agama di tengah kesibukan yang padat.
Efek Negatif Media Sosial
Namun di satu sisi, pembelajaran agama melalui media sosial juga menimbulkan efek-efek negatif dengan munculnya polarisasi serta pemahaman agama yang parsial dan terkotak-kotak. Yang seringkali menimbulkan konflik akibat masing-masing kelompok yang saling mengklaim kebenarannya masing-masing.
Munculnya konten keagamaan di media sosial menjadikan masyarakat mengalami divergensi dan konvergensi secara bersamaan. Konten-konten agama yang beragam menawarkan keragaman dan keluwesan pandangan dan pemahaman sekaligus membuat penyempitan dengan adanya pemutlakan terhadap pemahaman agama tertentu.
Hal ini semakin diperparah dengan mekanisme algoritma media sosial yang menyediakan konten-konten sesuai dengan preferensi dan kesukaan masing-masing penggunanya. Dalam kajian media, gejala ini disebut sebagai efek echo chamber, dimana orang hanya mengkonsumsi informasi yang ia percayai saja dan menyebabkan informasi lain yang bertentangan dengan pendapatnya ditolak.
Munculnya permasalahan intoleransi, ekstremisme, fundamentalisme, radikalisme, maupun politik identitas yang sekarang marak terjadi seringkali disebabkan dari pemahaman agama secara sepotong-sepotong dari media sosial seperti ini. Kecenderungan orang dalam mengkonsumsi materi agama yang serba cepat, praktis, dan vonis benar-salah secara hitam-putih dalam pengambilan kesimpulan, seringkali menyebabkan kedangkalan dan pengabaian atas keragaman pendapat dalam agama.
Adanya media sosial juga membuat terkikisnya peran-peran tokoh agama yang otoritatif. Kita sekarang melihat kasus dimana tokoh agama yang memiliki sanad dan kompetensi keilmuan yang mumpuni dengan mudah dibantah atau didebat oleh orang-orang yang baru belajar agama sebentar dengan bermodalkan video-video materi dan tulisan singkat yang banyak bertebaran di internet.
Semua orang merasa dapat berbicara dan berkomentar tentang agama. Di era media sosial saat ini, popularitas dan pengikut seringkali lebih digunakan sebagai standar kebenaran daripada validitas dan kompetensi keilmuan seseorang. Kita kehilangan kedalaman ajaran demi mengejar kecepatan pemahaman.
Berangkat dari fenomena di atas, bilamana Tom Nichols dalam bukunya menyebut hadirnya media sosial sebagai penyebab matinya pakar-pakar ilmuwan dan akademisi (2019). Apakah dalam konteks bidang agama, hadirnya media sosial juga menjadi pertanda matinya para ustadz, kyai, dan syaikh di masa depan? Atau bisa jadi ke depan akan semakin terjadi pergeseran dimana Instagram & YouTube akan semakin mapan sebagai masjid-masjid dan kiblat agama kita bergeser dari kyai dan ustadz ke kalangan selebgram & influencer?
Editor: Yusuf