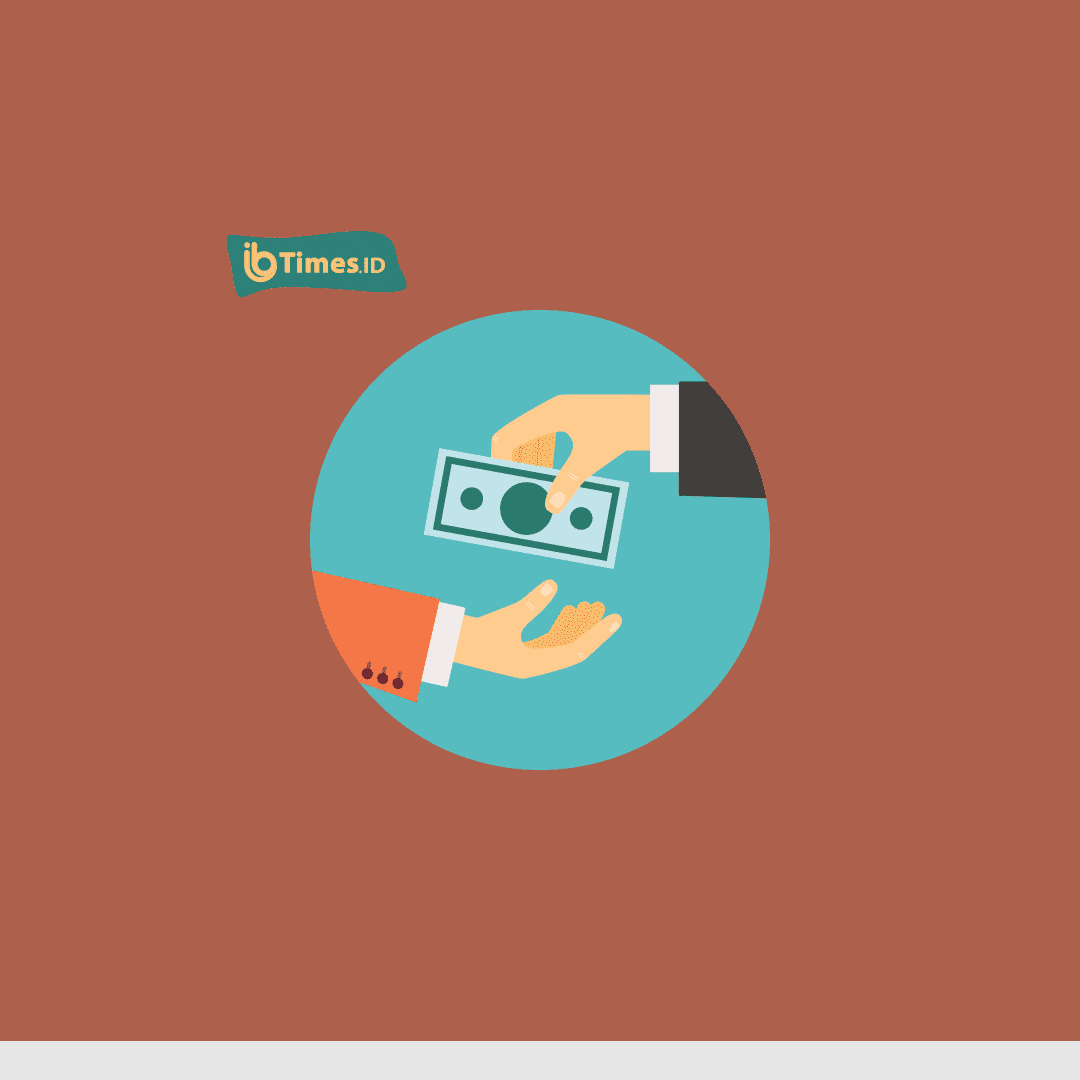Korupsi yang tumbuh di masyarakat yang dikenal religius memang menjadi paradoks. Di masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai agama, mestinya kejujuran, integritas, dan etika kerja yang baik dijunjung tinggi. Namun, korupsi tetap bisa terjadi bahkan di kalangan yang religius.
Beberapa koruptor di Indonesia bahkan bergelar kiyai, lora, ustadz, doktor, profesor. Juga beragam profesi bergengsi. Kenapa orang yang tampak religius bisa korupsi, mungkin kita bisa membedah beberapa fakta sosial.
Banyak individu yang menjalankan ritual keagamaan, tetapi tidak sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin beribadah secara teratur, tetapi memisahkan etika agama dari praktik bisnis atau pekerjaan. Ibadah urusan sendiri, korupsi kepentingan sendiri.
Beberapa orang bisa tergoda untuk mencari pembenaran atas tindakan korupsi mereka, misalnya dengan alasan “demi keluarga,” “demi kelangsungan organisasi” , ”demi membesarkan dan biaya partai”, atau bahkan “demi kebaikan bersama”, dan alasan lain sebagai pembenar. Semakin intelek semakin pintar membangun narasi alibi. Rasionalisasi ini memungkinkan mereka merasa tetap baik secara moral, meskipun melakukan korupsi.
Di masyarakat religius, keluarga dan komunitas sering memiliki harapan besar terhadap individu untuk tampil sukses secara finansial dan sosial. Tekanan ini kadang mendorong orang untuk menghalalkan segala cara agar memenuhi ekspektasi tersebut, meski dengan melanggar nilai kejujuran.
Bahkan ada tokoh agama yang membenarkan money politik hanya karena kadernya maju sebagai calon legislatif ataupun eksekutif. Keberadaan kader ormas pada jabatan-jabatan tertentu dianggap sebagai kemenangan dan dominasi eksistensi meskipun menghalalkan segala cara. Kader politik adalah mesin uang dan kekuasaan yang membanggakan.
Di beberapa masyarakat religius, terutama yang memiliki nilai-nilai kekeluargaan atau kolektifitas yang kuat, balas budi dan loyalitas terhadap kerabat bisa melampaui etika dan aturan formal. Budaya seperti ini bisa menjadi pintu masuk bagi korupsi, misalnya dengan memberikan jabatan atau kemudahan kepada orang yang punya hubungan dekat. Nepotisme adalah sisi mata uang korupsi yang cukup mengakar. Jika seorang kader menduduki jabatan tinggi, maka sebuah instansi menjadi sarang gerbong kelompoknya.
Tidak jarang posisi ini menjadi pintu terbuka bagi tindak korupsi. Tragisnya kader yang dibanggakan karena menjadi mesin uang dan kekuasaan bagi ormas, ketika terbukti korupsi maka dibuang ramai-ramai. Menyumbang uang kader disayang, tak ada manfaat kader dibuang.
Tidak jarang pula praktik keagamaan lebih ditekankan secara ritual tanpa penanaman nilai-nilai etis yang mendalam. Padahal, banyak ajaran agama yang secara jelas menentang perilaku koruptif, tapi ajaran ini sering tidak menjadi fokus pendidikan agama. Ajaran etika dan moral kalah oleh dzikir dan do’a yang terkadang juga menjadi alat politik.
Ketika lingkungan atau komunitas secara umum sudah terbiasa dengan tindakan korupsi kecil seperti “uang pelicin” atau suap, perilaku ini menjadi dianggap normal. Bahkan, ada pemahaman bahwa tidak melakukan praktik ini justru bisa merugikan, dan ini memengaruhi mentalitas bahkan di masyarakat religius.
Korupsi pada masyarakat religius menunjukkan bahwa religiusitas harus diperdalam agar lebih menyentuh sisi moral dan etika pribadi. Perbaikan mentalitas ini membutuhkan kesadaran kolektif serta pengaruh positif dari pemuka agama, tokoh masyarakat, dan lingkungan.
Pendekatan normatif sosiologis agama berupaya menggunakan kekuatan nilai, norma, dan komunitas agama untuk mencegah dan memerangi korupsi. Nilai agama tidak hanya menjadi acuan pribadi, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang membentuk perilaku masyarakat dalam menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
Korupsi pada dasarnya merupakan hasil dari kombinasi faktor-faktor pribadi, sosial, dan struktural. Perilaku ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya hukum, tetapi juga karena adanya kelemahan dalam pengawasan sosial, lemahnya integritas individu, serta struktur kekuasaan yang tidak seimbang dan tentu saja religiusitas palsu.
Membasmi korupsi tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan mendasar pada budaya, pendidikan agama yang benar, sistem sosial yang sehat, dan pengawasan kekuasaan yang seimbang.
Bagi masyarakat religius, mestinya nilai-nilai agama menjadi ruh pada setiap tindakan yang pada gilirannya membangun mentalitas spiritual al khauf wa raja. Sederhananya, takut neraka dan berharap surga. Jika neraka tidak ditakuti, dan surga tidak menarik hati, maka jangan harap korupsi bisa dibasmi.
Editor: Soleh