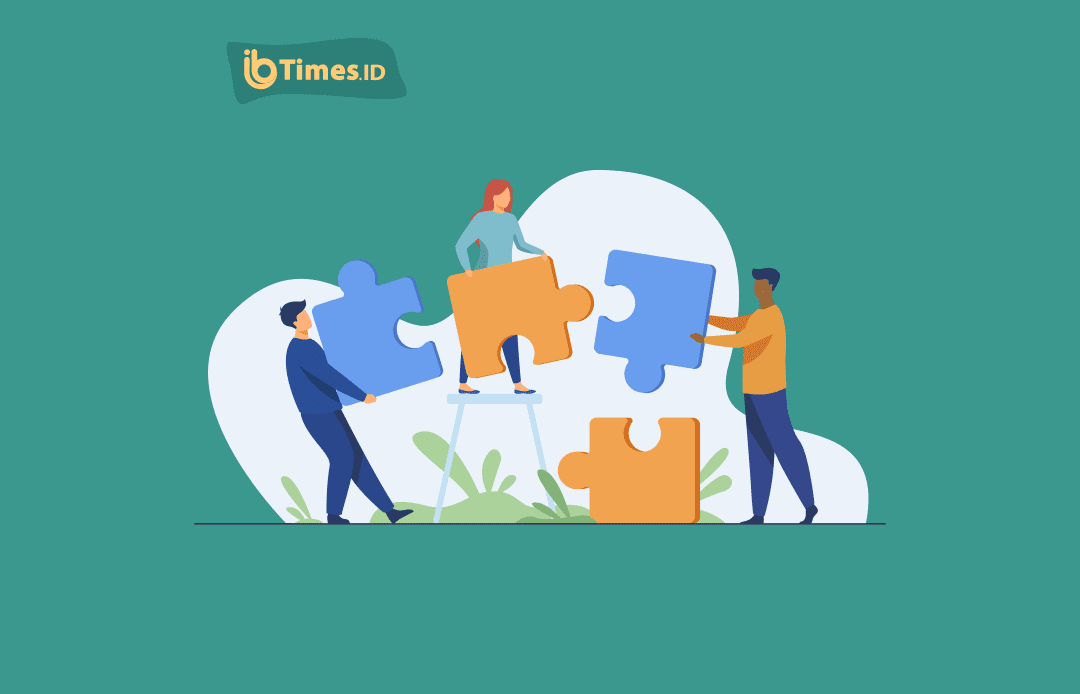Banyak yang gagal melihat peran guru dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Biasanya ketimbang guru, dalam benak kita akan mengingat tokoh-tokoh yang bergerilya di hutan sembari mengangkat senjata. Seolah perjuangan kemerdekaan hanya berada di medan perang.
Mungkin memang sudah budaya kita. Bukankah kita sendiri yang mengatakan bahwa ‘Guru adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’. Kira-kira mengapa sebabnya? Sebabnya adalah kita enggan melihat pendidikan sebagai kerja-kerja kemanusiaan yang vital.
Bahwa, pendidikan hanyalah tempat singgah anak setelah rumah, ketimbang ruang tumbuh-kembang bagi jiwa mereka.
Padahal, kelas merupakan arena yang tidak kalah penting untuk dimenangkan. Malah justru, di situ pertarungan ideologi yang menentukan kesadaran kebangsaan dapat terlahir. Kelas adalah ruang di mana seseorang belajar banyak hal penting mengenai arti kebebasan, kesetaraan, dan martabat diri.
Paulo Freire, sang mahaguru pedagogi kritis dari Brazil, barangkali adalah yang pertama dan paling lantang menunjukkan hal itu. Baginya, pendidikan tidak pernah bebas nilai. Ia selalu mengandung di antara dua sisi: humanisasi atau dominasi. Pendidikan kolonial sudah pasti menginginkan yang terakhir.
Pakar sejarah sendiri sering tenggelam dalam bias itu. Pendidikan lebih dilihat sebagai wilayah periferal. Kemerdekaan, bagi mereka, merupakan buah kerja keras para jenderal tempur dan diplomat ulung. Padahal darimana ide tentang merdeka itu hadir bila bukan dari kelas tempat jiwa-jiwa merdeka dihargai suaranya?
Formasi Kesadaran Kritis Guru
Agus Suwignyo, berargumen bahwa kesadaran guru mengenai realitas sosial yang menindas dan perlunya aksi kritis untuk mengatasinya telah muncul jauh sebelum mereka berprofesi. Kesadaran ini bahkan telah lahir ketika guru masih belia; ketika terbentur kenyataan bahwa kehidupan di tanah jajahan adalah kehidupan buangan.
Kehidupan yang penuh dengan penyesuaian terhadap ketimpangan sistematis atas dasar ras. Sementara jauh dalam lubuk hati mereka sadar bahwa mereka tidak jauh berbeda dengan Belanda. Ini hanya soal pecundang dan pemenang dalam sebuah perang, bukan karakteristik permanen yang melekat di dalam darah mereka.
Lagi-lagi, menurut Freire, hanya mereka yang ditindas yang benar-benar dapat terlahir sebagai pembebas bagi diri mereka yang tertindas. Mengapa tidak? Karena merekalah yang mengerti perihnya ketertindasan.
Mereka ini malam-malamnya diisi dengan menahan lapar, dingin dan sakit sembari memimpikan hari esok yang lebih baik. Demikian halnya para guru Indonesia di masa kolonial.
Guru-guru itu kebanyakan berasal dari golongan miskin. Dalam benak mereka, guru adalah profesi yang dapat menjanjikan perubahan nasib. Sekalipun prestise guru tidak setinggi dokter dan insinyur, namun menjadi guru adalah pilihan karir terbaik di samping profesi warga bumiputera lain.
Kesadaran kritis mereka segera tumbuh lebih tajam di hadapan realitas pendidikan. Mereka mengerti bahwa sistem pendidikan Belanda yang diskriminatif menempatkan mereka di sekolah-sekolah yang minim kualitas. Fasilitas yang mereka dapatkan seadanya, dan mereka harus membayar mahal dengan segala keterbatasan.
Sekolah itu juga menjadi tempat pertama kali mereka menyadari bahwa Belanda tidak sedang mendidik, namun mencuci otak mereka. Belanda berusaha membunuh ‘diri budaya’ mereka sembari melahirkan manusia baru yang ‘kebelanda-belandaan’. Menciptakan kompeni berkulit sawo matang.
Alasan Belanda sederhana: tentu selain untuk mempertahankan mental terjajah juga membangun kebencian dalam jiwa siswa atas darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Toh bagi Belanda, yang terjajah tak ada bedanya dengan suku primitif kanibal. Demikian bebal hingga tanah air mereka gadaikan dan tumpah darah bangsa mereka persembahkan demi diinjak-injak Belanda.
Guru-Guru Kritis dalam Aksi
Guru-guru paham betul bahwa bahasa memiliki kekuatan yang tak terhingga. Bahasa dapat menentukan pemenang dalam sebuah perang dan bahasa pula dapat membatalkan kemenangan itu. Pada Belanda, guru melihat bagaimana negara yang kecil nan jauh dapat menguasai Indonesia melalui muslihat kata-kata.
Dalam sebuah sidang Perikatan Perkoempoelan Goeroe Vorstenlanden (PPGV) diajukan mosi perubahan nama Sekolah Desa atau Volkschool menjadi Sekolah Rakyat. Kata mereka, terma desa memiliki makna terbelakang dan lemah. Khawatirnya cap negatif yang sama melekat pula pada guru dan siswa di sekolah-sekolah tersebut.
Pun, usulan nama Sekolah Rakyat sangat penting. Menurut para guru, Rakyat menunjukkan kesatuan seluruh masyarakat di satu sisi, berhadapan dengan pemerintah–dalam hal ini Belanda–di sisi lain. Kata rakyat menunjukkan suatu kesadaran dan aksi politik oposisional guru terhadap penjajah mereka.
Pergulatan bahasa lainnya terjadi pada 1930 kala surat kabar Persatoean Goeroe mengumumkan perubahan bahasa terbitan mereka, dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Hal ini memiliki dampak yang luar biasa karena memungkinkan semua guru dari latar belakang pendidikan apapun (baik alumni sekolah Belanda dan bukan) untuk dapat berkomunikasi melalui media itu.
***
Perlu dicatat disini bahwa Persatoean Goeroe bukan surat kabar kecil kala itu. Ia dicetak dan disebarkan kepada semua semua anggota organisasi di bawah Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB). PGHB sendiri memiliki 102 cabang dengan total 12.000 anggota didalamnya.
Pertarungan bahasa ini ternyata juga terjadi di kelas. Guru-guru menghidupkan kata ‘merdeka’ sebagai alat perjuangan. Merdeka tidak lagi hanya bermakna ‘mandiri’. Lebih dari itu: merdeka adalah tidak hidoep terperintah, berdiri tegak karena kekoeatan sendiri, dan tjakap mengatoer hidoepnya sendiri.
Puncaknya pada 1931, Oesman Idris, dalam interview oleh surat kabar Aboean Goeroe-Goeroe menyatakan secara tegas bahwa, ”Kita harus mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana menjadi tuan atas dirinya sendiri!”
Dengan pesan yang kurang lebih sama, guru lain menuliskan:
Sekarang sekolah-sekolah kita berada ditangan orang-orang asing. Namun kita guru-guru Indonesia harus yakin bahwa kita lebih mampu untuk mendidik anak-anak kita. Mari kita mendidik mereka dengan semangat Indonesia. Mari kita ajarkan seni dan sastra kita, serta kejayaan pahlawan-pahlawan seperti Diponegoro dan Teuku Oemar. Mari ajarkan anak kita lirik keindahan tanah-air kita! (Aboean 10, Tahun 11, Goeroe-Goeroe, 1931, 209-211)
Penutup
Hal paling penting yang dapat kita petik dari para guru transformatif ini adalah keyakinan, harapan dan kerja-kerja kritis yang tak pernah padam. Keyakinan memberi tenaga untuk melanjutkan pekerjaan pemerdekaan. Harapan melipur sakit, sedih dan rasa kehilangan. Lantas dari kerja nyata itu mereka mematri perubahan.
Terakhir, guru-guru itu bekerja ikhlas bagi kemanusiaan, bukan kepentingan pribadi mereka. Mereka rela tidak digaji, sementara sewaktu-waktu terancam dibui hingga dieksekusi. Namun lagi-lagi, optimisme mereka kepada bangsa tidak surut oleh kesulitan seperti apapun.
Buah dari kerja mereka sungguh luar biasa dan tidak disangka-sangka. Lima belas tahun dari sejak mimpi-mimpi itu, Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya. Lebih sulit lagi untuk mereka menyangka bahwa seorang guru di sebuah sekolah Muhammadiyah Belitung menjadi presiden pertama Republik Indonesia.