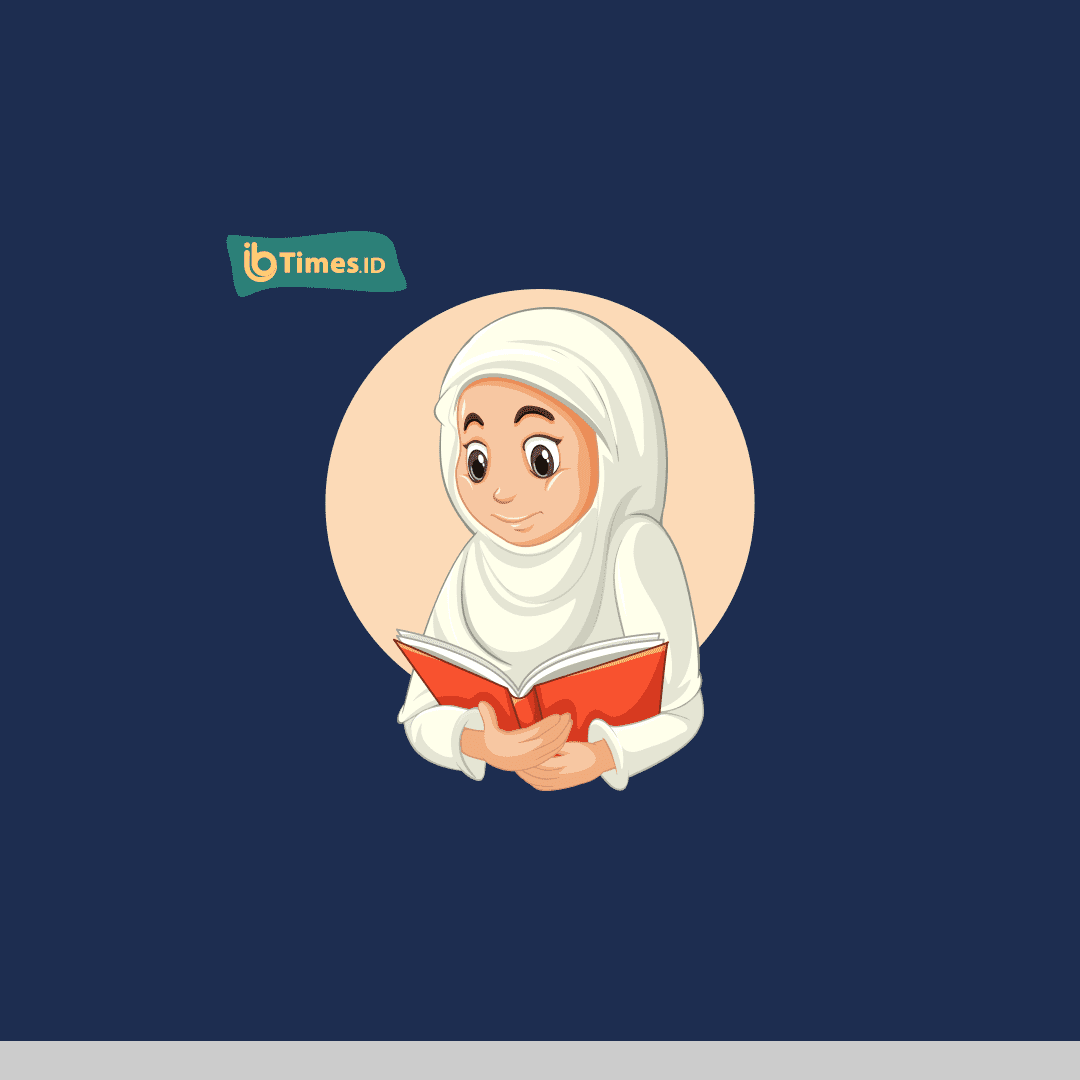Berbicara tentang perempuan, memang menjadi topik yang sangat seksi. Terutama di meja diskusi. Para aktivis yang terlibat dalam menggaungkan kesetaraan gender, ini tentu disebut sebagai kaum feminisme. Sementara itu, membahas madzhab feminisme ini sudah pasti sangat komplek.
Secara pribadi, bagaimana pun juga tidak terlalu intens terhadap konsentrasi topik yang digaungkan. Bilamana dikaji ulang, kehadiran feminisme ternyata buntut dari aksi protes terhadap eksploitasi perempuan di Barat pada akhir abad ke-18. Mereka menuntut kesetaraan gender dan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak yang seharusnya dijaga.
Kepeduliaan Islam terhadap Masalah Gender
Bukan menafikan, namun dengan hadirnya Islam kurang lebih abad ke-6, kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antar gender sudah terbangun pondasinya. Menela’ah sejarah Islam sendiri, terlihat bagaimana Islam selalu memberi jalan keluar terutama dalam masalah diskriminasi perempuan.
Selangkah demi selangkah, tentu menemukan kembali fitrahnya sebagai manusia yang setara derajatnya. Dengan jaminan bahwa Al-Quran itu shalihun likulli zaman wa makan. Tentunya ini sudah semestinya dituntut untuk menginternalisasi spirit dan nilai-nilai Al-Quran dalam segala lini kehidupan yang hakiki.
Tak hanya itu, hingga detik ini marjinalisasi perempuan kerap dipraktikkan dalam percaturan dunia kerja, pendidikan, kebebasan berbicara dan lain-lain. “Mengapa perempuan selalu salah? Mengapa tak boleh bicara? mengapa harus menjadi pihak yang harus paling ikhlas dan tak boleh melawan?” Kira-kira begitulah suara yang selalu diperjuangkan oleh salah satu tokoh feminisme di Indonesia, Kalis Mardiasih (Mardiasih, 2017).
Faktor Terbelenggunya Perempuan di Ranah Kebebasan
Agama bukan semata-mata gagal memberikan solusi. Tetapi, justru manusia-lah yang gagal memahami nilai-nilai agama secara komprehensif. Sehingga menurut Kalis, faktor yang menjadikan terbelenggunya perempuan di ranah kebebasan terbagi menjadi tiga bagian, di antaranya:
Pertama, adalah doktrin agama. Penyempitan pemahaman tentang agama ini lumayan fatal akibatnya. Refleksi yang diambil tentu mengandalkan exegenis takwa. M. Quraish Shihab menafsirkan takwa dalam tiga sifat. Yakni beriman, pengamalan syariat, dan akhlak (Shihab, 2000). Pengamalan syariat mewujud dalam kepatuhan dalam beribadah mahdhah seperti shalat guna membangun harmonisasi dengan Allah. Dan ibadah ghairu mahdhah yang mencakup segala bentuk ibadah sosial.
Sehingga, berbuat sesuatu agar bermanfaat sembari diniati ibadah kepada Allah, tentu tiada masalah bilamana sesuai dengan passion masing-masing. Seperti menjadi aktivis, menjadi pendidik, content creator, dsb. Lantas didayagunakan dengan semangat untuk selalu mewujudkan kebaikan yang mencerminkan akhlak mulia. Maka, wanita disebut shalihah, tidak sebatas dipandang pada pakaian. Namun juga banyak menebar kebaikan melalui pikiran, ucapan dan perbuatan.
Kedua, adalah kungkungan tradisi. Stereotip dari Istilah “macak, manak, masak” di Jawa dan “depor, kasor, somor” di Madura saja merupakan bukti wanita tidak merdeka dengan kehidupannya. Berbondong-bondong menginginkan sekolah tinggi, yang ada justru keburu dipatahkan oleh tradisi. Dan stereotip tersebut tak hanya terjadi pada suku Madura dan Jawa saja. Tapi berlaku juga bagi tradisi dari berbagai suku di Indonesia, bahkan dunia.
Ketiga, adalah kapitalisme. Diktum ini terwakili oleh superioritas laki-laki atas lawan jenisnya. Salah satunya adalah eksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan bisnis (yang kebanyakan dikuasai oleh laki-laki). Objektifikasi dan eksploitasi tubuhnya adalah mutlak diskriminasi. Hal ini justru dijadikan sebagai seni dan bentuk emansipasi wanita. Seakan-akan kecantikan sebatas material belaka. Ujung-ujungnya perempuan juga terjebak dalam candu perangkat kecantikan.
Sikap yang Harus Diambil untuk Kemajuan Gender “Perempuan”
Pada akhirnya, untuk maju saja, perempuan penuh dengan hal-hal yang dilematis. Ingin unjuk karya, namun disaat yang sama harus terkungkung oleh adat daerahnya. Ingin bebas bersuara, namun terhambat oleh doktrin agama. Modernisasi telah hadir begitu cepat, bahkan ruang-ruang untuk berekspresi begitu lebar. Sebagai perempuan, tinggal menunjukkan keberaniannya untuk menjadi “eksekutor” dalam mendobrak segala dilema yang ada.
Sejatinya, dalam mewujudkannya perlu dibutuhkan regulasi untuk melindungi hak-hak perempuan. Pemerintah juga harus hadir sebagai pemilik hak dalam menentukan regulasi tersebut. Tetapi, apakah Komnas HAM, Komnas Perlindungan Perempuan, Ormas, dll sudah menjamin kebebasan perempuan sepenuhnya? Sekalipun itu kewajiban mereka, namun itulah yang menjadi pertanyaan besar yang tak ujung terselesaikan.
Sekali lagi, tentunya karena perempuan dan laki-laki tercipta memiliki peranan masing-masing, maka dalam pemenuhan hak dan kewajibannya tidak bisa disama-samakan. Yang ada adalah bagaimana keduanya saling memahami antara hak dan kewajibannya. Sehingga tidak ada ketimpangan antar pemenuhan keduanya.
Akhirnya, maju tidaknya peradaban perempuan, tergantung pada sikap itu sendiri. Jika masih tidak mampu mengubah pradigma baru terkait perempuan atas adat dan tradisi lingkungannya dan pemahaman agamanya, atau masih saja dirundung dilema antar ketiganya, tentunya mazhab feminisme akan selalu menjadi teori dan wacana belaka!
Editor: Zulfikar