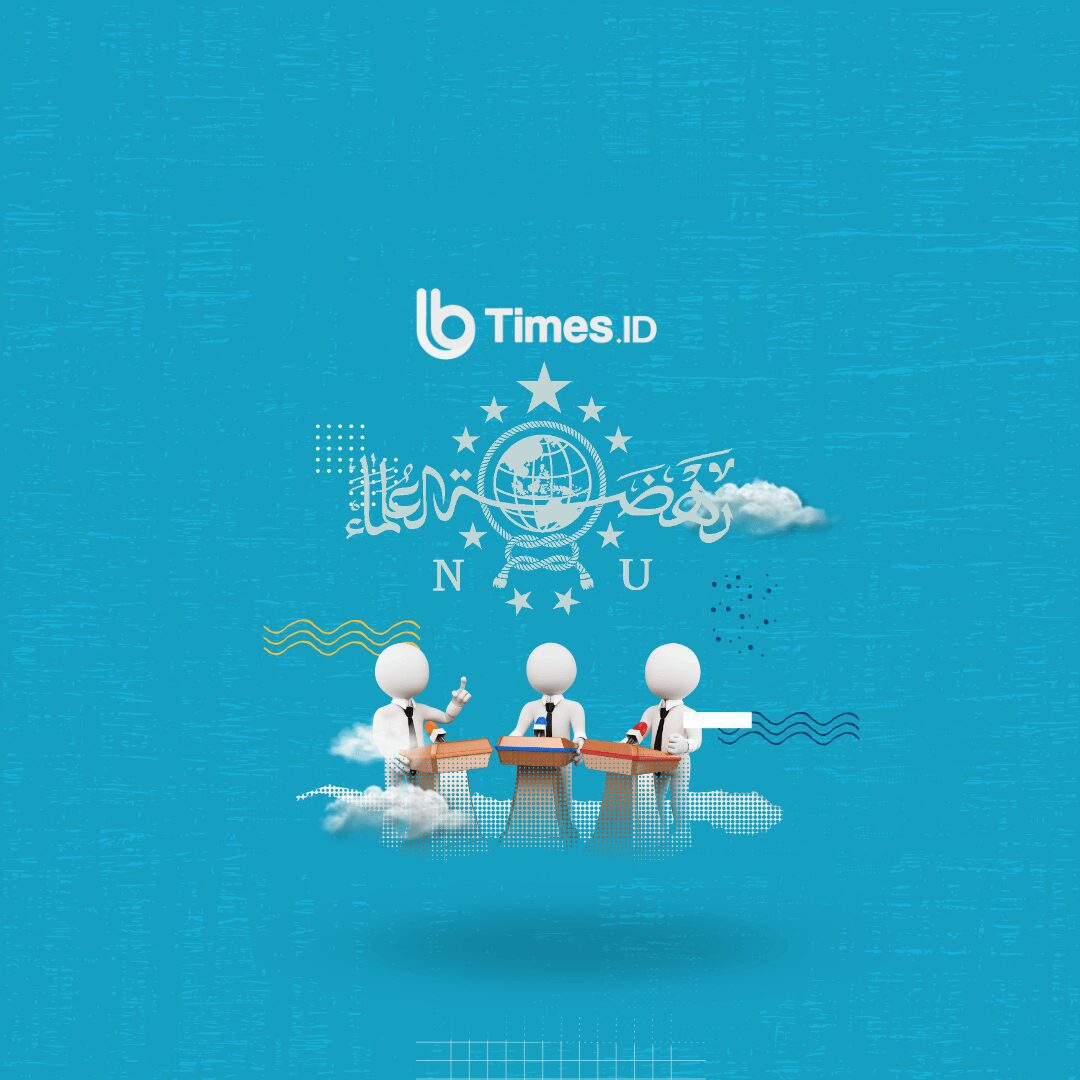Perayaan harlah Nahdlatul Ulama ke-100 tahun secara jamaah maupun jam’iyyah menjadi suatu parade kekuatan kolosal, dan pada saat yang sama mempunyai muatan politik yang kuat. Meskipun, organisasi NU bukan sebagai alat politik, tetapi NU dalam sejarah demokrasi mutakhir di Indonesia mempunyai pengaruh politik siginifikan.
Kekuatan Politik NU
Oleh sebab itu, siapa pun kekuatan politik di Indonesia akan mendapatkan atau membutuhkan dukungan dan legitimasi kekuatan Islam moderat dan wasathiyah. Sehingga, dalam konsep politik moderat-demokratis dan untuk mendapatkan kemenangan dalam setiap pemilu, maka terdapat dukungan dari basis kaum Nahdliyyin baik struktural maupun kultural.
Apabila dalam tatanan struktural diramaikan dengan wacana pengembalian arah politik NU kepada khittah 1926 untuk netral, independen, dan non-partisipan, maka basis kultural Nahdliyyin akan menjadi sebuah ladang perebutan basis pemilih loyal dari para kandidat pemimpin negara hingga daerah yang akan berlaga dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang.
Oleh sebab itu, seluruh pihak mempunyai kepentingan untuk memenangkan hati, pikiran, dan suara masyarakat Nahdliyyin, bukan hanya pada sektor umat Islam, khususnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dari rahim politik Nahdlatul Ulama (NU), tetapi juga partai-partai nasionalis-sekuler semacam PDIP, Nasdem, Demokrat, dan sebagainya.
Sebagaimana nampak pada gerak-gerik dan manuver para pemimpin partai tersebut yang berebut posisi terdepan ketika hadir di puncak perayaan harlah 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo lalu.
Bagaimana pun juga dalam aspek populasi diperkirakan warga Nahdliyyin baik secara kultural maupun struktural dapat mencapai 108 juta warga dan Muhammadiyah di posisi kedua.
Artinya, lebih daripada setengah masyarakat Muslim di Indonesia mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari NU dan hal tersebut dipengaruhi oleh komunitas santri dan para kyai di level kyai sepuh maupun muda untuk menunjukkan karakter Islam moderat di Indonesia. Sehingga, NU menjadi ladang subur luar biasa melimpah untuk diperebutkan.
Tetapi pada saat yang sama, ketika proses demokrasi mengalami polarisasi dalam konteks ini benturan-benturan politik identitas hingga SARA, lalu legitimasi dan dukungan NU sebagai jangkar kekuatan Islam moderat di Indonesia sangat dibutuhkan.
***
Siapa pun kekuatan nasionalis tersebut, tidak mungkin mereka mampu berdiri mandiri dalam konteks pemilu. Itulah mengapa tokoh kyai seperti KH. Hasyim Muzadi dahulu dipinang oleh Megawati untuk untuk maju menjadi cawapres di pemilu 2009 dan KH. Ma’ruf Amin yang mendampingi presiden Jokowi di pemilu 2019 yang lalu.
Hal ini merupakan suatu fakta konkrit politik, bahwa kaum nasional tak mampu berdiri sendiri, melainkan membutuhkan back up kekuatan Islam dan konteks perwujudan kekuatan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan daripada NU yang aspek jumlah dan justifikasi kekuatan politik moderatnya dibutuhkan oleh siapa pun yang berharap memenangkan pemilu di Indonesia.
Begitu kaya dan strategisnya NU, bahkan jargon para kyai sepuh NU yang khas berbunyi “NU tidak di mana-mana, tetapi NU di mana-mana” dan mampu ditunjukkan dalam konteks diaspora para politisi yang mempunyai latarbelakang Nahdliyyin di berbagai partai politik yang spektrum idelogisnya bervariasi dari nasionalis, moderat, hingga arus kanan.
Wajah PKB dan Nahdlatul Ulama
Tetapi, pada saat yang sama dalam menyambut tahun politik 2024 ada situasi-kondisi berbeda, di mana relasi antara PBNU dan PKB justru menampilkan sebuah wajah kurang harmonis, ketegangan, miskomunikasi antar elit pemimpinnnya.
Sebagaimana diketahui bahwa lahirnya PKB merupakan berasal dari rahim politik NU kala itu dan menjadi wadah aspirasi politik warga Nahdliyyin. Setidaknya dalam arus komunikasi yang melibatkan ketum PKB, Muhaimin Iskandar dengan ketum PBNU, KH. Yahya Chalil Staquf yang seolah-olah membuka ruang terbuka bagi partai-partai politik lainnya untuk memperebutkan basis pemilih loyal dari segmentasi Nahdliyyin.
Oleh sebab itu, seluruh pihak akan mencoba masuk dalam ruang tersebut dan pada saat yang sama NU harus mampu menjaga dirinya dengan baik. Menjaga marwahnya dengan baik, tidak mudah terjebak dalam konteks polarisasi politik yang ada, dan tetap menjaga nalar kritis ketika tetap berada di depan oligarki kekuasaan.
Sehingga, ini menjadi catatan penting sebagaimana dipesankan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahwa “NU harus mampu menjalankan perannya sebagai Islamic Peace Civil Society” yang tidak kehilangan nalar kritisnya di hadapan kekuasan. Sekaligus itu menjadi bahan koreksi dalam proses perkembangan laju demokrasi saat ini, jika muncul suatu bentuk keluh-kesah dan harapan yang lebih agar NU kembali menunjukan nalar kritisnya dalam mengawal kebijakan publik dan arus kekuasaan untuk tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan mursalah yang ada.
Diaspora kekuatan mesin politik NU yang menyebar ke berbagai kelompok dan partai politik akan mampu memberikan tampilan yang lebih variatif dan power full selama mampu diorkestrasikan dengan baik, terutama oleh mereka yang berada di jajaran elit Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Namun, apabila hal tersebut tidak mampu dikelola dengan baik seperti adanya kesalahpahaman komunikasi yang seakan sengaja diciptakan, justru berpotensi melemahkan NU sendiri.
Menjaga Marwah Politik NU
Dalam penentuan pemimpin di masa mendatang, misalnya pada tingkatan pemilihan presiden (pilpres), terdapat satu nama calon pemimpin yang mempresentasikan basis pemilih NU, memiliki cara pandang, visi-misi, dan platform yang sesuai dengan karakter Islam moderat dan wasathiyah, mungkin NU akan kuat dan terkonsolidasi dengan baik.
Tetapi, apabila tenyata mempunyai aspirasi berbeda dan tidak sesuai dengan basis keinginan akar rumput, maka basis pemilih loyal NU berpotensi terpecah di sana sebagaimana telah terjadi pada gejolak pemilu tahun 2004, 2009, dan 2014.
Kemudian, manakala ada sebuah kekuatan nama yang tidak mempunyai akar cukup kuat yang berasal dari kaum Nahdliyyin, maka masyarakat Nahdlatul Ulama akan cenderung lebih kritis dikarenakan mereka mempunyai literasi politik yang lebih baik dan mereka akan mengikuti nalar kritisnya untuk memilih pemimpin yang akan datang.
Pada akhirnya, dibutuhkan komitmen nyata dari pemimpin umat supaya NU menjadi pengayom, menyatukan, merangkul, dan membangkitkan soliditas di semua elemen kekuatan masyarakat. Bukan malah membentuk perbedaan dan mendiskreditkan yang lain ketika berbeda model cara pandangnya.
Sehingga, dalam konteks politik NU harus menata diri, meletakkan, dan mengkontekstualisasikan amanah khittah 1926 dengan tujuan utama yaitu tidak terjebak sebagai bagian dari instrumen politik kekuatan tertentu.
Harapan besar berada di pundak ketum PBNU yaitu KH. Yahya Chalil Staquf untuk mampu mengawal NU tetap berada di garis netral dan independen, khususnya sikapnya kepada PKB.
Namun, di saat yang sama berbagai kalangan masih mempunyai suatu persepsi negatif terhadap Gus Yahya dan NU yang seakan inkonsistensi dalam bersikap dengan ditunjukkan lahirnya potret ruang-ruang yang terbuka diberikan kepada satu nama tertentu yang seolah-olah memberikan panggung luar biasa. Politik NU merupakan politik moral, hal tersebut yang membedakan politik NU dengan politik partai.
Editor: Soleh