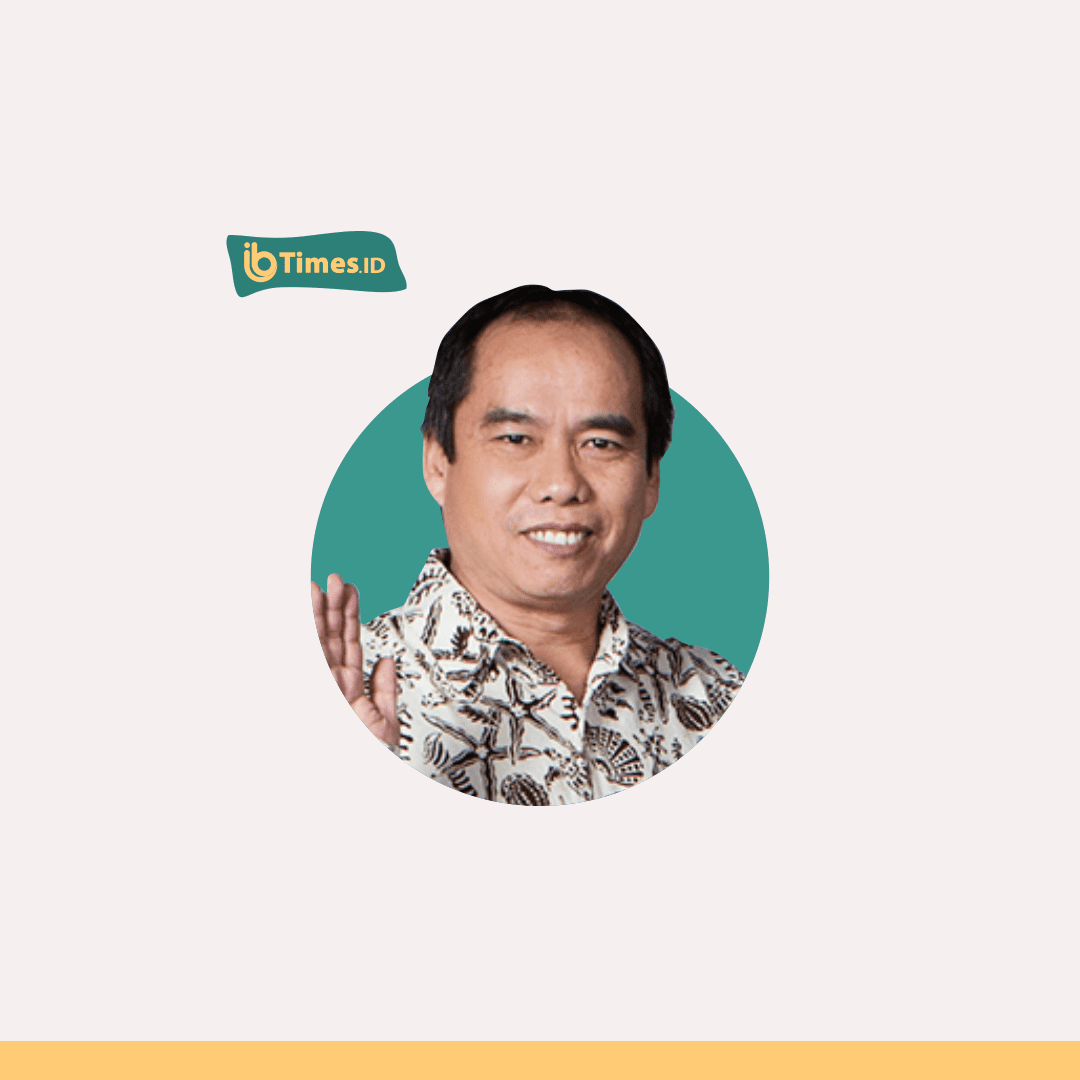Kisah ini merupakan kelanjutan dari cerita sebelumnya tentang Sawah Untoh dan Jelen Luhuih (1). Aku merasa beruntung karena selama masa tinggal di dusun mengalami langsung proses menjadi petani tradisonal. Di ladang Jelen Luhuih dan Ujung Tanjung aku mengalami menebang kayu, membakar lahan, menanam bibit, menyawat atau menyiang lahan, sampai memanen kopi atau kulit manis. Bagian paling berkesan dari proses membuka lahan adalah memanen cendawan (jamur) pada awal musim hujan.
Beberapa hari sebelum hujan perdana diperkirakan turun proses pembakaran lahan dilakukan. Pagi hari setelah hujan turun seluruh pohon kayu yang ditebang ditumbuhi berbagai macam cendawan. Nampaknya dari sini muncul pepatah “bagai cendawan tumbuh di musim hujan.” Cendawan segar inilah yang aku petik dan menjadi menu utama makan kami selama beberapa hari kemudian. Dua jenis cendawan paling aku sukai adalah cendawan mime dan cendawan kuku. Cendawan-cendawan ini bisa dikeringkan dengan dihamparkan di bawah sinar matahari. Ketika akan dikonsumsi cendawan kering terlebih dulu direndam beberapa menit dalam air hangat sampai mekar kembali. Kini cendawan kuku merupakan paket kiriman favorit yang selalu aku tunggu kedatangannya dari keluarga di kampung halamanku.
Kenangan Sawah Untoh dan Sawah Panjang
Di Sawah Untoh dan Sawah Panjang aku mengalami proses panjang sebelum nasi terhidang pada sepiring nasi untuk disantap. Aku mengalami proses menebas, mencangkul, membajak, berkirang, dan seterusnya. Tetapi secara umum keterlibatanku di Sawah Untoh dan Sawah Panjang tidak terlalu diperhitungkan oleh keluargaku. Ini karena secara fisik aku dikenal sebagai anak yang kule (tidak terlalu bertenaga secara fisik) tetapi pantaih (cemerlang secara pikiran). Maka aku tidak terlalu diperhtungkan untuk perkejaan-pekerjaan fisik.
Sebagai anak bungsu yang masih kecil aku sekadar saja menajalankan tugas-tugas sebagai petani itu. Pengalaman ke ladang dan ke sawah bagiku lebih banyak sebagai pengalaman rekreatif. Dalam hal ini Indok dan Upoak tidak pernah memaksa aku untuk bekerja keras di ladang dan di sawah. Demikian juga kakak-kakakku. Maka pada periode berikutnya setiap pulang kampung dari rantau salah satu rekreasi yang tidak terlupakan adalah naik ke ladang dan turun ke sawah.
Waktu turun ke sawah lebih banyak aku gunakan untuk salah satu hobiku yaitu memancing kapanjang (ikan panjang, belut). Ketika Upoak, indok, dan kakak-kakakku sedang asik bekerja di sawah, biasanya aku sudah menghiliri parit-parit sawah menuju ke arah dusun kami mencari lubang-lubang belut. Dengan pancing yang aku rakit sendiri aku bisa seharian meratai sawah-sawah di sekitar desa kami, mulai dari Sawah Untoh, Sawah Panjang, Sawah Seberang Lingkat, sampai ke Sawah Sayan di tepi Batang Merangin.
Keluargaku biasanya membiarkan aku menikmati petulaangan ini. Berapapun belut yang aku peroleh tidak dipersoalkan. Sampai usia SMA setiap pulang kampung hobi ini selalu aku ulangi. Belakangan ini terpaksa aku tinggalkan karena tidak banyak lagi lubang belut yang bisa ditemukan di parit-parit sawah dan sungai di dusun kami. Pupuk pestisida telah membunuh anak-anak dan induk belut. Tetapi hobi makan ikan panjang tetap bisa aku lanjutkan di Jogja. Tidak jauh dari rumahku di Kasihan Bantul, ada pasar Niten. Di sana selalu ada penjual ikan panjang yang disebut welut langgananku. Hanya saja sensasi memancing belut keliling sawah dan sungai tidak lagi bisa aku rasakan.
Perubahan Sosial di Kampung
Periode mengikuti Upoak dan Indok ke sawah dan ke ladang ini juga bagian tidak terlupakan dari kedekatanku dengan mereka. Kegiatan ini tetap berlangsung setiap aku pulang kampung dari rantau. Suatu saat aku mengikuti mereka ke ladang kami di Jeleh Luhuih. Kami berjalan kaki menyusuri jalan rodi melewati Desa Baru. Di ladang tidak banyak yang bisa aku lakukan. Aku lebih sekedar menemani Upoak dan Indok dan sedikit membersihkan ladang dan merawat batang-batang kopi dengan membuang tunas-tunas baru yang tumbuh yang tidak dibutuhkan.
Hal yang paling menyenangkan adalah sepulang dari ladang. Kami biasa singgah di rumah beberapa kemenakan Upoak di Desa Baru. Tentu kami mendapatkan minuman dan makanan kecil di rumah saudara sepupuku ini. Kebiasaan sainggah di rumah para sepupu ini aku lanjutkan meskipun Upoak dan Indok telah tiada. Aku selalu mengingat rasa sayang para kakak sepupuku dan anak-anak mereka yang banyak sebaya denganku. Ketika akan berangkat lagi ke Jogja aku memastikan berpamitan ke mereka di Desa Baru. Angpao yang mereka berikan melepas keberangkatanku tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa SMP atau SMA seperti aku saat itu.
Tetapi itu semua ini tinggal menjadi cerita lama yang indah bagiku. Perubahan sosial telah berlangsung di kampung halamanku. Sebagaimana ditempat lain, penyebab utamanya adalah lancarnya transportasi dan jalinan informasi. Seiring dengan perbaikan dan peningkatan status jalan rodi yang melintasi dusun kami, maka arus keluar masuk menjadi makin lancar.
Pada awal 1980-an, angkutan umum Kerinci-Bangko-Jambi terbuka sudah. Maka cerita tentang merantau ke mboak (bawah, sebutan untuk daerah Kerinci Rendah dan Jambi pada umumnya) dengan berjalan kaki tiga hari tiga malam sebelum mencapai desa terdekat berakhir sudah. Apalagi cerita tentang seorang informan yang pada zaman pendudukan Jepang berjalan kaki dari Kampung Bayo di dekat Muara Tembesi menuju Kerinci dengan waktu tempuh setengah bulan.
Sejak dibukanya jalur Tamiai-Perentak pada awal 1980-an itu maka Kerinci-Jambi bisa ditembus dalam satu malam perjalanan. Sehingga untuk keluar dari Kerinci, menuju Jakarta-Jogja, misalanya tidak lagi harus berputar ke Padang untuk kemudian berlayar dari Teluk Bayur menuju Tanjung Priok. Sebagaimana pengalamanku pertama keluar Kerinci pada 1979.
Perjalanan Jauh yang Tak Lagi Jauh
Kini Dusunku juga tidak lagi terasa jauh. Pada tahun 1981 saat mudik perdana ketika kelas dua SMP, aku harus menempuh perjalanan darat Jogja-Kerinci empat hari empat malam. Sekarang aku bisa mencapai dusunku hanya dalam satu hari perjalanan.
Pada tahun 2015, misalnya, aku pulang dalam rangka riset bersama seniorku Pak Said Tuhuleley. Perjalanan dimulai dengan flight pertama Garuda menuju Padang dengan transit di Bandara Soetta Jakarta. Menjelang zuhur kami sudah mendarat di Bandara Internasional Minangkabau di Ketaping. Lalu kami melanjutkan perjalanan darat menyusuri dan membelah punggung Bukit Barisan dari Padang-Indarung-Lubuk Selasih-Alahan Panjang-Muara Labuh-Kerinci. Ketika azan magrib berkumandang kami sudah bisa berbuka puasa di Minang Soto, rumah makan legendaris di Sungai Penuh. Jadi cukup dengan perjalanan efektif 12 jam aku sudah bisa mencapai kampung halamanku. Apalagi kini penerbangan regular Wings Air juga sudah dibuka dengan rute Jambi-Muaro Bungo-Kerinci PP.
Belakangan dengan teknologi informasi dusunku terasa menyatu sudah dengan Jogja. Tidak ada lagi jarak yang jauh dan waktu yang lama untuk berkomunikasi. Sampai era 1990-an komunikasi paling cepat dari rantau dengan kampung halaman adalah melalaui telegram. Tidak ada telepon di dusun kami sebelum era wartel menjamur. Juga tidak ada kantor pos. Komunikasi regular adalah melalui surat. Itupun dikirim via saudara di kota kabupaten. Maka aku masih ingat penulisan alamat surat untuk Upoak sebagai berikut. “Kepada Yth. Ayahanda Haji Zainuddin, d.a. Kakanda Haji Damhuri Gusti, Jalan Sriwijaya (belakangan berubah menjadi Jalan Depati parbo), Sawahan, Sungai Penuh Kerinci, via Sumatera Barat.”
Sumatera Barat dipakai karena kantor pos Sungai Penuh adalah bagian dari pos Sumatera Barat pada masa itu. Haji Dahmuri adalah suami dari kakak sepupu jauhku yang menjadi pedagang sukses dan menetap sekeluarga di kota kabupaten kami. Beliau menerima surat-suratku untuk kemudian menitipkannya ke para sopir angkutan yang menuju dusunku 33 km di hilir untuk disampaikan ke Upoak. Untuk ini aku berdoa semoga jasa baik kakanda Haji Damhuri menjadi bagian dari amal saleh beliau di alam sana. Aamiin. Kini aku tidak lagi menulis surat apalagi telegram. Aku bisa melakukan vidcall live kapanpun dengan keluarga di kampung halaman. Indosat dan Telkomsel telah lama memasang BTS di beberapa titik di kampung halamanku.
Generasi yang Berganti
Penduduk dusunku kini juga sudah berkembang pesat. Dusun kami pada empat dasawarsa yang lalu itu secara admisintrasi pemerintahan kini sudah berkembang menjadi empat desa: Pulau Sangkar, Desa Baru, Seberang Merangin, dan Pondok. Ketika berangkat meninggalkan kampung halaman pada 1979 aku hapal semua nama orang satu dusunku. Jumlah warga masih terbatas dan ada ikatan tali kekeluargaan yang menghubungkan antar penduduk. Bahkan persaudaraan juga terjalin dengan para pendatang yang berasal dari berbagai daerah yang banyak tinggal di dusun kami pada masa itu.
Kini generasi orangtuaku pada umumnya sudah berpulang. Generasi aku sudah mulai menjadi orang tua. Penduduk terbanyak kini adalah generasi anak dan cucuku. Maka ketika ada anak muda baru dari dusunku masuk Jogja dan berkunjung ke ruamahku aku tidak selalu bisa mengenalnya langsung. Aku memerlukan meminta dia menyebut nama orangtuanya atau bahkan kadang nama kakek atau neneknya terlebih dahulu. Barulah aku tahu siapa anak muda ini dan apa hubungan kekerabataku dengannya.
Pada sisi lain mata pencaharian penduduk juga sudah semakin bervariasi. Pada masa kecilku hampir semua penduduk adalah petani tradisional. Segelintir penduduk menjadi pedagang pengepul hasil pertanian. Sebagian dari petani ini adalah induk semang (juragan) yang memperkerjakan para anak upan (buruh tani) yang berasal dari negeri-negeri sekitar dekat maupun jauh. Ngah Kafrawi, salah satu saudara sepupu jauhku, misalnya, merupakan salah satu dari puluhan induk semang di dusunku.
Ngah Kaf pada 1985 sampai 1995 mempekerjakan 40 anak upan yang menggarapap ratusan hekatar ladangnya yang tersebar di bukit-bukit di seputar desa kami. Semua anak upan itu tinggal di ladang. Pada masa kecil aku juga samar-samar masih ingat Upoak juga mempunyai anak upan yang menggarap ladaang kami di Bukit Melgan. Namanya Jakpar dan berasal dari Dusun Pendung di Kerinci Tengah. Aku tidak ada lagi berjumpa dengan Wo Jakpar itu sejak aku berangkat ke Jogja. Kini dusunku sudah menjadi kota kecil. Berbagai profesi baru telah digeluti oleh penduduknya. Sebagian menjadi pebagwai negeri maupun swasta.
Sawah Untoh dan Jelen Luhuih Kini
Ada dua titik di kampung halamanku yang menjadi simpul tentang cerita dinamika ekonomi pertanian: Sawan Untoh dan Jelen Luhuih. Sawah Untoh adalah tentang masa kecil yang tenggelam ditelan zaman. Tidak ada lagi anak keturunan Indok yang berminat mengolahnya. Bersawah bukan lagi pekerjaan menarik bagi anak negeri kami kini. Sudung di tengah sawah, memancing belut, dan berbagai kenangan menjadi petani cilik tak bisa lagi aku temukan jejaknya disana. Jalan setapak kesana hilang ditelan semak belukar. Sawan Untoh ditinggalkan jauh di belakang.
Sebaliknya Jelen Luhuih. Ia adalah kawasan kenangan masa kecil yang dinamis mengikuti perubahan. Jelen Luhuih kini bukan lagi jalan rodi sepi di ujung dusun. Jalan rodi itu sudah menjadi jalan negara yang lebar, mulus, dan ramai oleh lalu-lalang kendaraan. Tidak ada lagi hutan lebat karena Jelen Luhuih sudah menjadi kawasan strategis desa kami. Beberapa rumah baru berdiri megah di kiri dan kanannya. Tetapi aku bersyukur masih bisa menikmati banyak kenangan masa kecil di sana. Lahan ladang Upoak masih utuh. Kenangan indah berladang disana tetap bisa aku nikmati lagi. Kapanpun aku pulang.
Editor: Nabhan