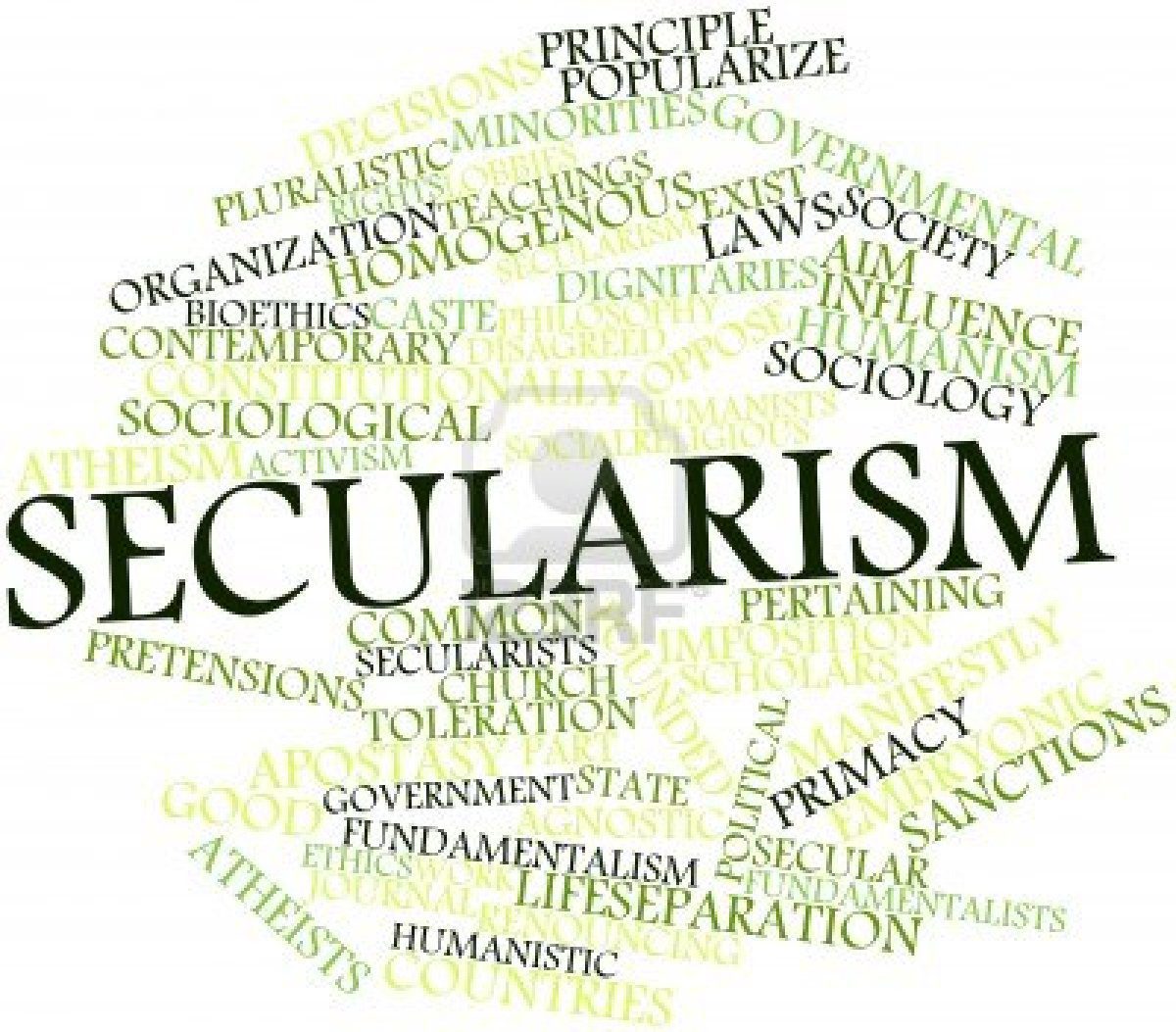Sekularisasi | Di Indonesia, semenjak tahun 1970-an sampai tahun 1990-an sering disebut sebagai masa “antusiasisme intelektual”. Di mana terjadi tendensi wacana keagamaan menuju wacana kultural. Kalangan Islam kultural Indonesia, mulai menempatkan suatu hubungan yang harmonis antara cita-cita Islam dan fenomena tradisi masyarakat yang plural (Syamsuddin Bahrun, 2019: 13).
Tantangan terbesar masyarakat pribumi pada waktu itu ialah isu-isu modernitas yang datang dari Barat. Sehingga perlu ada kontekstualisasi nilai-nilai Islam secara kultural, agar tidak terjadi benturan dan berakibat pada tergerusnya nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, perlu adanya sikap keterbukaan terhadap gagasan yang datang dari luar.
Di sinilah letak makna penting yang dibawa oleh Cak Nur dan Gus Dur dalam konstelasi pemikiran Islam di Indonesia yang memiliki ragam budaya. Pribumisasi dan sekularisasi sebenarnya dimaksudkan untuk itu. Sementara arahnya, yakni mengarah pada teologi inklusif: suatu teologi yang membentuk wajah Islam lebih cair, kosmopolitan, dan pluralistis (Syamsul Bakri dan Mudhofir, 2004: 14-15).
Sekularisasi ala Cak Nur
Dalam teologi inklusifnya, Cak Nur menawarkan konsep sekularisasi dalam beragama teruntuk masyarakat Islam pribumi. Dan menjelaskan bahwa konsep yang ditawarkannya sema sekali berbeda dari konsep sekularisme sebagaimana yang diterapakan oleh Barat sebagai bentuk penghapusan kepercayaan kepada Tuhan.
Sekularisasi yang dimaksud Cak Nur adalah setiap bentuk perkembangan yang besifat membebaskan. Karena menurutnya, proses pembebasan ini diperlukan umat Islam, yang karena perjalanannya sendiri sampai-sampai tidak mampu membedakan nilai-nilai yang disangkanya Islam transendental atau temporal.
Dengan demikian, kesediaan mental untuk selalu menguji dan mengkaji kembali kebenaran suatu nilai di hadapan kenyataan-kenyataan material, moral, ataupun historis, harusnya menjadi sifat kaum muslimin. Dan Sekularisasi itu dimaksudkan oleh Cak Nur guna memantapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah Allah Swt di bumi.
Fungsi sebagai khalifah memberikan ruang bagi adanya kebebasan manusia untuk menetapkan dan memilih sendiri cara dan tindakan dalam rangka perbaikan hidupnya di atas bumi, dan sekaligus memberikan pembenaran bagi adanya tanggung jawab manusia atas perbuatannya di hadapan Tuhan (Zainal Abidin, 2014: 675-676).
Jika ditelaah, sebenarnya konsep sekularisasi Cak Nur ini bersifat sosiologis; bukan bersifat filosofis. Karena dalam beberapa penjelasannya menyatakan tentang konsepsi beragama yang menduniawikan nilai-nilai yang semestinya bersifat dunia dan meng-ukhrawi-kan nilai-nilai yang semestinya bersifat akhirat.
***
Dalam rangka membumikan Islam pribumi ini, sebenarnya Cak Nur telah membuka ruang pemikiran para penganut Islam pribumi untuk menerima tantangan dan mengalahkanya. Bukan malah bersifat tertutup dan menghindarinya, justru ini yang keliru dalam pandangan Cak Nur. Karena Islam tidak pernah bertentangan dengan peradaban dan budaya. Oleh sebab itu, Islam yang sesungguhnya ialah Islam yang bergerak secara dinamis dan progresif.
Jadi dalam hal ini, Cak Nur mencoba memecahkan kejumudan berpikir, karena tidak mampu menafsirkan teks terhadap konteks. Sehingga yang ada adalah kebekuan sikap dan pikiran terhadap Islam itu sendiri. Nah konsep sekularisasi yang telah mendapat tafsiran baru itu, di tujukan untuk menghadapi tantangan peradaban dan budaya di tengah erupsi medernisasi.
Namun, kesalahpahaman demi kesalahpahaman masyarakat pribumi pada waktu itu terus saja bergulir karena ketidakmampuan menangkap makna yang terkandung. Mereka lebih fokus mengkritisi bahasa lahiriahnya saja, tanpa merenungi makna tersiratnya.
Jangankan waktu itu (masa Cak Nur), mungkin sampai saat ini pun rakyat pribumi belum jua menangkapnya secara betul. Meskipun toh sebenarnya sudah tidak menjadi kontroversi dan polemik lagi. Misalnya saja berita panas yang beredar baru-baru ini (baca: wayang). Ini adalah salah satu bentuk ketidakfahaman itu.
Kebaikan untuk Pribumi
Dalam sekala Penafsiran yang benar-benar baru, Cak Nur tidak semata-semata demi kepentingan pribadi atau hanya sekedar mencari pengikut. Melainkan demi rakyat pribumi yang sebenarnya sangat membutuhkannya. Jika dikaitkan dengan persoalan yang baru-baru ini tersiar, harap maklum bahwa wayang, dalang, dan para pecintanya adalah mereka yang sebenarnya paham tentang budaya dan agama secara universal. Betul tidak ?
Menurut saya, mereka bukan hanya sebagai orang yang beragama, tetapi juga turut andil dalam melestarikan budaya khas pribumi-nya. Satu hal lagi, mereka juga bangga bahwa Walisongo dulu pernah berperan penting dalam kelangsungan budaya itu. Tidak malah menyalah-nyalahkan atau menghukumi, laiknya hakim atau jaksa Tuhan.
Karena dalam konteks Indonesia, budaya pewayangan ini sudah mendarah daging, yang seolah-olah merupakan bagian dari tubuhnya sendiri. Jika saja ada yang mencelanya, tubuh yang lain juga merasakannya. Apalagi Walisongo yang merupakan kekasih Tuhan, justru memanfaatkannya sebagai media dakwah. Artinya ini sungguh suatu keharmonisan, manakala budaya dan agama saling berjalan beriringan tanpa mengorbankan salah satunya. Iya kan?
Bersambung…