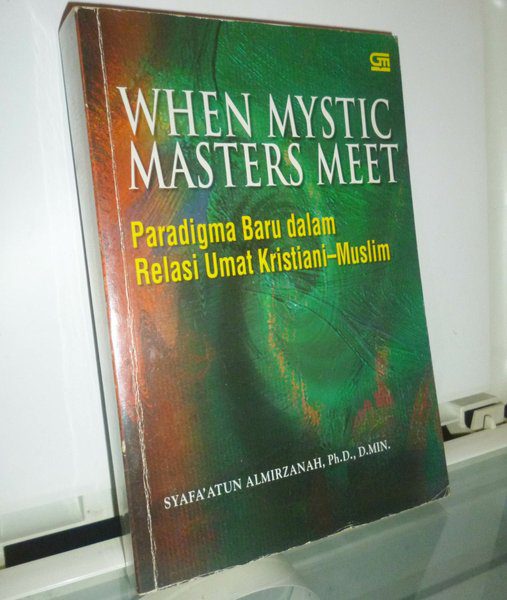Pengantar
Agama, sebagaimana diungkapkan Ninian Smart (2002), memiliki banyak dimensi, antara lain: dimensi ritual, naratif, pengalaman, dan doktrin.
Mendeskrispsikan agama sebagai sebuah realitas historis membutuhkan beragam pendekatan. Sebagai fakta historis, agama hadir tidak dalam ruang hampa dan sebagaimana adanya.
Dalam konteks inilah, pendekatan studi agama menjadi sebuah keniscayaan. Tidak hanya sebuah pendekatan dibutuhkan dalam studi agama, melainkan lintas pendekatan yang memungkinkan mendeskripsikan agama secara utuh.
Dalam buku yang dieditori Peter Connolly (2002) diintrodusir tujuh pendekatan yang sering dipergunakan dalam studi agama, yaitu pendekatan antropologis, feminis, fenomenologis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan teologis.
Setiap pendekatan tersebut memiliki titik tekan yang berbeda dengan beragam asumsi. Di samping itu, setiap pendekatan memiliki pula perspektif yang berbeda.
Tentu saja tersedia pendekatan lain dalam studi agama selain yang diintrodusir Connonly. Salah satunya adalah pendekatan sufistik yang berusaha menelisik dimensi mistik setiap agama.
Pendekatan sufistik sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam studi agama. Pendekatan ini telah dilakukan oleh banyak sarjana baik insider maupun outsider.
Sekadar untuk menyebut beberapa sarjana yang telah menggunakan pendekatan ini, antara lain: Annamarie Schimmel, Tor Andree, Martin van Bruinessen, Simuh, dan lain-lain.
Sekalipun menggunakan pendekatan sufistik, cara pandang dalam hal ini beragam serta berlainan tergantung core keilmuan masing-masing sarjana tersebut.
Di tengah berkecambahnya radikalisme dan ekstrimisme keagamaan, pendekatan sufistik dalam studi agama tampaknya menemukan relevansinya.
Dimensi esoterisme agama menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan pemahaman agama yang didasarkan atas welas asih terhadap alam semesta beserta isinya (rahmatan li al-alamin), termasuk pemeluk agama lain.
Ragam Pendekatan Sufistik
Studi agama dengan pendekatan sufistik biasanya menggunakan perspektif historis dan fenomenologis (Simuh, 2018). Dengan perspektif historis, pendekatan sufistik dipergunakan oleh Martin van Bruinessen (1996) untuk mendeskripsikan Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia.
Pengagas Islam rasional di Indonesia, Harun Nasution (1990) mengeditori sebuah buku tentang ordo sufi dengan perspektif historis.
Barangkali perspektif fenomenologi yang menjadikan pendekatan sufistik menghasilkan temuan dan buku yang melimpah. Dalam konteks ini, fenomenologi berupaya menelisik religiusitas pelaku tasawuf atau pengikut tarekat tertentu.
Nur Syam (2013), misalnya, penelitiannya terhadap pengikut Tarekat Syattariyah di desa Kuanyar Mayong Jepara menghasilkan apa yang disebutnya dengan tarekat petani. Demikian pula penelitian Sokhi Huda (2008) terhadap tarekat yang tidak mu’tabarah, Shalawat Wahidiyyah.
Berbeda dari perspktif historis dan fenomenologi, dalam karyaWhen Mystic Master Meet, Syafa’atun Almirzanah menawarkan pendekatan sufistik dalam perspektif relasi Islam-Kristen.
Melalui dua mahaguru mistik, Shaykh al-Akbar, Ibn ‘Arabi (1165-1240) dan Meister Echkrat (1260-1328), Prof Syafa’ menawarkan apa yang disebut dengan JB Banawiratma sebagai interreligious studies.
***
Menurut JB Banawiratma, model studi agama sekurang-kurangnya ada tiga, yaitu comparative studies of religion, religious studies, dan interreligious studies. Comparative studies of religion berupaya membandingkan dan menilai realitas agama.
Studi agama model ini dikritik lantaran subjektifitas yang kentara dalam menilai sebuah agama, terlebih bila penilaian tersebut dilakukan oleh outsider.
Religious studies menyajikan fakta-fakta agama sebagaimana adanya, sebagai sejarah agama (history of religion) atau fenemona agama (phenomenology of religion).
Lebih dari dua model tersebut, model interreligious studies seperti yang dilakukan Almirzanah menyadarkan banyak orang bahwa studi agama merupakan komunikasi berbagai subjek yang terlibat dan bertemu dalam pengalaman, interpretasi, dan pemahaman religius.
Studi agama-agama seyogyanya mampu mendialogkan dan memahami agama lain (liyan).
Dalam konteks tersebut, dengan subjek mahaguru mistik, baik Islam maupun Kristen, terjadi konvergensi. Dengan berbagai legasinya, terutama al-Futu>h{a>t al-Makkiyah dan Fus{u>s{ al-H{ika>m, Ibn ‘Arabi meyakini citra Tuhan sebagai ‘Perbendaharaan Tersembunyi’ (Kanzan Makhfiyyan), Nafas al-Rahman, Manusia Sempurna (Insan Kamil), dan wihdat al-wuju>d.
Di sisi lain, Meister Eckhrat berbicara perihal detachment (mengambil jarak atau tidak lekat) dengan diri sendiri, “orang yang (dalam sikap tidak lekatnya) tetap berada dalam cinta Tuhan harus mati bagi dirinya sendiri dan semua makhluk sehingga dia hanya mempunyai sedikit perhatian terhadap dirinya seperti perhatiannya terhadap sesuatu yang ribuan mil”. Almirzanah menyebutnya dengan asketisisme kontemplatif.
Relevansi Relasi antar Agama
Pertanyaannya, bagaimana relevansi kedua mahaguru sufi tersebut dalam dialog Islam-Kristen? Almirzanah mengaris bawahi empat hal (hlm. 292-297).
Pertama, hermeneutika skriptural. Kedua mahaguru tersebut berpandangan bahwa setiap teks ilahiah mempunyai makna yang tidak terhingga.
Kedua, keesaan wujud yang merupakan kesatuan mendasar semua eksistensi, penyingkapan diri Pencipta dalam seluruh tatanan ciptaan mendorong dialog antar agama tidak berkutat pada persoalan pembuktikan Tuhan, melainkan bagaimana dan dimana manusia menemukan Tuhan dalam kepercayaan dan praksis keagamaan.
Ketiga, penamaan Tuhan. Bahasa manusia mempunyai keterbatasan untuk ‘menampung’ nama Tuhan. Karena itu, dalam dialog agama, pemahaman tentang Tuhan harus ‘dipendam’ terlebih dahulu.
Sebab, pemahaman ini kadang kala menjadi penghalang bagi dialog sekaligus pemberhalaan pemahaman tersebut. Padahal, pemahanan tentang Tuhan bukanlah Tuhan itu sendiri.
Keempat, transformasi diri. Menjadi pribadi beriman kepada Tuhan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Setiap saat orang yang yakin kepada Tuhan menyediakan dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik, termasuk dalam dialog agama.
Dalam kadar tertentu, When Mystic Masters Meet Almirzanah merupakan proyek ilmiah melanjutkan apa yang ditulis oleh Sidney H. Griffith (2004), Mystic and Sufi Masters: Thomas Merton and Dialogue between Christian and Muslims.
Keterlibatan Thomas Merton dalam sufisme yang mengantarkannya mempelajari karya sufi dan bergaul dengan para sufi. Dalam surat yang ditujukan kepadanya, Sidi Abdessalam, keturunan Shaykh Ahmad Alawi Aljazair, menuliskan bahwa kata-kata dan pemahaman mengakibatkan kekacauan dan perpisahan.
Karena itu, pengalaman mistik tidak tercapai. Akibatnya manusia terhalangi untuk sampai kepada Dia yang sebetulnya tidak dapat dibelenggu oleh apa pun jua.
Mistisme mengajak manusia untuk mengabdi kepadaNya yang tidak pernah memadai diungkapkan dengan kata-kata (Sindunata, 2006). Dalam aras inilah, tasawuf, sufisme, atau mistisme menemukan relevansinya dalam setiap dialog agama.
Editor: Yahya FR
Buku : When Mystic Masters Meet: Paradigma Baru dalam Relasi Umat Kristiani-Muslim
Penulis : Syafa’atun Almirzanah
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, 2009
Tebal : xxxvi dan 387 halaman
ISBN : 978-979-22-4272-0