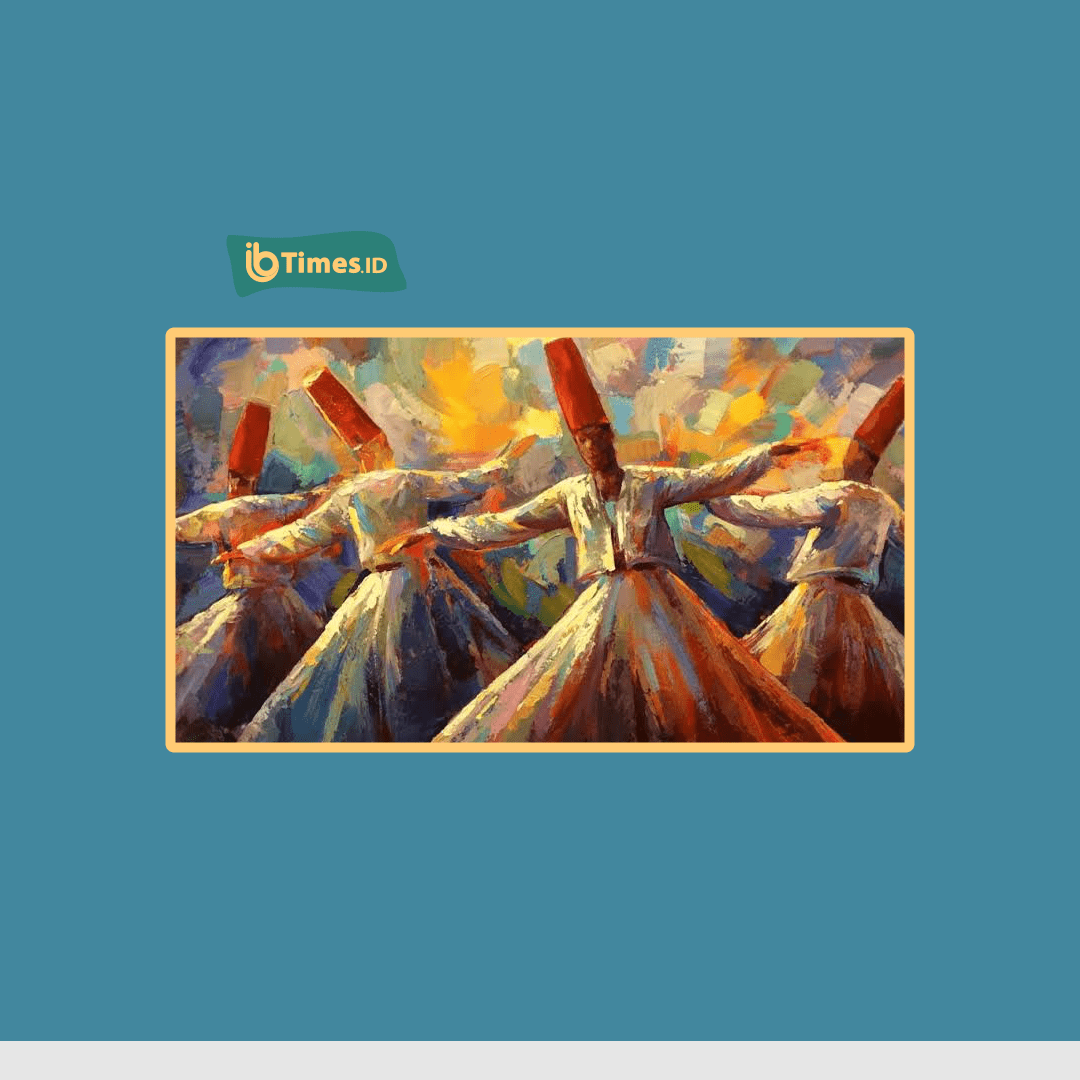Muhammadiyah pada awal mula berdirinya berasal dari kelompok mengaji yang dibentuk oleh KH. Ahmad Dahlan dan berubah menjadi sebuah organisasi kemasrayarakatan. Adapun beberapa penelitian selanjutnya menyebutkan bahwa hadirnya organisasi Muhammadiyah adalah untuk membentengi penetrasi penyebaran agama Kristen di Indonesia (Shihab, 1998).
Secara umum Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan pendidikan berbasis nilai-nilai kemodernan, dan disamping itu juga sebagai gerakan dakwah yang memberantas TBC (Tahayyul, Bi’dah, dan Churafat).
Memang akan sulit untuk melihat bagaimana tasawuf itu ada di Muhammadiyah, karena tasawuf sendiri tidak menjadi yang utama diamalkan oleh Muhammadiyah. Sebagaimana juga organisasi PERSIS atau Persatuan Islam yang sama juga mengusung nilai-nilai modernisme dalam orientasi dakwahnya. Sehingga praktik-praktik sufisme atau tasawuf sulit terlihat dalam organisasi-organisasi modern. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syafiq Mughni, Muhammadiyah menganut sebuah pemahaman bahwa Sufisme adalah penyebab kemunduruan umat Islam (Mughni, 2015).
KH. Ahmad Dahlan sendiri dikisahkan juga banyak membaca karya-karya ulama lintas generasi, dari tradisionalis hingga modernis, misalnya beliau membaca karya-karya Imam al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Jauzi, hingga Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dll. Sehingga Ahmad Dahlan mengelaborasi pemikiran-pemikiran dari setiap tokoh tersebut bagi organisasi Muhammadiyah.
Resistensi Tasawuf di Muhammadiyah
Mengapa Muhammadiyah tidak/kurang menjadikan tasawuf dalam gerak organisasi? Karena Muhammadiyah sendiri adalah organisasi modern dan reformis Islam yang hadir pada abad kedua puluh, dan merupakan penerus ide dari pemikiran tokoh-tokoh Modern lain seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan lain-lain.
Sebagai organisasi yang mengusung nilai-nilai modernisme, maka Muhammadiyah secara tidak langsung juga mengusung pandangan positivisme dan rasionalisme. Sebagaimana yang diungkapkan Syafiq Mughni, pandangan positivisme dan rasionalisme telah menolak beberapa unsur / konsep yang ada dalam tasawuf, seperti; karamah dan wasilah. Dan juga Muhammadiyah menolak konsep kewalian / sainthood yang ada dalam tasawuf, yang bisa memberikan jalan atau penyambung dalam berdoa. Bagi Muhammadiyah berdoa bisa langsung kepada Allah tanpa memalui perantara wali ataupun berziarah ke makam-makamya.
Sebagai organisasi Modern, Muhammadiyah menolak praktik mystical experience yang mana hal tersebut biasanya dilakukan oleh para pengamal tasawuf dengan beberapa konsep seperti: ittihad, fana, baqa, dll. Karena hal itu bertentangan dengan akal, rasionalitas dan intelek bagi seorang muslim modern, dan hal ini berlawanan dengan praktik yang dilakukan kalangan tradisionalis (Muttaqin, 2009).
Muhammadiyah sebagai perwakilan Reformis Islam menolak praktik-praktik TBC, Tahayyul, Bid’ah, Churafat yang bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis. Semangat reformis ini terinspirasi oleh beberapa tokoh dari Mazhab Hanbali, seperti Ibn Taimiyyah yang menolak beberapa praktik sufisme menyimpang dan Muhammad bin Abdul Wahhab, yang terkenal sebagai pendiri pemimpin Wahabi yang sangat menolak total praktik-praktif sufisme dan tasawuf (Mughni, 2015).
Selain itu, hal yang paling fundamen adalah awalnya Muhammadiyah terkenal dengan organisasi puritan. Hal ini memberikan pandangan bahwa Muhammadiyah ingin melakukan purifikasi terhadap praktik-praktik TBC, yang dinilai mendegradasi moral umat Islam pada awal organisasi ini berdiri, dimana Ahmad Dahlan sendiri yang memimpin gerakan ini.
Apakah Ada Tasawuf di Muhammadiyah?
KH. AR. Fahruddin sendiri mengungkapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi Sufisme. Meskipun penamaan organisasi ini yang berimbuhan yah, sebagaimana lazimnya nama-nama tarekat, yang berimbuhan sama yang disandarkan pada nama mursyid atau wilayah tarekat itu berasal. Misalnya seperti: Qadiriyah yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir al-Jilani dan Naqsyabandiyah, yang disandarkan pada Baha al-Din Naqsyaband, dari Asia Tengah.
Tentunya akan ambigu, jika Muhammadiyah mirip dengan sebuah tarekat dalam institusi sufisme atau tasawuf. Dimana adanya seorang Mursyid atau guru pembimbing spiritual bagi seorang murid atau salik untuk menempuh jalan tasawuf. Hal inilah yang ditolak oleh Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah tidak memerlukan sosok figur untuk memperbagus akhlak, sebagaimana ada dalam institusi tarekat (Nakamura, 1980)
Dalam tulisan selanjutnya, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa nilai-nilai tasawuf dalam hal ini akhlak diaplikasikan dalam praktik keseharian tokoh-tokoh Muhammadiyah, tanpa perlu adanya labelisasi atau institusionalisasi tasawuf atau sufisme. Dan hal inipun juga dalam perilaku organisasi Muhammadiyah, dan menjadi ruh organisasi.
Sebagai organisasi yang aktif dalam sosial kemasyarakatan, maka akan sulit bagi tokoh atau organisai Muhammadiyah mengadopsi salah satu aspek ajaran tasawuf, zuhd. Dalam sejarahnya awal dalam sufisme, zuhud diartikan secara bebas menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Maka para sufi awal itu melakukan zuhud secara ekstrim misalnya, menjauhi hiruk pikuk dunia, atau tidak menikah, yang disebut sebagai tasawuf negatif. Maka praktik semacam ini tidak akan dijumpai dalam Muhammadiyah.
Untuk menghindari perilaku semacam ini, Syafiq Mughni merumuskan kontekstualisasi zuhud untuk meghadapi kehidupan modern. Zuhud diartikan sebagai konsep yang mendorong Muslim agar bekerja keras meraih kemajuan dunia, dan memanfaatkannya bagi masyarakat (Mughni, 2015), dan konsep ini sendiri berlawanan dengan konsep zuhud awal dalam tradisi tasawuf. Dengan memiliki harta, seorang Muslim dapat mengamalkan sebagian kepada lingkungannya dan berguna bagi kemasalahatan umum.
***
Tentunya, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam akan menerima beberapa aspek yang mendorong menggugah spirit keberagaman umat Islam, sekalipun itu apa yang ada dalam nilai-nilai tasawuf. Orientasi dasar dalam tasawuf adalah akhlak, maka hal ini tidak ditolak oleh kalangan Muhammadiyah. Tetapi jika orientasinya adalah misalnya seperti penyatuan bersama Tuhan, dan beberapa unsur dari luar Islam sehingga melahirkan beberapa doktrin lainnya, maka inilah yang ditolak oleh Muhammadiyah.
Sebagai organisasi yang berhaluan; reformis, modernis, rasionalis Muhammadiyah tentunya akan menolak beberapa tingkatan dalam tasawuf misalnya, syariat, tarikat dan ma’rifat. Yang mana doktrin ini populer di kalangan para penempuh ajaran tasawuf. Ataupun beberapa doktrin lainnya misalnya wahdat al-wujud oleh Ibn Arabi atau Insan Kamil oleh al-Jili. Karena bagi Muhammadiyah, tidak ada penggolongan tingkatan-tingkatan seperti itu.
Hal ini juga yang sama menjadi orientasi dari Neo-Sufisme yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa dalam konsepsi Neo-Sufisme, mereka menolak hal-hal yang bersifat kontroversial, populer dan spekulatif. Karena mereka lebih memilih aktivitas komunal daripada invididual. Hal inilah yang akhirnya beberapa studi tasawuf dalam Muhammadiyah menyebutkan bahwa Tasawuf Muhammadiyah adalah bentuk baru Neo-Sufisme.
Hal inilah yang mendorong beberapa kalangan sarjana dan cendekiawan Muhamamdiyah menyusun sebuah buku Diskursus Neo-Sufisme Muhammadiyah yang diedit oleh Hasnan Bahtiar pada 2015. Dalam buku kumpulan tulisan ini, para sarjana mengkesplorasi lebih lanjut tentang praktik-praktik tasawuf dalam organisasi Muhammadiyah. Dan memang ditemukan beberapa praktik sufisme yang sudah bermula sejak Ahmad Dahlan hingga masa modern, yang diwakili oleh beberapa tokohnya.
Editor: Soleh