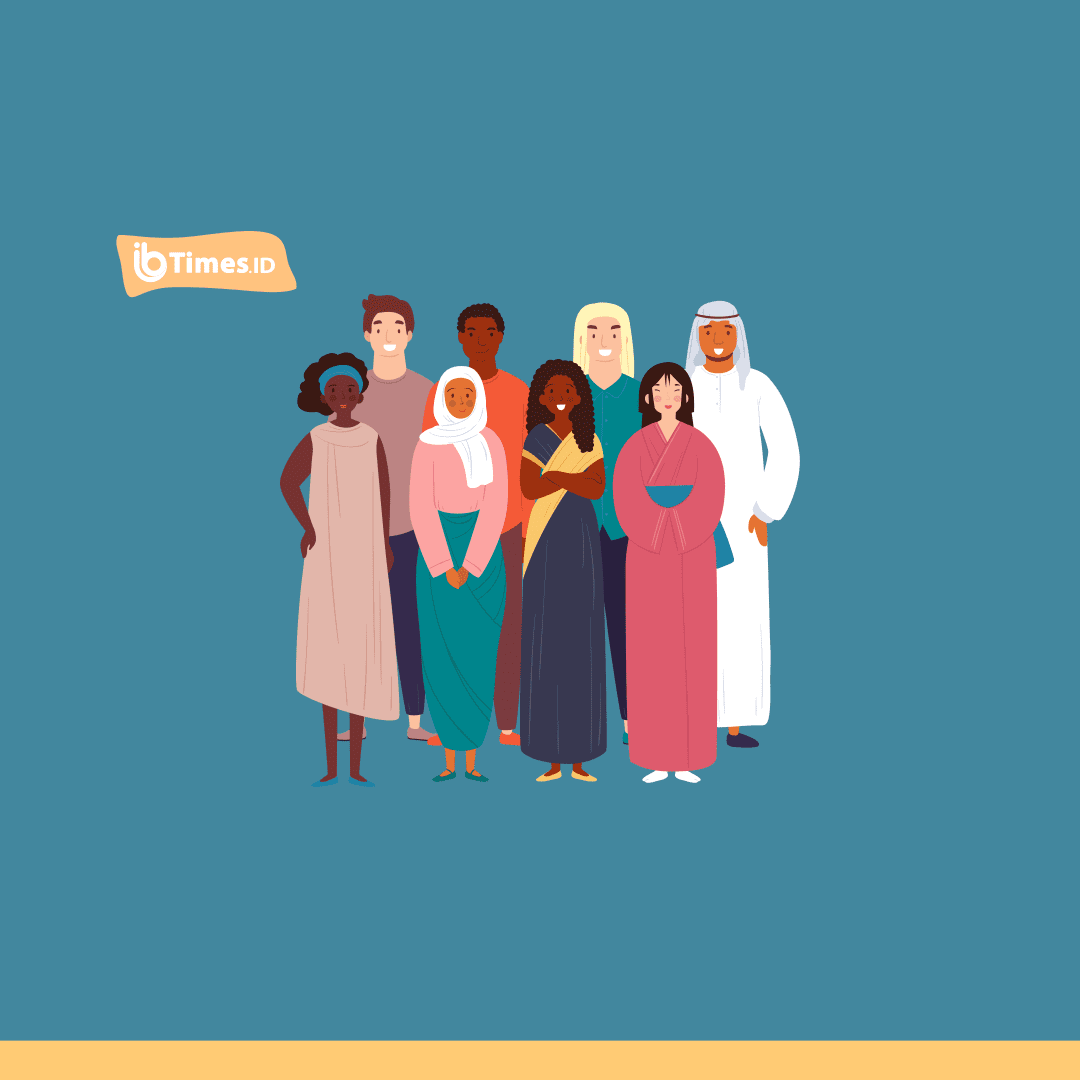Diksi ‘Plural’ yang memiliki konotasi sebagai sebuah ‘kemajemukan’ secara umum turut mengundang kontroversi bagi sebagian orang. Apalagi jika diksi ini diinterpretasikan sebagai sebuah ‘isme’ yang mengideologi dan dikaitkan dengan isu-isu keagamaan.
Lebih dari itu, diksi ini dianggap sebagai sebuah diksi yang menyesatkan. Tentu hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Apa yang salah dari gagasan pluralisme ini? Sejauh mana diksi ini bisa dipahami? Dan apakah gagasan ini hanya memiliki makna tunggal, tidak bisa ‘dikompromi’?
Dalam tulisan ini, penulis ingin mengemukakan korelasi antara gagasan pluralisme dan gagasan kebebasan beragama. Artinya, terlepas dari makna pluralisme yang dianggap menyesatkan oleh sebagian golongan, penulis hanya akan menitikberatkan gagasan ini—meskipun dengan mengupayakan makna lain—dan gagasan kebebasan beragama yang sejalan dengan firman Allah berikut: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)…” (Al-Baqarah: 256)
Pluralisme, jika ditilik dari akar katanya secara etimologis, maka makna yang terkandung dalam lafal ini adalah ‘kemajemukan’ dalam berbagai macam hal. Baik budaya, ras, pemikiran, peradaban, dan lain sebagainya. Makna yang demikian umum ini jarang sekali dipermasalahkan, kecuali bagi segelintir orang-orang yang fanatis, yang teramat takut akan kehilangan ‘eksitensinya’.
Berbeda dengan makna di atas, pluralisme jika diartikulasikan sebagai sebuah paham tertentu, bahkan sebagai sebuah ideologi yang erat kaitannya dengan penyatuan agama-agama, turut mengundang kontroversi bagi kebanyakan kaum intelektual.
Bahkan tak sedikit dari mereka yang menganggap bahwa ideologi ini adalah ideologi yang menyesatkan, harus dihindari, dan tak layak ‘dikonsumsi’. Pasalnya, tokoh-tokoh seperti Jalaluddin Rumi, Ibn Arabi, Hosein Nasr dan beberapa tokoh Islam yang lain juga turut menjadi sorotan mereka, ini sama saja halnya dengan tokoh seperti John Hick, Karl Rahnel dan tokoh-tokoh pluralis asal Barat yang lain.
Wacana pluralisme agama ini mulai semarak diperbincangkan di paruh awal abad ke 20. Pada saat abad ke 17 M, di Eropa terjadi peperangan yang berkepanjangan. Peperangan ini terkenal dengan sebutan The Thirty Years War, atau juga Secterian Wars. Menurut sebagian peneliti, peperangan ini pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan kepercayaan di kalangan penganut umat Kristen sendiri.
Tak hanya sampai di sini, peperangan-peperangan yang lain juga turut terjadi dalam tubuh umat Nasrani dan Yahudi yang disebabkan oleh sikap ekslusif dalam mendakwahkan kebenarannya (truth claim).
Masing-masing dari mereka, dengan diselimuti permusuhan yang membabi buta, saling menjatuhkan dan memonopoli kebenaran hanya untuk kelompoknya sendiri. Latar belakang seperti ini yang memicu ketegangan bagi kelompok agama lain, juga bagi para teolog dan pemikir saat itu.
Secara sederhana, berawal dari sini kemudian banyak dari kalangan pemikir dan teolog di Barat pada awal abad ke-20 M yang beranggapan bahwa pluralisme agama merupakan satu-satunya jalan keluar.
Dalam Encontering God, Diana Eck menyebutkan bahwa titik awal kemunculan sikap eksklusif umat Nasrani, jika ditelusuri lebih jauh, berakar pada sebuah jargon sejak abad ke-3 M yang berbunyi: “extra ecclessiam nulla salus” yang berarti “di luar gereja tidak ada keselamatan”.
Sikap eksklusif seperti ini sebenarnya bersumber dari ajaran Bible itu sendiri. Dalam Peter in Acts (4:12) disebutkan: “tidak ada keselamatan bagi orang lain, karena tidak ada orang lain di bawah langit ini, diantara para makhluk hidup, yang dengannya (Yesus) kita diselamatkan”.
Di sisi lain, al-Qur’an juga menyebutkan: “Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: ‘Tidak sekali-kali akan masuk surga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani….’”. (Al-Baqarah : 111).
Tak ayal, inklusivisme—sebagai langkah awal untuk menuju Pluralisme—lalu hadir dalam pemikiran keagamaan sebagai reaksi dari sikap eksklusif tersebut. Pada tahun 1990, The World Council of Churces mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan The Baar Statement, yang isinya:
“Keengganan dalam memberikan perhatian yang serius terhadap kepelbagaian dan kemajemukan agama-agama yang terdapat dalam masyarakat di seluruh dunia adalah sama dengan membuang kesaksian Bible terhadap Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu, dan Bapa kepada semua umat manusia”
Namun, dalam perjalanannya, inklusivisme sendiri dirasa masih belum cukup oleh golongan pluralis. Karena ia dianggap masih melihat yang lain dengan kaca mata sendiri, dan menegaskan keutamaan agama kristen.
Banyaknya sudut pandang yang saling bertentangan dalam tradisi keberagamaan di Barat merupakan pengalaman Barat tersendiri dalam beragama. Setelah eksklusivisme tidak dapat dipertahankan, maka inklusivisme diperkenalkan untuk memastikan wujud toleransi dan keterbukaan.
Setelah inklusivisme terealisasikan, barulah lahir kemudian gagasan pluralisme agama, untuk melihat agama dalam perspektif yang konon ‘katanya’ bisa lebih terbuka. Ini tercerminkan dalam perkataan john Hick dalam The Encyclopedia of Religion, ia mengatakan:
“Sebuah teori khusus yang menghubungkan antara agama-agama ini adalah teori bahwa agama-agama besar di dunia merupakan konsepsi dan persepsi varian, dan merupakan tanggapan terhadap Yang Ultimatum, realitas Ketuhanan yang misterius”.
Di tempat lain, Wilfred Cantwell Smith, salah seorang ahli sejarah agama yang sangat berpengaruh di abad ke-20, dalam magnum opusnya; Toward a World Theology, mencoba untuk meyakinkan orang-orang agar memahami kebutuhan kita saat ini terhadap satu teologi (theology of religions) yang dapat menyatukan semua agama dan semua umat manusia tanpa perlu meleburkan agama masing-masing.
Kiranya perlu untuk menjadi catatan, bahwa tidak semua para teolog dan pemikir di Barat sepakat dengan makna pluralisme yang telah disebutkan di atas. Ada beberapa tokoh yang memiliki definisi dan konsepsi tersendiri terkait dengan makna pluralisme tersebut.
Setidaknya, terdapat beberapa makna pluralisme agama yang dapat penulis kemukakan di sini. Pertama, pluralisme agama yang berarti keperbagaian agama (religious diversity). Tokoh yang mempelopori makna ini adalah Hussin Mutalib dalam bukunya, Religious Diversity and Pluralism in Southeast Asian Islam.
Kedua, Pluralisme agama tetapi yang dimaksud adalah dialog antar agama. Di sini, pluralisme dianggap sebagai satu usaha untuk bersikap terbuka kepada keperbagaian. Dengan makna ini, dialog dan kesepahaman akan dapat dijalankan dengan baik.
Ketiga, pluralisme agama dimaknai dengan menerima kebenaran agama lain. Makna yang satu ini yang terbilang cukup ekstrem untuk dianut. Karena makna ini menuntut adanya relativisme kebenaran. Diantara tokoh yang memaknai pluralisme yang seperti ini adalah Susan Laemmle, seorang Rahib dan Dekan di University of shouthern California, juga beberapa pendapat Rick Rood yang terepresentasikan dalam Evidence, Answer and Christian Faith.
Menurut hemat saya, dari tiga varian makna pluralisme diatas, nampaknya memungkiri keperbagaian agama-agama di dunia adalah sebuah anggapan yang sia-sia. Karna realitas sendiri yang langsung menjawabnya. Tetapi, hal ini juga bukan untuk dimaksudkan agar kita, sebagai umat beragama, turut serta mengakui kebenaran agama lain.
Kita berhak untuk mengklaim kebenaran atas apa yang kita yakini, tanpa menafikan adanya dialog secara terbuka, dan tanpa harus mengajak ‘pihak lain’ secara brutal terhadap apa yang menurut kita ‘benar’, sekaligus tanpa mendiskreditkan ‘keyakinan’ yang menurut kita keliru, bahkan sesat.
Editor: Yusuf