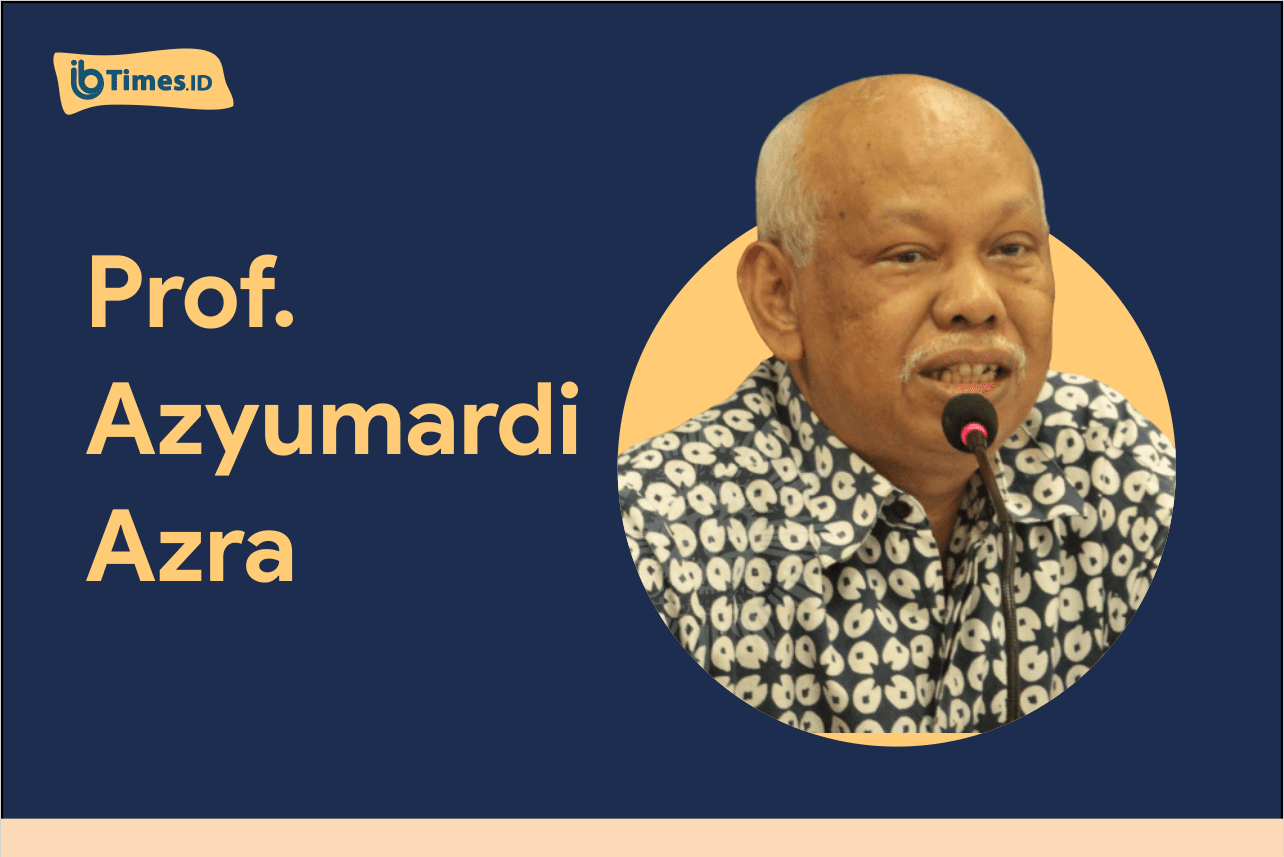Sebagai pendidik sekaligus Rasul, misi pendidikan pertama Nabi Muhammad Saw ialah menanamkan akidah yang benar; akidah tauhid – mengesakan Tuhan, yang by extension, memahami seluruh fenomena alam dan kemanusiaan sebagai suatu kesatuan yang holistik. Orang Jawa menyebutnya dengan manunggaling kawulo gusti, yang berarti, jika engkau mencintai Allah, berarti harus pula mencintai ciptaan-Nya.
Dalam kerangka tauhid ini, lanjut Azra, kemanusiaan – dan dengan demikian SDM – adalah manusia yang memiliki kualitas seimbang; beriman, berilmu, dan beramal; cakap lahiriah maupun batiniah, berkualitas secara rasional, spiritual dan emosional atau memiliki EQ, SQ dan IQ yang tinggi. Krisis dalam kualitas SDM terjadi tatkala – menurut Azyumardi Azra – harmoni semacam ini tidak lagi dipertimbangkan dan dipedulikan sebagaimana acap kali terjadi dalam pendidikan modern.
Adalah setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad melakukan beberapa perubahan mendasar terkait tugasnya sebagai pendidik utama dalam pembangunan masyarakat sosial-politik keagamaan Madinah. Di Madinah, Nabi Saw tidak hanya menciptakan tatanan politik sebagaimana diatur dalam Piagam Madinah, tetapi juga membangun tradisi pendidikan Islam dengan fungsionalisasi masjid sebagai tempat yang tidak hanya digunakan beribadah (shalat), melainkan tempat untuk menyelenggarakan dan menyemaikan nilai-nilai agama dalam pengertian seluas-luasnya.
Resiliensi Pesantren
Dalam rentang sejarah Indonesia, eksistensi pesantren sudah tak diragukan lagi. Ia menunjukkan, menurut Masdar Hilmy, daya tahan yang dimiliki begitu kuat (strong endurance) dari gempuran nilai-nilai baru yang berdatangan sekalipun dalam hemat Azra, pesantren hanya mengadopsi sebagian kecil dari pembaruan untuk sekadar bertahan hidup (survive).
Resiliensi yang telah dipertunjukkan oleh pesantren juga sekaligus menggambarkan fleksibilitasnya dalam berdialog dengan zaman. Dari proses dialog dan dialektika itulah, pesantren pada akhirnya muncul menjadi sebuah kekuatan pendidikan yang matang, dewasa, dan mandiri yang darinya lahir figur ulama-ulama besar yang kontributif terhadap agama, bangsa dan negara.
Sekalipun catatan sejarah telah membuktikan “kedigdayaan” pesantren dalam menghadapi tantangan zaman, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan-tantangan serupa di masa-masa mendatang akan semakin kompleks. Tantangan tersebut bukan hanya direspons oleh pesantren, melainkan pesantren juga dituntut memiliki kreativitas dalam mengartikulasi dan mengorkestrasikan produk-produk budaya yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
Artinya, kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman saja, bagi Masdar Hilmy, tidak cukup untuk membuat pesantren sebagai “lembaga yang digandrungi” semua lapisan masyarakat. Lebih dari itu, ia dituntut untuk mampu memainkan peran sebagai produsen budaya dan pangsa pasar yang menyediakan apa yang dibutuhkan manusia sekarang dan masa depan.
Tetapi dengan jujur harus kita akui, pendidikan Islam hingga saat ini – dalam amatan Azra – kelihatan sering terlambat merumuskan diri dalam merespons perubahan dan tantangan zaman. Sistem pendidikan Islam kebanyakan lebih cenderung memusatkan diri pada bidang humaniora dan ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi, astronomi, nuklir. Padahal gugusan ilmu tersebut mutlak diperlukan. Ilmu eksakta, dalam hal ini, belum mendapat apresiasi dan tempat yang sepatutnya dalam sistem pendidikan Islam.
Profesionalisme Pendidikan Islam
Karena itu, Azyumardi Azra memandang sudah saatnya lembaga pendidikan Islam dikelola secara profesional. Profesionalisme ini menyangkut reputasi lembaga pendidikan Islam di masa depan. Zaman sudah bergeser, tentu pengelolaannya harus semakin akuntabel. Selama ini, menurut Azyumardi Azra, usaha pembaruan dan peningkatan pendidikan Islam masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Sebab usaha tersebut dilakukan ala kadarnya (sebatas pengguguran kewajiban), sehingga tidak terjadi perubahan esensial dalam sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam lagi-lagi cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan atau kurang bersifat future-oriented.
Pendidikan Islam harus tanggap dan lebih sigap dalam merespons perubahan zaman. Paradigma pendidikan Islam harus bergeser pada pendidikan futuristik dengan tidak menanggalkan paradigma lama yang masih relevan. Paradigma futuristik ini juga harus merambah pada profesionalisme dalam pengelolaan pendidikan. Menurut Azra, mayoritas pendidikan Islam masih dikelola senada dengan ungkapan pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan “Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah” atau slogan Kementerian Agama “Ikhlas Beramal”.
***
Ungkapan tersebut tidaklah salah dan memang benar adanya, akan tetapi tanpa harus mengorbankan semangat keikhlasan dan jiwa pengabdian (khidmah) serta konsep barakah, sudah waktunya sistem dan lembaga pendidikan Islam dikelola secara profesional, bukan hanya dalam soal penggajian, honor, tunjangan atau pengelolaan administrasi, birokrasi dan keuangan. Profesionalisme ini mutlak dilakukan demi mewujudkan sistem pendidikan Islam yang adaptif dan akomodatif terhadap perubahan zaman.
Harus jujur diakui, manajemen lembaga pendidikan Islam masih tersentral pada figur kiai atau ketokohan sebagai pemimpin tunggal lembaga, bukan pada penciptaan sistem penyelenggaraannya. Konsekuensinya, maju mundurnya sebuah lembaga sangat dipengaruhi oleh figur ketokohan tersebut. Sepanjang figur tersebut memiliki kemampuan yang memadai, maka lembaga tersebut akan tetap eksis, dan sebaliknya akan gulung tikar jika figur tersebut tidak cakap dalam mengelola dan memajukan lembaga.
Jika beberapa kelemahan yang disebutkan Azyumardi Azra tersebut tidak segera diatasi, agak sulit bagi kita mengharapkan sistem dan lembaga pendidikan Islam bisa benar-benar fungsional dalam ikhtiar penyiapan SDM yang berkualitas dan kompetitif untuk menjawab tantangan zaman. Dalam hemat Azra, berbagai pembaruan harus segera dilakukan dalam sistem pendidikan Islam.
Pembaruan Kultur Akademik
Pembaruan yang dirasa penting dalam sistem pendidikan Islam adalah menciptakan kultur akademik yang kondusif, sebuah nilai-nilai adiluhung yang terhimpun dalam budaya akademik (academic culture). Kultur akademik yang dimaksud adalah berlakunya sebuah sistem nilai yang menempatkan kegiatan ilmiah sebagai – meminjam istilah Bourdieu – habitus dan ujung tombak dari seluruh rangkaian proses pembelajaran dan pengajaran guna mencapai tujuan-tujuan yang terkait dengan pengembangan ilmiah dan inovasi sosial-budaya, sains, dan teknologi.
Dalam konteks ini, budaya akademik harus dijadikan – dalam istilah Bourdieu – doxa bagi para anak didik dan santri agar mereka terbiasa mendapatkan pengayaan perspektif sehingga menjadikannya pribadi yang inklusif. Budaya akademik sebenarnya tidak hanya sekadar meneliti dan berpikir ilmiah, melainkan seluruh aktivitas ilmiah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adiluhung dalam dunia akademik. Ia tidak saja menyangkut aspek ontologis, tetapi epistemologis dan aksiologis.
Lebih jauh, budaya akademik sebagai – mengutip Masdar Hilmy – sebuah eksistensi, metodologi dan penggunaannya bagi perbaikan kualitas kehidupan manusia secara kaffah. Sayangnya, sistem pendidikan Islam semisal surau, dayah, pesantren, seakan tabu mendengar istilah “budaya akademis” dan dipersepsikan sebagai sebuah ancaman yang dapat menggoyang status quo. Akan tetapi, tidak sedikit juga sebagian lembaga pendidikan Islam mulai perlahan-lahan menerapkan “budaya akademis” di dalam sistem pembelajarannya.
Karena itu, makna profesionalisme yang ditekankan di sini adalah tidak hanya tertuju pada kelembagaan semata, melainkan sub-kultur yang ada padanya, meliputi sistem, manajemen keuangan, gaji, tunjangan dan honor guru, peningkatan kualitas SDM, komunikasi interaktif terhadap murid dan wali murid, serta program yang menstimulus adanya inovasi dan kreasi. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang terbukti mampu berdialog dengan zaman, lembaga pendidikan Islam (baca: pesantren, surau, dayah, meunasah dan semacamnya) pada akhirnya menjadi tumpuan terakhir bagi manusia modern yang haus akan nilai-nilai spiritual akibat ketidakpuasan mereka terhadap realitas kemodernan.
Editor: Soleh